Kehadiran komunitas semakin menjadi keniscayaan, tak bisa ditahan dan dihindari. Kunci mengelolanya: berkolaborasi dalam kemitraan.
Teguh S. Pambudi
Mereka muncul bak cendawan di musim hujan. Ada yang lahir secara organik, karena persamaan pengalaman, kepentingan, dan hobi para anggotanya. Ada pula yang sengaja didesain dan disponsori oleh produsen tertentu.
Itulah komunitas-komunitas yang tumbuh di sekitar kita. Dan, mungkin Anda, para pembaca yang budiman, tergabung pula dalam satu komunitas tertentu. Atau bahkan menjadi anggota dua-tiga komunitas sekaligus!
Apa pun latar belakang kemunculannya – organik ataupun sponsored – komunitas tampak menjadi “keluarga baru” bagi masyarakat modern, khususnya di perkotaan. Di sinilah mereka berhimpun, dan kemudian melakukan hal berikut yang dipandang baik sekaligus bermanfaat buat mereka dan masyarakat yang mereka pedulikan: to love, honor, cherish, consume bila mereka berkumpul karena faktor kesamaan menggunakan atau memakai produk tertentu.
Akan tetapi, wahai produsen yang terhormat, jangan pernah mengabaikan mereka, terutama yang tumbuh secara organik, yang menyebar dalam senyap, dan kelahirannya tidak Anda bidani lewat launching di hotel berbintang. Terlebih setelah teknologi, belakangan malah kian memacu percepatan kemunculan mereka lewat jejaring sosial semacam Facebook, melahirkan apa yang disebut Charlene Li dan Josh Bernoff dari Forrester, Inc. sebagai fenomena groundswell.
Di balik kegiatan komunitas-komunitas yang lahir organik yang sepertinya hanya to love, honor, and cherish (lewat kongko bareng di kafe, jalan-jalan, dan sebagainya), sesungguhnya mereka bukan hanya punya power to purchase. Jalur online ataupun offline, perbincangan mereka tentang produk, perusahaan, bahkan perilaku eksekutif, dapat menyebar seperti virus mematikan. Artinya, mereka juga memiliki power to influence. Entah itu memengaruhi sesama anggota, komunitas lain, atau masyarakat luas. Mereka adalah pressure group.
Ya, komunitas sesungguhnya adalah fenomena demokratisasi di ranah bisnis. Kini adalah eranya pelanggan yang makin bebas untuk mendefinisikan perspektif mereka terhadap perusahaan, produk, dan merek tertentu. Perspektif yang mungkin tampak aneh dari gambaran yang diinginkan produsen. Atau bahkan mengejutkan, karena tidak pernah terpikir sebelumnya.
Tentu saja perusahaan tidak perlu menanggapi dengan rasa gentar atas fenomena yang ada ini. Jajaran eksekutif, bagian public relations ataupun pemasaran tak perlu gemetar. Sikap perusahaan tinggal dua: berkolaborasi atau mengabaikan sama sekali, menganggap kawan atau sang pengganggu.
Sikap mengabaikan jelas bukan pilihan bijak karena seperti disinggung di atas, teknologi membuat komunitas menjamur dan kian ampuh dalam menyebarkan berita negatif. Charlene Li dan Josh Bernoff bahkan menyebutnya sebagai sesuatu yang unstoppable, tidak bisa ditahan. Tidak pula bisa dihindari. Komunitas adalah keniscayaan. Perusahaan akan hidup di tengahnya. Alhasil, bagi perusahaan, isunya adalah yang satu ini: how to manage community?
Sebagai sebuah “keluarga”, mayoritas komunitas – terlebih yang muncul secara organik – cenderung bersikap independen dan merasa berposisi setara dengan produsen yang produknya mereka gunakan. Untuk merangkul komunitas, kolaborasi adalah jalan terbaik. Bukan kooptasi. Sebab dengan berdiri sejajar, berdialog tentang apa yang bisa dikontribusikan produsen dan bisa dilakukan bersama, maka akan muncul feeling of engagement dalam komunitas, perasaan terikat. Dari sinilah lahir energi positif yang menguntungkan banyak pihak: produsen, komunitas, dan stakeholder lainnya.
Dengan demikian, kata kunci dalam mengelola komunitas adalah kemitraan, memperlakukan sebagai mitra. Caranya?
“Money can’t buy me love”, meniru The Beatles. Guyuran uang bukan selalu yang dibutuhkan komunitas. Bukan pula gelontoran produk-produk tercanggih. Berbagi ide, jejaring, dan perhatian mungkin akan lebih banyak bermanfaat untuk komunitas yang masing-masing memiliki keunikan tersendiri, juga tujuan sendiri mengapa mereka lahir di tengah masyarakat.
Survei SWA dengan Prasetiya Mulya Business School memperkuat hal itu. Di tengah sorotan negatif atas perilaku korporasi, masyarakat berharap banyak munculnya perilaku korporasi yang etis dan bertanggung jawab. Mengutip John Elkington, masyarakat makin rindu akan lahirnya perusahaan yang berperilaku seperti lebah, menghasilkan madu. Bukan korporasi jenis ulat, yang bisanya cuma merusak alam dan lingkungan sekitarnya.
Survei juga melihat bahwa produsen dapat memberi kontribusi positif kepada masyarakat. Jalannya bisa beragam, tapi prinsip dasarnya tetaplah kemitraan, bergandeng tangan bersama. Tidak semata melihat komunitas sebagai kumpulan orang yang hanya mengonsumsi produk tertentu.
skip to main |
skip to sidebar

Catatan ringan dari Taman Tanah Abang III
Come on
Follow me @teguhspambudi
Calendare
Time is ...
Welcome
Salam. Blog ini dihadirkan di tengah Taman Tanah Abang III. Celoteh ringan di sela pekerjaan. Sebagian dimuat di SWA. Sebagian tercurah begitu saja.
About Me
From Zero to Growth

Categories
- Creative Economy (33)
- CSR (3)
- Diaspora (2)
- Digital Technology (11)
- Entrepreneur (26)
- Entrepreneurship (24)
- Family Business (7)
- Green Business (1)
- HR (4)
- Leadership (44)
- Life (12)
- Live (3)
- Macroeco (6)
- Management (21)
- Marketing (28)
- Social Entrepreneur (8)
- Social Media (4)
- Strategy (34)
- Sustainability Development (2)
- Technopreneur (12)
- Women Leadership (7)
Blog Archive
-
▼
2009
(22)
-
▼
April
(15)
- Ketika Bicara tak Lagi Murah
- CEO versi 3.0.
- Inspirasi dari Kakek Jeno
- Mengentaskan Para Pangeran
- Pembuktian Kaisar Es Krim
- Kembalinya Sang Legenda
- Tiga Menguak Cokelat
- Hidup di Tengah Komunitas
- Empat Kaki Kapitalisme Kreatif
- Duh, Carly ...
- Master Efisiensi di HP
- Raja e-Commerce Negeri Sakura
- Mark si Fenomenal
- Maestro Desain dari Boxtel
- Lelaki di Balik Anomali Porsche
-
▼
April
(15)



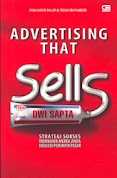
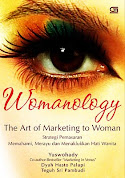












0 comments:
Post a Comment