
Di tengah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang cenderung jadi alat promosi, kapitalisme kreatif menawarkan pendekatan lain. Bagaimana caranya?
Pada mulanya sebuah gagasan. Lalu menyebar menjadi gerakan. Seperti open sources, bagi yang pro, maknanya diperkaya dan disesuaikan dalam konteks serta kebutuhan yang ada. Lalu, jadilah ia fashion. Dikemas dalam aneka bentuk, dibicarakan di mana-mana. Namun, alih-alih makin bernas, pengayaan makna malah sering membuatnya jadi miskin substansi, terlepas dari esensi yang dicitakan semula.
Itulah yang sering terjadi pada sebuah konsep. Tak terkecuali corporate social responsibility (CSR). Setelah mendarat 5-6 tahun lalu di Tanah Air, konsep ini seperti lepas dari makna esensialnya: memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan, dan meminimalkan dampak negatif demi pembangunan berkelanjutan. Alih-alih memperhatikan pada bagian “dalam” (core) operasi perusahaan, yakni proses bisnis serta value chain yang etis dan bertanggung jawab, CSR lebih diletakkan dan dimaknai di “ujung” operasi perusahaan dengan napas promosi, branding dan public relations yang terlalu kental. Bahkan, banyak yang menempatkannya sebagai tools of marketing belaka. Sebagai a new way of marketing, malah! Alamak!
Dalam operasi perusahaan, pasti ada value chain hingga akhirnya menjadi output, berbentuk produk atau jasa. Proses mengolah value chain ini memerlukan pengelolaan yang bertanggung jawab agar dampak positifnya lebih besar ketimbang negatifnya. Pasokan bahan produksinya sudah harus diperhatikan mulai dari asal mulanya, illegal atau tidak, sampai limbahnya, mencemari lingkungan atau tidak. Dari sisi para pemasoknya, sudahkah diperhatikan apakah mereka mengindahkan semua aturan ini. Di sisi para pengolahnya itu sendiri (internal perusahaan), apakah telah mendapatkan hak-hak yang semestinya, apakah sudah terbebas dari aneka diskriminasi. Jadi, perusahaan air minum dalam kemasan, misalnya, seharusnya lebih terpusat berbicara CSR pada aspek water management agar sumber airnya terbarukan dan sustain buat masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Sejatinya, CSR memang berbicara tentang tanggung jawab yang sangat dalam; rangkaian value chain, dari input hingga output. Akan tetapi, makna itu kini kian tereduksi. Ia diletakkan terlalu berada di “depan”. Di bagian ouput, CSR diletakkan pada produk, dikemas sebagai cause related marketing. Perusahaan mendonasikan setiap rupiah dari produk yang dijualnya untuk program-program kegiatan sosial, tak peduli apakah rangkaian proses bisnis untuk menghasilkan ouput itu sudah memenuhi aneka standar atau belum, memaksimalkan dampak positif bagi stakeholders-nya ataukah tidak. Tanggung jawab sosial diletakkan untuk agenda-agenda yang acapkali tidak terhubung dengan proses bisnisnya.
Salah seorang yang mengakui fenomena ini adalah Guntur Siboro, Direktur Pemasaran Indosat Tbk. Dia mengakui program-program yang dilabeli CSR di perusahaannya dilakukan dalam konteks membangun corporate branding. Dengan awareness yang terbangun, diharapkan masyarakat akan lebih mudah menerima produk Indosat.
Model ini, menurutnya, merupakan bentuk soft marketing. “Yang penting, kami tunjukkan kepada orang lain bahwa kami care, concern, dan bukan perusahaan yang cari untung saja. Dengan begitu, orang akan memiliki empati pada kami,” ujar Guntur. Dan, “Sepertinya bukan hanya Indosat, deh. Perusahaan yang lain saya rasa mengaitkan CSR dengan corporate branding,” dia menandaskan.
Ups!
Tentu mereka sah-sah saja melakukan itu. Toh, memang wajar mencari profit. Program-program sosial yang dikemas dengan label CSR pun tetap diperlukan masyarakat luas, langsung ataupun tidak. Namun, memaknainya sebagai tools of marketing bisa membuat agenda-agenda sosial cuma jadi tempelan, jadi pulasan kosmetik semata demi citra perusahaan yang dermawan – padahal mungkin ia sesungguhnya tak bertanggung jawab karena lalai dalam memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif proses bisnisnya. Ini sungguh disayangkan. Mengapa?
Program-program berlabel CSR diperlukan karena sejatinya banyak sederet persoalan di masyarakat yang bisa turut diselesaikan atas peran besar perusahaan tanpa terlalu kental bermuatan pemasaran. Diselesaikan kalangan bisnis karena pemerintah tampak kepayahan bila bekerja sendirian untuk menyelesaikan 8 target Millenium Development Goals (MDGs) yang dijanjikannya, yang tampaknya belum tersosialisasi dengan baik: (1) menurunkan tingkat kemiskinan dan kelaparan; (2) meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan; (3) mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian bayi; (5) meningkatkan kesehatan; (6) memberantas penyakit HIV, malaria, dll.; (7) mengusahakan keberlangsungan lingkungan hidup; dan (8) melakukan kemitraan global untuk pembangunan.
Masyarakat, terutama mereka yang berada dalam sasaran 8 target MDGs, jelas masih membutuhkan peran perusahaan. Terlebih, dana yang diputar dalam seabrek kegiatan berlabel CSR nilainya sudah sangat besar. Bisa ratusan miliar rupiah setahun. Itu baru dari kalangan perusahaan swasta. Dari kalangan BUMN, total dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang diambil dari laba bersih perusahaan pelat merah mencapai lebih dari Rp 1 triliun setiap tahun. Jumlah yang sungguh tak sedikit. Dan bila kita lebarkan lagi pada dana-dana yang bertebaran di masyarakat, yang berada dalam aneka ragam bentuk kedermawanan (infak, sedekah, dsb.), bisa dibayangkan multiplier effect yang bisa disatukan bila itu semua bergerak selaras.
Jadi, tanpa berpanjang kata, sesungguhnya yang kita butuhkah sekarang adalah kapitalisme kreatif. Apa itu?
Gagasan ini pertama kali dipopulerkan Bill Gates dalam World Economic Forum di Davos, Swiss, awal 2008. Creative capitalism merupakan bentuk baru kapitalisme yang mengawinkan antara kebutuhan menghasilkan laba dan keinginan menyelesaikan masalah mereka yang secara ekonomi tertinggal, yang disebut bottom of the pyramid – istilah yang pertama kali dilontarkan Franklin D. Roosevelt dalam pidatonya, “The Forgotten Man”, 7 April 1932, yang kemudian dipopulerkan C.K. Prahalad dalam bukunya, Fortune at the Bottom of the Pyramid.
Mengambil inspirasi dari Prahalad dan dengan spirit turut menyelesaikan MDGs, Gates mengeluarkan gagasan tersebut dengan tesis bahwa dunia bisnis dapat menggunakan keahlian bisnisnya untuk menemukan cara inovatif guna melayani mereka yang termarginalkan dari proses pembangunan, sekaligus mendapatkan keuntungan. Tak seperti filantropi yang cenderung ”memberikan ikan”, kapitalisme kreatif lebih “menjual kail” yang inovatif dengan harga terjangkau kepada mereka yang memiliki daya beli lemah, yang berada di dasar piramida agar bisa ikut kereta kemakmuran.
Laiknya gagasan, konsep Gates yang tak memunculkan definisi operasionalnya ini menimbulkan pro-kontra. Karena creative capitalism yang dilontarkannya tak menghilangkan unsur laba sama sekali ketika menjangkau orang-orang yang tertinggal, gagasan ini dikritik sebagai bentuk kreativitas kalangan kapitalis. Tujuan dari menjangkau dan melebarkan pasar, tentunya, agar bisnis tetap survive, tumbuh dan berkembang. Tak jauh-jauh dari habitat para kapitalis: mengeruk laba.
Gagasan Gates pasti akan melelahkan bila hanya jadi bahan wacana. Sebuah inspirasi lahir dari semangat membebaskan. Melihat spirit Gates untuk menyukseskan MDGs, gagasan itu layak disambut. Terlebih di negeri ini yang 37,17 juta penduduknya dililit kemiskinan, berada di dasar piramida, hidup di bawah Rp 186.636 per kapita per bulan. Namun, gagasan itu tentunya tak mesti ditelan mentah-mentah karena mesti dikontekstualkan dengan kondisi yang ada. Caranya?
Pertama, luaskan dulu batasan kapital dari konteks yang sempit: uang. Lepaskan dari pikiran tentang ideologi yang memerangkap itu – sistem ekonomi yang free competition demi profit seeking. Kapital di sini bukan hanya perkara fulus. Majalah ini melihat bahwa kapital di sini bisa dalam bentuk social capital (terutama jejaring), intellectual capital, technology capital dan financial capital.
Alhasil, kapitalisme kreatif adalah tentang memutar seluruh kapital tersebut secara kreatif agar masyarakat yang tertinggal menjadi lebih berdaya dan sejahtera. Memutar kapital secara kreatif berarti memutar seluruh sumber daya yang dimiliki tidak dengan semata memberikan kail, tapi dengan jalan yang memberdayakan, dan bersifat berkelanjutan untuk menciptakan kemandirian.
Kedua, aktornya pun harus diluaskan, jangan hanya kalangan bisnis dan pemerintah. Ada empat elemen yang terlibat dalam kapitalisme kreatif: bisnis, masyarakat/individu, institusi pendidikan dan pemerintah. Itulah empat elemen kapitalisme kreatif. Itulah empat kaki yang masing-masing memiliki kapital dengan kapasitas masing-masing, yang kemudian memutarnya secara kreatif untuk menghasilkan hal-hal bermanfaat bagi masyarakat, terutama yang berada di dasar piramida.
Sekarang, mari lihat lebih dekat.
Dari aspek modal finansial, misalnya. Di kalangan bisnis, uang yang mereka miliki sangat besar. Program berlabel CSR dan PKBL mencapai triliunan rupiah. Dana masyarakat dan individu pun demikian yang dikumpulkan lewat BAZIS serta institusi lain macam Dompet Dhuafa. Juga, dana pemerintah (pusat maupun daerah) yang diarahkan untuk mencapai target MDGs. Sementara kalangan akademisi pasti kaya akan penelitian yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Bayangkan kalau dana-dana ini diputar dengan kreatif! Akan banyak persoalan di masyarakat yang bisa terselesaikan. Belum lagi kalau kapita-kapital yang lain dipadukan.
Sayangnya, aneka kapital ini belum diputar kreatif. Dari sisi pemerintah, misalnya, tiap tahun triliunan rupiah dikucurkan untuk bantuan langsung tunai yang tidak membuat masyarakat jadi mandiri dan berdaya. Sungguh tidak kreatif untuk menuntaskan target MDGs nomor wahid: mengangkat 37,17 juta jiwa dari garis kemiskinan. Bantuan tunai adalah program yang begitu rapuh.
Memutar kapital secara kreatif berarti memutar seluruh sumber daya yang dimiliki tidak dengan semata memberikan kail. Langkah awalnya adalah cara pandang. Mengacu pada Zaim Saidi, Direktur PIRAC, sejatinya setiap elemen adalah aktor yang memiliki sumber daya untuk memproduksi sesuatu. Agar kapital terputar maksimal, harus ada kesetaraan. Ada keterlibatan seluruh elemen. Tak memperlakukan yang lain sebagai penonton dan minoritas. Dengan cara pandang semacam ini, program-program kreatif yang selanjutnya dilahirkan bisa tepat guna. Jadi, “Ubah sistem, dan jadikan manusia sebagai subjek,” ujar Zaim.
Program kreatif, di mata Timotheus Lesmana, Direktur Eksekutif Eka Tjipta Foundation, tak akan pernah bisa terjadi bila pihak yang menjadi sasaran dari suatu program tidak dilibatkan. Dan itulah yang kerap terjadi pada perusahaan yang melakukan program CSR. Terperangkap dengan tujuan branding, program yang dilakukan perusahaan tidak melakukan stakeholders mapping terlebih dulu untuk memetakan apa sesungguhnya yang dibutuhkan masyarakat, dan apa kapital yang mereka miliki sehingga bisa berkolaborasi dengan perusahaan. Itulah sebabnya, terminologi community development sebagai bagian dari CSR dirasa kurang tepat lagi lantaran sifat satu arah (top-down) lebih terasa, community yang di-develop. Di mancanegara, terminologi ini diganti dengan community involvement (ada unsur keterlibatan komunitas sejak awal) atau convening stakeholders network (perusahaan membangun jejaring multistakeholder untuk mengatasi persoalan bersama-sama).
Dalam kapitalisme kreatif, CSR dan PKBL jelas tetap diperlukan. Begitu pula dengan seluruh kapital dari elemen masyarakat dan institusi pendidikan. Oh ya, perusahaan pun tak mesti terjebak harus mengguyur uang. Modal lainnya, yakni jejaring, pengetahuan dan teknologi, bisa dimainkan. Sementara pemerintah, dengan power yang dimilikinya, bisa menciptakan regulasi agar seluruh sumber daya yang tengah diputar elemen lain bisa berjalan. Yang jelas, yang ideal adalah terjadi kolaborasi yang menguatkan satu sama lain. Pemerintah, kalangan bisnis, masyarakat dan institusi pendidikan bergandengan tangan untuk membuat program-program kreatif.
Sejauh ini setidaknya ada 7 jalan yang bisa ditempuh untuk memaksimalkan kapital yang ada, yakni penyediaan infrastruktur, pelibatan stakeholders dalam rantai pasokan, pendidikan, kesehatan gratis, fasilitas kredit untuk UKM gurem, pola inti-plasma, dan modal ventura. Ke-7 jalan ini tak hanya dilakukan pemerintah (pusat dan daerah), tapi juga perusahaan hingga individu dengan kapital yang dimiliki masing-masing.
Salah satu contoh yang bisa diangkat adalah bagaimana Unilever bekerja sama dengan petani untuk memasok kedelai hitam buat produksi kecapnya. Belakangan, bersama Universitas Gadjah Mada, Unilever melahirkan Malika, bibit kedelai hitam unggul. Inilah kapitalisme kreatif tiga elemen: perusahaan, masyarakat dan institusi pendidikan. Pemerintah daerah pun bisa melakukan seperti yang dilakukan Pemkot Solo yang ingin mengangkat kemakmuran para pedagang kaki lima dengan membuat kawasan PKL, kantong-kantong PKL, shelter, gerobak dan tenda, yang semuanya diberikan secara gratis. Dengan kapitalnya, Pemkot Solo mengeluarkan Rp 9,6 miliar dari APBD 2006 untuk pemindahan PKL Banjarsari ke Semanggi.
Semua elemen pasti memiliki kapital untuk diputar secara kreatif, dan tidak hanya seperti 7 bentuk di atas. Di kalangan perusahaan, sekalipun dikritik terlalu bermuatan promosi, beberapa telah berupaya membenahi program CSR atau PKBL-nya agar semakin kreatif, tidak semata memberi ikan.
Di Telkom, Dodi M. Gozali, AVP Hubungan Eksternal & Komunitas PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., menjelaskan bahwa tim community development Telkom melakukan proses evaluasi bagi proposal yang masuk, dan kalau sifatnya erat dengan strategi bisnis Telkom, yang akan dicari adalah yang punya kaitan dengan bisnis inti Telkom. Salah satu yang ditempuh adalah membangun convening stakeholders network dengan Indigo, wadah komunitas yang dibentuk oleh Telkom untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif di Indonesia.
Di Bank Mandiri, program utama yang menjadi tema CSR-nya adalah Wirausaha Muda Mandiri yang bertujuan mengajak dan mengubah generasi muda menjadi generasi pencipta lapangan kerja, bukan pencari kerja. Dengan kapital yang dimilikinya (finansial, pengetahuan dan jejaring), Mandiri membantu dalam hal pembiayaan, pemasaran, coaching dan pendampingan. ”Sehingga mereka dapat menjadi pengusaha yang tangguh dan ulet hingga akhirnya dapat mengakses perbankan secara komersial,” ungkap Sukoriyanto Saputro, Sekretaris Korporat PT Bank Mandiri Tbk.
Menyentuh kalangan UKM juga dilakukan PT Wijaya Karya Tbk. Menurut Dirham Su'udi, Manajer PKBL Wika, sejak awal 2008 perusahaannya berupaya mengelola dana PKBL-nya yang sebesar Rp 3-5 miliar per tahun secara sistematis dan terorganisasi agar tujuan program tepat sasaran. Sebelumnya, berbuat baik pada lingkungan sekitar masih bersifat insidentil dan momental seperti donasi korban bencana alam. Kini, untuk program kemitraan yang mengambil 40% dari dana PKBL, Wika bergerak membantu permodalan para UKM atau mikro yang berasal dari berbagai sektor industri yang berada di sekitar lingkungan kantor pusat, kantor-kantor cabang, atau proyek Wika. Bantuannya pun, menurut Dirham, masih berupa bantuan permodalan dengan jumlah minimal modal yang bisa diberikan Rp 5 juta. Untuk memantau kredit yang digulirkan, Wika menggunakan mekanisme pembukuan dengan jadwal penagihan yang teratur.
Di tempat lain, tak ingin dinilai hanya melakukan karitas, PT Aneka Tambang Tbk. menggelar program kemitraan dengan warga yang telah memiliki usaha dan memang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya. Jumlah mitra binaan Antam saat ini mencapai 2.583 orang di seluruh daerah operasional di Indonesia. Tim Antam aktif memonitor mitranya untuk melihat secara langsung sejauh mana kemajuan mereka. “Kami berkunjung dan melihat apakah omset dan aset mereka bertambah atau tidak. Jika ternyata tidak ada kemajuan, mitra tersebut akan kami panggil dan kami berikan pelatihan atau kursus untuk mereka,” kata Denny Maulasa, Direktur Umum dan CSR Antam. Indikator kesuksesan program ini adalah PK rate, jumlah dana yang dapat dikembalikan dibanding yang disalurkan. Semakin tinggi PK rate artinya semakin banyak mitra yang bisnisnya berkembang. “PK rate kami saat ini cukup tinggi, yaitu 66,97%,” ujar Denny.
Tak hanya perusahaan. Kalangan society maupun individu pun bisa berpartisipasi dalam kapitalisme kreatif, baik dengan finansial maupun modal jejaring yang dimilikinya.
Setelah sukses dengan PT Sarana Jabar Ventura yang sudah tersebar dari Aceh hingga Papua untuk mendukung lahirnya para wirausaha (300 UKM telah dibantu), Arifin Panigoro terus meluaskan perputaran kapitalisme kreatifnya. Bersama tim Medco Foundation, dia menyebarluaskan micro financing services yang mengadopsi Grameen Bank. Tak kurang dari 2.000 mitra usaha kecil yang tersebar di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah telah digarap. Lalu, dia kini juga menggelar program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). Ini adalah upaya menjadikan Merauke sebagai tempat pengembangan pertanian terpadu. Dengan seluruh kapitalnya, Arifin mengerahkan tim Medco Foundation membangun Medco Research Center for MIFEE.
Seperti saat membangun modal ventura, dalam MIFEE, Arifin juga aktif berkolaborasi dengan elemen lain, pemerintah. Pemerintah Kabupaten Merauke menyediakan lahan seluas 20 hektare di kawasan Sirapu untuk menanam sorghum, kedelai, jagung dan tebu. “Hasilnya menggembirakan pada jagung dan sorghum,” katanya tentang proyek yang baru mulai tahun lalu itu.
Bukan hanya kaliber konglomerat yang bisa melakukan kapitalisme kreatif. Asep Sulaiman Sabanda, Presiden Direktur Grup Sabanda, adalah contoh kapitalis kreatif. Lewat pola kemitraan inti-plasma, muncul bisnis peternakan ayam potong dengan produksi 1,1 juta ekor per bulan, hasil kolaborasi 600 peternak binaan. ”Saya tidak pernah berpikir untuk mengeksploitasi mereka. Yang dipikirkan bagaimana peternak bisa continous. Jika membuat mereka berkembang, bisnis saya juga berkembang,” ujar pria 31 tahun ini.
Asep Sulaiman tengah menyiapkan pola kemitraan untuk budi daya sapi. Ini bermula ketika dia melihat banyak problem ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerahnya, Subang. Banyak orang menawarkan sapi untuk dijual guna memenuhi kebutuhan sekolah atau lainnya. Menurutnya, jika terus dibiarkan, aset-aset ini akan berpindah terus ke tangan orang kaya. ”Kalau saya berpikiran kapitalisme sempit, saya beli saja dengan harga murah ketika mereka butuh,” katanya.
Lain Asep, lain pula Harry Darsono, sang desainer andal. Lewat Yayasan Hamien dan Yayasan Sakatukin yang berdiri pada 1970-an, dia mengelola 4.616 anak-anak putus sekolah, membiayai mereka kembali ke sekolah dan memberi pelatihan kerja. “Kalau dibandingkan dengan yayasan milik Sampoerna Grup, saya sih nothing. Tapi buat saya, yang penting efektivitasnya dan tanpa pandang bulu,” katanya. Dia bersyukur didukung teman-teman yang punya komitmen. Dan lewat modal jejaring sosial yang dimilikinya, dia mendapat dukungan sejumlah kedutaan besar asing untuk kegiatan yayasannya.
Sementara itu, setelah merasa tak cukup hanya dengan mendonasikan dana ke Yayasan Abhimata, Samuel Mulia aktif di yayasan yang menampung anak-anak yang dibuang orang tuanya, mayoritas karena hubungan gelap. “Saya turun sendiri ke lapangan untuk tahu bagaimana kondisi bayi yang dibuang. Setelah itu, saya tak mau hanya menyumbang uang. Saya ingin memberi lebih,” tutur pengisi kolom Parodi di Kompas Minggu itu. Dan tak puas dengan aktivitasnya sekarang, dia berencana mendirikan yayasan yang berkonsentrasi pada pendidikan, membuat sekolah yang menampung kurikulum life skill.
Yang terhitung mendapat manfaat dari modal jejaring yang dimilikinya adalah Dik Doank, pendiri Sekolah Alam & Seniman Kandank Jurank Doank. Saat ini pemilik nama lengkap Rizki Mulyana Hayang Denda Kusuma itu memiliki sekitar 2500 siswa. Dia dibantu 8 karyawan dan 70 relawan. Untuk relawan ini, diakui pria kelahiran 21 September 1968 ini, tak sedikit yang berasal dari kaum berada, satu di antaranya adalah pemilik pabrik minuman. Mereka tertarik menyumbangkan kapital yang mereka miliki bersama Dik. Dan Dik sendiri tak mau berhenti memutar kapitalnya secara kreatif. Dia ingin mengembangkan sekolahnya lebih besar. Dia mempunyai tanah 5 ha di daerah Rumpin, Bogor, yang nantinya menjadi tempat pengembangan sekolah alamnya. “Saya punya mimpi membangun tempat pendidikan bagi orang-orang sakit jiwa. Di situ mereka kami didik.”
Memutar kapital secara kreatif tak mesti mengucurkan dana dari kantong sendiri. Dengan modal jejaring sosialnya, kalangan anggota masyarakat bisa berbuat banyak. Dalam konteks ini, dari kalangan society yang terbilang sukses adalah Dompet Dhuafa (DD). Lembaga ini kini terbilang lengkap dalam program-program mengangkat derajat masyarakat yang kurang beruntung dan menjadikan mereka lebih mandiri. Program yang menonjol, di antaranya, Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), dengan mendirikan klinik 24 jam yang layanannya tak kalah dari rumah sakit. Tercatat tak kurang dari 150 ribu pasien yang berasal dari warga miskin berobat ke LKC yang merupakan program pendayagunaan dana zakat.
DD juga memiliki Lembaga Pengembangan Insani (LPI). Jejaring yang khusus menangani bidang pendidikan ini punya tiga program utama: Makmal (program pelatihan guru), SMART Ekselensia Indonesia (sekolah menengah bebas biaya), dan Beastudi Etos (beasiswa untuk mahasiswa). Aktivitas LPI menyebar di beberapa kota di Tanah Air. SMART adalah model sekolah unggulan bebas biaya dan berasrama. Muridnya berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. “Tahun ini adalah tahun kelulusan pertama,” kata Ismail A. Said, Presdir DD.
Ada juga program Masyarakat Mandiri. Program yang dimulai pada tahun 2000 ini dimaksudkan memutus lingkaran kemiskinan di kantong-kantongnya. Lalu, di ranah micro-finance, ada BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Center. Kegiatannya meliputi advokasi, konsultasi, jasa audit syariah, pelatihan, pooling fund dan penempatan dana. Dana yang berhasil dihimpun DD dari 1993 sampai 31 Agustus 2008 mencapai Rp 334,2 miliar. Belakangan, semakin banyak perusahaan besar yang memercayakan sebagian dana CSR-nya pada DD, antara lain Exxon.
Kini, kesuksesan DD bukan cuma dilirik perusahaan. Lembaga pangan PBB sedang meminang DD untuk menjadi mitra di Indonesia. Harvard University pun sudah menjalin komunikasi via e-mail, untuk melakukan studi kasus, karena mereka menilai banyak program DD yang berhasil.
Potensi untuk melakukan kapitalisme kreatif memang besar. Terlebih bila itu dilakukan serempak oleh empat elemen di atas. Repotnya, Timotheus menegaskan, fakta di lapangan sering menunjukkan setiap elemen sering jalan sendiri-sendiri. Terutama, di kalangan dunia usaha. “Tidak ada kebersamaan. Masing-masing memiliki tujuan, program dan agenda sendiri,” katanya. Di sini dia menilai perlunya sebuah koordinasi besar di tangan pemimpin yang kredibel untuk menggerakkan kapital-kapital yang terserak itu.
“Yang menjadi pertanyaan adalah ada atau tidak orang yang bersih dan memiliki leadership serta memiliki back-up sumber daya yang cukup,” ujar Sonny S. Sukada, partner di Kiroyan Partners yang menspesialisasi diri pada CSR. Dia menilai langkah rasional yang bisa dilakukan adalah elemen-elemen dalam satu daerah berkoordinasi dan membuat agenda bersama. Terutama, dari kalangan bisnis. Alasannya, mirip yang diutarakan Gates, perusahaan memiliki segala kelebihan dan kekayaan sumber daya (people, innovation, traction, money dan execution) yang lebih banyak ketimbang elemen lainnya. Pendek kata, perusahaan bisa menjadi engine of growth ketimbang yang lain.
Pada titik ini, memang benar bahwa perusahaan memiliki kapital yang lebih banyak dan beragam ketimbang elemen lainnya. Justru karena itulah, sangat disayangkan bila kekuatan itu hanya jadi alat promosi semata tanpa desain besar turut membantu target MDGs. Akan tetapi, seperti diuraikan di atas, dengan kapital masing-masing, seluruh elemen sejatinya bisa berkontribusi dalam kapasitas berikut kapabilitasnya. Dan kontribusi akan maksimal bila empat kaki kapitalisme kreatif ini saling bergandengan tangan, lalu secara kreatif membuat program yang membawa kemaslahatan bersama.
Inilah kapitalisme kreatif yang dibutuhkan. Dan yakinlah, bila diterapkan dengan serius, gagasan ini bukan fashion atau kegenitan sebuah konsep belaka.




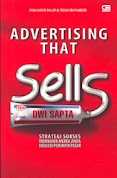
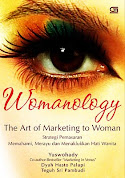












0 comments:
Post a Comment