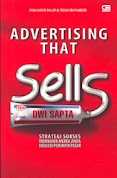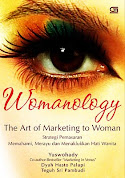Menyadari pentingnya WOMM, perusahaan-perusahaan kelas dunia terus mengupayakannya dalam beragam gaya. Bahkan, menjadikannya nyawa operasional sehari-hari.
Teguh S. Pambudi
“It doesn't matter whether you're selling real estate, jelly, or jet engines. People will ask other people about you before they decide to buy from you. We turn to people we trust first -- friends, family, coworkers, and other people like us -- when starting to look for something to buy. Not ads, not brochures, not phone books.”
Itulah petikan dari buku Word of Mouth Marketing karya Andy Sernovitz (2006). Dan di abad ke-21, hal tersebut sangatlah sahih. Alhasil, “Apa yang dikatakan orang tentang merek Anda” merupakan intangible asset yang sangat berharga, dan terbilang sulit menilainya. Ini tak ubahnya aset sejenis seperti yang diutarakan Kaplan dan Norton yakni customer relationships, operating processes, skills, knowledge of the workforce, dan merek itu sendiri.
Sebuah studi yang dilakukan Northeastern University bahkan menguatkan fakta di atas. Studi itu menemukan kenyataan bahwa lebih dari 15% percakapan manusia ternyata membuat referensi tentang perusahaan, merek, produk atau jasa. Demikian Walter J. Carl dalam makalahnya, “What’s All the Buzz About? Everyday Communication and Relational Basis of Word-of-Mouth and Buzz Marketing Practices” (2006).
Karena itulah, banyak perusahaan yang berupaya melakukan word of mouth marketing (WOMM) secerdas mungkin, termasuk memanfaatkan dinamika yang kini berkembang seperti tren media sosial. Dikatakan secerdas mungkin karena dalam mengupayakan WOMM, sesungguhnya kreativitaslah yang menentukan. Sebab, praktik WOMM terdiri atas seperangkat teknik yang terus dikembangkan oleh perusahaan dalam segmen industri yang sangat beragam. Lantaran itu pula, sangatlah sulit mengukur dampak satu aktivitas WOMM. Dalam WOMMA Terminology Framework (2005) disebutkan “Until now, there has been no common language or methodology available for discussing, measuring, or comparing the impact of various word of mouth marketing efforts.”
Di kalangan penggiat WOMM di mancanegara, terutama dari lingkungan akademisi, upaya mencari pengukuran yang sahih hingga kini terus dilakukan. Sejumlah model lahir, antara lain model Tobit dan model ZIP yang menghubung-hubungkan sejumlah variabel yang diasumsikan akan membuat orang mereferensikan produk atau merek tertentu kepada pihak lain. Jadi, jangankan sebuah indeks WOMM, model pengukurannya pun terus berkembang. Sesuatu yang bisa dimaklumi lantaran pihak yang diukur, yakni perusahaan, memang terus mengembangkan teknik-teknik praktik WOMM-nya.
Ya, perkara WOMM sebagai “seperangkat teknis yang terus berkembang” – lebih tepatnya dikembangkan oleh perusahaan dalam pelbagai industri – ini memang benar adanya. Perusahaan tak henti mengembangkan teknik-teknik baru karena tidak bisa menyandarkan diri pada WOMM tipe organic, melainkan lebih kepada tipe amplified.
Tipe organik adalah WOMM yang terjadi secara natural ketika orang dengan sukarela dan penuh antusiasme menjadi advocator lantaran senang dengan produk yang digunakannya. Adapun tipe amplified terjadi secara by design. Pemasar meluncurkan aneka strategi untuk menciptakan sekaligus mempercepat WOMM di komunitas yang disasarnya. Sementara medianya bisa melalui jalur online maupun offline.
Dalam konteks WOMM tipe amplified, cara atau aktivitas yang lazim dilakukan perusahaan di antaranya membuat blog sekaligus berinteraksi dengan blogger, menggelar customer reference program termasuk program VIP, menciptakan fans club/komunitas loyal, kampanye viral, dan program evangelis. Itu hanya beberapa contoh, masih banyak lagi jenis teknik yang dikembangkan, yang sangat dinamis serta inovatif.
Yang pasti, menyadari pentingnya WOMM tipe amplified, perusahaan-perusahaan kelas dunia berupaya mengerahkan segala cara untuk bisa melakukannya dengan efisien, tepat dan sesuai dengan harapan. Konteks tepat serta sesuai dengan harapan di sini artinya membuat pelanggan membicarakan (do the talking), mempromosikan (do the promotion) dan menjual (do the selling). Dan yang pasti, hal mendasar tidak boleh dilupakan: kualitas produk/jasa itu sendiri mesti excellent.
Salah satu contoh perusahaan kaliber dunia yang dipuji Sernovitz dalam menggelar WOMM adalah Microsoft lewat program Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Ini merupakan penghargaan bagi orang-orang di seluruh dunia yang dipandang telah menyumbangkan keahlian teknisnya untuk masyarakat dengan menggunakan produk atau teknologi milik Microsoft.
Langkah-langkah yang dilakukan Microsoft untuk mencari para MVP terbilang sederhana tapi sistematis. Pertama, find the talkers. Microsoft menelusuri message boards, blog, komunitas, untuk menemukan the most engaged and credible talkers. Mereka mencari orang-orang yang piawai dalam hal software dan senang menolong sesama.
Kedua, surprise them. Para MVP mendapat surat pemberitahuan bahwa mereka telah diseleksi. Mereka juga memperoleh kotak hadiah kejutan seperti tas komputer. Hadiah ini kelak jadi legendaris karena seputar isinya menjadi bahan terkaan dan spekulasi.
Ketiga, make them feel special. MVP mendapat surat dari Microsoft yang harus dikirim ke tiga alamat: bosnya, pasangannya dan tempat kuliahnya. Keempat, engage them. Para MVP mendapat kesempatan melihat langsung dan berbicara dengan para pengembang sekaligus memperoleh informasi di belakang layar tentang produk Microsoft yang mereka gunakan. Microsoft menyediakan lebih dari 500 live web meetings, chats dan webcasts setiap tahun untuk para MVP.
Kelima, have fun. Pertemuan tahunan MVP Summit di Redmond, AS, menjadi acara yang wajib dikunjungi para MVP. Microsoft menyediakan dan membayar semuanya. Para MVP akan bertemu dengan pemenang tahun-tahun sebelumnya sekaligus dengan para pengembang produk-produk Microsoft. Di sini, dua “dewa” Microsoft, Bill Gates atau Steve Ballmer, akan tampil.
Acara ini sepertinya sederhana, tapi bagi Microsoft sangat berguna karena progam MVP menjadi ajang yang disebut para penggiat WOMM sebagai energizing talkers. Para MVP seperti disuntik energi yang luar biasa dengan pengalaman yang tidak didapat setiap orang. Mereka menjadi advokator paling depan dalam urusan mempromosikan dan menggunakan produk-produk Microsoft.
Experience. Itulah yang ditawarkan Microsoft. Hal yang serupa juga ditempuh Zara, salah satu merek yang kenaikan brand value-nya tertinggi dibanding merek lain pada Interbrand Best Brand Global 2008. Posisi Zara memang peringkat 62 dari 100 merek. Kendati demikian, brand value-nya naik 15%.
Selain kustomisasi yang tinggi dengan tingkat produktivitas yang mengagumkan, kunci sukses Zara hingga bisa meraih prestasi seperti itu adalah kemampuannya dalam strategi WOMM. Tak bertumpu pada iklan-iklan konvensional, Zara menawarkan customer experience yang membuat para pelanggannya menjadi advokator.
Customer experience ini dimulai dari di toko-toko Zara yang eksklusif. Semua toko Zara yang jumlahnya mencapai 500 di 70 negara – termasuk Indonesia – menerima model pakaian baru sekitar dua kali dalam sepekan. Kondisi ini membuat para pelanggan datang secara reguler guna mengecek koleksi terbaru dengan hukum reservasi yang absolut: siapa cepat, dia dapat. Dan pelanggan bisa memberikan umpan balik yang akan diterima oleh para desainer Zara, termasuk usulan-usulan mode. Pengalaman menyenangkan inilah yang mendorong pelanggan membicarakan, mempromosikan dan menjual Zara ke komunitasnya, sekaligus menjadikan merek dari Spanyol ini terus menjadi brand papan atas dunia.
Apa yang dilakukan Microsoft atau Zara bisa dikatakan belumlah memanfaatkan media sosial yang kini tumbuh berkembang. Sekarang, banyak perusahaan yang berupaya menggunakan media sosial sebaik-baiknya, di antaranya blog atau website, dalam menggelar WOMM.
Epson, umpamanya, lewat Epson & Sparkplugging. Sparkplugging adalah kumpulan 14 blogger. Epson mendanai mereka, para penulis, yang ingin pergi ke pertemuan BlogWorld Expo di AS. Lewat jejaring sosial yang mulai menyaingi Facebook, yakni Twitter, para penulis itu kemudian membuat sebuah game dengan hadiah printer Epson yang akan diluncurkan. Mereka ini juga membuat blog baru yang khusus meliput pelaksanaan BlogWorld. Di dalam situs tersebut terdapat wawancara, foto dan informasi seputar pertemuan akbar itu dengan menampilkan logo-logo Epson. Dalam blog tersebut, pembicaraan tentang Epson mengalir deras.
Apa yang dipraktikkan Epson merupakan pengejawantahan dari saran Sernovitz tentang bagaimana memanfaatkan media sosial yang kini kian berkembang dalam melakukan WOMM. Setidaknya ada lima saran yang bisa dilakukan: pertama, look on the web for people talking about you. Kedua, assign someone to join these conversations. Start today. Ketiga, create a blog. Keempat, make a new rule: Ask "Is this buzzworthy?" in every meeting. Dan kelima, come up with one buzzworthy topic. Keep it simple.
Buatlah tetap sederhana. Di tempat lain, prinsip ini dipraktikkan Nivea dengan gayanya sendiri. Pada malam tahun baru lalu, lewat acara "Kiss and Be Kissed" di New York Times Square, Nivea memberikan 25 ribu sampel lini produk Lip Care yang mengandung minyak jojoba dan Shea butter kepada pasangan-pasangan yang hadir. Nivea memberi kesempatan kepada pasangan yang saling berciuman di malam pergantian tahun untuk mengunggah foto-fotonya ke http://www.niveaxoxo.com/ buat memenangi kompetisi yang hadiahnya bertemu dengan Lionel Richie.
Lewat program ini Nivea ingin membuat konsumennya merasakan emotional attachment ketika bibir-bibir mereka yang telah dibasahi Nivea Lip Care saling berpagut. Nivea ingin konsumennya merasakan itu ketimbang melihat produknya sebatas functional product. Dia ingin menciptakan hal-hal penting: hasrat dan pembicaraan (buzz) di kalangan para penggunanya. Agar makin hot, Nivea juga mensponsori situs selebriti Yahoo!'s yakni OMG!, menampilkan foto para selebriti yang saling berciuman. "We like to do things in a way that is not pretentious, but is still surprising to the consumer," ujar Nicolas Maurer, SVP Pemasaran Nivea dan Eucerin, Beiersdorf.
Saking pentingnya WOMM, perusahaan seperti Zappos malah menjadikannya “nyawa” operasionalnya sehari-hari. Berdiri pada 1999, Zappos nyaris tidak punya prestasi apa-apa dalam rapor penjualan di awal-awal tahun berdirinya. Namun pada 2007 penjualannya lebih dari US$ 800 juta dan ditaksir menembus US$ 1 miliar pada 2008.
Kunci sukses perusahaan yang kini disebut the world’s biggest online shoe store ini adalah keahliannya dalam WOMM. Dari sekitar 1.400 karyawannya, ada sedikitnya 440 orang yang aktif di Twitter untuk terus membincangkan perusahaan dan terus keep in touch dengan pelanggan. Cara ini ditempuh karena manajemen Zappos sadar bahwa bisnis online shoes bersandar pada kepercayaan pelanggan atas perusahaan yang menjualnya. Karena itulah, manajemen harus membuat karyawannya enganged dengan para pembeli dan rajin-rajin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan.
Dengan stok lebih dari 3 juta sepatu, tas tangan, pakaian dan aksesori dari sedikitnya 1.100 merek, Zappos harus bisa menjual terus-menerus agar inventorinya terjaga. Dan lewat layanan yang memuaskan, pelanggan terus berdatangan. Tingkat repeat customer bahkan mencapai 60%. Mereka yang datang kembali ini lalu terus menyuarakan kepuasannya dan merekomendasikan kepada orang lain lewat aneka media, termasuk lewat blog dan Twitter. Seperti virus, kepuasan ini kian menyebar, mengundang datangnya pelanggan-pelanggan baru.
Apa yang ditempuh perusahaan-perusahaan di atas jelas suatu hal yang bisa ditiru dengan kreativitas dan inovasi sendiri. Yang jelas, apa pun cara yang dipilih, buatlah agar konsumen melakukan apa yang diutarakan Sumardy dari Octobrand: TAPS (talking, promoting dan selling).
Dulu, kata Walter J. Carl, “Talk is cheap”. Sekarang, itu tidak lagi. Sebab, dari omongan biasa, akan lahir buzz yang berefek besar bagi bisnis. Ya, talk is not cheap anymore.
Monday, April 13, 2009
Thursday, April 9, 2009
CEO versi 3.0.
Perubahan di lingkup domestik serta global memunculkan persoalan besar bagi para pemimpin bisnis. Karakter dan kemampuan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasinya?
Teguh S. Pambudi
Dalam 6 bulan terakhir, isu seputar kepemimpinan bisnis kian marak dikupas majalah maupun jurnal manajemen. Terpentalnya beberapa CEO top macam Charles O. Prince di Citigroup dan ancaman dipenjarakannya para pemimpin bisnis yang dipandang telah melakukan fraud, menjadi santapan media. Jauh sebelum Lehmann Brothers tutup usia, Harvard Business Review edisi Januari 2008, bahkan khusus mengangkat topik leadership. Rupanya, kekisruhan krisis kredit perumahan di AS yang membawa tsunami finansial sedikit banyak memunculkan kembali trauma atas skandal-skandal korporasi era Enron. Dan ujung pertanyaan dari masalah ini, siapa lagi kalau bukan para pemimpin bisnis; mengapa ini sampai terjadi? Apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin?
Dalam tulisannya di New York Times (11 November 2007), Nelson D. Schwartz melempar wacana menarik. Mengutip guru besar tentang leadership di School of Management at Yale, Jeffrey A. Sonnenfeld, kini dunia korporasi (khususnya di AS) memerlukan apa yang disebut CEO versi 3.0. Versi 1.0. adalah mereka yang fokus pada mega-merger serta manajemen finansial untuk memuaskan Wall Street dan rasa lapar para investor. Mereka adalah para empire builder. Berlangsung 1950-1990-an, fase yang terpaku pada pemuasan bottom line ini segera berakhir begitu Enron meledak. Lahirlah era CEO versi 2.0., para pemimpin berjenis cleanup artist yang tugasnya membereskan masalah. Mereka disebut juga kaum Fix-it Man. Sayang, mereka yang berkiprah di awal 2000-an ini pun banyak yang tidak sukses. Terbukti lahir skandal subprime mortgage yang hingga kini menimbulkan kerugian besar; lebih dari US$ 400 miliar.
Dari sinilah dibutuhkan CEO Versi 3.0. Mereka adalah para pemimpin yang bukan hanya fokus pada bottom line, tapi juga menyinergikan bisnis secara kelompok (tim). Mereka bervisi membangun kerajaan (empire builder), diiringi kerendahatian, dan mampu membangun tim yang kuat. Contohnya adalah CEO-nya P&G, AG Lafley serta Anne Mulcahy di Xerox. Disiplin individu yang mereka kembangkan bukan hanya teknikal seperti keuangan atau pemasaran, tapi lebih mengarah pada team oriented approach. Dan perusahaan yang mereka pimpin terbukti tangguh menghadapi krisis yang kini terjadi akibat subprime mortgage.
Pemikiran Sonnenfeld boleh jadi terlalu menyederhanakan, kendati ada hal-hal yang masuk akal, seperti fakta betapa menghambanya para pemimpin bisnis pada kalangan investor, terutama di tahun-tahun 1980-an ketika falsafah “greedy is good” menjadi “agama”. Lantas, bagaimana dengan wacana kepemimpinan bisnis di Indonesia? Apakah kita juga membutuhkan CEO versi 3.0.?
Sebelum menjawab hal tersebut, ada baiknya diketahui apa saja isu yang mengelilingi para pemimpin bisnis kita. Sebab, dari sini bisa ditarik garis bagaimana sesungguhnya dinamika bisnis yang sedang berlangsung, beserta lanskap yang menjadi arena permainannya. Untuk mencari tahu apa persoalan para pemimpin bisnis di Tanah Air, beberapa waktu lalu SWA melakukan survei pada 46 CEO, dengan pola jawaban terbuka dan bersifat multiple answers. Hasilnya?
Managing change, sustaining business growth, dan develop leader. Itulah 3 besar (berturut-turut) isu seputar leadership yang dihadapi para pemimpin bisnis kita. Perubahan yang makin sulit diprediksi serta dikelola, menjadi permasalah besar mereka (67,39%). Ini sesuatu yang wajar. Sekedar menyebutkan beberapa contoh, cobalah tengok ke panggung internasional. Krisis serta fluktuasi harga minyak, membuat lanskap bisnis kian tak ramah lagi. Tak heran, perkara ini akhirnya membuat mereka juga merasa bahwa mempertahankan pertumbuhan bisnis kian tak mudah, meski optimisme harus dipelihara (56,52%).
Yang menarik, urusan develop leader cukup mendapat porsi yang besar (56,52%). Ini sebuah sinyal positif sebagai jawaban terhadap isu bahwa stok leader kita terbatas, alias yang itu-itu saja. Artinya, bagi para responden, menjadi pemimpin hebat tidaklah cukup. Sanggup melahirkan para pemimpin selanjutnya, itu baru disebut hebat. Pemimpin-pemimpin baru ini tidak saja dalam konteks untuk berekspansi bisnis -- yang nota bene memerlukan orang-orang yang akan mengendalikan percepatan usaha --, tapi juga dalam regenerasi serta kelangsungan perusahaan.
Urusan yang satu ini, bukan perkara main-main. Garuda Food, misalnya, kini tengah serius menggojlok program creating business leader. Hingga 3-5 tahun ke depan, kelompok usaha di sektor makanan-minuman ini membutuhkan sedikitnya 400 orang pemimpin bisnis untuk mengelola akselerasi usahanya. Hal yang sama juga terjadi di Pertamina. Perusahaan itu mencanangkan bisa mencetak 200 business leader guna mengelola laju ekspansi di tengah gempuran para pesaing. Apakah target itu tercapai atau tidak, itu perkara lain. Yang pasti, urusan mencetak para pemimpin baru sangat mendesak.
Perkara mencetak leader memang hal penting. Steven Wheeler, Walter McFarland, dan Art Kleiner di Strategic+Business, 10 Januari 2008 menggugah para CEO untuk membangun kepemimpinan strategis, yakni “build an organization in which executives will flourish”. Menumbuhkan para eksekutif dari dalam adalah tugas yang makin krusial. Bahkan, bagi Robby Djohan, orang yang telah menelurkan sejumlah pemimpin bisnis di negeri ini, mencetak leader merupakan tugas yang tak bisa ditawar. “Sering kawan-kawan dalam pertemuan berkata pada saya, 'CEO saya pergi nih. Saya butuh CEO baru. Menurut kamu, saya harus bagaimana?' Di mata saya, itu a stupid question! Mengapa? Yang saya katakan adalah mengapa kamu tidak melihat portofolio manusia yang ada di dalam organisasimu untuk dilihat mana yang berpotensi menjadi CEO, dan pikirkan langkah yang tepat dan terbaik untuk menjadikan calon itu siap menjadi pemimpin.”
Adapun cara melahirkan pemimpin itu sendiri, Riri Satria, Consulting Director People Performance Consulting, melihatnya bisa dilakukan dalam 2 jalur; berdasarkan sistem, atau tidak berdasarkan sistem (sentuhan individu). Jalur pertama ditandai adanya kebijakan tertulis yang mengatur pengembangan kompetensi dengan memberikan peluang yang sama kepada karyawan. Adapun jalan yang kedua sifatnya lebih kepada personal touch. Para pimpinan sudah membidik orang-orang tertentu untuk menjadi kader dengan memberi kesempatan dan tantangan yang lebih banyak. ”Pendekatan yang ideal dan banyak dilakukan adalah kombinasi dari kedua pendekatan di atas,” katanya.
Kembali pada wacana CEO versi 3.0. Secara sederhana, sesungguhnya lanskap bisnis di Tanah Air juga bisa diklasifisikan dengan periode tertentu, dengan meminjam pandangan Sonnenfeld. Pertama, pra-1997. Ditandai -- terutama -- dengan deregulasi perbankan 1988, sedikit banyak para CEO di Indonesia juga menjadi empire builder. Sebutlah ini versi 1.0. Tandanya; semua berlomba berekspansi demi kebesaran kelompok usahanya sampai akhirnya krisis moneter 1997 menyapu bangunan yang ada, sekaligus mengantar pada era ke-2; pembenahan. Mulai 1998, dunia usaha melakukan restrukturisasi utang dan skala usaha, yang membuat para CEO menjadi kaum fix-it man yang sibuk membenahi sekaligus mengonsolidasi diri. Inilah versi 2.0. Dan dibubarkannya BPPN beserta sejumlah inisiatif macam Prakarsa Jakarta, semestinya menjadi tanda bahwa para CEO memasuki fase ke tiga; era stabilisasi dan pertumbuhan.
Tahun 2008 adalah satu dasawarsa setelah krisis menerpa. Dan kini, 2009, ancaman krisis kembali datang. Bicara lanskap bisnis, sungguh banyak perubahan yang semestinya membuat para CEO kita juga masuk pada fase atau menjadi versi tersendiri (3.0.). Di lingkup domestik, ranah ekonomi tak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi, otonomi daerah dan tekanan stakeholders yang lebih kuat, mulai dari good corporate governance hingga corporate social responsibility. Ini berjalan seiring persaingan yang lebih ketat karena kompetisi berjalan tanpa bayangan monopoli. Sementara itu, di lingkup internasional, persoalan menjadi lebih rumit karena mengglobalnya perekonomian diikuti pelebaran kutub-kutub pertumbuhan di sejumlah belahan dunia, khususnya Asia. Ini ditandai dengan kebangkitan Cina dan India, yang segera akan diikuti pemain dari negara lain, mulai dari Uni Emirates Arab, Qatar, Vietnam, dan bersiap-siaplah menyambutnya; Kamboja. Mereka menambah daftar pesaing yang sebelumnya telah mapan menunggangi globalisasi.
Kalau begitu, bagaimana karakter serta kemampuan versi 3.0. yang dibutuhkan CEO kita untuk melakukan stabilisasi dan menggenjot pertumbuhan?
Dari persoalan yang ada, tampaknya CEO masih dituntut menjalankan hal-hal yang kerap disebut basic task; konsolidasi bisnis dan biaya, reorganisasi, serta menjalankan prioritas strategis. Adapun nilai yang dikembangkan sering disebut sebagai classic leadership values, seperti disiplin. fokus, dan eksekusi. Akan tetapi, itu saja tampaknya tidak memadai.
Dalam pandangan Harry Sasongko, Presdir & CEO GE Money Indonesia, mengglobalnya ekonomi menuntut pemimpin perusahaan bersikap sekaligus berpikiran terbuka. Dari sisi jabatan CEO itu sendiri, misalnya. Globalisasi membuat orang bergerak lintas negara dan perusahaan. Menurutnya, kalau tidak sigap serta mempunyai keahlian yang lebih unggul dari warganegara asing, CEO akan tersingkir. Dan bisnisnya juga otomatis akan tersingkir kalau dia tak pandai meniti setiap peluang yang ada.
Bersikap sekaligus berpikiran terbuka, atau openness. Selanjutnya, Tanri Abeng menambahkan bahwa di era sekarang yang kian menuntut kecepatan sekaligus ketepatan bertindak, CEO harus mampu bersikap adaptif. Artinya sanggup menyesuaikan diri dengan situasi serta kondisi ekstrim sekalipun. Bedanya dengan sikap fleksibel? Fleksibel hanyalah sebatas bersedia bertoleransi dengan ketidaknyamanan, tetapi belum tentu mau beradaptasi. “Pemimpin yang fleksibel belum tentu mampu beradaptasi. Tetapi pemimpin yang mampu beradaptasi, itu pasti punya sikap fleksibilitas tinggi. Sikap adaptif sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis,” tandas Komisarit Utama PT Telkom ini. Cuma itu?
Openness dan adaptif saja, rupanya tidaklah memadai. Bagi Nugroho Supangat, mantan Mitra Pengelola Dunamis Organization Services, CEO masa kini juga harus lebih mampu merangkul stakeholders, terutama di lingkungan internal. Para pemimpin harus bisa mengayomi SDM yang kini disebut knowledge worker di tengah tuntutan standar kerja yang tinggi. Adapun untuk lingkup eksternal, kompetisi global yang menjadi salah satu dari 10 persoalan CEO, harus dijawab dengan kemampuan negosiasi yang hebat. “Mereka harus memiliki negotiation level tidak hanya level nasional tapi minimal regional level. Jadi tidak hanya bisa buat lobby dan network di Indonesia saja. Karena keran globalisasi di Indonesia ini rupanya terbuka lebar,” ujarnya serius.
Menambahkan pendapat di atas, Andreas Budihardjo, Guru Besar Manajemen Organisasi & SDM Prasetiya Mulya menggarisbawahi perlunya CEO memiliki kemampuan lain. “Dia juga harus bisa mengelola paradoks,” ulasnya. Paradoks dalam konteks ini, menurutnya adalah mengatasi antara persaingan dan kolaborasi sekaligus. “Mungkin kita sama-sama pengusaha restoran. Kita bersaing. Tapi kita juga berkolaborasi, bersama-sama membesarkan bisnis ini,” tutur peraih gelar master Manajemen Organisasi di Universitas Groningen, Belanda itu penuh arti.
Buat TP Rahmat, sejatinya tidak ada tipe karakter tertentu yang dibutuhkan oleh pemimpin bisnis masa kini. Baginya, yang terpenting adalah ketegasan, keberanian dan integritas. Di atas itu semua, hal terpenting yang harus ada dalam diri seorang CEO adalah karakter kejujuran dan ketegasan. Apapun, kondisi dan situasinya. “Kalau 'gak jujur, keras dan tegas mah sekarang ini lewat sajalah,” ujar Teddy dengan logat Sunda yang cukup kental. “Seperti Pak Agus (Matowardojo) di Bank Mandiri. Kalau semua CEO BUMN kayak dia, wah, beres deh permasalahan,” tambah mantan CEO Astra yang pernah meraih predikat Best CEO dari SWA itu. Teddy terkesan dengan gaya Agus membenahi Bank Mandiri. “Contohnya pengumuman di media massa (tentang) para pengutang. Itu butuh keberanian,” ujarnya.
Bagi Teddy, keberanian selalu dibutuhkan pemimpin dalam situasi serta kondisi apapun. Karena itulah, di luar tantangan eksternal dan internal organisasi, persoalan terbesar bagi CEO, justru datang dari dalam dirinya sendiri. “CEO juga manusia. Punya anak istri, butuh duit. Itu yang membuat sebagian diantara mereka tidak memiliki keberanian dan ketegasan. Kalau yang pintar mah banyak,” tandasnya. Teddy melanjutkan, “Jadi, tantangan terbesar adalah mengalahkan rasa takut di dalam diri sendiri atas tekanan dari luar yang mengancam akan mencopot dari posisinya.”
Billy Jean King, mantan ratu tenis dunia pernah berujar bahwa bagi sang juara, pressure is privilege. Begitu juga bagi para CEO, sejatinya tekanan adalah privilese yang tak dinikmati sembarang orang. Dan kata Jenderal AS, George Patton, “Pressure makes diamonds.” Tekananlah yang akan mengantar seseorang menjadi emas atau loyang.
Bicara karakter dan kemampuan yang dibutuhkan CEO kita, tulisan Klaus-Peter Gushurst, The New Leadership; Sober, Spirited, and Spiritual, layak disimak. Menurutnya, era terbaik di masa globalisasi adalah mengombinasikan antara classic leadership values dengan contemporary values, termasuk openness, komunikasi yang berkualitas, dan kebersahajaan (naturalness), yang nota bene sejalan dengan pandangan Sonnenfeld. Tak lupa, juga memiliki nilai-nilai spiritualitas.
Dunia bisnis terus dinamis. Persoalan demi persoalan yang muncul, merupakan gambaran betapa dunia bisnis membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat. CEO Versi 3.0. Andakah itu orangnya?
Teguh S. Pambudi
Dalam 6 bulan terakhir, isu seputar kepemimpinan bisnis kian marak dikupas majalah maupun jurnal manajemen. Terpentalnya beberapa CEO top macam Charles O. Prince di Citigroup dan ancaman dipenjarakannya para pemimpin bisnis yang dipandang telah melakukan fraud, menjadi santapan media. Jauh sebelum Lehmann Brothers tutup usia, Harvard Business Review edisi Januari 2008, bahkan khusus mengangkat topik leadership. Rupanya, kekisruhan krisis kredit perumahan di AS yang membawa tsunami finansial sedikit banyak memunculkan kembali trauma atas skandal-skandal korporasi era Enron. Dan ujung pertanyaan dari masalah ini, siapa lagi kalau bukan para pemimpin bisnis; mengapa ini sampai terjadi? Apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin?
Dalam tulisannya di New York Times (11 November 2007), Nelson D. Schwartz melempar wacana menarik. Mengutip guru besar tentang leadership di School of Management at Yale, Jeffrey A. Sonnenfeld, kini dunia korporasi (khususnya di AS) memerlukan apa yang disebut CEO versi 3.0. Versi 1.0. adalah mereka yang fokus pada mega-merger serta manajemen finansial untuk memuaskan Wall Street dan rasa lapar para investor. Mereka adalah para empire builder. Berlangsung 1950-1990-an, fase yang terpaku pada pemuasan bottom line ini segera berakhir begitu Enron meledak. Lahirlah era CEO versi 2.0., para pemimpin berjenis cleanup artist yang tugasnya membereskan masalah. Mereka disebut juga kaum Fix-it Man. Sayang, mereka yang berkiprah di awal 2000-an ini pun banyak yang tidak sukses. Terbukti lahir skandal subprime mortgage yang hingga kini menimbulkan kerugian besar; lebih dari US$ 400 miliar.
Dari sinilah dibutuhkan CEO Versi 3.0. Mereka adalah para pemimpin yang bukan hanya fokus pada bottom line, tapi juga menyinergikan bisnis secara kelompok (tim). Mereka bervisi membangun kerajaan (empire builder), diiringi kerendahatian, dan mampu membangun tim yang kuat. Contohnya adalah CEO-nya P&G, AG Lafley serta Anne Mulcahy di Xerox. Disiplin individu yang mereka kembangkan bukan hanya teknikal seperti keuangan atau pemasaran, tapi lebih mengarah pada team oriented approach. Dan perusahaan yang mereka pimpin terbukti tangguh menghadapi krisis yang kini terjadi akibat subprime mortgage.
Pemikiran Sonnenfeld boleh jadi terlalu menyederhanakan, kendati ada hal-hal yang masuk akal, seperti fakta betapa menghambanya para pemimpin bisnis pada kalangan investor, terutama di tahun-tahun 1980-an ketika falsafah “greedy is good” menjadi “agama”. Lantas, bagaimana dengan wacana kepemimpinan bisnis di Indonesia? Apakah kita juga membutuhkan CEO versi 3.0.?
Sebelum menjawab hal tersebut, ada baiknya diketahui apa saja isu yang mengelilingi para pemimpin bisnis kita. Sebab, dari sini bisa ditarik garis bagaimana sesungguhnya dinamika bisnis yang sedang berlangsung, beserta lanskap yang menjadi arena permainannya. Untuk mencari tahu apa persoalan para pemimpin bisnis di Tanah Air, beberapa waktu lalu SWA melakukan survei pada 46 CEO, dengan pola jawaban terbuka dan bersifat multiple answers. Hasilnya?
Managing change, sustaining business growth, dan develop leader. Itulah 3 besar (berturut-turut) isu seputar leadership yang dihadapi para pemimpin bisnis kita. Perubahan yang makin sulit diprediksi serta dikelola, menjadi permasalah besar mereka (67,39%). Ini sesuatu yang wajar. Sekedar menyebutkan beberapa contoh, cobalah tengok ke panggung internasional. Krisis serta fluktuasi harga minyak, membuat lanskap bisnis kian tak ramah lagi. Tak heran, perkara ini akhirnya membuat mereka juga merasa bahwa mempertahankan pertumbuhan bisnis kian tak mudah, meski optimisme harus dipelihara (56,52%).
Yang menarik, urusan develop leader cukup mendapat porsi yang besar (56,52%). Ini sebuah sinyal positif sebagai jawaban terhadap isu bahwa stok leader kita terbatas, alias yang itu-itu saja. Artinya, bagi para responden, menjadi pemimpin hebat tidaklah cukup. Sanggup melahirkan para pemimpin selanjutnya, itu baru disebut hebat. Pemimpin-pemimpin baru ini tidak saja dalam konteks untuk berekspansi bisnis -- yang nota bene memerlukan orang-orang yang akan mengendalikan percepatan usaha --, tapi juga dalam regenerasi serta kelangsungan perusahaan.
Urusan yang satu ini, bukan perkara main-main. Garuda Food, misalnya, kini tengah serius menggojlok program creating business leader. Hingga 3-5 tahun ke depan, kelompok usaha di sektor makanan-minuman ini membutuhkan sedikitnya 400 orang pemimpin bisnis untuk mengelola akselerasi usahanya. Hal yang sama juga terjadi di Pertamina. Perusahaan itu mencanangkan bisa mencetak 200 business leader guna mengelola laju ekspansi di tengah gempuran para pesaing. Apakah target itu tercapai atau tidak, itu perkara lain. Yang pasti, urusan mencetak para pemimpin baru sangat mendesak.
Perkara mencetak leader memang hal penting. Steven Wheeler, Walter McFarland, dan Art Kleiner di Strategic+Business, 10 Januari 2008 menggugah para CEO untuk membangun kepemimpinan strategis, yakni “build an organization in which executives will flourish”. Menumbuhkan para eksekutif dari dalam adalah tugas yang makin krusial. Bahkan, bagi Robby Djohan, orang yang telah menelurkan sejumlah pemimpin bisnis di negeri ini, mencetak leader merupakan tugas yang tak bisa ditawar. “Sering kawan-kawan dalam pertemuan berkata pada saya, 'CEO saya pergi nih. Saya butuh CEO baru. Menurut kamu, saya harus bagaimana?' Di mata saya, itu a stupid question! Mengapa? Yang saya katakan adalah mengapa kamu tidak melihat portofolio manusia yang ada di dalam organisasimu untuk dilihat mana yang berpotensi menjadi CEO, dan pikirkan langkah yang tepat dan terbaik untuk menjadikan calon itu siap menjadi pemimpin.”
Adapun cara melahirkan pemimpin itu sendiri, Riri Satria, Consulting Director People Performance Consulting, melihatnya bisa dilakukan dalam 2 jalur; berdasarkan sistem, atau tidak berdasarkan sistem (sentuhan individu). Jalur pertama ditandai adanya kebijakan tertulis yang mengatur pengembangan kompetensi dengan memberikan peluang yang sama kepada karyawan. Adapun jalan yang kedua sifatnya lebih kepada personal touch. Para pimpinan sudah membidik orang-orang tertentu untuk menjadi kader dengan memberi kesempatan dan tantangan yang lebih banyak. ”Pendekatan yang ideal dan banyak dilakukan adalah kombinasi dari kedua pendekatan di atas,” katanya.
Kembali pada wacana CEO versi 3.0. Secara sederhana, sesungguhnya lanskap bisnis di Tanah Air juga bisa diklasifisikan dengan periode tertentu, dengan meminjam pandangan Sonnenfeld. Pertama, pra-1997. Ditandai -- terutama -- dengan deregulasi perbankan 1988, sedikit banyak para CEO di Indonesia juga menjadi empire builder. Sebutlah ini versi 1.0. Tandanya; semua berlomba berekspansi demi kebesaran kelompok usahanya sampai akhirnya krisis moneter 1997 menyapu bangunan yang ada, sekaligus mengantar pada era ke-2; pembenahan. Mulai 1998, dunia usaha melakukan restrukturisasi utang dan skala usaha, yang membuat para CEO menjadi kaum fix-it man yang sibuk membenahi sekaligus mengonsolidasi diri. Inilah versi 2.0. Dan dibubarkannya BPPN beserta sejumlah inisiatif macam Prakarsa Jakarta, semestinya menjadi tanda bahwa para CEO memasuki fase ke tiga; era stabilisasi dan pertumbuhan.
Tahun 2008 adalah satu dasawarsa setelah krisis menerpa. Dan kini, 2009, ancaman krisis kembali datang. Bicara lanskap bisnis, sungguh banyak perubahan yang semestinya membuat para CEO kita juga masuk pada fase atau menjadi versi tersendiri (3.0.). Di lingkup domestik, ranah ekonomi tak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi, otonomi daerah dan tekanan stakeholders yang lebih kuat, mulai dari good corporate governance hingga corporate social responsibility. Ini berjalan seiring persaingan yang lebih ketat karena kompetisi berjalan tanpa bayangan monopoli. Sementara itu, di lingkup internasional, persoalan menjadi lebih rumit karena mengglobalnya perekonomian diikuti pelebaran kutub-kutub pertumbuhan di sejumlah belahan dunia, khususnya Asia. Ini ditandai dengan kebangkitan Cina dan India, yang segera akan diikuti pemain dari negara lain, mulai dari Uni Emirates Arab, Qatar, Vietnam, dan bersiap-siaplah menyambutnya; Kamboja. Mereka menambah daftar pesaing yang sebelumnya telah mapan menunggangi globalisasi.
Kalau begitu, bagaimana karakter serta kemampuan versi 3.0. yang dibutuhkan CEO kita untuk melakukan stabilisasi dan menggenjot pertumbuhan?
Dari persoalan yang ada, tampaknya CEO masih dituntut menjalankan hal-hal yang kerap disebut basic task; konsolidasi bisnis dan biaya, reorganisasi, serta menjalankan prioritas strategis. Adapun nilai yang dikembangkan sering disebut sebagai classic leadership values, seperti disiplin. fokus, dan eksekusi. Akan tetapi, itu saja tampaknya tidak memadai.
Dalam pandangan Harry Sasongko, Presdir & CEO GE Money Indonesia, mengglobalnya ekonomi menuntut pemimpin perusahaan bersikap sekaligus berpikiran terbuka. Dari sisi jabatan CEO itu sendiri, misalnya. Globalisasi membuat orang bergerak lintas negara dan perusahaan. Menurutnya, kalau tidak sigap serta mempunyai keahlian yang lebih unggul dari warganegara asing, CEO akan tersingkir. Dan bisnisnya juga otomatis akan tersingkir kalau dia tak pandai meniti setiap peluang yang ada.
Bersikap sekaligus berpikiran terbuka, atau openness. Selanjutnya, Tanri Abeng menambahkan bahwa di era sekarang yang kian menuntut kecepatan sekaligus ketepatan bertindak, CEO harus mampu bersikap adaptif. Artinya sanggup menyesuaikan diri dengan situasi serta kondisi ekstrim sekalipun. Bedanya dengan sikap fleksibel? Fleksibel hanyalah sebatas bersedia bertoleransi dengan ketidaknyamanan, tetapi belum tentu mau beradaptasi. “Pemimpin yang fleksibel belum tentu mampu beradaptasi. Tetapi pemimpin yang mampu beradaptasi, itu pasti punya sikap fleksibilitas tinggi. Sikap adaptif sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis,” tandas Komisarit Utama PT Telkom ini. Cuma itu?
Openness dan adaptif saja, rupanya tidaklah memadai. Bagi Nugroho Supangat, mantan Mitra Pengelola Dunamis Organization Services, CEO masa kini juga harus lebih mampu merangkul stakeholders, terutama di lingkungan internal. Para pemimpin harus bisa mengayomi SDM yang kini disebut knowledge worker di tengah tuntutan standar kerja yang tinggi. Adapun untuk lingkup eksternal, kompetisi global yang menjadi salah satu dari 10 persoalan CEO, harus dijawab dengan kemampuan negosiasi yang hebat. “Mereka harus memiliki negotiation level tidak hanya level nasional tapi minimal regional level. Jadi tidak hanya bisa buat lobby dan network di Indonesia saja. Karena keran globalisasi di Indonesia ini rupanya terbuka lebar,” ujarnya serius.
Menambahkan pendapat di atas, Andreas Budihardjo, Guru Besar Manajemen Organisasi & SDM Prasetiya Mulya menggarisbawahi perlunya CEO memiliki kemampuan lain. “Dia juga harus bisa mengelola paradoks,” ulasnya. Paradoks dalam konteks ini, menurutnya adalah mengatasi antara persaingan dan kolaborasi sekaligus. “Mungkin kita sama-sama pengusaha restoran. Kita bersaing. Tapi kita juga berkolaborasi, bersama-sama membesarkan bisnis ini,” tutur peraih gelar master Manajemen Organisasi di Universitas Groningen, Belanda itu penuh arti.
Buat TP Rahmat, sejatinya tidak ada tipe karakter tertentu yang dibutuhkan oleh pemimpin bisnis masa kini. Baginya, yang terpenting adalah ketegasan, keberanian dan integritas. Di atas itu semua, hal terpenting yang harus ada dalam diri seorang CEO adalah karakter kejujuran dan ketegasan. Apapun, kondisi dan situasinya. “Kalau 'gak jujur, keras dan tegas mah sekarang ini lewat sajalah,” ujar Teddy dengan logat Sunda yang cukup kental. “Seperti Pak Agus (Matowardojo) di Bank Mandiri. Kalau semua CEO BUMN kayak dia, wah, beres deh permasalahan,” tambah mantan CEO Astra yang pernah meraih predikat Best CEO dari SWA itu. Teddy terkesan dengan gaya Agus membenahi Bank Mandiri. “Contohnya pengumuman di media massa (tentang) para pengutang. Itu butuh keberanian,” ujarnya.
Bagi Teddy, keberanian selalu dibutuhkan pemimpin dalam situasi serta kondisi apapun. Karena itulah, di luar tantangan eksternal dan internal organisasi, persoalan terbesar bagi CEO, justru datang dari dalam dirinya sendiri. “CEO juga manusia. Punya anak istri, butuh duit. Itu yang membuat sebagian diantara mereka tidak memiliki keberanian dan ketegasan. Kalau yang pintar mah banyak,” tandasnya. Teddy melanjutkan, “Jadi, tantangan terbesar adalah mengalahkan rasa takut di dalam diri sendiri atas tekanan dari luar yang mengancam akan mencopot dari posisinya.”
Billy Jean King, mantan ratu tenis dunia pernah berujar bahwa bagi sang juara, pressure is privilege. Begitu juga bagi para CEO, sejatinya tekanan adalah privilese yang tak dinikmati sembarang orang. Dan kata Jenderal AS, George Patton, “Pressure makes diamonds.” Tekananlah yang akan mengantar seseorang menjadi emas atau loyang.
Bicara karakter dan kemampuan yang dibutuhkan CEO kita, tulisan Klaus-Peter Gushurst, The New Leadership; Sober, Spirited, and Spiritual, layak disimak. Menurutnya, era terbaik di masa globalisasi adalah mengombinasikan antara classic leadership values dengan contemporary values, termasuk openness, komunikasi yang berkualitas, dan kebersahajaan (naturalness), yang nota bene sejalan dengan pandangan Sonnenfeld. Tak lupa, juga memiliki nilai-nilai spiritualitas.
Dunia bisnis terus dinamis. Persoalan demi persoalan yang muncul, merupakan gambaran betapa dunia bisnis membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat. CEO Versi 3.0. Andakah itu orangnya?
Labels:
Leadership
Monday, April 6, 2009
Inspirasi dari Kakek Jeno
Dia jatuh bangun mengembangkan bisnisnya. Prinsipnya yang pro buruh dan orang-orang kurang beruntung mengundang puji dan inspirasi banyak orang.
Teguh S. Pambudi
Pada suatu malam di tahun 1945. Luigino Francesco (Jeno) Paulucci mabuk berat. Dia mengejar seseorang di jalan di Duluth, Minnesota, AS. Tangannya menggenggam pisau. Tak terjadi pembunuhan, memang. Hanya perkelahian. Toh, Jeno ditangkap. Didakwa membahayakan keselamatan orang, dia dibui semalam di hotel prodeo di Duluth.
Sekeluarnya dari penjara, Jeno memutuskan untuk bangkit. Menjadi seseorang yang lebih berarti dengan cara menolong sesama. Dan kini, di usianya yang mendekati 90 tahun, lelaki ini tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Inpirasi lewat bisnis yang dibangunnya, yang kini berada dalam naungan Bellisio Food.
Bagaimana tidak inspiratif. Untuk kalangan pebisnis, Jeno punya ide yang tidak umum tentang buruh. Lelaki ini sangat pro serikat pekerja. Itu dibuktikan dengan rekam jejaknya saat mendirikan aneka usaha. Jeno sangat mendorong berdirinya serikat pekerja di perusahaan miliknya. Yang menarik, dia juga sangat peduli pada orang-orang yang kurang beruntung. Selama menjadi pengusaha, dia ditaksir telah mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang dengan catatan yang buat orang lain mungkin mengerikan; krimial, masalah emosi, dan cacat fisik. Banyak narapidana yang ada di penjara, yang diberi tahu untuk menelponnya begitu keluar dari penjara. “Call Paulucci”, adalah kalimat yang terkenal di penjara, terutama di Minnesota.
Bukan cuma mempekerjakan orang-orang bermasalah dan punya keterbatasan fisik, Jeno juga punya prinsip filantropi yang kuat. Baginya, bisnis seharusnya memberikan 5% dari laba sebelum pajak untuk proyek-proyek komunitas. Lalu menurutnya, siapa saja yang meraup US$ 100 ribu per tahun, juga harus menyisihkan sepersekian dari pendapatannya untuk komunitas yang kurang beruntung. Pokoknya, pengusaha dan orang-orang berkocek tebal, nggak boleh pelit.
Dengan kebijakannya tersebut, tak heran, Pada 1972, Jeno pernah dinobatkan sebagai US Employer of the Year oleh Council on Employment of the Handicapped. Dia dinilai memberi hal yang sangat bernilai atas kebijakannya merekrut, melatih, serta mempekerjakan orang-orang mengalami keterbatasan, mantan narapidana dan pecandu yang oleh orang lain mungkin tak akan dipekerjakan.
Dirunut ke belakang, jauh sebelum dia di penjara di tahun 1945, Jeno yang lahir tahun 1918 di Aurora, Minnesota, lahir dan tumbuh dalam situasi yang sulit. Anak Ettore and Michelina Paulucci, yang pada 1912 beremigrasi ke Amerika ini, tumbuh di Hibbing, Minnesota. Ayahnya, bekerja serabutan di pertambangan. Sementara ibunya menjalankan sebuah toko.
Sejak belia, Jeno sudah membanting tulang untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Dia mengambil arang yang tersisa di rel kereta. Dia juga menolong ibunya di toko, menjual anggur. Pada usia 10 tahun, dia menjual buah serta sayur-sayuran ke pasar lokal di Minnesota. Dan pada pada usia 14 tahun, dia bekerja di pabrik roti pada hari Sabtu, dari jam 5 pagi sampai malam. Hari-hari biasa dia sekolah di Hibbing State Junior College.
Ketika PD II meletus, Jeno masuk militer dan bertempur di Pasifik. Di sinilah dia melihat sesuatu yang kelak mengubah hidupnya. Di tengah kecamuknya perang, dia menyakiskan bagaimana pasukan AS amat menyukai masakan Cina. Menurutnya, membuka restoran makanan Cina di Minnesota akan sangat menarik.
Pada 1947, dengan menggunakan resep ibunya untuk menambahkan cita rasa, Jeno memberanikan diri membuat bisnis makanan Cina dalam kalengan. Meminjam US$ 2500 dari teman, dia meluncurkan makan kaleng dengan merek Chun King. Bisnis ini laris manis. Chun King menjadi pemain penting dan memancing perusahaan top saat itu, R.J. Reynolds untuk mencaploknya. Tahun 1967, setelah melewati dua tahun negosiasi, Jeno melepas Chun King ke R.J. Reynolds senilai US$ 63 juta. Tunai. Setelah itu, perusahaan pun berganti nama menjadi R.J. Reynolds Foods Inc.
Dapat uang banyak tak membuat Jeno ongkang-ongkang kaki. Selama di Chun King, dia mengembangkan mesin pembuat egg-roll. Lewat mesin itulah kemudian dia membuat pizza roll, yang kemudian disajikan dalam keadaan beku. Maka berdirilah Jeno's, Inc. dengan jualan utama, frozen pizza. Dan dengan cepat, frozen pizza miliknya menjadi primadona. Jeno sukses mengantisipasi mood konsumen AS. Pada 1972, Jeno’s Inc. menjadi penguasa pasar frozen pizza.
Laiknya Chun King, keberhasilan pizza beku memancing datangnya pesaing-pesaing besar. Pillsbury, Purex, dan Quaker Oats datang menyerbu pasar yang sedang tumbuh ini. Pada awal 1980-an, kinerja Jeno's yang terus digerogoti pesaing akhirnya melempem hingga merugi US$ 16 juta dari total penjualan yang mencapai US$ 170 juta. Pada 1981, Jeno pun menyerah. Dia menutup pabrik di Duluth, memindahkannya ke Ohio. Tapi dia berjanji akan kembali ke Duluth, dan memberi pekerjaan pada karyawan yang di-PHK. Pada 1985, Jeno's resmi dilego ke Pillsbury senilai US$ 150 juta.
Tahun 1990, Jeno menepati janjinya. Di usia 72 tahun, setelah menyelesaikan masa kontrak untuk tidak berkompetisi (non-competition contract) dengan Pillsbury, dia memutuskan untuk come back dalam bisnis. Membenamkan US$ 8 juta dari uangnya sendiri dan tambahan US$ 3,9 juta uang pinjaman, Jeno kembali menekuni bisnis makanan beku. Lahirlah Luigino's, Inc. di Duluth. Dan sesuai janjinya untuk memberi pekerjaan di Duluth, dia menghubungi sejumlah orang yang pernah bekerja dengannya, yang beberapa diantaranya telah masuk masa pensiun. Ada sekitar 29 eks-karyawannya, -- yang kalau umurnya dijumlah mencapai 758 tahun pengalaman kerja untuk Jeno – bersedia bergabung.
Boleh dibilang, mendrikan Luigino’s adalah langkah yang berani. Sebab, bisnis makanan beku sudah sangat jenuh. Beberapa pemain besar malah sudah masuk seperti Healthy Choice milik ConAgra, Weight Watchers dari H.J. Heinz, dan Stouffer's dari Nestlé.
Toh Jeno bukan pemain kemarin sore. Menyadari rival-rivalnya punya dana tak terbatas, dia percaya akan bisa bertanding bila sanggup menemukan ceruk dalam produk pasta single-serve dengan harga bersaing. Membuka kembali pabriknya yang lama di Duluth dan mempekerjakan 100 orang, dia segera meluncurkan produk-produk makanan Cina dengan merek Michelina, diambil dari nama ibunya. Dia juga memroduksi saus beku untuk kebutuhan militer.
Di tahun 1990 itu, kakek tua ini kembali berbisnis dengan posisi yang berbeda dibanding dulu saat mendirikan Chun King dan Jeno’s. Luigino’s adalah underdog di depan ConAgra, H.J.Heinz, dan Nestle. Tapi uniknya, come back-nya si kakek ini justru tmengundang para pesaingnya untuk meniru, dan saling mengadu harga.
Setelah berdiri, Luigino's Inc., tumbuh dengan mantap. Perusahaan ini menawarkan lebih dari 200 single-serve makanan Italia, Oriental, Meksiko, juga Swedia, dan Cina. Merek-mereknya segera terkenal, diantarnya Authentico, Budget Gourmet, Homestyle Bowls, Lean Gourmet, Michelina's, Oven Baked Pizzas, Signature, Yu Sing, dan Zap'ems.
Kendati masuk di tengah pasar yang sudah sesak, sejak awal Jeno menggariskan bisnis Luigino’s Inc. berorientasi nasional. Agar bisa menang dalam persaingan, diapun berupaya efisien dan menekan harga jual. Tak ada iklan yang biasanya mengambil 5-10% dari pendapatan. Jeno memanfaatkan reputasi serta jaringannya untuk masuk supermarket. Produknya dibandrol US$ 50-70 sen lebih murah dibanding pesaingnya.
Strategi ini sukses. Tahun pertama kembali ke bisnis, Jeno meraup penjualan US$ 50 juta, yang kemudian mencapai US$ 200 juta di tahun 1992. Dan setelah itu, dia membawa Luigino’s melesat. Pada pertengahan 1990-an, pasar Kanada dimasukinya. Pada 1999, produsen makanan Paradise Kitchen dari Minneapolidia diakuisisi, disusul pembelian The All American Gourment Co., Budget Gourmet serta Budget Gourmet Value Classics milik Heinz Frozen Food pada tahun 2001. Masih belum cukup, Jeno membeli Arden International Kitchens yang berbasis di Lakeville, Minnesota pada 2002.
Bagi sebagian orang, sepak terjangnya mungkin membuat dahi berkernyit; untuk apa berbisnis hingga usia senja?
“Ketika Anda menciptakan pekerjaan, Anda adalah seorang pahlawan. Tapi, ketika Anda menutup pabrik, Anda adalah sampah di muka bumi,” ujarnya. Baginya, membangun bisnis adalah pekerjaan mulia. Memang kini dia telah mengundurkan diri sebagai CEO. Namun, prinsip-prinsip di atas, seperti mempekerjakan orang kurang beruntung tetap dimonitornya di Luigino’s yang sejak Februari 2008 menjadi Bellisio Food. Sebagai tambahan, sejak niat berbisnis lagi, Jeno sudah bertekad untuk membawa perusahaannya go public. Sekalipun dia sangat kecanduan berbisnis, dia mengaku tak pernah menjadi orang yang terikat dengan bisnis. Dia selalu siap menjual Bellisio yang mencetak laba operasi US$ 105 jut pada tahun 2006 kapan saja bila dirasa waktunya tepat. Itulah inspirasi dari seorang Jeno. Berbisnis tanpa meninggalkan misi sosial.
Teguh S. Pambudi
Pada suatu malam di tahun 1945. Luigino Francesco (Jeno) Paulucci mabuk berat. Dia mengejar seseorang di jalan di Duluth, Minnesota, AS. Tangannya menggenggam pisau. Tak terjadi pembunuhan, memang. Hanya perkelahian. Toh, Jeno ditangkap. Didakwa membahayakan keselamatan orang, dia dibui semalam di hotel prodeo di Duluth.
Sekeluarnya dari penjara, Jeno memutuskan untuk bangkit. Menjadi seseorang yang lebih berarti dengan cara menolong sesama. Dan kini, di usianya yang mendekati 90 tahun, lelaki ini tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Inpirasi lewat bisnis yang dibangunnya, yang kini berada dalam naungan Bellisio Food.
Bagaimana tidak inspiratif. Untuk kalangan pebisnis, Jeno punya ide yang tidak umum tentang buruh. Lelaki ini sangat pro serikat pekerja. Itu dibuktikan dengan rekam jejaknya saat mendirikan aneka usaha. Jeno sangat mendorong berdirinya serikat pekerja di perusahaan miliknya. Yang menarik, dia juga sangat peduli pada orang-orang yang kurang beruntung. Selama menjadi pengusaha, dia ditaksir telah mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang dengan catatan yang buat orang lain mungkin mengerikan; krimial, masalah emosi, dan cacat fisik. Banyak narapidana yang ada di penjara, yang diberi tahu untuk menelponnya begitu keluar dari penjara. “Call Paulucci”, adalah kalimat yang terkenal di penjara, terutama di Minnesota.
Bukan cuma mempekerjakan orang-orang bermasalah dan punya keterbatasan fisik, Jeno juga punya prinsip filantropi yang kuat. Baginya, bisnis seharusnya memberikan 5% dari laba sebelum pajak untuk proyek-proyek komunitas. Lalu menurutnya, siapa saja yang meraup US$ 100 ribu per tahun, juga harus menyisihkan sepersekian dari pendapatannya untuk komunitas yang kurang beruntung. Pokoknya, pengusaha dan orang-orang berkocek tebal, nggak boleh pelit.
Dengan kebijakannya tersebut, tak heran, Pada 1972, Jeno pernah dinobatkan sebagai US Employer of the Year oleh Council on Employment of the Handicapped. Dia dinilai memberi hal yang sangat bernilai atas kebijakannya merekrut, melatih, serta mempekerjakan orang-orang mengalami keterbatasan, mantan narapidana dan pecandu yang oleh orang lain mungkin tak akan dipekerjakan.
Dirunut ke belakang, jauh sebelum dia di penjara di tahun 1945, Jeno yang lahir tahun 1918 di Aurora, Minnesota, lahir dan tumbuh dalam situasi yang sulit. Anak Ettore and Michelina Paulucci, yang pada 1912 beremigrasi ke Amerika ini, tumbuh di Hibbing, Minnesota. Ayahnya, bekerja serabutan di pertambangan. Sementara ibunya menjalankan sebuah toko.
Sejak belia, Jeno sudah membanting tulang untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Dia mengambil arang yang tersisa di rel kereta. Dia juga menolong ibunya di toko, menjual anggur. Pada usia 10 tahun, dia menjual buah serta sayur-sayuran ke pasar lokal di Minnesota. Dan pada pada usia 14 tahun, dia bekerja di pabrik roti pada hari Sabtu, dari jam 5 pagi sampai malam. Hari-hari biasa dia sekolah di Hibbing State Junior College.
Ketika PD II meletus, Jeno masuk militer dan bertempur di Pasifik. Di sinilah dia melihat sesuatu yang kelak mengubah hidupnya. Di tengah kecamuknya perang, dia menyakiskan bagaimana pasukan AS amat menyukai masakan Cina. Menurutnya, membuka restoran makanan Cina di Minnesota akan sangat menarik.
Pada 1947, dengan menggunakan resep ibunya untuk menambahkan cita rasa, Jeno memberanikan diri membuat bisnis makanan Cina dalam kalengan. Meminjam US$ 2500 dari teman, dia meluncurkan makan kaleng dengan merek Chun King. Bisnis ini laris manis. Chun King menjadi pemain penting dan memancing perusahaan top saat itu, R.J. Reynolds untuk mencaploknya. Tahun 1967, setelah melewati dua tahun negosiasi, Jeno melepas Chun King ke R.J. Reynolds senilai US$ 63 juta. Tunai. Setelah itu, perusahaan pun berganti nama menjadi R.J. Reynolds Foods Inc.
Dapat uang banyak tak membuat Jeno ongkang-ongkang kaki. Selama di Chun King, dia mengembangkan mesin pembuat egg-roll. Lewat mesin itulah kemudian dia membuat pizza roll, yang kemudian disajikan dalam keadaan beku. Maka berdirilah Jeno's, Inc. dengan jualan utama, frozen pizza. Dan dengan cepat, frozen pizza miliknya menjadi primadona. Jeno sukses mengantisipasi mood konsumen AS. Pada 1972, Jeno’s Inc. menjadi penguasa pasar frozen pizza.
Laiknya Chun King, keberhasilan pizza beku memancing datangnya pesaing-pesaing besar. Pillsbury, Purex, dan Quaker Oats datang menyerbu pasar yang sedang tumbuh ini. Pada awal 1980-an, kinerja Jeno's yang terus digerogoti pesaing akhirnya melempem hingga merugi US$ 16 juta dari total penjualan yang mencapai US$ 170 juta. Pada 1981, Jeno pun menyerah. Dia menutup pabrik di Duluth, memindahkannya ke Ohio. Tapi dia berjanji akan kembali ke Duluth, dan memberi pekerjaan pada karyawan yang di-PHK. Pada 1985, Jeno's resmi dilego ke Pillsbury senilai US$ 150 juta.
Tahun 1990, Jeno menepati janjinya. Di usia 72 tahun, setelah menyelesaikan masa kontrak untuk tidak berkompetisi (non-competition contract) dengan Pillsbury, dia memutuskan untuk come back dalam bisnis. Membenamkan US$ 8 juta dari uangnya sendiri dan tambahan US$ 3,9 juta uang pinjaman, Jeno kembali menekuni bisnis makanan beku. Lahirlah Luigino's, Inc. di Duluth. Dan sesuai janjinya untuk memberi pekerjaan di Duluth, dia menghubungi sejumlah orang yang pernah bekerja dengannya, yang beberapa diantaranya telah masuk masa pensiun. Ada sekitar 29 eks-karyawannya, -- yang kalau umurnya dijumlah mencapai 758 tahun pengalaman kerja untuk Jeno – bersedia bergabung.
Boleh dibilang, mendrikan Luigino’s adalah langkah yang berani. Sebab, bisnis makanan beku sudah sangat jenuh. Beberapa pemain besar malah sudah masuk seperti Healthy Choice milik ConAgra, Weight Watchers dari H.J. Heinz, dan Stouffer's dari Nestlé.
Toh Jeno bukan pemain kemarin sore. Menyadari rival-rivalnya punya dana tak terbatas, dia percaya akan bisa bertanding bila sanggup menemukan ceruk dalam produk pasta single-serve dengan harga bersaing. Membuka kembali pabriknya yang lama di Duluth dan mempekerjakan 100 orang, dia segera meluncurkan produk-produk makanan Cina dengan merek Michelina, diambil dari nama ibunya. Dia juga memroduksi saus beku untuk kebutuhan militer.
Di tahun 1990 itu, kakek tua ini kembali berbisnis dengan posisi yang berbeda dibanding dulu saat mendirikan Chun King dan Jeno’s. Luigino’s adalah underdog di depan ConAgra, H.J.Heinz, dan Nestle. Tapi uniknya, come back-nya si kakek ini justru tmengundang para pesaingnya untuk meniru, dan saling mengadu harga.
Setelah berdiri, Luigino's Inc., tumbuh dengan mantap. Perusahaan ini menawarkan lebih dari 200 single-serve makanan Italia, Oriental, Meksiko, juga Swedia, dan Cina. Merek-mereknya segera terkenal, diantarnya Authentico, Budget Gourmet, Homestyle Bowls, Lean Gourmet, Michelina's, Oven Baked Pizzas, Signature, Yu Sing, dan Zap'ems.
Kendati masuk di tengah pasar yang sudah sesak, sejak awal Jeno menggariskan bisnis Luigino’s Inc. berorientasi nasional. Agar bisa menang dalam persaingan, diapun berupaya efisien dan menekan harga jual. Tak ada iklan yang biasanya mengambil 5-10% dari pendapatan. Jeno memanfaatkan reputasi serta jaringannya untuk masuk supermarket. Produknya dibandrol US$ 50-70 sen lebih murah dibanding pesaingnya.
Strategi ini sukses. Tahun pertama kembali ke bisnis, Jeno meraup penjualan US$ 50 juta, yang kemudian mencapai US$ 200 juta di tahun 1992. Dan setelah itu, dia membawa Luigino’s melesat. Pada pertengahan 1990-an, pasar Kanada dimasukinya. Pada 1999, produsen makanan Paradise Kitchen dari Minneapolidia diakuisisi, disusul pembelian The All American Gourment Co., Budget Gourmet serta Budget Gourmet Value Classics milik Heinz Frozen Food pada tahun 2001. Masih belum cukup, Jeno membeli Arden International Kitchens yang berbasis di Lakeville, Minnesota pada 2002.
Bagi sebagian orang, sepak terjangnya mungkin membuat dahi berkernyit; untuk apa berbisnis hingga usia senja?
“Ketika Anda menciptakan pekerjaan, Anda adalah seorang pahlawan. Tapi, ketika Anda menutup pabrik, Anda adalah sampah di muka bumi,” ujarnya. Baginya, membangun bisnis adalah pekerjaan mulia. Memang kini dia telah mengundurkan diri sebagai CEO. Namun, prinsip-prinsip di atas, seperti mempekerjakan orang kurang beruntung tetap dimonitornya di Luigino’s yang sejak Februari 2008 menjadi Bellisio Food. Sebagai tambahan, sejak niat berbisnis lagi, Jeno sudah bertekad untuk membawa perusahaannya go public. Sekalipun dia sangat kecanduan berbisnis, dia mengaku tak pernah menjadi orang yang terikat dengan bisnis. Dia selalu siap menjual Bellisio yang mencetak laba operasi US$ 105 jut pada tahun 2006 kapan saja bila dirasa waktunya tepat. Itulah inspirasi dari seorang Jeno. Berbisnis tanpa meninggalkan misi sosial.
Labels:
Leadership
Mengentaskan Para Pangeran
Menyiapkan putra makota bukanlah perkara mudah. Ada 4 ujian yang umumnya akan dijalani. Dan bagi orang tua, semua sinyal yang muncul dari anak harus diperhatikan serta didengar.
Teguh S. Pambudi
“Mami, bisa nggak ya saya seperti Papi?” ujar Peni (bukan nama sebenarnya) pada sang bunda seraya mengempaskan badannya di sofa. Belum genap tiga bulan memegang tampuk salah satu perusahaan dalam kelompok bisnis keluarganya, dia sudah merasa tertekan sewaktu menghadapi rentetan permintaan sejumlah klien yang menuntut kesabaran serta toleransi tinggi. “Saya capek, Mami,” katanya. Kepada wanita yang melahirkannya, Peni lalu tak segan mengungkap kekhawatirannya. Kecemasan seorang anak yang tengah dimagangkan sang ayah yang ingin buah hatinya meneruskan perusahaan rintisannya. Kekhawatiran bahwa dia tak akan sehebat sang ayah.
Adegan di atas bukanlah rekaan. Cerita nyata di atas adalah apa yang disebut inside the princess room, yang muncul di sebuah perusahaan Tanah Air. Dan yakinlah, hal semacam ini juga banyak terjadi di bilik paling pribadi para putra-putri makota di panggung bisnis. Keraguan, kecemasan dan keyakinan, semuanya saling bertaut. Ke luar menampilkan ketegaran, padahal di dalam hati bersemayam kegalauan.
Munculnya perasaan di atas merupakan hal yang wajar karena ketika seorang pebisnis berupaya menempa para pangerannya, sesungguhnya salah satu aspek yang memang tengah digojlok adalah emosinya. Hal lain yang juga diuji adalah ketahanan fisik, kapasitas intelektualnya, berikut ketajaman intuisinya. Empat hal (emosi, fisik, intelektual, dan intuisi) tersebutlah yang paling diasah, terlepas pola penempaannya; dilakukan dalam lingkup perusahaan keluarga, ataupun di tempat lain. Juga, terlepas dari model penempaanya; dengan menggunakan mentor atau dibiarkan sendiri.
Khusus bagi orang-orang tua itu -- terutama mereka yang ingin anaknya melanjutkan bisnis --, pertanyaan kemudian adalah; bagaimana caranya agar para pangeran itu matang sehingga bisa mentas dengan meyakinkan?
Sebelum menjawab hal tersebut, mengacu ke Ivan Lansberg dalam tulisannya The Test of a Prince, (Harvard Business Review, September 2007), sejatinya ada 4 tes yang untuk melihat sejauh mana kematangan seorang putra makota.
Pertama, qualifying test. Uji ini lebih merujuk pada kapabilitas yang sifatnya formal seperti melihat latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengembangan kepribadian yang dimiliki sang pangeran. Juga menelisik bagaimana kinerja yang diinginkan darinya. Misalnya sejauh mana penyelesaian proyek yang diberikan padanya.
Kedua, self-imposed test. Ini melihat bagaimana sang pangeran membuat sesuatu yang kemudian diukur oleh orang tua dan para stakeholders. Contohnya, ketika mempresentasikan visi serta strategi yang dibuatnya, sang putra makota harus bisa membuat parameter yang bisa diukur efektivitasnya, sekaligus menjelaskan bagaimana semua itu bisa dicapai. Kemampuan meyakinkan tentang apa yang bisa dilakukan, akan menimbulkan persepsi sejauh mana kredibilitasnya.
Ketiga, circumcial test. Ini merupakan ujian yang sifatnya tidak terencana dan datang tiba-tiba. Bentuknya bisa beragam. Demikian pula situasi dan kondisinya, bisa sangat tidak beraturan. Umumnya berujud dalam bentuk krisis. Adapun yang keempat, political test. Biasanya berbentuk tantangan dari para pesaing yang ingin meruntuhkan pengaruh sang pangeran. Caranya tidak tunggal; meremehkan kemampuannya, menjegal rencana-rencananya, atau membangun koalisi untuk menandinginya. Pokoknya, membuat putra makota terlihat bodoh dan orang yang tak kapabel.
Menurut Ivan, tentu saja tak seluruh tes tersebut akan dihadapi para pangeran mengingat situasi serta kondisi yang dihadapi tiap orang tidaklah sama. Yang terpenting, lanjutnya, para pangeran mesti menyadari bahwa keempat ujian ini merupakan iterative test. Dari sudut pandang psikologi, uji iteratif adalah “the way followers 'write' a leader's story in their minds”. Jadi bagaimana para pangeran melewati tes yang ada, itulah yang akan terekam di benak orang lain, terutama orang tua, pemegang saham, dan karyawannya.
Karena itulah, kalau ada pertanyaan “bagaimana caranya agar para pangeran itu matang sehingga bisa mentas dengan meyakinkan?”, maka jawaban pertama adalah memberi mereka ruang untuk mengekspresikan dan mengasah seluruh kapabilitasnya. Lalu, mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan mereka. Hanya saja, yang harus diwaspadai adalah bila menggunakan mentor -- dengan sebutan apapun, misalnya “Assistant to CEO”. Sebab kalau sang asisten terlampau dominan, tulis Ivan, ini bisa mengikis kemampuan sang pangeran untuk memberikan yang terbaik dari dirinya.
Itu jawaban pertama. Yang kedua, adalah orang tua harus terus memonitornya. Mereka harus bisa melihat indikator-indikator sukses tidaknya sang putra makota melewati tes yang ada. Kalau gagal?
Proses dalam seluruh tes iteratif biasanya memang tak berjalan sempurna. Dan saat melihat tanda-tanda negatif, yakni kegagalan sang pangeran, maka Ivan memberi 4 jalan keluar yang bisa dilakukan oleh orang tua atau stakeholders. Pertama, protect and coach: melindungi, tapi lalu mengajarnya. Kedua, blow the whistle: beritahu segera untuk melakukan tindakan korektif. Ketiga, hide and wait: diam saja dan tunggu sampai sang pangeran gagal untuk kemudian jatuh, dan digantikan orang lain. Keempat, exit the company: tinggalkan perusahaan dan pindah ke tempat lain.
Semua pilihan tersebut tergantung pada penilaian atas kapabilitas sang pangeran; masih bisa diandalkan atau tidak. Namun tentu saja idealnya adalah melatih dan melempangkan yang bengkok, sampai kondisinya memang menunjukkan yang bersangkutan tak memiliki leadership yang kuat alias memang tak bisa menjadi pengendali bisnis.
Bicara melatih (coaching) para putra makota, AB Susanto dari Jakarta Consulting Group mengaku menggembangkan model assessment untuk membantu orang tua yang ingin menempa anaknya. Metodenya adalah apreciative inquiry. “Kita ingin mengasah sisi kuatnya saja, yang positif, habis-habisan. Saya tidak akan konsentrasi dengan kelemahannya,” urainya. Yang pasti, Susanto ingin menekankan kepada pangeran dan puteri penerus bahwa banyak hal yang saling terkait dalam perusahaan. “Bisnisnya buruk bisa karena organisasinya tidak bagus. Bisa karena tidak memperhatikan kastemer. Bisa juga karena reputasinya yang buruk,” cetusnya. Jadi, mereka mesti memperhatikan itu semua. “Kami mengharapkan putra mahkota bukan sekadar menjadi pemimpin operasional, namun juga harus bisa menjadi strategic leader,” ujarnya.
Tentu saja tak ada jaminan bahwa proses yang dilewati para pangeran akan mengantarkan pada hasil yang sama. Akan tetapi, Kresnayana Yahya dari Enciety Consulting, Surabaya melihat para pangeran yang tumbuh di tengah keluarga yang mengutamakan nilai (values), cenderung berpotensi sukses. ”Mereka yang dibesarkan dalam pandangan jauh ke depan, dan sangat sederhana pola dan gaya hidupnya, pada umumnya berhasil membentuk jiwa usaha dan semangat berkeringat, dan kemampuan melanjutkan bisnis keluarga secara sangat inovatif,” katanya.
Bagi Riri Satria, urusan sistem nilai ini bukan perkara main-main. Untuk menentukan kemampuan putra makota, maka ada tiga hal yang menandainya; kompetensi, motivasi, serta sistem nilai. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, serta attitude. Motivasi biasanya ditunjukkan oleh keyakinan, keseriusan, serta ketabahan. Dan, ”Semuanya dikendalikan oleh sistem nilai yang dianut,” ujar Consulting Director People Performance Consulting Indonesia ini.
Di mancanegara, tak sedikit putra makota yang mental karena gagal dalam tesnya masing-masing. Diantaranya adalah Christopher Galvin di Motorola, Edgar Bronfman Jr. di Seagram, dan William Clay Ford Jr. di Ford.
Namun ada yang juga sukses. Salah satu yang terkenal adalah Brian Roberts, CEO Comcast, raksasa telekomunikasi AS. Karyawan perusahaan yang berbasis di Philadelphia ini banyak yang mengenal Brian sejak kanak-kanak. Mereka ingat bagaimana sang bocah bergelayutan pada jas ayahnya, Ralph Roberts, salah seorang pendiri Comcast. Anak itu bahkan sudah tertarik bisnis kabel, sejak kecil; dia sudah memotong kupon yang dikirim Comcast ke pelanggan.
Seiring bertambahnya usia, Ralph mengajarkan anaknya hal-hal yang akan diperlukan dalam mengelola perusahaan. Ketika masih di sekolah menengah, secara teratur dia mengajak anaknya rapat bersama bankir dan pengacara Comcast. Pada usia 15, di hari pertama summer job, Brian pun merasakan bagaimana karyawan Comcast berhubungan dengannya. Seperti diceritakannya pada Wharton Alumni Magazine (Spring 2000), ketika dia muncul dengan jas dan dasi, penyelianya mewanti-wanti; “Saya tak peduli anak siapa kamu. Kamu akan bekerja pada saya, maka bekerjalah.”
Lulus sarjana keuangan dari Universitas Pennsylvania pada 1981, Brian ingin bergabung dengan Comcast. Namun, Ralph ingin anaknya itu bekerja dulu di tempat lain. Brian pun ngotot sampai akhirnya sang ayah memberi pekerjaan. Awalnya, dia mengira akan ditempatkan di corporate finance. Namun, Ralph menempatkannya di sebuah proyek di Trenton, New Jersey. Posisinya adalah seorang trainee. Pekerjaannya? Membentangkan kabel dan menjual kabel door-to-door.
Pada 1986 ketika Comcast mengambil Turned Broadcasting Sustem, Ralph menempatkan anaknya itu menjadi anggota direksi. Dan setelah melewati aneka ujian, baru pada 1990 Brian diangkat menjadi Presiden Comcast, di usia 31 tahun. Ralph sendiri menjadi Chairman Comcast. Sejak itu Brian terkenal dengan reputasinya sebagai dealmaker yang agresif. Pada tahun 2002 ketika Comcast mengakuisisi AT&T Broadband, investor mengritiknya atas akuisisi senilai US$ 25 miliar di tengah lemahnya ekonomi. Namun ketika dua perusahaan selesai mengintegrasikan operasinya, marjin laba meningkat dan pada 2003, majalah Institutional Investor menyebut Brian sebagai salah satu CEO Terbaik AS. Kini dia terus mengendalikan Comcast, perusahaan beromset US$ 25 miliar/tahun.
Di luar Brian, masih banyak anak yang tengah ditempa sang ayah. Salah satu yang top adalah raja baja, Lakhsmi Narayan Mittal. Lelaki yang tahun lalu memiliki kekayaan pribadi US$ 51 miliar itu tengah menggembleng Aditya Mittal dengan menempatkannya sebagai Group Chief Financial Officer Arcellor Mittal. Bagaimana kelak Aditya yang berusia 31 tahun itu benar-benar mentas, pastinya masih dinanti publik.
Kembali ke ihwal cara mengentaskan para pangeran. Memberi ruang serta mengontrolnya, merupakan cara yang terbaik sepanjang yang bersangkutan menunjukkan minat berikut kapabilitas yang mumpuni. Dan bila tanda-tanda negatif sudah muncul, segeralah ambil tindakan, yang menurut Ivan ada 4 jalan (protect and coach, dst.).
Melihat tanda-tanda ini sedari dini sungguhlah penting. Riri Satria punya cerita menarik yang layak direnungkan. Sebagai seorang dosen di sekolah manajemen, dia pernah memiliki mahasiswa yang merupakan seorang putri yang disiapkan orang tuanya untuk melanjutkan bisnis keluarga. Kepada Riri, anak itu bercerita, situasinya tidaklah mudah. Pihak luar melihatnya sebagai orang yang sudah senang, memiliki segala-galanya, mau apa saja tersedia. Padahal yang terjadi adalah tekanan yang sangat besar, yang tidak jarang membuatnya stress.
“Saat mau presentasi di kelas, saya perhatikan dia merokok di luar ruangan, dan wajahnya gelisah. Oh, rupanya dia mau mempresentasikan business plan, untuk perusahaan sendiri, dan dia ditantang untuk mewujudkan itu semua oleh orang tuanya, tidak hanya di atas kertas,” kata Riri mengenang. Dia tahu mahasiswinya itu punya pengetahuan dan keterampilan bisnis secara teoritik atau konseptual. “Nilainya (akademiknya) tinggi dan sangat cerdas menurut saya. Tetapi rupanya masalah mental dan kesiapan inilah yang tidak mudah untuk diwujudkan,” katanya.
Dalam proses mengentaskan putra makota, orang tua yang baik mestinya memang melihat semua proses yang dijalani anaknya. Keluhan mahasiswi Riri, dan juga Peni, adalah cetusan para putra makota yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka harus sering didengar. “Mami, bisa nggak ya saya seperti Papi?” termasuk sinyal untuk segera melakukan cara pertama yang diberikan Ivan; protect and coach. Ingat, uji iteratif yang dilakoni sang anak, akan menjadi pencitraan yang muncul di kepala para follower. Apa jadinya kalau Peni menceritakan kecemasan itu di depan karyawannya?
Jawabannya cuma satu; runtuhlah kredibilitasnya!
Teguh S. Pambudi
“Mami, bisa nggak ya saya seperti Papi?” ujar Peni (bukan nama sebenarnya) pada sang bunda seraya mengempaskan badannya di sofa. Belum genap tiga bulan memegang tampuk salah satu perusahaan dalam kelompok bisnis keluarganya, dia sudah merasa tertekan sewaktu menghadapi rentetan permintaan sejumlah klien yang menuntut kesabaran serta toleransi tinggi. “Saya capek, Mami,” katanya. Kepada wanita yang melahirkannya, Peni lalu tak segan mengungkap kekhawatirannya. Kecemasan seorang anak yang tengah dimagangkan sang ayah yang ingin buah hatinya meneruskan perusahaan rintisannya. Kekhawatiran bahwa dia tak akan sehebat sang ayah.
Adegan di atas bukanlah rekaan. Cerita nyata di atas adalah apa yang disebut inside the princess room, yang muncul di sebuah perusahaan Tanah Air. Dan yakinlah, hal semacam ini juga banyak terjadi di bilik paling pribadi para putra-putri makota di panggung bisnis. Keraguan, kecemasan dan keyakinan, semuanya saling bertaut. Ke luar menampilkan ketegaran, padahal di dalam hati bersemayam kegalauan.
Munculnya perasaan di atas merupakan hal yang wajar karena ketika seorang pebisnis berupaya menempa para pangerannya, sesungguhnya salah satu aspek yang memang tengah digojlok adalah emosinya. Hal lain yang juga diuji adalah ketahanan fisik, kapasitas intelektualnya, berikut ketajaman intuisinya. Empat hal (emosi, fisik, intelektual, dan intuisi) tersebutlah yang paling diasah, terlepas pola penempaannya; dilakukan dalam lingkup perusahaan keluarga, ataupun di tempat lain. Juga, terlepas dari model penempaanya; dengan menggunakan mentor atau dibiarkan sendiri.
Khusus bagi orang-orang tua itu -- terutama mereka yang ingin anaknya melanjutkan bisnis --, pertanyaan kemudian adalah; bagaimana caranya agar para pangeran itu matang sehingga bisa mentas dengan meyakinkan?
Sebelum menjawab hal tersebut, mengacu ke Ivan Lansberg dalam tulisannya The Test of a Prince, (Harvard Business Review, September 2007), sejatinya ada 4 tes yang untuk melihat sejauh mana kematangan seorang putra makota.
Pertama, qualifying test. Uji ini lebih merujuk pada kapabilitas yang sifatnya formal seperti melihat latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan pengembangan kepribadian yang dimiliki sang pangeran. Juga menelisik bagaimana kinerja yang diinginkan darinya. Misalnya sejauh mana penyelesaian proyek yang diberikan padanya.
Kedua, self-imposed test. Ini melihat bagaimana sang pangeran membuat sesuatu yang kemudian diukur oleh orang tua dan para stakeholders. Contohnya, ketika mempresentasikan visi serta strategi yang dibuatnya, sang putra makota harus bisa membuat parameter yang bisa diukur efektivitasnya, sekaligus menjelaskan bagaimana semua itu bisa dicapai. Kemampuan meyakinkan tentang apa yang bisa dilakukan, akan menimbulkan persepsi sejauh mana kredibilitasnya.
Ketiga, circumcial test. Ini merupakan ujian yang sifatnya tidak terencana dan datang tiba-tiba. Bentuknya bisa beragam. Demikian pula situasi dan kondisinya, bisa sangat tidak beraturan. Umumnya berujud dalam bentuk krisis. Adapun yang keempat, political test. Biasanya berbentuk tantangan dari para pesaing yang ingin meruntuhkan pengaruh sang pangeran. Caranya tidak tunggal; meremehkan kemampuannya, menjegal rencana-rencananya, atau membangun koalisi untuk menandinginya. Pokoknya, membuat putra makota terlihat bodoh dan orang yang tak kapabel.
Menurut Ivan, tentu saja tak seluruh tes tersebut akan dihadapi para pangeran mengingat situasi serta kondisi yang dihadapi tiap orang tidaklah sama. Yang terpenting, lanjutnya, para pangeran mesti menyadari bahwa keempat ujian ini merupakan iterative test. Dari sudut pandang psikologi, uji iteratif adalah “the way followers 'write' a leader's story in their minds”. Jadi bagaimana para pangeran melewati tes yang ada, itulah yang akan terekam di benak orang lain, terutama orang tua, pemegang saham, dan karyawannya.
Karena itulah, kalau ada pertanyaan “bagaimana caranya agar para pangeran itu matang sehingga bisa mentas dengan meyakinkan?”, maka jawaban pertama adalah memberi mereka ruang untuk mengekspresikan dan mengasah seluruh kapabilitasnya. Lalu, mengerahkan sumber daya yang dibutuhkan mereka. Hanya saja, yang harus diwaspadai adalah bila menggunakan mentor -- dengan sebutan apapun, misalnya “Assistant to CEO”. Sebab kalau sang asisten terlampau dominan, tulis Ivan, ini bisa mengikis kemampuan sang pangeran untuk memberikan yang terbaik dari dirinya.
Itu jawaban pertama. Yang kedua, adalah orang tua harus terus memonitornya. Mereka harus bisa melihat indikator-indikator sukses tidaknya sang putra makota melewati tes yang ada. Kalau gagal?
Proses dalam seluruh tes iteratif biasanya memang tak berjalan sempurna. Dan saat melihat tanda-tanda negatif, yakni kegagalan sang pangeran, maka Ivan memberi 4 jalan keluar yang bisa dilakukan oleh orang tua atau stakeholders. Pertama, protect and coach: melindungi, tapi lalu mengajarnya. Kedua, blow the whistle: beritahu segera untuk melakukan tindakan korektif. Ketiga, hide and wait: diam saja dan tunggu sampai sang pangeran gagal untuk kemudian jatuh, dan digantikan orang lain. Keempat, exit the company: tinggalkan perusahaan dan pindah ke tempat lain.
Semua pilihan tersebut tergantung pada penilaian atas kapabilitas sang pangeran; masih bisa diandalkan atau tidak. Namun tentu saja idealnya adalah melatih dan melempangkan yang bengkok, sampai kondisinya memang menunjukkan yang bersangkutan tak memiliki leadership yang kuat alias memang tak bisa menjadi pengendali bisnis.
Bicara melatih (coaching) para putra makota, AB Susanto dari Jakarta Consulting Group mengaku menggembangkan model assessment untuk membantu orang tua yang ingin menempa anaknya. Metodenya adalah apreciative inquiry. “Kita ingin mengasah sisi kuatnya saja, yang positif, habis-habisan. Saya tidak akan konsentrasi dengan kelemahannya,” urainya. Yang pasti, Susanto ingin menekankan kepada pangeran dan puteri penerus bahwa banyak hal yang saling terkait dalam perusahaan. “Bisnisnya buruk bisa karena organisasinya tidak bagus. Bisa karena tidak memperhatikan kastemer. Bisa juga karena reputasinya yang buruk,” cetusnya. Jadi, mereka mesti memperhatikan itu semua. “Kami mengharapkan putra mahkota bukan sekadar menjadi pemimpin operasional, namun juga harus bisa menjadi strategic leader,” ujarnya.
Tentu saja tak ada jaminan bahwa proses yang dilewati para pangeran akan mengantarkan pada hasil yang sama. Akan tetapi, Kresnayana Yahya dari Enciety Consulting, Surabaya melihat para pangeran yang tumbuh di tengah keluarga yang mengutamakan nilai (values), cenderung berpotensi sukses. ”Mereka yang dibesarkan dalam pandangan jauh ke depan, dan sangat sederhana pola dan gaya hidupnya, pada umumnya berhasil membentuk jiwa usaha dan semangat berkeringat, dan kemampuan melanjutkan bisnis keluarga secara sangat inovatif,” katanya.
Bagi Riri Satria, urusan sistem nilai ini bukan perkara main-main. Untuk menentukan kemampuan putra makota, maka ada tiga hal yang menandainya; kompetensi, motivasi, serta sistem nilai. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, serta attitude. Motivasi biasanya ditunjukkan oleh keyakinan, keseriusan, serta ketabahan. Dan, ”Semuanya dikendalikan oleh sistem nilai yang dianut,” ujar Consulting Director People Performance Consulting Indonesia ini.
Di mancanegara, tak sedikit putra makota yang mental karena gagal dalam tesnya masing-masing. Diantaranya adalah Christopher Galvin di Motorola, Edgar Bronfman Jr. di Seagram, dan William Clay Ford Jr. di Ford.
Namun ada yang juga sukses. Salah satu yang terkenal adalah Brian Roberts, CEO Comcast, raksasa telekomunikasi AS. Karyawan perusahaan yang berbasis di Philadelphia ini banyak yang mengenal Brian sejak kanak-kanak. Mereka ingat bagaimana sang bocah bergelayutan pada jas ayahnya, Ralph Roberts, salah seorang pendiri Comcast. Anak itu bahkan sudah tertarik bisnis kabel, sejak kecil; dia sudah memotong kupon yang dikirim Comcast ke pelanggan.
Seiring bertambahnya usia, Ralph mengajarkan anaknya hal-hal yang akan diperlukan dalam mengelola perusahaan. Ketika masih di sekolah menengah, secara teratur dia mengajak anaknya rapat bersama bankir dan pengacara Comcast. Pada usia 15, di hari pertama summer job, Brian pun merasakan bagaimana karyawan Comcast berhubungan dengannya. Seperti diceritakannya pada Wharton Alumni Magazine (Spring 2000), ketika dia muncul dengan jas dan dasi, penyelianya mewanti-wanti; “Saya tak peduli anak siapa kamu. Kamu akan bekerja pada saya, maka bekerjalah.”
Lulus sarjana keuangan dari Universitas Pennsylvania pada 1981, Brian ingin bergabung dengan Comcast. Namun, Ralph ingin anaknya itu bekerja dulu di tempat lain. Brian pun ngotot sampai akhirnya sang ayah memberi pekerjaan. Awalnya, dia mengira akan ditempatkan di corporate finance. Namun, Ralph menempatkannya di sebuah proyek di Trenton, New Jersey. Posisinya adalah seorang trainee. Pekerjaannya? Membentangkan kabel dan menjual kabel door-to-door.
Pada 1986 ketika Comcast mengambil Turned Broadcasting Sustem, Ralph menempatkan anaknya itu menjadi anggota direksi. Dan setelah melewati aneka ujian, baru pada 1990 Brian diangkat menjadi Presiden Comcast, di usia 31 tahun. Ralph sendiri menjadi Chairman Comcast. Sejak itu Brian terkenal dengan reputasinya sebagai dealmaker yang agresif. Pada tahun 2002 ketika Comcast mengakuisisi AT&T Broadband, investor mengritiknya atas akuisisi senilai US$ 25 miliar di tengah lemahnya ekonomi. Namun ketika dua perusahaan selesai mengintegrasikan operasinya, marjin laba meningkat dan pada 2003, majalah Institutional Investor menyebut Brian sebagai salah satu CEO Terbaik AS. Kini dia terus mengendalikan Comcast, perusahaan beromset US$ 25 miliar/tahun.
Di luar Brian, masih banyak anak yang tengah ditempa sang ayah. Salah satu yang top adalah raja baja, Lakhsmi Narayan Mittal. Lelaki yang tahun lalu memiliki kekayaan pribadi US$ 51 miliar itu tengah menggembleng Aditya Mittal dengan menempatkannya sebagai Group Chief Financial Officer Arcellor Mittal. Bagaimana kelak Aditya yang berusia 31 tahun itu benar-benar mentas, pastinya masih dinanti publik.
Kembali ke ihwal cara mengentaskan para pangeran. Memberi ruang serta mengontrolnya, merupakan cara yang terbaik sepanjang yang bersangkutan menunjukkan minat berikut kapabilitas yang mumpuni. Dan bila tanda-tanda negatif sudah muncul, segeralah ambil tindakan, yang menurut Ivan ada 4 jalan (protect and coach, dst.).
Melihat tanda-tanda ini sedari dini sungguhlah penting. Riri Satria punya cerita menarik yang layak direnungkan. Sebagai seorang dosen di sekolah manajemen, dia pernah memiliki mahasiswa yang merupakan seorang putri yang disiapkan orang tuanya untuk melanjutkan bisnis keluarga. Kepada Riri, anak itu bercerita, situasinya tidaklah mudah. Pihak luar melihatnya sebagai orang yang sudah senang, memiliki segala-galanya, mau apa saja tersedia. Padahal yang terjadi adalah tekanan yang sangat besar, yang tidak jarang membuatnya stress.
“Saat mau presentasi di kelas, saya perhatikan dia merokok di luar ruangan, dan wajahnya gelisah. Oh, rupanya dia mau mempresentasikan business plan, untuk perusahaan sendiri, dan dia ditantang untuk mewujudkan itu semua oleh orang tuanya, tidak hanya di atas kertas,” kata Riri mengenang. Dia tahu mahasiswinya itu punya pengetahuan dan keterampilan bisnis secara teoritik atau konseptual. “Nilainya (akademiknya) tinggi dan sangat cerdas menurut saya. Tetapi rupanya masalah mental dan kesiapan inilah yang tidak mudah untuk diwujudkan,” katanya.
Dalam proses mengentaskan putra makota, orang tua yang baik mestinya memang melihat semua proses yang dijalani anaknya. Keluhan mahasiswi Riri, dan juga Peni, adalah cetusan para putra makota yang tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka harus sering didengar. “Mami, bisa nggak ya saya seperti Papi?” termasuk sinyal untuk segera melakukan cara pertama yang diberikan Ivan; protect and coach. Ingat, uji iteratif yang dilakoni sang anak, akan menjadi pencitraan yang muncul di kepala para follower. Apa jadinya kalau Peni menceritakan kecemasan itu di depan karyawannya?
Jawabannya cuma satu; runtuhlah kredibilitasnya!
Labels:
Leadership
Pembuktian Kaisar Es Krim
Dia disindir, diragukan, dan berada di bawah bayang-bayang dewa fesyen. Toh, dia berhasil sehingga kini dipuja dan dipuji. Apa saja prinsip manajemen yang diterapkannya?
Teguh S. Pambudi
Ketika PPR (Pinault-Printemps-Redoute) menunjuk Robert Polet sebagai CEO Gucci Group pada April 2004, sontak muncul reaksi negatif dari kalangan internal industri fesyen. Skeptisisme serta sindiran tentang telah terjadinya sesuatu yang konyol mendarat ke kantor para petinggi PPR. Maklum, Polet yang menggantikan Domenico De Sole, datang dari luar industri fesyen. Tepatnya, dia adalah presiden divisi es krim dan makanan beku Unilever. "Bisakah kaisar es krim bertahan di tengah sorot lampu dunia fesyen?” menjadi lead artikel tentang dirinya di New York Times. Bahkan The New Yorker ikut-ikutan mengritisi dengan menampilkan karikatur tentang orang yang mengapit tas Gucci seperti membawa kudapan.
Melihat situasi saat itu sangatlah wajar Polet disindir habis-habisan. Siapa yang tak kenal duet Tom Ford dan Domenico De Sole? Selama kurun 1993-2004, pamor Grup Gucci berada di tangan keduanya, terutama Tom, seorang desainer yang fenomenal yang karya-karyanya banyak ditunggu khalayak. Sebagai kepala kreatif Gucci dia mengontrol mulai dari produk, iklan, hingga interior gerai. Saking powerful-nya, gaji Tom bahkan melebihi De Sole. Dia dibayar US$150 juta/tahun sementara CEO-nya, De Sole hanya US$ 75 juta/tahun.
Tom dan De Sole juga telah menghasilkan kinerja cemerlang. Mereka mentransformasi Gucci menjadi korporasi multimiliar dolar setelah nyaris kolaps. Penjualan Gucci yang meningkat dari US$ 250 juta di tahun 1993 mereka dongkrak menjadi US$ 3,2 miliar pada 2003, membuat perusahaan ini menjadi pemain ketiga terbesar di dunia setelah LVMH dan Compagnie Financiere Richemont SA, pemilik Cartier. Para pesaing telak-telak berupaya meniru strategi Tom dan De Sole, membetot desainer-desainer top untuk membenahi label masing-masing. Duet di Gucci ini membuat industri fesyen berkembang.
Namun, bulan madu harus segera berakhir. Ketika PPR membenamkan US$ 8 miliar untuk mengakuisisi Gucci pada 2003, masalah pun segera menyapa Tom dan De Sole. PPR sendiri diundang para pemegang saham untuk membeli Gucci yang akan diakuisisi paksa oleh Bernard Arnault dari LVMH. Pertempuran pengambilalihan ini sangat seru. Dan ketika berakhir, giliran sang pembeli yang mulai merasa khawatir dengan perusahaan yang telah diakuisisinya. “Gucci itu organisasi yang aneh, dengan begitu banyak sentralisasi,” ujar Serge Weinberg, CEO PPR. “Balancing power antara desainer dan manager, betul-betul keliru,” katanya merujuk pada begitu berkuasanya Tom Ford. François-Henri Pinault menambahkan, "De Sole kerjanya bagus di Gucci. Tapi dia tak berpengalaman menjalankan perusahaan dengan beragam merek,” kata pendiri PPR itu tegas.
Sewaktu PPR mengakuisisi, performa Gucci memang tak sepenuhnya bagus. Beberapa merek seperti Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, dan Yves Saint Laurent -- yang nota-bene merupakan merek-merek yang dibeli Tom dan De Sole --, kinerjanya sedang melempem, Yves Saint Laurent bahkan berdarah-darah.
Namun, yang membuat Tom dan De Sole akhirnya tak disodori kontrak untuk melanjutkan karier di Gucci adalah lantaran mereka enggan menerima gaya para pemilik PPR. Keduanya tak ingin Henri Pinault mengutak-atik otonomi mereka. Padahal, justru itulah yang diinginkan investor; memangkas dominasi Tom dan De Sole.
Polet direkrut lewat cara tersendiri. “Ketika pertama kali headhunter mengontak saya, dia bilang begini, 'Kalau saya sebut Gucci, apa yang Anda pikirkan?'. Saya pun bilang, 'Wow.' Dan perasaan itu sampai sekarang masih ada.” kenang Polet.
November 2003. Di Amsterdam, Polet bertemu Beatrice Ballini dari Russell Reynolds, headhunter yang ditugaskan Henri Pinault mencari CEO Gucci. Kata pertama yang terlontar dari Polet adalah, “Saya itu seorang Gipsy modern.” Tentu saja ini kiasan, kendati faktanya dia memang orang yang berpindah-pindah. Lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, Polet menempuh pendidikannya di Inggris dan Belanda (studi administrasi bisnis di Nijenrode). Setelah mendapat MBA-nya di University of Oregon, AS, dia kemudian dikirim Unilever ke Belgia dan Malaysia. Kelak, dia dirotasi ke 11 negara selama berkarir di Unilever.
Fakta dari “Gipsy” modern ini sangat sesuai dengan keinginan Ballini. Dari pesanan yang diterimanya, bos-bos PPR memang tengah mencari seseorang dengan pengalaman internasional. Dan di atas segalanya; dengan rekam jejak mampu mengelola beragam merek.
Di Unilever, Polet terbiasa mengelola banyak merek. Anak seorang penjabat di perusahaan perdagangan di Belanda ini, pertama kali berurusan bisnis saat usia 7 tahun ketika membeli pencil, mematahkannya menjadi dua bagian, meruncingkannya, dan kemudian mejualnya ke temannya dengan harga dua kali lipat dibanding saat membeli. Dia bergabung dengan Unilever pada 1978 dengan rentang pengalaman terbanyak di bidang pemasaran. Salah satu kepiawaiannya mengelola merek adalah tatkala menjadi Chairman Unilever Malaysia di tahun 1990. Polet yang ketika itu berusia 35 tahun, memangkas jumlah merek dari 32 menjadi 14. Kemudian, dia fokus ke bisnis es krim dengan melahirkan merek populer macam Magnum.
Pengalaman kerja Polet sangat mengesankan pemilik PPR. Henri Pinault memang meminta dewan direksi Gucci memasukkan eksekutif dari perusahaan consumer goods, bukan hanya dari industri fesyen, dalam daftar buruan sebagai calon pengganti De Sole. Dan Polet yang disodorkan Ballini, merupakan pilihan tepat.
Bagi Polet sendiri, sebetulnya tawaran memimpin Gucci terasa agak ”merendahkan”. Bagaimana tidak, divisi es krim Unilever, nilai bisnisnya mencapai US$ 11 miliar: dua kali Grup Gucci. Dan di tangan Polet, marjin operasi divisi ini naik 3% ke 15%. Toh, tawaran Henri Pinault disambarnya. Dia merasa setelah 26 tahun berkarir di Unilever, sekaranglah saatnya mencari tantangan baru. Dan kelak, keputusan itu memang betul-betul menjadi sebuah tantangan.
Memimpin Gucci di tengah bayang-bayang apa yang disebut ”Tom-Dom show” -- untuk menunjukkan betapa dominannya Tom Ford dan Domenico De Sole --, Polet diuji sejak awal. Setelah dia masuk, banyak eksekutif Gucci yang hengkang mengikuti jejak Tom dan De Sole. Beberapa diantaraya keluar karena merasa direndahkan ketika sang bos baru membawa konsultan manajemen terlibat dalam perusahaan. Beberapa juga keluar karena rencana Polet untuk Gucci, seperti menambahkan lebih banyak logo pada merchandise, dianggap akan merusak label Gucci, sekaligus membuat produk dijauhi kalangan elit.
Sejak mengendalikan Gucci, Polet memang mengubah gaya manajemen. Sebagai pendatang baru di industri fesyen, dia mengangkat konsultan untuk membantunya. Langkah ini sangat mengejutkan karena ini merupakan sesuatu yang tak pernah dilakukan Gucci sebelumnya. Bain & Co. yang diundang Polet, akhirnya membuat eksekutif Gucci terpecah karena mereka tak terbiasa menerima nasihat dari pihak luar. Apa sebenarnya nasihat Bain & Co.?
Dalam salah satu laporannya, konsultan ini memaparkan bahwa model bisnis Gucci sangat ketinggalan jaman. Rencana desain Gucci yang memerlukan waktu 8 bulan sejak desain, produksi, sampai pengiriman, terbilang amat lama. Para konsultan dari Bain menyarankan Polet harus bisa melawan para pesaing yang lebih murah dan lincah dalam mengirim produk ke toko-toko sekaligus mengantisipasi datangnya sebuah musim busana. Bain mencatat Zara, pemain fesyen dari Spanyol, sanggup mengubah 75% merchandise-nya setiap 3 atau 4 minggu. Gucci? Perusahaan ini mengubah kumpulan koleksinya hanya 5 kali setiap tahun. Hasilnya jelas-jelas memiriskan: sementara pelanggan Zara mengunjungi toko 17 kali dalam setahun, pelanggan Gucci hanya datang ke butik 4 kali setahun.
Banyak yang tak suka nasihat ini, dan kemudian memilih hengkang. Namun, Polet jalan terus. Dia bahkan menerapkan sejumlah prinsip yang terasa radikal bagi perusahaan yang didirikan Guccio Gucci di Florence, Italia pada 1921 ini. Prinsip itu adalah, pertama, make the brand, not the talent, the star. Pada akhir 1990-an, Tom Ford adalah bintang. Dia mengotaki turnaround Gucci dan membuatnya menjadi merek utama dalam daftar para selebriti serta orang-orang kaya. Setelah menjadi CEO Gucci, Polet mengatakan bahwa yang terpenting adalah mengutamakan produk, bukan personalitas di baliknya. Maka untuk menghapus dominasi ala Tom, dia mengangkat tiga desainer Gucci yang namanya tak terkenal untuk mengurusi kreatif. Lalu, dia mengangkat manajer bisnis untuk setiap merek.Tak ada lagi era ketika seseorang mengontrol semua merek. "Kerja desainer adalah mengabdi pada merek,” katanya.
Grup Gucci punya merek-merek top. Jumlahnya juga tidak sedikit. Diantaranya; Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Roger & Gallet, Bottega Veneta, Bédat & Co, Alexander McQueen, Stella McCartney dan Balenciaga. Pada masa sebelumnya, Tom memang mengontrol semua itu. Dengan cara baru, kata Polet, akan membuat produk bukan cuma terlihat oke, tapi juga punya strategi merchandising yang bagus karena tidak bergantung pada kreativitas satu orang.
Itu yang pertama. Prinsip kedua, don't micromanage. Tak seperti pendahulunya, Polet tak mengontrol semua keputusan para desainernya. Dia hanya mengontrol dalam hal mencari pemimpin yang tepat, menetapkan rencana bisnis dalam tiga tahun mendatang, dan membuat aturan main untuk semuanya. “Setelah itu, saya tinggal bilang, 'Kerjakan',” katanya.
Cara ini menghancurkan kultur “Tom & Dom show”. Polet mendorong otoritas ke setiap merek di grup, memberi keleluasan bagi setiap direktur bisnis untuk mengelolanya. Agar maksimal, dia pun membuat apa yang disebutnya sistem "freedom within a framework". Ini adalah sesuatu yang tak lazim dalam perusahaan fesyen. “Dengan Domenico De Sole, jika Anda punya masalah, Anda akan pergi menghadapnya, dan dia akan membereskannya, bahkan cuma lewat telpon pun bisa. Dengan Polet, ceritanya lain. Anda harus pecahkan sendiri masalahnya,” ujar seorang eksekutif Gucci.
Adapun prinsip ketiga, know your customer. Gaya ini sedikit banyak mirip dengan konsep pengelolaan merek di Unilever. “Sebenarnya saya melihat lebih banyak kesamaan dibanding perbedaan antara pekerjaan lama dan baru,” kata Polet. Melakukan polling, terutama. Di Gucci, hal ini dipandang tidak penting karena Tom Ford adalah dewa. Dia menciptakan tren yang akan diikuti konsumen. Karena itu polling untuk mengetahui selera konsumen tidaklah perlu.
Sikap ini bersebrangan dengan Polet. Dia berpikir tak ada alasan mengapa rumah fesyen enggan meminjam praktik bisnis dari industri lain. Maka dia pun menekankan para desainernya untuk terus mendeteksi apa yang diinginkan konsumen lewat riset serta focus group discussion. Alhasil, Polet melebarkan Gucci ke produk-produk seperti scarf sutra. "Seluruh organisasi harus fokus melihat ke luar, termasuk pada konsumennya. Kita perlu tahu bagaimana dan kapan mereka menginginkan sesuatu,” katanya.
Dulu, sikap ini sangat dijauhi. “Tentu saja Anda harus tahu pasar. Namun, di industri produk mewah, Anda harus menjadi inovatornya,” ucap De Sole. “Kami punya ide sendiri tentang apa yang kami inginkan,” ujarnya pada satu kesempatan. Polet mengritik sikap ini. Apa yang diperlukan Gucci, tegasnya, adalah bagaimana para desainer mengelola kreativitasnya. Dan dia meyakini hal itu bisa ditempuh lewat jalan memahami kesukaan pelanggan. “Ini bukanlah kreativitas untuk kreativitas semata,” ujarnya.
Gaya manajemen di atas, didapat Polet dari pengalamannya. Di Unilever, dia belajar banyak tentang otonomi, terutama tatkala diminta mengelola Unilever Malaysia. Dia ingat bagaimana sulitnya situasi saat itu: pendapatan yang stagnan, laba yang sedikit, dan dewan direksi yang tak berfungsi di mana orang Cina, Melayu, dan Jerman tak bicara dengan bahasa bisnis yang sama. Polet juga tidak takut untuk memperkenalkan ide-ide baru di jagat fesyen. Sebab baginya kreativitas ada di mana saja. Seperti halnya di bisnis es krim. Di sini, dia memperkenalkan coklat dan es krim vanila dalam mangkuk kecil. Untuk urusan kreativitas, Polet sangat menekankan para pembantu dekat dan para desainer Gucci untuk belajar dari Zara, raksasa fesyen yang memukul butik-butik mewah yang lamban bergerak.
Bisnis luxury-goods, setelah konsolidasi konglomerat industri ini selama 1990-an, memang berada dalam masa sulit. Perusahaan yang membandrol harga murah dengan jadwal produksi cepat, seperti Zara, terus menggerogoti para pemain mapan macam LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Prada Group NV dan Gucci. Model bisnis ala Zara yang cepat dan efisien, mengubah aturan main serta gaya hidup konsumen. Sekarang banyak perempuan dengan bangganya memadu-padankan celana Armani seharga US$ 1000 dengan jaket Zara yang cuma dibandrol US$ US$ 89.
Polet menginginkan awak Gucci melihat realitas ini dengan cerdas. Dan setelah 3,5 tahun memimpin, harapannya itu pun tercapai. Sikapnya yang memberikan kewenangan untuk orang-orang dibawahnya, melahirkan dukungan berikut pujian. “Saya memang tak suka kalau seseorang memberi tahu tentang apa yang mesti saya lakukan,” ujar Patrizio Di Marco, yang mengelola Bottega Veneta. “Ini adalah persoalan kepercayaan,” kata Valérie Hermann, mantan eksekutif Dior yang direkrut untuk mengelola Yves Saint Laurent pada tahun 2005.
Kewenangan dari Polet mereka manfaatkan untuk berkreasi dan menjual produk sebagus mungkin. Bottega Veneta bahkan kini menjadi cerita hebat di Gucci; dari rugi US$ 10 juta menjadi laba operasi US$ 80 juta dalam 2 tahun terakhir. Yves Saint Laurent memang belum mencetak laba. Namun di bawah Valérie dan Stefano Pilati, kinerjanya terus membaik. Valérie memuji Polet sebagai direktur yang baik. Satu contoh yang dipuji adalah ide Polet untuk penggunaan Internet. Yves Saint Laurent meluncurkan situs e-commerce pada Oktober tahun lalu, yang diserbu pengunjung. Bahkan Boucheron juga telah menjadi merek yang sehat setelah masuk jalur online.
Secara total, Polet kini membuat Gucci menjadi grup dengan portofolio merek yang kuat -- hanya Yves Saint-Laurent yang masih merugi. Marjin operasi Gucci meningkat dari 10% di tahun 2003, menjadi 16% di tahun 2006, dan diharapkan menjadi 18% pada 2007. Tahun lalu, laba naik 44% menjadi US$ 741 juta. Hasil ini jelas mengejutkan banyak orang. Henri Pinault bahkan tak bisa menutupi rasa senang lantaran perkembangan yang ada melebihi harapannya. “Polet telah melakukan hal yang luar biasa hebat,” ujar Chairman PPR ini.
Pujian itu sungguh bukan basa-basi. Orang luar pun mengakuinya. Buktinya Polet dinobatkan Fortune sebagai European Businessman of The Year 2007. Toh, dia tak mau menyombongkan diri. Dia ingat bagaimana saat awal memimpin Gucci. “Setelah 3,5 minggu jadi CEO Gucci, saya bilang ke istri saya. 'Saya nggak bisa lagi berlibur bersamamu'. Setelah itu saya mengepak barang, terbang ke banyak negara, mengunjungi 168 toko Gucci. Saya bicara dengan 2500 dari 11 ribu karyawan Gucci. Saya kunjungi 100 toko kompetitor. Dari situlah saya punya peluang menemukan kembali Gucci, budayanya, orang-orangnya, mengetahui kompetisi, dan aturan main di dalamnya. Barulah setelah itu saya kembali ke kantor dengan pengetahuan dan cara pandang yang sangat baik,” katanya. Itulah resep Polet sebelum menjalankan prinsip-prinsipnya di Gucci, yang membuatnya mampu membuktikan betapa kaisar es krim juga bisa menjadi salah seorang kaisar fesyen.
Teguh S. Pambudi
Ketika PPR (Pinault-Printemps-Redoute) menunjuk Robert Polet sebagai CEO Gucci Group pada April 2004, sontak muncul reaksi negatif dari kalangan internal industri fesyen. Skeptisisme serta sindiran tentang telah terjadinya sesuatu yang konyol mendarat ke kantor para petinggi PPR. Maklum, Polet yang menggantikan Domenico De Sole, datang dari luar industri fesyen. Tepatnya, dia adalah presiden divisi es krim dan makanan beku Unilever. "Bisakah kaisar es krim bertahan di tengah sorot lampu dunia fesyen?” menjadi lead artikel tentang dirinya di New York Times. Bahkan The New Yorker ikut-ikutan mengritisi dengan menampilkan karikatur tentang orang yang mengapit tas Gucci seperti membawa kudapan.
Melihat situasi saat itu sangatlah wajar Polet disindir habis-habisan. Siapa yang tak kenal duet Tom Ford dan Domenico De Sole? Selama kurun 1993-2004, pamor Grup Gucci berada di tangan keduanya, terutama Tom, seorang desainer yang fenomenal yang karya-karyanya banyak ditunggu khalayak. Sebagai kepala kreatif Gucci dia mengontrol mulai dari produk, iklan, hingga interior gerai. Saking powerful-nya, gaji Tom bahkan melebihi De Sole. Dia dibayar US$150 juta/tahun sementara CEO-nya, De Sole hanya US$ 75 juta/tahun.
Tom dan De Sole juga telah menghasilkan kinerja cemerlang. Mereka mentransformasi Gucci menjadi korporasi multimiliar dolar setelah nyaris kolaps. Penjualan Gucci yang meningkat dari US$ 250 juta di tahun 1993 mereka dongkrak menjadi US$ 3,2 miliar pada 2003, membuat perusahaan ini menjadi pemain ketiga terbesar di dunia setelah LVMH dan Compagnie Financiere Richemont SA, pemilik Cartier. Para pesaing telak-telak berupaya meniru strategi Tom dan De Sole, membetot desainer-desainer top untuk membenahi label masing-masing. Duet di Gucci ini membuat industri fesyen berkembang.
Namun, bulan madu harus segera berakhir. Ketika PPR membenamkan US$ 8 miliar untuk mengakuisisi Gucci pada 2003, masalah pun segera menyapa Tom dan De Sole. PPR sendiri diundang para pemegang saham untuk membeli Gucci yang akan diakuisisi paksa oleh Bernard Arnault dari LVMH. Pertempuran pengambilalihan ini sangat seru. Dan ketika berakhir, giliran sang pembeli yang mulai merasa khawatir dengan perusahaan yang telah diakuisisinya. “Gucci itu organisasi yang aneh, dengan begitu banyak sentralisasi,” ujar Serge Weinberg, CEO PPR. “Balancing power antara desainer dan manager, betul-betul keliru,” katanya merujuk pada begitu berkuasanya Tom Ford. François-Henri Pinault menambahkan, "De Sole kerjanya bagus di Gucci. Tapi dia tak berpengalaman menjalankan perusahaan dengan beragam merek,” kata pendiri PPR itu tegas.
Sewaktu PPR mengakuisisi, performa Gucci memang tak sepenuhnya bagus. Beberapa merek seperti Bottega Veneta, Balenciaga, Boucheron, dan Yves Saint Laurent -- yang nota-bene merupakan merek-merek yang dibeli Tom dan De Sole --, kinerjanya sedang melempem, Yves Saint Laurent bahkan berdarah-darah.
Namun, yang membuat Tom dan De Sole akhirnya tak disodori kontrak untuk melanjutkan karier di Gucci adalah lantaran mereka enggan menerima gaya para pemilik PPR. Keduanya tak ingin Henri Pinault mengutak-atik otonomi mereka. Padahal, justru itulah yang diinginkan investor; memangkas dominasi Tom dan De Sole.
Polet direkrut lewat cara tersendiri. “Ketika pertama kali headhunter mengontak saya, dia bilang begini, 'Kalau saya sebut Gucci, apa yang Anda pikirkan?'. Saya pun bilang, 'Wow.' Dan perasaan itu sampai sekarang masih ada.” kenang Polet.
November 2003. Di Amsterdam, Polet bertemu Beatrice Ballini dari Russell Reynolds, headhunter yang ditugaskan Henri Pinault mencari CEO Gucci. Kata pertama yang terlontar dari Polet adalah, “Saya itu seorang Gipsy modern.” Tentu saja ini kiasan, kendati faktanya dia memang orang yang berpindah-pindah. Lahir di Kuala Lumpur, Malaysia, Polet menempuh pendidikannya di Inggris dan Belanda (studi administrasi bisnis di Nijenrode). Setelah mendapat MBA-nya di University of Oregon, AS, dia kemudian dikirim Unilever ke Belgia dan Malaysia. Kelak, dia dirotasi ke 11 negara selama berkarir di Unilever.
Fakta dari “Gipsy” modern ini sangat sesuai dengan keinginan Ballini. Dari pesanan yang diterimanya, bos-bos PPR memang tengah mencari seseorang dengan pengalaman internasional. Dan di atas segalanya; dengan rekam jejak mampu mengelola beragam merek.
Di Unilever, Polet terbiasa mengelola banyak merek. Anak seorang penjabat di perusahaan perdagangan di Belanda ini, pertama kali berurusan bisnis saat usia 7 tahun ketika membeli pencil, mematahkannya menjadi dua bagian, meruncingkannya, dan kemudian mejualnya ke temannya dengan harga dua kali lipat dibanding saat membeli. Dia bergabung dengan Unilever pada 1978 dengan rentang pengalaman terbanyak di bidang pemasaran. Salah satu kepiawaiannya mengelola merek adalah tatkala menjadi Chairman Unilever Malaysia di tahun 1990. Polet yang ketika itu berusia 35 tahun, memangkas jumlah merek dari 32 menjadi 14. Kemudian, dia fokus ke bisnis es krim dengan melahirkan merek populer macam Magnum.
Pengalaman kerja Polet sangat mengesankan pemilik PPR. Henri Pinault memang meminta dewan direksi Gucci memasukkan eksekutif dari perusahaan consumer goods, bukan hanya dari industri fesyen, dalam daftar buruan sebagai calon pengganti De Sole. Dan Polet yang disodorkan Ballini, merupakan pilihan tepat.
Bagi Polet sendiri, sebetulnya tawaran memimpin Gucci terasa agak ”merendahkan”. Bagaimana tidak, divisi es krim Unilever, nilai bisnisnya mencapai US$ 11 miliar: dua kali Grup Gucci. Dan di tangan Polet, marjin operasi divisi ini naik 3% ke 15%. Toh, tawaran Henri Pinault disambarnya. Dia merasa setelah 26 tahun berkarir di Unilever, sekaranglah saatnya mencari tantangan baru. Dan kelak, keputusan itu memang betul-betul menjadi sebuah tantangan.
Memimpin Gucci di tengah bayang-bayang apa yang disebut ”Tom-Dom show” -- untuk menunjukkan betapa dominannya Tom Ford dan Domenico De Sole --, Polet diuji sejak awal. Setelah dia masuk, banyak eksekutif Gucci yang hengkang mengikuti jejak Tom dan De Sole. Beberapa diantaraya keluar karena merasa direndahkan ketika sang bos baru membawa konsultan manajemen terlibat dalam perusahaan. Beberapa juga keluar karena rencana Polet untuk Gucci, seperti menambahkan lebih banyak logo pada merchandise, dianggap akan merusak label Gucci, sekaligus membuat produk dijauhi kalangan elit.
Sejak mengendalikan Gucci, Polet memang mengubah gaya manajemen. Sebagai pendatang baru di industri fesyen, dia mengangkat konsultan untuk membantunya. Langkah ini sangat mengejutkan karena ini merupakan sesuatu yang tak pernah dilakukan Gucci sebelumnya. Bain & Co. yang diundang Polet, akhirnya membuat eksekutif Gucci terpecah karena mereka tak terbiasa menerima nasihat dari pihak luar. Apa sebenarnya nasihat Bain & Co.?
Dalam salah satu laporannya, konsultan ini memaparkan bahwa model bisnis Gucci sangat ketinggalan jaman. Rencana desain Gucci yang memerlukan waktu 8 bulan sejak desain, produksi, sampai pengiriman, terbilang amat lama. Para konsultan dari Bain menyarankan Polet harus bisa melawan para pesaing yang lebih murah dan lincah dalam mengirim produk ke toko-toko sekaligus mengantisipasi datangnya sebuah musim busana. Bain mencatat Zara, pemain fesyen dari Spanyol, sanggup mengubah 75% merchandise-nya setiap 3 atau 4 minggu. Gucci? Perusahaan ini mengubah kumpulan koleksinya hanya 5 kali setiap tahun. Hasilnya jelas-jelas memiriskan: sementara pelanggan Zara mengunjungi toko 17 kali dalam setahun, pelanggan Gucci hanya datang ke butik 4 kali setahun.
Banyak yang tak suka nasihat ini, dan kemudian memilih hengkang. Namun, Polet jalan terus. Dia bahkan menerapkan sejumlah prinsip yang terasa radikal bagi perusahaan yang didirikan Guccio Gucci di Florence, Italia pada 1921 ini. Prinsip itu adalah, pertama, make the brand, not the talent, the star. Pada akhir 1990-an, Tom Ford adalah bintang. Dia mengotaki turnaround Gucci dan membuatnya menjadi merek utama dalam daftar para selebriti serta orang-orang kaya. Setelah menjadi CEO Gucci, Polet mengatakan bahwa yang terpenting adalah mengutamakan produk, bukan personalitas di baliknya. Maka untuk menghapus dominasi ala Tom, dia mengangkat tiga desainer Gucci yang namanya tak terkenal untuk mengurusi kreatif. Lalu, dia mengangkat manajer bisnis untuk setiap merek.Tak ada lagi era ketika seseorang mengontrol semua merek. "Kerja desainer adalah mengabdi pada merek,” katanya.
Grup Gucci punya merek-merek top. Jumlahnya juga tidak sedikit. Diantaranya; Gucci, Yves Saint Laurent, Sergio Rossi, Boucheron, Roger & Gallet, Bottega Veneta, Bédat & Co, Alexander McQueen, Stella McCartney dan Balenciaga. Pada masa sebelumnya, Tom memang mengontrol semua itu. Dengan cara baru, kata Polet, akan membuat produk bukan cuma terlihat oke, tapi juga punya strategi merchandising yang bagus karena tidak bergantung pada kreativitas satu orang.
Itu yang pertama. Prinsip kedua, don't micromanage. Tak seperti pendahulunya, Polet tak mengontrol semua keputusan para desainernya. Dia hanya mengontrol dalam hal mencari pemimpin yang tepat, menetapkan rencana bisnis dalam tiga tahun mendatang, dan membuat aturan main untuk semuanya. “Setelah itu, saya tinggal bilang, 'Kerjakan',” katanya.
Cara ini menghancurkan kultur “Tom & Dom show”. Polet mendorong otoritas ke setiap merek di grup, memberi keleluasan bagi setiap direktur bisnis untuk mengelolanya. Agar maksimal, dia pun membuat apa yang disebutnya sistem "freedom within a framework". Ini adalah sesuatu yang tak lazim dalam perusahaan fesyen. “Dengan Domenico De Sole, jika Anda punya masalah, Anda akan pergi menghadapnya, dan dia akan membereskannya, bahkan cuma lewat telpon pun bisa. Dengan Polet, ceritanya lain. Anda harus pecahkan sendiri masalahnya,” ujar seorang eksekutif Gucci.
Adapun prinsip ketiga, know your customer. Gaya ini sedikit banyak mirip dengan konsep pengelolaan merek di Unilever. “Sebenarnya saya melihat lebih banyak kesamaan dibanding perbedaan antara pekerjaan lama dan baru,” kata Polet. Melakukan polling, terutama. Di Gucci, hal ini dipandang tidak penting karena Tom Ford adalah dewa. Dia menciptakan tren yang akan diikuti konsumen. Karena itu polling untuk mengetahui selera konsumen tidaklah perlu.
Sikap ini bersebrangan dengan Polet. Dia berpikir tak ada alasan mengapa rumah fesyen enggan meminjam praktik bisnis dari industri lain. Maka dia pun menekankan para desainernya untuk terus mendeteksi apa yang diinginkan konsumen lewat riset serta focus group discussion. Alhasil, Polet melebarkan Gucci ke produk-produk seperti scarf sutra. "Seluruh organisasi harus fokus melihat ke luar, termasuk pada konsumennya. Kita perlu tahu bagaimana dan kapan mereka menginginkan sesuatu,” katanya.
Dulu, sikap ini sangat dijauhi. “Tentu saja Anda harus tahu pasar. Namun, di industri produk mewah, Anda harus menjadi inovatornya,” ucap De Sole. “Kami punya ide sendiri tentang apa yang kami inginkan,” ujarnya pada satu kesempatan. Polet mengritik sikap ini. Apa yang diperlukan Gucci, tegasnya, adalah bagaimana para desainer mengelola kreativitasnya. Dan dia meyakini hal itu bisa ditempuh lewat jalan memahami kesukaan pelanggan. “Ini bukanlah kreativitas untuk kreativitas semata,” ujarnya.
Gaya manajemen di atas, didapat Polet dari pengalamannya. Di Unilever, dia belajar banyak tentang otonomi, terutama tatkala diminta mengelola Unilever Malaysia. Dia ingat bagaimana sulitnya situasi saat itu: pendapatan yang stagnan, laba yang sedikit, dan dewan direksi yang tak berfungsi di mana orang Cina, Melayu, dan Jerman tak bicara dengan bahasa bisnis yang sama. Polet juga tidak takut untuk memperkenalkan ide-ide baru di jagat fesyen. Sebab baginya kreativitas ada di mana saja. Seperti halnya di bisnis es krim. Di sini, dia memperkenalkan coklat dan es krim vanila dalam mangkuk kecil. Untuk urusan kreativitas, Polet sangat menekankan para pembantu dekat dan para desainer Gucci untuk belajar dari Zara, raksasa fesyen yang memukul butik-butik mewah yang lamban bergerak.
Bisnis luxury-goods, setelah konsolidasi konglomerat industri ini selama 1990-an, memang berada dalam masa sulit. Perusahaan yang membandrol harga murah dengan jadwal produksi cepat, seperti Zara, terus menggerogoti para pemain mapan macam LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Prada Group NV dan Gucci. Model bisnis ala Zara yang cepat dan efisien, mengubah aturan main serta gaya hidup konsumen. Sekarang banyak perempuan dengan bangganya memadu-padankan celana Armani seharga US$ 1000 dengan jaket Zara yang cuma dibandrol US$ US$ 89.
Polet menginginkan awak Gucci melihat realitas ini dengan cerdas. Dan setelah 3,5 tahun memimpin, harapannya itu pun tercapai. Sikapnya yang memberikan kewenangan untuk orang-orang dibawahnya, melahirkan dukungan berikut pujian. “Saya memang tak suka kalau seseorang memberi tahu tentang apa yang mesti saya lakukan,” ujar Patrizio Di Marco, yang mengelola Bottega Veneta. “Ini adalah persoalan kepercayaan,” kata Valérie Hermann, mantan eksekutif Dior yang direkrut untuk mengelola Yves Saint Laurent pada tahun 2005.
Kewenangan dari Polet mereka manfaatkan untuk berkreasi dan menjual produk sebagus mungkin. Bottega Veneta bahkan kini menjadi cerita hebat di Gucci; dari rugi US$ 10 juta menjadi laba operasi US$ 80 juta dalam 2 tahun terakhir. Yves Saint Laurent memang belum mencetak laba. Namun di bawah Valérie dan Stefano Pilati, kinerjanya terus membaik. Valérie memuji Polet sebagai direktur yang baik. Satu contoh yang dipuji adalah ide Polet untuk penggunaan Internet. Yves Saint Laurent meluncurkan situs e-commerce pada Oktober tahun lalu, yang diserbu pengunjung. Bahkan Boucheron juga telah menjadi merek yang sehat setelah masuk jalur online.
Secara total, Polet kini membuat Gucci menjadi grup dengan portofolio merek yang kuat -- hanya Yves Saint-Laurent yang masih merugi. Marjin operasi Gucci meningkat dari 10% di tahun 2003, menjadi 16% di tahun 2006, dan diharapkan menjadi 18% pada 2007. Tahun lalu, laba naik 44% menjadi US$ 741 juta. Hasil ini jelas mengejutkan banyak orang. Henri Pinault bahkan tak bisa menutupi rasa senang lantaran perkembangan yang ada melebihi harapannya. “Polet telah melakukan hal yang luar biasa hebat,” ujar Chairman PPR ini.
Pujian itu sungguh bukan basa-basi. Orang luar pun mengakuinya. Buktinya Polet dinobatkan Fortune sebagai European Businessman of The Year 2007. Toh, dia tak mau menyombongkan diri. Dia ingat bagaimana saat awal memimpin Gucci. “Setelah 3,5 minggu jadi CEO Gucci, saya bilang ke istri saya. 'Saya nggak bisa lagi berlibur bersamamu'. Setelah itu saya mengepak barang, terbang ke banyak negara, mengunjungi 168 toko Gucci. Saya bicara dengan 2500 dari 11 ribu karyawan Gucci. Saya kunjungi 100 toko kompetitor. Dari situlah saya punya peluang menemukan kembali Gucci, budayanya, orang-orangnya, mengetahui kompetisi, dan aturan main di dalamnya. Barulah setelah itu saya kembali ke kantor dengan pengetahuan dan cara pandang yang sangat baik,” katanya. Itulah resep Polet sebelum menjalankan prinsip-prinsipnya di Gucci, yang membuatnya mampu membuktikan betapa kaisar es krim juga bisa menjadi salah seorang kaisar fesyen.
Labels:
Leadership,
Strategy
Saturday, April 4, 2009
Kembalinya Sang Legenda
Dengan double viral loop, dia membungkam kritik yang muncul. Jejaring sosialnya bahkan menjadi the fast growing social site. Inilah ketika sang legenda turun gunung, membawa harap dan ambisi.
Teguh S. Pambudi
Nama itu singkat saja: Ning. Diakses di www.ning.com. Namun, nama yang singkat itu kini tengah naik daun di jagat maya, di tengah dominasi Google, Facebook, dan MySpace. Dengan positioning “Social Networks for Everything” situs ini terus menyita perhatian. Banyak orang yang mengaksesnya, bergabung dengan jejaring sosial (social network) yang ada di dalamnya, atau membuat jejaring sosial sendiri untuk kemudian mengajak orang untuk terlibat.
Diluncurkan resmi pada Februari 2007, anggota Ning terus melonjak drastis. Pada Juni 2007, ada 60 ribu anggota bergabung. Dua bulan kemudian, 80 ribu. Akhir 2007, ada 150 ribu. Mei 2008 mencapai 230 ribu dan sekarang lebih dari 275 ribu. Sekitar 40% anggota datang dari luar AS, dari 176 negara. Di Ning, mereka dilayani dalam beberapa bahasa termasuk Cina, Jepang, Spanyol, serta Belanda. Pada akhir 2009, Ning ditaksir menjadi rumah bagi 4 juta jejaring sosial, puluhan juta member, dan mencapai page view miliaran dalam sehari.
Pencapaian serta estimasi itu terbilang fantastis. Awalnya, Ning tidaklah terlalu dipedulikan. Di awal-awal kemunculannya, tak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan Ning. Sampai-sampai, Michael Arrington mengirim tulisannya dalam blognya di TechCrunch dengan judul bernada sindiran: "Ning RIP?" Alasannya, ia tak akan bisa melawan situs jejaring sosial yang lebih dulu hadir, terutama Facebook dan MySpace.
Belakangan, Arrington meralat sindirannya itu manakala Ning makin menarik minat publik dan mencapai 100 ribu jejaring sosial. Ning menjadi the fast growing social site.
Adalah Marc Andreessen orang yang berada di balik semua ini. Bagi yang belum mendengarnya, Marc adalah legenda hidup di dunia maya. Dia adalah nama besar. Dialah co-author penjelajah Internet pertama, Mosaic. Dia juga co-founder Netscape Communications dan pendiri Opsware. Lelaki tinggi besar ini adalah orang elit di dunia Internet. Memiliki dua perusahaan (Netscape dan Opsware), Marc adalah sedikit orang yang bisa menjual perusahaan di atas US$ 1 miliar. Netscape dibeli AOL pada 1998 senilai US$ 4,2 miliar -- yang kemudian diakuisisi Time Warner. Sementara Opsware, perusahaan server jaringan dibeli Hewlett-Packard US$ 1,6 miliar di tahun 2007. Tak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu, kecuali mantan mitranya saat membangun Netscape, Jim Clark.
Keberadaan Marc di balik Ning sungguh menarik perhatian. Kembalinya sang legenda hidup -- kadang dijuluki juga sang raja --, tulis kolumnis BusinessWeek, Sarah Lacy malah sempat memunculkan keheranan. Sebab, relatif sulit untuk melihatnya turun gelanggang. Bahkan dia jarang meninggalkan Palo Alto, kecuali bepergian ke Los Angeles atau Las Vegas. Lelaki berkepala plontos yang baru menikahi Laura Arrillaga pada tahun 2007 ini juga cenderung jarang keluar kota.
Marc, secara berseloroh, menyebut bahwa dia turun gunung karena seorang wanita, Gina Bianchini. Tahun 2004, Gina meyakinkan Marc bahwa Internet tetaplah lahan yang menggiurkan. Mereka berdua bertemu lewat Harmonic Communications, perusahaan yang didanai Sequoia Capital. Marc adalah direksi Harmonic, penjual software untuk membuat kampanye iklan, termasuk via internet. Kelak, perusahaan ini dijual ke Dentsu, raksasa periklanan dari Jepang.
Gina (35 tahun) yang lulusan MBA dari Stanford segera menarik perhatian Marc. Bukan karena parasnya yang ayu, tapi lebih pada pemikirannya. Wanita ini sangat terobsesi dengan perilaku sosial di dunia online. Di tahun itu (2004), Facebook baru saja berdiri. Gina meyakinkan Marc bahwa jejaring sosial akan tumbuh dengan pesat. Dan dia tak ingin melewatkan ini semua.
Marc menyambut ide anak California tersebut. Namun dia ingin membangun situs jejaring sosial yang berbeda dari yang ada. Lelaki itu ingin sebuah situs yang menyediakan platform terbuka, yang membuat orang bisa berkreativitas total, mewujudkan apa yang mereka inginkan. Sebuah diferensiasi dibanding jejaring sosial yang lebih dulu hadir.
Maka lahirlah Ning. Gina menjadi CEO-nya, sementara Marc menjadi Chief Technology Officer-nya. Uang Marc sebesar US$ 15 juta dikucurkan sebagai dana awal. Berdua, dan dibantu 14 karyawan, mereka membangun Ning selama 2 tahun (2004-2006). Tak ada hiruk-pikuk ketika mereka mengembangkan situs ini dalam sebuah operasi bernama "24 Hour Laundry". Suasana gempita baru mulai pada November 2006 di Palace Hotel, San Francisco ketika Gina mengumumkan peluncuran Ning, didampingi Marc.
Dalam bahasa Cina, Ning artinya damai, “Ning itu singkat, manis, dan tak akan pergi dari fokus utama jasa kami: jejaring sosial Anda. Jasa kami, adalah seputar Anda, bukan kami.” Begitu tulis Gina dalam blog Ning.
Dia benar. Ning adalah platform online untuk para pengguna yang ingin menciptakan situs sosial serta jejaring sosialnya masing-masing. Di situs ini, setiap orang bisa bergabung atau membangun sendiri jejaring sosialnya dengan topik yang mereka suka, butuhkan, dan dengan audiens yang spesifik. Climate change, misalnya. Anda tertarik wacana perubahan iklim, tinggal mendaftar.
Atau, katakan Anda ingin membangun situs yang isinya adalah teman-teman sekolah SD dulu, maka tinggal masuk ke Ning. Buat situs sesukanya. Undang teman-teman sekolah. Seperti halnya Facebook atau MySpace, Ning juga punya halaman profil, foto, video, dan messaging. Jadi, buatlah nama jejaring sesuka hati, pilih layout-nya, maka terujudlah jejaring sosial milik Anda.
Pendek kata, segala hal tentang Ning adalah tentang hal-hal yang bisa dikustomisasi. Kalau memahami bahasa web seperti HTML, bisa merekonstruksi tampilan situs. Tak terlalu jago? Tak usah ambil pusing, tinggal gunakan template yang ada. Situs ini gratis jika mengijinkan iklan lalu lalang di situs Anda. Jika tak mengijinkan iklan, bayarlah fee bulanan ke Ning.
Simpel dan menarik. Tapi, seperti diulas di atas, di awal kemunculannya Ning dianggap sepi. Banyak kritik mengatakan bahwa orang tak ingin membangun jejaring sosialnya sendiri. Tak sedikit pula yang meyakini buah karya Marc-Gina ini akan sulit menandingi, atau malah menjungkalkan MySpace dan Facebook. Padahal, Gina berharap situsnya dapat bersaing dengan MySpace serta Facebook yang kantornya hanya di seberang jalan kantor Ning di Palo Alto.
Namun, waktu menjawab itu semua. Ning terus meroket sekaligus membungkam kritik. Platform-nya yang terbuka dan terkustomisasi menarik minat orang untuk menggunakannya. Bahkan tak sampai setahun setelah peluncuran, tepatnya Juli 2007, Ning menarik minat investor: mendapat suntikan US$ 44 juta dari pemodal ventura yang dikomandoi Legg Mason dan T. Rowe Price.
Ketika ditanya apa rahasia sukses Ning, Marc menjawab demikian: "Pada umumnya, pada layanan social networking, pengguna bergabung dengan satu jejaring sosial besar yang didesain dan dijalankan oleh pemegang layanan (pembangun situs),” katanya. "Users kemudian mengundang pengguna lainnya untuk bergabung di jejaring yang sama. Ini adalah apa yang disebut sebagai viral loop.” Kalau Ning?
“Pada Ning, users bisa bergabung dengan jejaring yang sudah ada, maupun menciptakan jejaringnya sendiri. Ini adalah double viral loop. Ini rahasianya. Model ini akan menciptakan situasi berikut: semakin banyak jejaring di Ning, semakin banyak user yang diundang bergabung. Dan kian banyak user yang bergabung, maka makin banyak pula jejaring baru yang tercipta.” Demikian uraian Marc yang meyakini model double viral loop punya keunggulan dibanding situs jejaring sosial lainnya.
Tapi tak semua orang meyakini kehebatan Ning. Tak sedikit pula yang tetap skeptis atas masa depan online social networking. Terhadap yang seperti itu, secara personal Marc merasa tak perlu membuktikan apapun. “Ketika usia Anda 35 tahun, Anda akan mulai punya pemahaman yang bagus tentang hal yang mungkin dan mustahil untuk dilakukan,” jelas pria kelahiran 9 Juli 1971 ini kalem. Yang jelas, dia mengaku punya ambisi besar: bila saatnya tepat, dia ingin menjual Ning menjadi miliaran dolar-nya yang ketiga, yang tentu membuatnya semakin kaya.
Tampaknya ambisi itu bukan sesuatu yang mustahil bila melihat kecenderungan yang belakangan kian marak: banjir uang di era Web 2.0 yang kental dengan model jejaring sosial dan pola saling berbagi (sharing) secara interaktif, entah itu foto maupun video. Ambil contoh Mark Zuckerberg. Pendiri sekaligus CEO Facebook ini telah mengundang banyak investor untuk turut mengembangkan situs yang baru seumur jagung dibesutnya. Dan investor itu sendiri telah menikmati keberuntungan. Salah satunya, Peter Thiel. Uang yang dibenamkannya sebesar US$ 500 ribu saat membangun Facebook, sekarang nilainya telah mencapai US$ 750 juta (Fast Company, Mei 2008).
Zuckerberg sendiri menyusul rekan-rekannya. Sebelumnya, News Corp. telah membeli MySpace senilai US$ 580 juta, Google membeli YouTube milik Chad Hurley dan Steven Chen senilai US$ 1,65 miliar, dan eBay memborong PayPal serta Skype (masing-masing senilai US$ 1,5 miliar serta US$ 2,6 miliar). Adapun Yahoo! membeli Flickr senilai US$ 35 juta dari pembuatnya, Stewart Butterfield. Flickr adalah situs berbagi foto.
Gebrakan teranyar adalah LinkedIn. Situs jejaring profesional yang telah menarik 23 juta user yang bergabung untuk mencari kerja, mencari karyawan, dan kemungkinan mengerjakan proyek bisnis bersama-sama ini, terus membetot investor. Pada 17 Juni 2008, Bain Capital Ventures, Bessemer Venture Partners, Sequoia Capital, dan Greylock Partners membenamkan US$ 53 juta ke situs ini. Hebatnya, uang sebesar itu hanya untuk membeli 5% saham LinkedIn. Mereka yakin akan masa depan LinkedIn sekalipun mesti mengucurkan uang untuk jumlah saham yang terbilang kecil. Pembelian 5% saham ini menjadikan LinkedIn bernilai US$ 1,015 miliar.
Dengan mendesain produk secara tepat, bisnis miliaran dolar di jagat Internet kini memang sangat dimungkinkan. Kini, Ning ditaksir sedikitnya bernilai US$ 500 juta dan kian popular dengan page view yang meningkat 10% setiap minggunya. Ke depannya, tak mustahil Marc meraup miliaran US dolar untuk perusahaannya yang ke-3. Sebuah pencapaian yang kian mengukuhkannya sebagai sang legenda hidup.
Terlepas dari itu, Ning kini menjadi salah satu ikon Web 2.0 yang diperhitungkan selain Google, YouTube, Facebook, MySpace, Digg, LinkedIn, Twitter, dan Flickr. Menjadi ikon setelah diragukan.
Teguh S. Pambudi
Nama itu singkat saja: Ning. Diakses di www.ning.com. Namun, nama yang singkat itu kini tengah naik daun di jagat maya, di tengah dominasi Google, Facebook, dan MySpace. Dengan positioning “Social Networks for Everything” situs ini terus menyita perhatian. Banyak orang yang mengaksesnya, bergabung dengan jejaring sosial (social network) yang ada di dalamnya, atau membuat jejaring sosial sendiri untuk kemudian mengajak orang untuk terlibat.
Diluncurkan resmi pada Februari 2007, anggota Ning terus melonjak drastis. Pada Juni 2007, ada 60 ribu anggota bergabung. Dua bulan kemudian, 80 ribu. Akhir 2007, ada 150 ribu. Mei 2008 mencapai 230 ribu dan sekarang lebih dari 275 ribu. Sekitar 40% anggota datang dari luar AS, dari 176 negara. Di Ning, mereka dilayani dalam beberapa bahasa termasuk Cina, Jepang, Spanyol, serta Belanda. Pada akhir 2009, Ning ditaksir menjadi rumah bagi 4 juta jejaring sosial, puluhan juta member, dan mencapai page view miliaran dalam sehari.
Pencapaian serta estimasi itu terbilang fantastis. Awalnya, Ning tidaklah terlalu dipedulikan. Di awal-awal kemunculannya, tak semua orang tahu bagaimana cara menggunakan Ning. Sampai-sampai, Michael Arrington mengirim tulisannya dalam blognya di TechCrunch dengan judul bernada sindiran: "Ning RIP?" Alasannya, ia tak akan bisa melawan situs jejaring sosial yang lebih dulu hadir, terutama Facebook dan MySpace.
Belakangan, Arrington meralat sindirannya itu manakala Ning makin menarik minat publik dan mencapai 100 ribu jejaring sosial. Ning menjadi the fast growing social site.
Adalah Marc Andreessen orang yang berada di balik semua ini. Bagi yang belum mendengarnya, Marc adalah legenda hidup di dunia maya. Dia adalah nama besar. Dialah co-author penjelajah Internet pertama, Mosaic. Dia juga co-founder Netscape Communications dan pendiri Opsware. Lelaki tinggi besar ini adalah orang elit di dunia Internet. Memiliki dua perusahaan (Netscape dan Opsware), Marc adalah sedikit orang yang bisa menjual perusahaan di atas US$ 1 miliar. Netscape dibeli AOL pada 1998 senilai US$ 4,2 miliar -- yang kemudian diakuisisi Time Warner. Sementara Opsware, perusahaan server jaringan dibeli Hewlett-Packard US$ 1,6 miliar di tahun 2007. Tak banyak orang yang bisa melakukan seperti itu, kecuali mantan mitranya saat membangun Netscape, Jim Clark.
Keberadaan Marc di balik Ning sungguh menarik perhatian. Kembalinya sang legenda hidup -- kadang dijuluki juga sang raja --, tulis kolumnis BusinessWeek, Sarah Lacy malah sempat memunculkan keheranan. Sebab, relatif sulit untuk melihatnya turun gelanggang. Bahkan dia jarang meninggalkan Palo Alto, kecuali bepergian ke Los Angeles atau Las Vegas. Lelaki berkepala plontos yang baru menikahi Laura Arrillaga pada tahun 2007 ini juga cenderung jarang keluar kota.
Marc, secara berseloroh, menyebut bahwa dia turun gunung karena seorang wanita, Gina Bianchini. Tahun 2004, Gina meyakinkan Marc bahwa Internet tetaplah lahan yang menggiurkan. Mereka berdua bertemu lewat Harmonic Communications, perusahaan yang didanai Sequoia Capital. Marc adalah direksi Harmonic, penjual software untuk membuat kampanye iklan, termasuk via internet. Kelak, perusahaan ini dijual ke Dentsu, raksasa periklanan dari Jepang.
Gina (35 tahun) yang lulusan MBA dari Stanford segera menarik perhatian Marc. Bukan karena parasnya yang ayu, tapi lebih pada pemikirannya. Wanita ini sangat terobsesi dengan perilaku sosial di dunia online. Di tahun itu (2004), Facebook baru saja berdiri. Gina meyakinkan Marc bahwa jejaring sosial akan tumbuh dengan pesat. Dan dia tak ingin melewatkan ini semua.
Marc menyambut ide anak California tersebut. Namun dia ingin membangun situs jejaring sosial yang berbeda dari yang ada. Lelaki itu ingin sebuah situs yang menyediakan platform terbuka, yang membuat orang bisa berkreativitas total, mewujudkan apa yang mereka inginkan. Sebuah diferensiasi dibanding jejaring sosial yang lebih dulu hadir.
Maka lahirlah Ning. Gina menjadi CEO-nya, sementara Marc menjadi Chief Technology Officer-nya. Uang Marc sebesar US$ 15 juta dikucurkan sebagai dana awal. Berdua, dan dibantu 14 karyawan, mereka membangun Ning selama 2 tahun (2004-2006). Tak ada hiruk-pikuk ketika mereka mengembangkan situs ini dalam sebuah operasi bernama "24 Hour Laundry". Suasana gempita baru mulai pada November 2006 di Palace Hotel, San Francisco ketika Gina mengumumkan peluncuran Ning, didampingi Marc.
Dalam bahasa Cina, Ning artinya damai, “Ning itu singkat, manis, dan tak akan pergi dari fokus utama jasa kami: jejaring sosial Anda. Jasa kami, adalah seputar Anda, bukan kami.” Begitu tulis Gina dalam blog Ning.
Dia benar. Ning adalah platform online untuk para pengguna yang ingin menciptakan situs sosial serta jejaring sosialnya masing-masing. Di situs ini, setiap orang bisa bergabung atau membangun sendiri jejaring sosialnya dengan topik yang mereka suka, butuhkan, dan dengan audiens yang spesifik. Climate change, misalnya. Anda tertarik wacana perubahan iklim, tinggal mendaftar.
Atau, katakan Anda ingin membangun situs yang isinya adalah teman-teman sekolah SD dulu, maka tinggal masuk ke Ning. Buat situs sesukanya. Undang teman-teman sekolah. Seperti halnya Facebook atau MySpace, Ning juga punya halaman profil, foto, video, dan messaging. Jadi, buatlah nama jejaring sesuka hati, pilih layout-nya, maka terujudlah jejaring sosial milik Anda.
Pendek kata, segala hal tentang Ning adalah tentang hal-hal yang bisa dikustomisasi. Kalau memahami bahasa web seperti HTML, bisa merekonstruksi tampilan situs. Tak terlalu jago? Tak usah ambil pusing, tinggal gunakan template yang ada. Situs ini gratis jika mengijinkan iklan lalu lalang di situs Anda. Jika tak mengijinkan iklan, bayarlah fee bulanan ke Ning.
Simpel dan menarik. Tapi, seperti diulas di atas, di awal kemunculannya Ning dianggap sepi. Banyak kritik mengatakan bahwa orang tak ingin membangun jejaring sosialnya sendiri. Tak sedikit pula yang meyakini buah karya Marc-Gina ini akan sulit menandingi, atau malah menjungkalkan MySpace dan Facebook. Padahal, Gina berharap situsnya dapat bersaing dengan MySpace serta Facebook yang kantornya hanya di seberang jalan kantor Ning di Palo Alto.
Namun, waktu menjawab itu semua. Ning terus meroket sekaligus membungkam kritik. Platform-nya yang terbuka dan terkustomisasi menarik minat orang untuk menggunakannya. Bahkan tak sampai setahun setelah peluncuran, tepatnya Juli 2007, Ning menarik minat investor: mendapat suntikan US$ 44 juta dari pemodal ventura yang dikomandoi Legg Mason dan T. Rowe Price.
Ketika ditanya apa rahasia sukses Ning, Marc menjawab demikian: "Pada umumnya, pada layanan social networking, pengguna bergabung dengan satu jejaring sosial besar yang didesain dan dijalankan oleh pemegang layanan (pembangun situs),” katanya. "Users kemudian mengundang pengguna lainnya untuk bergabung di jejaring yang sama. Ini adalah apa yang disebut sebagai viral loop.” Kalau Ning?
“Pada Ning, users bisa bergabung dengan jejaring yang sudah ada, maupun menciptakan jejaringnya sendiri. Ini adalah double viral loop. Ini rahasianya. Model ini akan menciptakan situasi berikut: semakin banyak jejaring di Ning, semakin banyak user yang diundang bergabung. Dan kian banyak user yang bergabung, maka makin banyak pula jejaring baru yang tercipta.” Demikian uraian Marc yang meyakini model double viral loop punya keunggulan dibanding situs jejaring sosial lainnya.
Tapi tak semua orang meyakini kehebatan Ning. Tak sedikit pula yang tetap skeptis atas masa depan online social networking. Terhadap yang seperti itu, secara personal Marc merasa tak perlu membuktikan apapun. “Ketika usia Anda 35 tahun, Anda akan mulai punya pemahaman yang bagus tentang hal yang mungkin dan mustahil untuk dilakukan,” jelas pria kelahiran 9 Juli 1971 ini kalem. Yang jelas, dia mengaku punya ambisi besar: bila saatnya tepat, dia ingin menjual Ning menjadi miliaran dolar-nya yang ketiga, yang tentu membuatnya semakin kaya.
Tampaknya ambisi itu bukan sesuatu yang mustahil bila melihat kecenderungan yang belakangan kian marak: banjir uang di era Web 2.0 yang kental dengan model jejaring sosial dan pola saling berbagi (sharing) secara interaktif, entah itu foto maupun video. Ambil contoh Mark Zuckerberg. Pendiri sekaligus CEO Facebook ini telah mengundang banyak investor untuk turut mengembangkan situs yang baru seumur jagung dibesutnya. Dan investor itu sendiri telah menikmati keberuntungan. Salah satunya, Peter Thiel. Uang yang dibenamkannya sebesar US$ 500 ribu saat membangun Facebook, sekarang nilainya telah mencapai US$ 750 juta (Fast Company, Mei 2008).
Zuckerberg sendiri menyusul rekan-rekannya. Sebelumnya, News Corp. telah membeli MySpace senilai US$ 580 juta, Google membeli YouTube milik Chad Hurley dan Steven Chen senilai US$ 1,65 miliar, dan eBay memborong PayPal serta Skype (masing-masing senilai US$ 1,5 miliar serta US$ 2,6 miliar). Adapun Yahoo! membeli Flickr senilai US$ 35 juta dari pembuatnya, Stewart Butterfield. Flickr adalah situs berbagi foto.
Gebrakan teranyar adalah LinkedIn. Situs jejaring profesional yang telah menarik 23 juta user yang bergabung untuk mencari kerja, mencari karyawan, dan kemungkinan mengerjakan proyek bisnis bersama-sama ini, terus membetot investor. Pada 17 Juni 2008, Bain Capital Ventures, Bessemer Venture Partners, Sequoia Capital, dan Greylock Partners membenamkan US$ 53 juta ke situs ini. Hebatnya, uang sebesar itu hanya untuk membeli 5% saham LinkedIn. Mereka yakin akan masa depan LinkedIn sekalipun mesti mengucurkan uang untuk jumlah saham yang terbilang kecil. Pembelian 5% saham ini menjadikan LinkedIn bernilai US$ 1,015 miliar.
Dengan mendesain produk secara tepat, bisnis miliaran dolar di jagat Internet kini memang sangat dimungkinkan. Kini, Ning ditaksir sedikitnya bernilai US$ 500 juta dan kian popular dengan page view yang meningkat 10% setiap minggunya. Ke depannya, tak mustahil Marc meraup miliaran US dolar untuk perusahaannya yang ke-3. Sebuah pencapaian yang kian mengukuhkannya sebagai sang legenda hidup.
Terlepas dari itu, Ning kini menjadi salah satu ikon Web 2.0 yang diperhitungkan selain Google, YouTube, Facebook, MySpace, Digg, LinkedIn, Twitter, dan Flickr. Menjadi ikon setelah diragukan.
Labels:
Leadership
Friday, April 3, 2009
Tiga Menguak Cokelat

Kerajaan cokelat keluarga Chuang tak bisa dilepaskan dari sentuhan midas generasi kedua. Siapa saja mereka? Apa nilai-nilai dan budaya perusahaan yang mereka kembangkan?
Teguh S. Pambudi
Beromset Rp 8 triliun dengan sejumlah merek yang berjaya di 17 negara. Itulah bisnis keluarga Chuang. Dengan bendera Petra Foods Limited sebagai holding-nya, skala usaha keluarga ini di bisnis cokelat memang tak bisa dianggap sepele.
Secara garis besar, bisnis cokelat keluarga dari Garut ini dibagi dua: produsen bahan baku cokelat (cocoa ingredient) dan produk-produk konsumer berbasis cokelat seperti cokelat batangan, wafer cokelat, biskuit cokelat, dan meises, yang dilabeli merek.
BusinessWeek pernah menyebut mereka sebagai pemain terbesar ketiga dunia untuk pemasok cocoa ingredients, berada di belakang ADM (Archier Daniels Midland) dan Cargill. “Kalau di Asia, kami yang terbesar,” kata Cynthia P., Sekretaris Korporat Grup Ceres – Operasi Indonesia, yang juga profesional kepercayaan keluarga Chuang. Ceres adalah salah satu anak usaha keluarga ini yang terkenal dengan salah satu produknya, meises.
Di Indonesia, bisnis keluarga Chuang diberi bendera PT General Food Industries yang 90% produknya diekspor. Sementara itu, produk konsumer berbasis cokelat dimasukkan dalam PT Ceres yang 85% produknya dipasarkan ke dalam negeri. Merek-merek utamanya antara lain Ceres, Silver Queen, Cha-cha, Delfi, Selamat, Take-It, Top dan Tulip. Di Indonesia merek-merek itu tak asing. Silver Queen misalnya, dari hasil studi berbagai lembaga riset pemasaran, merupakan pemimpin pasar di segmen cokelat batangan. Demikian pula Top, Cha-Cha, Delfi dan meises Ceres. Ditaksir, keluarga Chuang menguasai 60% pasar cokelat bermerek Indonesia.
Di tangan generasi ke-2, yakni John, Joseph dan William Chuang, omset bisnis keluarga yang mempekerjakan lebih dari 3.000 karyawan ini terus menjulang, tembus Rp 8 triliun. Menariknya, meski terbilang sangat sukses, keluarga Chuang bukan sosok keluarga pengusaha yang beken di Tanah Air. Mereka cenderung low profile.
Lantas, siapa mereka sebenarnya?
John, Joseph dan William. Ketiganya adalah tokoh di balik menjulangnya bisnis cokelat keluarga Chuang lewat bendera Petra Foods Limited. Ketiganya adalah orang-orang yang menguak takdir bagi bisnis cokelat rintisan orang tua.
John Chuang Tiong Choon (60 tahun) adalah anak tertua dari lima bersaudara putra-putri mendiang M.C. Chuang. MBA dari Cranfield Business School ini adalah sosok yang menjadi motor utama sekaligus patron bisnis keluarganya, terlebih setelah M.C. Chuang mangkat di awal 1990-an. Lahir hanya beberapa tahun sebelum sang ayah mulai merintis bisnis cokelat di Garut, John mengantar Petra Foods bertransformasi menjadi pabrikan dan pemasok pemain cocoa ingredients nomor 3 di dunia dengan menjangkau lebih dari 30 negara.
Forbes mencantumkan John serta keluarga Chuang sebagai orang tajir Singapura nomor 31, dengan nilai kekayaan US$ 185 juta. Kemakmuran tersebut dihimpun dalam naungan perusahaan induk, Petra Foods, yang didirikan John pada 1984, yang kemudian terdaftar di bursa Singapura tahun 2004 dan dinobatkan sebagai pendatang bursa terbaik.
Tak mudah mendeskripsikan John serta dua adik lelakinya. Kesamaan dari ketiganya adalah mereka low profile. Jauh dari publikasi dan jepretan kamera wartawan. Mereka bukan CEO selebriti yang wira-wiri keriuhan acara sosialita ataupun media masa. Mereka tipikal para pemimpin bisnis yang digambarkan James Collins dan Jerry Porras dalam bukunya, Built to Last,sebagai orang-orang yang fokus pada pengembangan bisnis. Kesamaan lain adalah seperti diutarakan John yang dikutip Business Times, “Darah saya adalah cokelat. Ketika bangun pagi memikirkan kakao, siang dan malam hari memikirkan kakao dan cokelat.”
Cokelat, cokelat, dan hanya cokelat. Itulah yang mereka pikirkan. “Ketiga orang itu belum ada yang menandingi. Beliau-beliau itu hanya dengan menjilat sedikit saja sudah tahu apakah cokelat itu berkualitas atau tidak. Bahkan, terkadang dengan mencium baunya saja dapat menentukan bagus- tidaknya,” ujar Udja Sudjana, mantan karyawan PT Ceres, menyebut kehebatan tiga bersaudara itu dalam urusan cokelat.
Udja, lelaki separuh baya itu, masih terlihat segar di usianya yang ke-58 tahun. Tiga tahun lalu dia pensiun setelah mengabdi lebih dari 30 tahun. Kemudian, atas permintaan manajemen Ceres, dia dipekerjakan kembali sebagai konsultan mesin, yang kontraknya berakhir Agustus 2008. “Pak John pernah bilang, ‘Kamu, selama masih semangat, jangan berpikir untuk berhenti. Teruslah bergabung bersama.’ Karena itulah, saya bekerja berhati-hati jangan sampai mengecewakan,” kata lelaki yang bertugas memeriksa mesin pabrik Ceres di Filipina yang merupakan pabrik pertama keluarga Chuang di luar negeri.
Distribusi, konsistensi membangun merek, dan upaya untuk fokus pada bisnis cokelat memang menjadi pilar sukses keluarga Chuang. Akan tetapi, nilai kekeluargaan yang dibangun dalam keluarga ini tak pelak juga menjadi pilar suksesnya.
Di keluarga Chuang, pemutusan hubungan kerja diharamkan terjadi. Salah satu filosofi M.C. Chuang adalah jangan pernah mengeluarkan karyawan kecuali karena dua hal: mati dan mencuri. Jangan heran bila menjumpai karyawan yang puluhan tahun, sampai 40 tahun, bekerja di perusahaan ini. Atau yang seperti Udja, dipekerjakan kembali setelah pensiun. Kerja keras, loyalitas, kejujuran dan kekeluargaan menjadi values. Dan nilai-nilai ini ditanamkan sejak M.C. Chuang merintis usaha dan memindahkan operasional Ceres dari Garut ke Bandung di 1950-an.
Mendiang Chuang senior, di mata Udja, merupakan sosok yang dekat dengan karyawan. Terkadang dia malah lebih dulu menyapa jika bertemu karyawan. “Mereka biasa dirangkul Pak Chuang lalu ditanya apakah sudah berkeluarga dan senang bekerja di Ceres,” Udja menjelaskan. Matanya menerawang sembari mengingat masa lalu ketika dia sendiri pernah dirangkul Chuang senior. “Waktu itu beliau bilang pada saya, ‘Ini pabrik adalah sawah ladang kalian. Cobalah dikelola bersama-sama. Mati-hidup kita adalah dari sini. Betul saya memang yang memilikinya, tapi kalian yang mengelolanya’.”
Bagi sejumlah karyawan, sosok Chuang senior tak bisa dilupakan begitu saja. Itu bisa terlihat bila mengunjungi kantor Ceres di Bandung.
Patung M.C. Chuang terpaku di samping meja resepsionis yang menghadap tangga menuju lantai 2 kantor PT Ceres di Jalan Moh. Toha 94, Bandung. Bersuasana modern minimalis, kantor yang didominasi warna krem dan putih itu berdampingan dengan kantor dan pabrik “saudaranya”, PT General Food Industries, yang memproduksi cocoa ingredients, PT Nirwana Lestari, sang distributor produk. Total, mereka menempati lahan seluas lebih dari 10 hektare. Lahan ini terus diperluas sejak 1970-an ketika Ceres masih hanya pabrik kecil satu lantai.
Di sepanjang ruas Jalan Moh. Toha, hanya mereka yang bergerak di industri makanan. Yang lainnya adalah pabrik tekstil. Melewati kompleks Ceres, akan segera tercium aroma khas terpanggang. Tertiup angin, aroma yang menyengat hidung itu bisa dihirup dari pinggir jalan yang jaraknya puluhan meter dari pabrik. Dari sinilah sebagian produk meises Ceres, Silver Queen dan biskuit Selamat yang manis di lidah itu dibuat. Dari sini pula M.C. Chuang mulai memutar roda bisnisnya.
Dibentuk dari tembaga, patung di samping meja resepsionis yang berwujud setengah badan tanpa lengan itu menampilkan raut wajah orang tua yang sederhana. Inilah patung yang mengapresiasikan penghormatan anggota keluarga pada sang ayah, pendiri dan panutan bisnis yang telah mempekerjakan ribuan orang semasa hayatnya.
Kesederhanaan Chuang senior, menurut beberapa karyawan Ceres, menurun pada anak-anaknya. Penulis sendiri sempat bertemu Joseph di tahun 2005, dalam kesempatan wawancara untuk penulisan buku Advertising that Sells, yang mengupas strategi Dwi Sapta menopang merek-merek lokal menjadi pemimpin pasar lewat iklan-iklannya. Meises Ceres dan “keluarga” biskuit Selamat (Selamat, Briko, Funtime, Any Time) adalah merek milik Ceres dan General Food Industries yang komunikasinya ditangani Dwi Sapta.
Sepanjang pertemuan di Hotel Four Seasons, Jakarta, itu, Joseph lugas menjawab pertanyaan. Mengenakan baju lengan panjang yang digulung hingga siku, di sore hari itu dia tampil sederhana untuk kelas manusia puluhan juta dolar. Bajunya, yang kancing atasnya terbuka, membuatnya seperti bukan juragan kelas dunia. Selalu tersenyum dan tertawa setiap menjawab pertanyaan, dia dekat dengan kesan sersan: serius tapi santai. Dengan nada sopan dan halus, dia yang didampingi Ridwan C. Kidjo, Direktur Penjualan PT Ceres, selalu menolak ketika penulis mengutarakan keinginan meliput bisnis keluarga Chuang yang saat itu menjadi sorotan media-media Singapura. “Liput saja brand-brand kami. Saya sih nggak penting,” kata lelaki bernama Joseph Chuang Tiong Liep ini diiringi tawa berderai. Buat mereka, yang penting adalah the song, not the singer.
Kendati bergaya sederhana, pria 57 tahun ini adalah penikmat seni kelas tinggi. Dia adalah kolektor sekaligus investor lukisan papan atas. Di lantai 2 kantor Ceres, tergantung beberapa lukisan dengan ukiran “Collection of TLC” di bingkainya. TLC adalah akronim Tiong Liep Chuang. “Dia itu berburu sampai ke balai lelang Christie’s. Kalau harganya sudah naik, baru dia lepas, seperti berdagang saja,” kata seorang sumber, sebut saja Donny.
Saking terkenalnya sebagai kolektor lukisan, beberapa balai lelang serta galeri ternama terkadang meminjamkan lukisannya untuk dipajang Joseph. ”Kalau suka, baru dibayar setelah beberapa waktu. Kalau tidak, ya… diambil lagi sama pemilik galeri,” ujar Donny. Joseph sendiri bisa melukis. Namun, itu hanya untuk konsumsi pribadi, dipajang di rumahnya di Jakarta dan Singapura.
Tak seperti abangnya yang mengontrol bisnis dari Singapura dan tengah sibuk membangun pabrik pengolahan kakao di Jerman, Joseph lebih banyak bermarkas di Cibitung. Di Petra Foods, jabatan John adalah CEO Grup, sementara Joseph menjadi Presdir Divisi Branded Consumer mengendalikan operasional bisnis di Indonesia. Dengan posisi itu, Joseph sangat diandalkan sang kakak untuk mengurusi bisnis bermerek (Silver Queen, meises Ceres, dsb.) yang menyasar ke sektor ritel, terutama modern trade yang bernaung di PT Ceres. Dan, Joseph dikenal mitra-mitranya sebagai orang yang luwes dalam melobi untuk mempertahankan sekaligus meluaskan penetrasi produk-produknya.
Pudjianto, Direktur Pengelola PT Sumber Alfaria Trijaya (pengelola Alfamart), melukiskan hal tersebut. “Top ketemu top. Duduk satu meja sambil makan siang. Beberapa kali saya yang ketemu dengan Joseph Chuang. Setahun sekali mesti ketemu saya atau Bu Feny, kadang-kadang Pak Djoko juga,” tuturnya. Djoko Susanto adalah bos Alfa, sementara Feny adalah anaknya yang kini menjabat Presdir PT Sumber Alfaria Trijaya.
“Saya beberapa kali saja bertemu beliau. Sifatnya informal, ya, jadi pas beliau datang ke Bandung, lihat pabriknya, beliau sempatkan ke sini. Ajak makan distributor Bandung, lalu sambil lihat-lihat ke toko-toko pinggir jalan, tanya-tanya ke pedagang bagaimana kondisinya, tanya apa yang kurang dari Ceres. Dia teliti, hal-hal kecil nggakluput, sampai difotoin segala, walau jabatannya sudah bos, ya,” ungkap Hari, Manajer Operasional Sumber Utama Priangan (SUP), distributor Ceres untuk wilayah Kotamadya Bandung.
“Orangnya biasa-biasa saja penampilannya, nggak sok bos atau gimana,” lanjut pria yang telah bekerja di SUP sejak 1983 itu. “Beliau juga nggakotoriter, mau membina dan mendengarkan distributor. Jika ada keberhasilan di satu distributor, ditanyain detail, untuk menjadi pelajaran juga buat yang lain. Sebaliknya kalau ada yang distributor yang kurang berhasil, juga ditanya sampai detail mengapa bisa gagal.”
Hubungan dengan distributor ini betul-betul dijaga oleh Joseph sehingga terjalin kemitraan yang erat. Edward Hilman, Direktur PT Trijaya Makmur Lestari (TML), punya kesan tersendiri. Sebagai distributor Ceres, TML boleh dibilang ikut mengalami pasang-surutnya bisnis keluarga Chuang. Pendiri TML, yakni kakek Edward, sangat percaya bahwa menjadi bagian dari bisnis Ceres tidak hanya bagian dari bisnis, tapi juga bagian dari tradisi. “Banyak sih nawarin ke kami (untuk mendistribusikan produk lain), tapi kami tolak. It's not only about money. Asal kami fokus, pasti akan berhasil,” ujar Edward.
Kakek Edward, yang asli Bandung, adalah rekan Chuang senior. Sewaktu bisnis Ceres masih kecil, M.C. Chuang memercayakan distribusi produk kepada rekan-rekannya sendiri. Kakek Edward dipercaya mengurus distribusi wilayah Bandung. Selain dia, Chuang mengangkat rekannya yang lain untuk memegang distribusi di daerah, antara lain di Medan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan Sulawesi. Mereka ini boleh dibilang distributor eksklusif produk Ceres. Meski tidak ada larangan dari Ceres untuk memasarkan produk lain, tapi secara moral mereka merasa ada keterikatan dengan keluarga Chuang.
Itulah yang terjadi pada Edward. Total produk Ceres yang dijual TML kini mencapai 400-an item. TML termasuk distributor yang berprestasi. Anak perusahaannya di Tasikmalaya pada April 2007 mendapat gelar Distributor Terbaik 2007, sekaligus mendapat Chuang Cupatas prestasinya sebagai distributor berkinerja memuaskan (tumbuh 30% ke atas) selama tiga tahun. ”Saya sedikit-banyak terinspirasi oleh Pak Joseph, terutama semangatnya. Dia selalu katakan, 'Jadilah yang terbaik.' Kami juga ingin jadi yang terbaik di antara distributor karena kesempatan kami sama,” papar Edward.
Joseph memang rajin turun ke bawah, menghubungi para distributor, memompa semangat mereka, dan juga bertemu petinggi gerai modern. Seperti halnya John, dia relatif jarang di Bandung. “Tapi sekali datang ke Ceres, dia seharian di kantor. Dari pagi sampai malam. Pukul 7 pagi sudah datang dengan Land Rover-nya,” ujar seorang sumber tentang Joseph yang kerap menyebut “my man” untuk orang-orang yang dipercayainya, dan menyebut “my friend” untuk mereka yang dianggapnya dekat dengan dirinya.
Lantaran jarang datang dan penampilan mereka yang sederhana, banyak karyawan di Bandung yang tak mengenal John serta Joseph. Mereka, menurut Udja, sering tidak tahu bahwa yang sedang lewat di depan mereka adalah pemilik Ceres. Di samping rapat yang sesekali diadakan di Bandung, ketiga kakak-beradik biasanya berkumpul saat ulang tahun Ceres, 20 Januari.
Operasional di Bandung memang lebih banyak diserahkan ke adik terkecil, William Chuang Tiong Kie (49 tahun). Berperawakan lebih gemuk ketimbang kakak-kakaknya, William menjabat COO Divisi Branded Consumer Foods. Namun, oleh John, dia juga ditugasi mengurus bisnis yang terkait kalangan korporasi.
Seperti abang-abangnya, William yang juga berkacamata adalah orang yang murah senyum. Tawa tak pernah lepas dari bibirnya. Penampilannya pun sederhana, kerap mengenakan kemeja biasa yang dipadupadankan dengan celana pantalon. Seperti Joseph, dia jarang mengenakan jas. Dan seperti kedua kakaknya, dia juga tak suka yang rumit-rumit. Pikiran berbisnisnya sangat praktis. Toh, oleh John, dia yang sering menginspeksi pabrik dari depan hingga belakang ini diminta selalu mengontrol aspek compliance dalam bisnis keluarga Chuang.
Dari ketiganya, John adalah sosok yang paling dihormati dan disegani. Bukan hanya oleh karyawan yang mengenalnya, tapi juga oleh adik-adiknya. “Orangnya lugas,” ujar seorang sumber. Bertemu John, atau meeting dengannya, berarti harus well prepared dan siap untuk hal-hal yang rinci. Namun, ada kesamaan bila meeting atau dijamu ketiga anak M.C. Chuang ini: habiskan yang mereka tawarkan. “Itu menunjukkan kita menyukai makanan mereka. Mereka juga suka kita berlaku seperti itu,” ujar Donny dengan nada serius.
Di luar sejumlah kesamaan, menurut Donny, ketiganya juga memiliki karakter yang khas, yang lebih terkesan sebagai pembagian tugas. Dengan sikapnya yang lugas, John adalah ahli strategi dalam keluarga. Joseph lebih bersikap sebagai motivator dan pemasar. Sementara William lebih sebagai orang yang mengurusi aspek operasional.
Kendati ada pembagian tugas, ada salah satu budaya perusahaan yang menyatukan mereka: window shopping ide-ide bisnis dan pengembangan produk. Dalam setahun, ketiga kakak-beradik ini akan menyebar ke pelbagai penjuru dunia. Sambil piknik, sambil vacancy,mereka mewajibkan pulangnya harus membawa oleh-oleh produk yang inspiratif untuk dibedah tim riset & pengembangan (R & D). Selain dibedah, produk yang mereka beli terkadang juga dijadikan mitra. Inilah yang terjadi ketika John ke Afrika Selatan. Di sana dia menjumpai jus bermerek Ceres. Tanpa berpikir panjang, John mengajukan diri menjadi distributornya. Bila menjumpai jus Ceres di gerai modern di Indonesia, itu adalah produk milik produsen Afrika Selatan yang didistribusikan Nirwana Lestari.
Proses mengeluarkan produk baru banyak bergantung pada ketiga anak M.C. Chuang. Lazimnya, mereka mengadakan rapat dan menggulirkan ide pada tim panel. Tim panel yang juga merangkap sebagai tim R & D mencoba menerjemahkan jenis rasa dan produk yang diminta oleh Chuang bersaudara. Setelah itu, setiap tim R & D membuat resep tertentu. Untuk mengetes kelaikan sebagai produk Ceres, Chuang bersaudaralah yang menjadi tempat terakhir mencicipinya. Mereka yang menentukan sudah sesuai atau belum dengan yang diinginkan.
Udja mengaku tidak heran dengan kemampuan ketiganya dalam citarasa. John dan kedua adiknya yang semuanya menempuh SMA-nya di Singapura kerap diberangkatkan sang ayah untuk memperdalam ilmu tentang cokelat di luar negeri. Mereka sering mengikuti kursus tentang bagaimana menghasilkan citarasa yang baik. “Mereka belajar mengatur komposisi takaran fat content atau lemak dan susu, apakah terlalu manis atau sudah pas. Mereka sangat peka dengan rasa,” ujarnya. Dan tidak mengherankan pula, di kantor Ceres banyak dijumpai aneka produk mancanegara.
Bukan cuma peka rasa. “Jiwa perang mereka itu sangat tinggi. Begitu ada gerakan kompetitor, langsung kumpul. Mereka beli produknya, dianalisis, diuraikan, dan dilihat secara fisik. Strukturnya dibedah,” Donny menjelaskan.
Gabungan ketiga orang inilah yang diyakini menjadi pilar utama kesuksesan bisnis keluarga Chuang di samping nilai-nilai yang dikembangkan sang ayah (kerja keras, loyalitas, kejujuran dan kekeluargaan). Karakter ketiganya pun tak bisa dilepaskan dari pola asuh yang dikembangkan M.C. Chuang.
Chuang senior tak langsung menarik anak-anaknya untuk menggeluti bisnis keluarga. Agar anak-anaknya punya pengalaman bisnis yang matang, selain menitahkan kursus citarasa, dia pun memberikan keleluasan bekerja di mancanegara. Dan, karier mereka juga cemerlang.
John, misalnya, pada 1979-83 menjadi Vice Chairman Bank of California dan Presiden Wardley Development Inc., California. Saat kembali pada 1984, dia mendirikan Petra Foods.
Joseph sempat menjadi Presiden McCoa Inc., Filippines, 1980-83. Dia bergabung dengan PT Perusahaan Industri Ceres pada 1984.
Adapun William, selulus dari California State University Long Beach tahun 1984 sempat menjadi Analis Finansial W. R. Grace (New York), 1984-85. Setelah itu, di usia 26 tahun dia bergabung dengan Ceres sebagai penasihat teknis.
Dengan pengalaman-pengalaman inilah, mereka punya bekal ketika sang ayah memanggil pulang untuk mengurusi bisnis keluarga. Akan tetapi, kabar yang berembus adalah mereka sendiri justru tengah kesulitan melakukan regenerasi. Generasi ketiga Chuang yang kini berusia pertengahan 20 tahunan itu cenderung lebih suka menggeluti sektor lain di luar, antara lain komunikasi dan teknologi informasi. “Generasi ketiga nggak mau gabung, karena nggak mau kotor. Generasi ketiga melihatnya tidak sarat teknologi, tradisional dan tidak menarik,” ungkap Donny.
Itulah sebabnya, pada tiga tahun terakhir keluarga Chuang sempat menarik beberapa profesional dari luar untuk mengelola Ceres dan General Food, termasuk dari Indofood dan Grup Rajawali. Dan tatkala para profesional ini hengkang karena satu dan lain hal, maka Joseph pun terpaksa turun tangan kembali. Lantas, bagaimana masa depan regenerasi di keluarga Chuang?
“Selanjutnya, tampuk kepemimpinan akan diserahkan kepada profesional, pada saatnya nanti. Perkiraan saya, tidak ada regenerasi ke generasi ketiga dari founder. Exit strategy mereka adalah ke konsultasi,” kata seorang mantan konsultan Ceres. Artinya, kakak-beradik Chuang lebih akan memosisikan diri sebagai tempat bertanya bagi para eksekutifnya, tak ubahnya konsultan.
Bagi sebagian orang, ketidakterlibatan generasi penerus dalam bisnis keluarga mungkin sebuah ironi. Akan tetapi, di tengah paradigma bisnis keluarga masa kini yang lebih menonjolkan profesionalisme ketimbang darah biru, hal itu tampaknya bukan sesuatu yang bisa dihindari. Dan rasanya, ketiga Chuang akan menghadapi itu dengan kepala dingin. Maklum, setelah mentransformasi bisnis keluarga Chuang sejak 1984 -- saat John dan Joseph mulai bergabung -- bagi mereka yang terpenting adalah bisnis itu sendiri, bukan para pengelolanya. Dan inilah yang mendorong keluarga Chuang mengalir ke lebih dari 30 negara.
John, Joseph dan William sangat memahami ini.
Labels:
Strategy