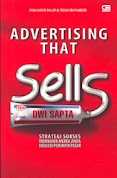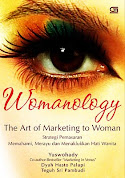Produknya
menjadi bintang industri telepon seluler. Dengan kian berkembangnya teknologi
layar sentuh, mereka pun akan kian dibutuhkan. Tapi kecemerlangan itu tak bisa
terjadi tanpa tiga rahasia yang dibangun lebih dari satu abad.
KULTUR INOVASI
Amory Houghton pastinya tidak akan pernah tahu bagaimana
digdayanya kelak perusahaan kaca yang dibelinya di kota Corning, New York tahun
1851. Kini siapa yang tak mengenal Gorilla Glass sebagai kaca premium yang
digunakan terutama oleh industri smartphone.
Produk keluaran Corning Inc. ini menjadi jaminan kaca ponsel yang anti gores
dan tak mudah pecah. Tercatat, sedikitnya 1 miliar hand held devices telah menggunakannya. Dan akan semakin banyak
jumlah yang menggunakannya dari waktu ke waktu.
Tentu saja pecapaian ini merupakan buah dari perjalanan yang
panjang, terutama dalam lingkungan perusahaan yang dibeli Amory, Corning Inc.
Gorilla Glass, sebut contoh. Produk primadona ini merupakan buah dari akar yang
sudah ditanam lebih dari satu abad lamanya sehingga para peneliti Corning mampu
menjawab kebutuhan pasar.
Cerita Gorilla Glass dimulai tahun 2006. Steve Jobs mendatangi CEO Corning Inc., Wendell Weeks. Jobs
meminta dibuatkan kaca untuk layar iPhone yang akan diluncurkannya. Kaca yang
ringan, kuat dan anti gores. Kaca yang berbeda dengan telepon seluler biasa.
Saat itu, umumnya layar ponsel masih banyak berupa layar plastik yang begitu
mudah rusak ketika ponsel jatuh. Pun mudah tergores sehingga mengurangi penampilan.
Mencium peluang bisnis,
sebuah tim kecil di divisi specialty
material Corning segera mencari arsip-arsip yang memuat formula tentang
pembuatan kaca yang sangat kuat tapi fleksibel, sesuatu yang disebut Chemcor,
yang pernah gagal saat diperkenalkan pada tahun 1962 untuk industri otomotif. Formula
ini akan mereka uji cobakan pada telepon seluler, sekaligus menjawab tantangan
Jobs.
Jalan menuju sukses tak
selalu mudah. Biaya produksi untuk eksperimentasi ini mencapai US$ 300 ribu.
James Steiner, bos tim divisi ini menentang ide tersebut. “Saya benar-benar tak
bisa memahami konsep penggunaan kaca untuk telepon seluler,” Steiner mengenang.
Beruntung, sang team leader, Mark Matthews adalah orang
yang persisten dengan ide yang diyakini benar. Dan dia telah membuktikan
sebelumnya. Pada tahun 2003, Matthews sukses memimpin penjualan produk kaca
khusus ke Texas Instruments untuk proyektor digital.
Sekali lagi, mempercayai
insting Matthews, Steiner pun memberi lampu hijau untuk melakukan proyek
percobaan di Danville, Virginia. “Matthes mengambil semua risiko begitu mengetahui
saya tak terlalu antusias tentang rencana ini,” kata Steiner.
Kini, setelah lewat
beberapa tahun beredar di pasar, lembaran kaca alkali-aluminosilikat yang dilabeli
merek Gorilla Glass ini mencetak sukses besar. LG, Samsung, Motorolla
memilihnya untuk beragam ponselnya. Asus serta Dell memilihnya untuk sejumlah
laptop-nya. Dan tentu saja iPhone.
Gorilla Glass mencetak
penjualan US$ 100 juta dan diproyeksi mencapai US$ 500 juta di tahun 2015. Produk
ini menjadi kontributor signifikan bagi Corning yang total penjualan 2012
mencapai US$ 8 miliar.
Jelaslah bahwa inovasi
menjadi jantungnya Corning. Tapi ini tidak muncul begitu saja. Akarnya begitu
dalam, dimulai sejak era Amory. Saat mengambil perusahaan kaca kecil di Corning
ini, keluarga Houghton sangat percaya – bahkan cenderung menjadikannya sebagai
“agama” – pada apa yang disebut sebagai riset dan pengembangan. Sejak awal,
perusahaan ini memutuskan berinvestasi pada ilmu tentang pembuatan kaca untuk
menghindari persaingan dengan para produsen kaca berbiaya rendah (low-cost). Mulai dengan mematenkan kaca
sinyal untuk industri jalan raya dan kelautan, Corning memroduksi serangkaian
inovasi yang berasal dari pemahamannya atas kaca dan keramik.
Jadi, jauh sebelum CK
Prahalad dan Gary Hamel mengartikulasikan konsep core competence, manajemen Corning secara intuitif memahami
pentingnya perusahaan berinvestasi pada “core
competence”. Tak heran, perusahaan ini pun menjadi spesialis kaca yang disegani
sehingga disambat pihak lain.
Kapabilitas teknologinya membuat mereka mampu merespons permintaan pasar dengan
cepat.
Pada tahun 1880, ambil contoh, Thomas Edison yang setahun
sebelumnya menemukan lampu pijar, datang ke Corning untuk membuat kaca bohlam
bagi penemuan terbarunya itu, yang kemudian memunculkan manufaktur kaca bohlam
kecepatan tinggi. Inovasi yang lain adalah Pyrex yang diperkenalkan pada tahun
1915 dan produksi masal tabung TV di tahun 1940-an. Tapi Corning juga piawai
untuk produk lain. Diantaranya: ceramic
subtrates untuk catalytic converters di era 1970-an dan serat optik di tahun 1980-an.
Kultur inovasi menjadi
kunci. Pada kasus Gorilla Glass, seperti disinggung di atas, proses fusi yang
digunakan Corning untuk produk ini berawal di tahun 1962. Ketika itu Corning
berupaya membuat kaca yang lebih tipis dapi dan lebih kuat untuk kendaraan
bermotor. Sewaktu para pabrikan kendaraan menolaknya dengan alasan biaya,
Corning menyimpan teknologi itu hingga tahun 2006, saat CEO Apple, Steve Jobs
mengontak Wendell Weeks mencari kaca anti gores dan ringan buat iPhone.
 |
| CEO Corning, Wendell Weeks terus mendorong inovasi. Sumber : Forbes |
Namun kultur inovasi hanyalah
satu hal yang sudah berakar ditanam Amory. Yang menarik adalah bagaimana proses
R&D di tubuh Corning bisa melewati tahap demi tahap hingga sukses secara
komersial.
Seperti perusahaan top
lainnya, Corning punya sistem untuk mengelola ide melewati sejumlah tahapan.
Mereka memiliki apa yang disebut sebagai “Tahap 1-5” dengan urutan sebagai
berikut: research, applied research,
development, scale-up, dan production.
Kehebatan di Corning
adalah tahap demi tahap ini mayoritas berjalan baik: dari konsep ke sukses
secara komersial. “Jika saya punya 100 siswa di kelas dan saya tanya mereka
‘berapa dari Anda yang punya tahap-tahap proses di perusahaan Anda?’ Sekitar 95
orang mengangkat tangan,” kata Rebecca M. Henderson, Guru Besar Harvard
Business School yang mempelajari inovasi di Corning. “Tapi kalau saya bertanya,
‘berapa banyak dari Anda yang tahapan prosesnya berhasil?’ hanya sekitar 15
orang yang mengangkat tangan. Untuk perusahaan dengan ukuran dan kompleksitas
seperti Corning, apa yang mereka capai adalah luar biasa.”
Apa rahasianya?
TIGA RAHASIA
Ada tiga. Pertama,
organisasi yang solid, yang multidisiplin. Apa yang tampak dari Corning adalah
mereka menunjukkan bahwa inovasi dapat dikelola oleh individu atau tim kecil
yang berdiri terpisah, tapi dengan kelompok multidisiplin di seluruh lini
organisasi sebagai penopangnya. Yang menjadi konduktor adalah 2 lembaga:
Corporate Technology Council yang dipimpin CTO, David L. Morse, dan Growth
& Strategy Council, dipimpin Chairman
dan CEO, Wendell Weeks.
Organisasi yang pertama (Corporate
Technology Council) berkonsentrasi pada early
stage. Mereka mengevaluasi ide-ide yang ada dan memutuskan yang mana yang
akan didanai. Sementara organisasi berikutnya (Growth & Strategy Council) mengelola
tahap ide menuju komersialisasi. Mereka bergerak lebih detail, menyoroti biaya
dan rencana eksekusi.
Pada tahap awal, pada early stage, Corning memiliki amunisi
hebat untuk menciptakan produk, yang juga diwariskan sejak lama. Salah satu
sumber daya penting adalah para tenaga ahli di Sullivan Park Research Center,
di Erwin, New York, lokasi tempat fasilitas R&D. Di Sullivan Park yang
seluas 2 juta m2 inilah sejumlah terobosan teknis dilakukan seperti tabung cathode-ray, advanced purification materials, dan serat optik kualitas tinggi.
Untuk menggodok Gorilla Glass, contohnya, sedikitnya 100 ilmuwan terlibat dalam
proyek ini, baik terlibat penuh ataupun paruh waktu. “Para ilmuwan kami akan
bekerja di tempat di mana mereka meyakini bisa memberikan dampak dan
diapresiasi,” kata Steiner.
 |
| Gorilla Glass, kaca yang kuat, tipis dan fleksibel. Sumber: Corning |
Dalam kasus Gorilla
Glass, begitu uji produk telah selesai, Steiner segera bergerak ke seluruh
organisasi, meminta bantuan serta masukan tim sains, manajemen dan penjualan.
Tak banyak waktu terbuang. “Anda harus menempatkan seluruh sumber daya di
belakang sebuah peluang, dan segera melompat,” ujar Matthews, sang pemimpin
proyek. Sampel mulai dilakukan pada Desember 2007. Empat bulan kemudian Corning
meluncur di pasar dan mendapat sambutan antusias.
Itu yang pertama: tim
yang solid. Yang kedua, connecting to
customer yang juga telah lama dibudayakan. Selama pengembangan Gorilla,
Steiner memastikan bahwa para ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini bertemu
dengan calon pembeli potensial. “Kami harus menciptakan permintaan, dan para
ilmuwan kami adalah senjata komersial paling ampuh (untuk memahami pasar),”
katanya. Dengan berbincang pada pelanggan secara intens, para peneliti bisa
mengantisipasi kebutuhan pasar.
Di lingkungan Corning, sudah
menjadi budaya bila para ilmuwan memberikan prototipe produk di tahap awal
dalam rangka mencari umpan balik sekaligus kemungkinan pengembangan yang
dibutuhkan pasar. Para peneliti Corning memang diminta secara proaktif bertemu dengan
para pelanggan, terutama dari perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung dan
Sony untuk memahami sekaligus mengantisipasi kebutuhan teknologi seperti organic light-emitting diodes (OLEDs)
dan televisi 3D.
Rahasia ketiga adalah
dukungan total dari jajaran manajemen puncak. Menurut David L. Morse,
menghubungkan para ilmuwan dengan pelanggan adalah satu hal. Hal berikutnya
yang signifikan adalah kepemimpinan yang memahami pekerjaan para ilmuwan.
“Meluncurkan produk,” kata Morse, “itu seperti orang yang memegang air buat
para pelari marathon. Mereka harus ada di sisinya, melatihnya, dan
berpatisipasi di dalamnya. Kami harus membantu mereka dengan menyediakan
seluruh sumber daya.”
Lantaran iklim kerja
yang solid serta dukungan atasan yang total, bukan rahasia bila para ilmuwan di
Corning akhirnya terkenal enggan berpindah ke “lain hati”. Mereka loyal.
“Bahkan setelah pensiun pun mereka sering datang setiap hari,” kata Morse. Dan
para pimpinan Corning memfasilitasi para veteran ini. Mereka menciptakan apa
yang disebut sebagai program Safe Haven. Lewat program ini, para pensiunan
tersebut diperkenankan untuk menulis dan mengajukan proposal penelitian yang
akan didanai perusahaan, atau difasilitasi agar bisa didanai pihak lain.
Budaya inilah yang kuat
mengakar di dalam tubuh Corning. Dan mereka sangat bangga dengan budaya
tersebut. Terbukti, untuk urusan investasi riset dan pengembangan produk, manajemen
Corning tak henti mengucurkan dana. Pada saat banyak perusahaan memangkas biaya inovasi bisnisnya,
Wendell Weeks mengucurkan hanpir 10% dari pendapatannya untuk RD&E (research, development, and engineering).
Sekarang, Corning fokus
mereinvestasikannya pada produk-produk intinya: serat optik, kristal cair dan
tentu saja kaca Gorilla Glass. Mereka yakin masa depan cerah di ketiga sektor
tersebut. Terlebih pada Gorilla Glass. Mengapa?
“Pada pasar consumer electronics, aspek sentuhan telah
menjadi kebutuhan di mana-mana. Bahkan bayi pun main iPad dengan sentuhan.
Mereka ini akan tumbuh besar dan berharap bisa mendapat respons dari barang
elektronik yang mereka sentuh. Semuanya yang membutuhkan respons sentuhan akan
ada di mana-mana, di kulkas, komputer, dan segala hal di sekolah,” kata Morse.
Apa artinya? “Perusahaan akan membutuhkan kaca yang tipis dan kuat untuk
seluruh aplikasi ini.”
Tapi laiknya lahan yang
gurih, tak semua pihak rela Corning merajai segmen layar sentuh ini sendirian.
Belakangan, Gorilla Glass mendapat tantangan hebat dari GT Advanced. Perusahaan ini meluncurkan produk dengan merek Sapphire,
dan dengan janji serupa: produk layar anti gores dan anti pecah.
Tantangan GT Advanced Technologies tidak
main-main. Dalam satu kesempatan pada ajang Mobile
World Congress 2013 yang digelar Februari lalu, GT Advanced mendemokan
kekuatan material yang dipakai produknya, yakni lembaran batu safir saat
digesek secara keras dengan material kasar seperti batu. Hasilnya? Layar Sapphire
tetap mulus. Berbeda dengan layar Gorilla Glass menjadi pembanding dalam demo
tersebut, yang mudah tergores saat digesek dengan batu.
 |
| Sapphire, pesaing berat Corning. Sumber: Google |
Harga Sapphire memang lebih mahal 3 kali lipat
dibanding Gorilla Glass. Untuk memasang layar Saphhire pada sebuah smartphone, produsen mesti memayar US$
15, sementara Gorilla Glass US$ 5. Tapi GT Advanced berkoar produk mereka jauh
lebih hebat dibanding keluaran Corning. “Sebagus apapun Gorilla Glass tetaplah
kaca yang bisa pecah. Ini berbeda dengan Sapphire. Kendati ponsel terjatuh dari
ketinggian dan hancur, Sapphire tidak akan tergores sedikitpun”, ucap Dan
Squiller, COO GT Advanced.
Tentu saja pihak Corning tak mau berdiam diri.
Belakangan mereka merilis Gorilla Glass 3 yang diklaim lebih unggul dibanding Sapphire.
Bagaimana produk ini meyakinkan pasar, tentu masih ditunggu. Tapi Steiner dan
timnya kini terus berpacu karena menyadari sekali mereka kalah dari Sapphire
yang juga kini masih dalam tahap pengembangan, reputasi yang sudah dibangun
lebih dari satu abad akan ternoda. ***