Merek-merek
lokal yang berjaya di pasar global, tak bisa dilepaskan dari peran pemerintah,
pebisnis dan nasionalisme konsumen. Jepang, Korea Selatan dan China telah
membuktikannya.
INDIGENEOUS BRAND
Di kancah internasional, sebenarnya, istilah original brand boleh dikata
tidak terlalu populer. Tidak umum, bahkan. Istilah ini hanya merujuk pada
keaslian sebuah merek. Bahwa merek itu dipatenkan sebagai yang pertama kali. Lawannya,
atau yang biasa dihadapkan pada terminologi ini adalah “counterfeit brand”
atau “fake brand”. Merek palsu yang mengekor, yang melakukan tindakan
meniru.
Untuk
merujuk pada istilah “merek asli” dari sebuah negara, terminologi yang umum
digunakan adalah “national brand” atau “local brand”. Bahkan Katsuhiro
Sasuga, Associate Professor Department of International Studies, Tokai
University menyebutnya dengan istilah “indigenous brands”, merek
pribumi. Adapun yang menjadi tandingannya adalah “global brand” atau “international
brand”.
Okelah,
sedikit lupakan tentang terminologi “original brand” yang boleh jadi
bermain di ranah semantik. Yang menarik, sebagaimana ditulis Sasuga, bicara
tentang mengembangkan merek lokal, kalangan pemerintah kerap kali terlibat.
Terutama di wilayah Asia Timur. Satu kasus menarik yang diketengahkannya adalah
bagaimana merek-merek otomotif lokal China, mampu bersaing dengan nama-nama
besar otomotif dunia.
Ketertarikan
Sasuga bermula dari produksi industri otomotif China yang terus melesat. Di
tahun 2006 melewati Jerman, lalu melampaui AS di tahun 2008, dan Jepang di
tahun 2009. Di tahun 2010, pabrikan China bahkan sanggup memproduksi 18,26 juta
unit (23,5% dari total produksi otomotif di dunia), sementara gabungan AS dan
Jepang mencapai 40%. Di tahun 2010, penjualan otomotif domestik Negeri Panda ini
mencapai 18,06 juta unit (AS 11,58 juta unit, sementara di Jepang 4,94 juta
unit).
Bukan
hanya jumlah produksi yang menarik perhatian Sasuga. Di tahun 2009 sedikitnya
ada 258 merek mobil penumpang di China. Dari total merek yang bersaing
tersebut, merek lokal China mencapai 145 merek. Dari merek lokal yang ada, 3 nama
menyeruak menjadi penantang yang hebat, yakni BYD (berbasis di Shenzhen), Chery
(bermarkas di Anhui) dan Geely (di Zhejiang). Teristimewa adalah Chery yang
dalam setahun mampu menjual lebih dari 3 juta unit.
Dalam
tulisannya, The Rise of the Chinese Indigenous Brands, Sasuga menyebut
pemerintah China sangat berperan di balik melejitnya merek-merek otomotif lokal
tersebut, terutama mobil. Dari penelusurannya, aktivitas pemerintah dimulai
tahun 1979. Saat itu China mulai memburu teknologi maju dari para pabrikan
mobil asing. Mereka menawarkan potensi pasar China untuk teknologi otomotif asing.
Namun pemerintah tak mau sekadar mengundang pemain luar. Mereka menyaratkan
satu hal: bila ingin berproduksi di negeri itu, pabrikan asing harus mendirikan
joint venture dengan perusahaan lokal, dengan kepemilikan saham minoritas,
tak boleh lebih dari 50%.
Bergelombanglah
pemain raksasa masuk ke daratan China, diawali dengan Volkswagen di tahun 1984,
bergandengan dengan SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation). Mereka
membentuk Shanghai VW. Di luar itu, VW juga menggandeng First Auto Work (FAW)
yang bermarkas di Changchin, Jilin. Berdirilah FAW-VW.
General
Motor juga mendarat, menggandeng SAIC sehingga berdirilah Shanghai General
Motor. Sementara FAW juga membuat perusahaan patungan dengan Toyota untuk
mendirikan FAW Toyota.
Kebijakan
Pintu Terbuka 1979 merupakan upaya terobosan pemerintah China setelah
produsen-produsen otomotif lokal berupaya membangun industrinya. Namun bisa
dikata mereka kurang berkembang. FAW, misalnya. Pabrikan mobil pertama di China
ini telah meluncurkan mobil penumpang pertama, Hong Qi di tahun 1958. Namun, level
teknologinya sangat rendah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan otomotif
lokal lainnya.
Hingga
1979, aspek produksi, distribusi dan konsumsi kendaraan berada dalam kontrol
pemerintah. Namun itu semua tidak bisa mendorong level produksi yang efisien.
Setelah Open Door Policy 1979, pemerintah China secara besar-besaran
mengintervensi pengembangan industri otomotif melalui aneka peraturan. Selain mengembangkan
zona ekonomi khusus, mereka mengeluarkan kebijakatan yang mendukung sektor
industri pendukung otomotif.
Tahun
1994, misalnya. Setelah sejumlah perusahaan otomotif patungan bermunculan, pemerintah
China secara aktif mendorong munculnya “indigeneous brand” di sektor
otomotif. Tahun itu diperkenalkanlah Kebijakan Industri Otomotif yang berniat menguatkan
otomotif lokal. Satu aturan yang mengikat adalah pabrikan otomotif harus melakukan
lokalisasi konten sejak awal produksi sehingga mereka mesti memulai produksi
otomotif dengan lebih dari 40%-nya adalah kandungan lokal. Apa artinya ini?
Jelas, tujuannya menguatkan industri pendukung otomotif lokal sehingga satu
waktu bisa menopang pabrikan otomotif yang tangguh.
Dua
tahun berikutnya (1996), kebijakan yang lebih memihak lokal kembali
diluncurkan. Pemerintah menetapkan impor pajak mobil penumpang berkisar antara
100%-220% sementara kendaraan komersial antara 15%-230%. Kebijakan ini secara
efektif melindungi kompetisi domestik dari terkaman pabrikan otomotif global.
Tahun
2001, seiring masuknya China ke WTO, pemerintah pun mulai melonggarkan aturan. Secara
bertahap pajak impor turun hingga 25% di mobil penumpang di tahun 2006. Namun
selang waktu selama satu dekade (1996-2006) itu telah memberikan banyak
kesempatan untuk pabrikan otomotif lokal mengembangkan mereknya di medan laga.
Toh
pemerintah China masih mengawal merek-merek lokalnya. Maklum, harus diakui,
persepsi atas kata “Made in China” sangat berbeda bila dibandingkan
dengan “Made in Germany”. Dalam kata yang terakhir, persepsinya adalah
“kualitas tinggi dan awet”, sementara produk China dipersepsikan “kualitas
rendah, mudah rusak”.
Tahun
2004, pemerintah mengumumkan Kebijakan Baru Pengembangan Industri Otomotif yang
semakin menekankan pentingnya mengembangkan merek lokal dan hak cipta yang
dipegang perusahaan China. Dan dua tahun kemudian (2006), setelah melihat
perkembangan yang ada, pemerintah dengan berani menyatakan bahwa merek lokal
akan mencapai lebih dari 50% pangsa pasar otomotif. Mereka bahkan telah mendorong
pelaku domestik untuk mulai mengekspor.
Masih
merasa kurang juga, tahun 2009, pemerintah membuat panduan untuk mengintegrasikan
industri otomotif China, khususnya pabrikan otomotif lokal.
Perusahaan-perusahaan otomotif yang ada direstrukturisasi. Pilarnya dibagi dua:
Pertama, “Four Big”, perusahaan-perusahaan otomotif besar seperti First
Auto Works, SAIC, Dongfeng Motor Co., dan Changan Automobile. Kedua, “Four
Little”, yakni Beijing Automotive Group, Guangzhou Automobile Industry
Group, Chery, dan Sinotruk di Shandong. Kedelapan perusahaan ini menjadi
perusahaan inti. Pemerintah pusat juga mengumumkan pemerintah lokal harus
membeli kendaraan merek lokal lebih dari 50% untuk pelayanan publik. Inilah
yang kemudian menjadi pilar kian bergeraknya sektor otomotif China mengerek
merek-mereknya sendiri.
Ya,
selama 2 dekade mendorong pabrikan otomotif tumbuh, akhirnya China memiliki
sektor otomotif yang kian kuat. Menariknya, sekalipun bukan pemain terbesar,
Chery menjadi pemain independen yang terbilang inovatif. Bahkan telah memancing
para petinggi China, termasuk Presiden Hu Jintao dan PM Wen Jiabao untuk
mengunjungi pabriknya. Produk-produk Chery yang inovatif menunjukkan
orang-orang China membeli produk ini bukan semata karena dorongan pemerintah,
tapi lebih pada fungsi serta desainnya.
 |
| Cherry, mobil lokal China yang melejit di tengah persaingan |
NASIONALISME KONSUMEN
Perkara
pemerintah membantu berkibarnya merek lokal semacam ini bukanlah hal asing. Memang
caranya tidaklah selalu langsung dengan memromosikan merek-merek lokal, tapi
dengan bermain di sisi hulu (dukungan pada sektor manufaktur) hingga hilir
(distribusi). Jauh sebelum pemerintah China melakukan hal seperti disinggung di
atas, pemerintah Jepang telah melakukannya.
Sekalipun
pembangunan ekonomi negeri Matahari Terbit ini merupakan produk dari private entrepreneurship, pemerintah sangat berkontribusi. Mereka mengatasi
depresi ekonomi, menolong munculnya industri baru, dan membangkitkan
merek-merek lokal untuk berkibar bukan hanya di panggung domestik, tapi juga
medan internasional. Tak heran, karena demikian besarnya pengaruh pemerintah
sehingga lahir terminologi “Japan Inc.” untuk menggambarkan aliansi yang kuat
antara kalangan bisnis dan pemerintah.
Mekanisme yang digunakan oleh pemerintah Jepang
dalam mendorong merek-merek lokalnya adalah lewat kebijakan yang terkait
perdagangan, pasar tenaga kerja, persaingan, dan insentif pajak. Pemerintah menelurkan
proteksi dagang, memberikan subsidi dan mendorong ekspor serta investasi lewat
JETRO. Yang menarik, berkibarnya merek-merek Jepang seperti yang kita kenal
selama ini, itu merupakan buah dari strategi di sisi hulu dengan pemikiran yang
cermat. Ketimbang memproduksi aneka barang, pemerintah Jepang menyeleksi
sejumlah area di mana mereka bisa mengembangkan barang dengan mutu tinggi,
jumlah yang banyak, dan harga yang kompetitif. Satu contohnya adalah industri
kamera yang sejak tahun 1960-an didominasi merek-merek Jepang.
Bicara
bagaimana mengembangkan merek lokal, untuk urusan ini tak ada yang lebih baik
ketimbang Korea Selatan. Pasalnya, selain komitmen pemerintahnya, juga muncul
apa yang kemudian disebut sebagai “nasionalisme konsumen”. Di satu sisi,
melejitnya merek-merek Samsung, LG, KIA, dan Hyundai
memang tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah di sisi industri, terutama
sejak tahun 1980-an.
Di tahun 1980-an, pemerintah Korea Selatan mulai mengubah orientasi
industrinya yang selama ini dijalankannya menjadi industri berbasis pengetahuan.
Dirunut ke belakang, baru pada awal periode 1960-an Korea Selatan mulai
membangun industrinya selepas perang saudara dengan Korea Utara. Saat itu, yang
dimulai adalah industri pengolahan biji besi, tungsten dan bahan baku sutra yang
tidak memiliki nilai tambah tinggi. Namun sejak 1970-an, orientasi ini
bergeser. Maka berkembanglah sektor-sektor industri baru berorientasi ekspor
seperti tekstil, petrokimia, garmen, dan kayu lapis, sampai akhirnya digeser ke
knowledge base pada tahun 1980-an. Dan seperti periode sebelumnya, untuk
menyukseskan kebijakan ini, pemerintah Korea Selatan pun menggandeng kemitraan
strategis dengan kalangan bisnis serta perguruan tinggi, yang dikenal dengan
istilah triple helix.
 |
| Selain kualitas, merek Korea Selatan berkembang karena nasionalisme konsumen. Samsung juga menikmatinya. |
Hasilnya mengagumkan. Setelah krisis 1997, Negeri Ginseng
melemparkan banyak produk-produk inovatif bermutu tinggi. Bukan hanya di pasar
lokal, merek-mereknya kian berkibar di pentas global. Kebijakan pemerintah Korea
Selatan membangun perekonomian berbasis pengetahuan telah mengantarkan merek-merek
nasionalnya menginvasi dunia.
Tapi strategi dan kebijakan ini hanya satu hal. Yang berperan
paling penting, terutama pada awal-awal industrialisasi yang menjadi fondasi
kehidupan merek-merek nasional Korea Selatan adalah nasionalisme konsumen.
Sekalipun kualitas merek-merek lokalnya masih sangat buruk dan tertinggal
dibanding AS, Eropa serta Jepang di tahun 1960-1980-an, rakyat Korea Selatan
dengan bangga menggunakannya. Sebagai bangsa yang pernah dijajah China dan
Jepang, mereka sangat anti untuk menggunakan produk para penjajah. Selain itu,
mereka pun meyakini bahwa dengan membeli produk buatan saudara sendiri, maka
itu berarti memberi kesempatan untuk tumbuh berkembang bersama.
Di sisi lain, produsen juga tidak melakukan moral hazard.
Mereka mengembalikan kepercayaan dan nasionalisme konsumen ini dalam bentuk
peningkatan kualitas produk serta layanannya. Mereka tak mau sekedar
mengandalkan nasionalisme konsumen serta keyakinan bahwa produknya pasti dibeli
bangsa sendiri. Inilah yang kemudian turut membuat konsumen jadi loyal: karena mereka
disuguhi produk lokal yang kualitasnya berkembang dari waktu ke waktu. Maka tak
heran jika merek-merek Korea Selatan pun dipersepsikan berkualitas dan berdaya
saing tinggi. Bahkan semakin diakui secara internasional.
Dengan nasionalisme konsumennya yang kuat, tidak mengherankan bila
gerakan invasi budaya yang masuk ranah ekonomi kreatif, yang dikenal sebagai
“Korean Wave (hallyu)” pun relatif mudah digerakkan, tidak saja di
domestik, tapi juga ke mancanegara. Karena orang Korea Selatan memang mencintai
produk-produk negerinya sehingga mereka mempromosikannya habis-habisan.
Belakangan, yang menarik, selain urusan mendorong merek-merek
lokal dari sektor manufaktur, kita masih disuguhi pemandangan bagaimana seriusnya
pemerintah Korea Selatan terus memromosikan produk gelombang kebudayaannya ini.
Hal tersebut bisa dilihat pada situs forthenextgeneration.com.
Masyarakat seluruh dunia bisa mengenal Korea Selatan lebih dalam lewat situs
ini. Di luar situs tersebut, pemerintah Korea Selatan juga aktif berpromosi
lewat media-media ternama. Beberapa minggu lalu, mereka berpromosi di New
York Times untuk memperkenalkan “Hansik Globalisation”. Hansik adalah
makanan Korea. Promosi ini dibuat setelah mendunianya Kimchi yang bahkan telah
dibuat acaranya, Kimchi Chronicle yang ditayangkan di stasiun PBS, Amerika
Serikat.
Kesuksesan
sejumlah negara di atas dalam mendorong merek-merek lokalnya, tak ayal kerap
memancing negara lain untuk menempuh jalan serupa. Salah satunya yang tengah
berupaya melakukannya adalah Vietnam.
7
Januari 2013, Deputy Perdana Menteri Vietnam, Hoang Trung Hai telah
mengafirmasi bahwa adalah tanggung jawab pemerintah Vietnam untuk mendukung
berkibarnya merek-merek lokal di pasar domestik.
Akan
tetapi, belajar dari kesuksesan Jepang, Korea Selatan dan China, pemerintahan
Vietnam sejak awal menegaskan bahwa kesuksesan ini akan bergantung juga pada
kalangan bisnis itu sendiri. Dengan terus terang, Hoang meminta kalangan bisnis
tak henti mencari cara agar bisa menggenjot ekspor dan mengambil keuntungan
dari kampanye nasionalisme yang sudah diluncurkan pemerintah, yakni “Orang
Vietnam menggunakan produk-produk Vietnam”.
Pemerintah
Vietnam memang telah berupaya mati-matian untuk menggenjot berkibarnya merek
lokal mereka di pasar domestik. Diantaranya, mereka telah mendirikan Dewan
Merek Nasional yang diketuai langsung Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Vu
Huy Hoang. Sejauh ini, Dewan Merek telah menelurkan beberapa inisiatif. Salah
satunya yang dijagokan adalah “Program Merek Nasional” dalam rangka memromosikan
serta mencitrakan produk-produk Vietnam.
Hoang
Trung Hai mungkin benar bahwa pemerintah tak akan bisa berjalan tanpa dukungan
kalangan bisnis, terutama dalam hal menghasilkan produk yang berkualitas. Namun
melihat bagaimana merek-merek Korea Selatan tumbuh, unsur nasionalisme konsumen
tetap memegang peranan. Di Jepang pun, hal tersebut amat terasa di tahun-tahun
awal industrialisasi berjalan. Orang mengenal Toyota pada masa kini adalah
produk otomotif kelas dunia. Tapi di awal-awal berdiri, Toyota akan ambruk
lebih dini jika orang Jepang tidak mau menggunakannya. Maklum, modelnya seperti
kotak sabun.
Apa
yang bisa dipetik dari kesuksesan Jepang, Korea Selatan dan China dalam
mengembangkan merek lokalnya? Benang merahnya sama: strategi pemerintah yang jelas,
komitmen pengusaha untuk terus meningkatkan kualitas serta mengikis moral
hazard, dan nasionalisme konsumen. Bila melihat ke Indonesia, adakah kita
memiliki ketiganya? ***




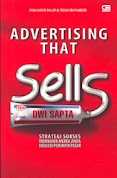
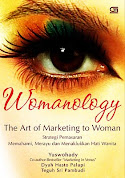












0 comments:
Post a Comment