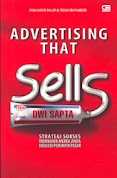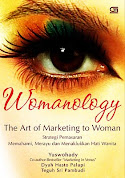Monday, December 10, 2007
Apa yang mau kita sombongkan?
Seorang pria yang bertamu ke rumah Sang Guru tertegun keheranan. Dia melihat Sang Guru sedang sibuk bekerja; ia mengangkuti air dengan ember dan menyikat lantai rumahnya keras-keras. Keringatnya bercucuran deras. Menyaksikan keganjilan ini orang itu bertanya, apa yang sedang Anda lakukan ?
Sang Guru menjawab, tadi saya kedatangan serombongan tamu yang meminta nasihat. Saya memberikan banyak nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Mereka pun tampak puas sekali. Namun, setelah mereka pulang tiba-tiba saya merasa menjadi orang yang hebat. Kesombongan saya mulai bermunculan. Karena itu, saya melakukan ini untuk membunuh perasaan sombong saya.
Sombong adalah penyakit yang sering menghinggapi kita semua, yang benih-benihnya terlalu kerap muncul tanpa kita sadari. Di tingkat terbawah, sombong disebabkan oleh faktor materi. Kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat daripada orang lain. Di tingkat kedua, sombong disebabkan oleh faktor kecerdasan. Kita merasa lebih pintar, lebih kompeten, dan lebih berwawasan dibandingkan orang lain. Di tingkat ketiga, sombong disebabkan oleh faktor kebaikan. Kita sering menganggap diri kita lebih bermoral, lebih pemurah, dan lebih tulus dibandingkan dengan orang lain.
Yang menarik, semakin tinggi tingkat kesombongan, semakin sulit pula kita mendeteksinya. Sombong karena materi sangat mudah terlihat, namun sombong karena pengetahuan, apalagi sombong karena kebaikan, sulit terdeteksi karena seringkali hanya berbentuk benih-benih halus di dalam batin kita.
Akar dari kesombongan ini adalah ego yang berlebihan. Pada tataran yang lumrah, ego menampilkan dirinya dalam bentuk harga diri (self-esteem) dan kepercayaan diri (self-confidence) . Akan tetapi, begitu kedua hal ini berubah menjadi kebanggaan (pride), Anda sudah berada sangat dekat dengan kesombongan. Batas antara bangga dan sombong tidaklah terlalu jelas.
Kita sebenarnya terdiri dari dua kutub, yaitu ego di satu kutub dan kesadaran sejati di lain kutub. Pada saat terlahir ke dunia, kita dalam keadaan telanjang dan tak punya apa-apa. Akan tetapi seiring dengan waktu, kita mulai memupuk berbagai keinginan, lebih dari sekadar yang kita butuhkan dalam hidup. Keenam indra kita selalu mengatakan bahwa kita memerlukan lebih banyak lagi.
Perjalanan hidup cenderung menggiring kita menuju kutub ego. Ilusi ego inilah yang memperkenalkan kita kepada dualisme ketamakan (ekstrem suka) dan kebencian (ekstrem tidak suka). Inilah akar dari segala permasalahan.
Perjuangan melawan kesombongan merupakan perjuangan menuju kesadaran sejati. Untuk bisa melawan kesombongan dengan segala bentuknya, ada dua perubahan paradigma yang perlu kita lakukan.
Pertama, kita perlu menyadari bahwa pada hakikatnya kita bukanlah makhluk fisik, tetapi makhluk spiritual. Kesejatian kita adalah spiritualitas, sementara tubuh fisik hanyalah sarana untuk hidup di dunia. Kita lahir dengan tangan kosong, dan (ingat!) kita pun akan mati dengan tangan kosong.
Pandangan seperti ini akan membuat kita melihat semua makhluk dalam kesetaraan universal. Kita tidak akan lagi terkelabui oleh penampilan, label, dan segala tampak luar lainnya. Yang kini kita lihat adalah tampak dalam. Pandangan seperti ini akan membantu menjauhkan kita dari berbagai kesombongan atau ilusi ego.
Kedua, kita perlu menyadari bahwa apa pun perbuatan baik yang kita lakukan, semuanya itu semata-mata adalah juga demi diri kita sendiri. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain adalah juga demi kita sendiri. Dalam hidup ini berlaku hukum kekekalan energi. Energi yang kita berikan kepada dunia tak akan pernah musnah. Energi itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang lain. Kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk persahabatan, cinta kasih, makna hidup, maupun kepuasan batin yang mendalam. Jadi, setiap berbuat baik kepada pihak lain, kita sebenarnya sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri.
Kalau begitu, apa yang bisa kita sombongkan ?
Thursday, December 6, 2007
Kematian Teori Manajemen?
Beberapa tahun lalu, saya membaca buku The Witch Doctors yang ditulis para editor The Economist, John Micklethwait dan Adrian Wooldridge. Diantara sejumlah buku, saya harus akui, ini adalah buku yang sangat bagus. Bercerita tentang arus-arus besar pemikiran di ranah manajemen, yang kemudian berpengaruh pada dinamika kehidupan perusahaan di dunia bisnis. Salah satu yang banyak diperbincangkan dalam buku ini adalah tentang reengineering yang kelak memakan banyak korban karena ditelan mentah-mentah oleh sejumlah perusahaan.
Akhir November lalu, dalam artikel bertitel "What Witch Doctors?" yang dipublikasikan pada 13 November 2007, The Economist menyoroti kembali dunia manajemen. Kali ini, dari sisi para konsultannya; para dokternya, alias para empunya. Ada apa gerangan?
Rupanya, ini berawal dari buku terbaru Gary Hamel yang memang tengah ngetop, The Future of Management. Dalam buku itu, Hamel mencatat bahwa sejumlah eksekutif puncak, termasuk the Google Guys, Sergey Brin dan Larry Page, juga John Mackey dari Whole Foods Market, disebutnya "did not go to business school". Donald Trump memang alumnus Wharton, tapi, tulis Hamel, orang bisa menebak dari buku bestseller terbarunya, “Think Big and Kick Ass in Business and Life ” banyak pelajaran dan nasehat yang didapatnya justru bukan dari konsultan. Menarikya, pandangan Hamel ini kemudian dapat penguatan dari buku terbaru Rakesh Khurana tentang sekolah bisnis, From Higher Aims to Hired Hands. Dalam buku itu, ada charts tentang "how management science declined from a serious intellectual endeavour to a slapdash set of potted theories".
Akhirnya, tulis The Economist, "All of this seems in keeping with the sceptical title of a book about management theorists written a decade ago by two journalists at The Economist (one now its editor-in-chief) called “The Witch Doctors”. Dan teori manajemen, is not hocus pocus after all.
Untuk memperkuat pendapat itu, The Economist kemudian menyodorkan satu bukti tentang sebuah studi yang punya keinginan mulia; menunjukkan bahwa perusahaan yang mengimplementasikan sound management practice memiliki produktivitas karyawan, sales growth dan return on capital lebih tinggi. Faktanya, “Improved management practice is one of the most effective ways for a firm to outperform its peers.” Perhatikan; improved management practice. Begitu kesimpulan studi bertitel Management Practice and Productivity: Why They Matter. Maka, tulis majalah ini, "That this is at all controversial shows how far management theory has fallen from its peak early in the 20th century, when it seemed that the science of running firms would be as rigorous as, say, applied physics."
Untuk membuktikan kesimpulan tersebut, para pelaksana studi di atas, termasuk Nick Bloom dari Stanford University dan John Van Reenen dari London School of Economics, telah menginterview manager di 4000 perusahaan di Amerika, Eropa, dan Asia. Ini lebih banyak ketimbang studi sebelumnya yang hanya 700 perusahaan di Amerika, Britain, Prancis, dan Jerman.
Menggunakan interview tersebut, para pelaksana studi kemudian melakukan rating praktik manajemen dalam skala 1-5 (the worst sampai the best) pada 18 kategori di 3 area; shop-floor operations, performance management serta talent management. Hasilnya, "There seems to be no magic bullet: a firm’s average score across all 18 dimensions was the best guide to whether it would outperform its peers."
Dari studi tersebut, banyak temuan lain yang mengejutkan. "In every part of the world, the spread between the best and worst run firms is wide. American firms tend to be best run, with an average score of 3.3, and Indian firms worst, with an average score of 2.62. But the best 20% of firms in India performed better than the average American firm, and the best 10% of Indian firms outscored 75% of American firms."
Di setiap negara yang disurvey, perusahaan yang dimiliki multinasiona, cenderung berjalan lebih baik ketimbang perusahaan milik lokal. Perusahaan multinasional di India mencetak skor lebih baik, kecuali multinasional Amerika yang beroperasi di Amerika. "When a local firm is acquired by a multinational, the quality of its management tends to rise."
"Multinationals have an edge." Begitu tulis para peneliti studi. Alasannya, “have been forced to take a systematic approach to management. Only by having strong, effective management practices in place have they been able to replicate the same standards of performance across different regions, cultures and markets.”
Pendorong lain bagi lahirnya praktik management yang lebih baik memang kompetisi. Di banyak negara, weak competition membuat kinerja memburuk. Temuan lain yang patut dicatat dari studi di atas; "firms with dispersed ownership scored best and performed best, whilst those owned and run by their founders or members of the founder’s family performed relatively poorly." Terburuk dari yang ada adalah "family-owned firms run by the founder’s eldest son, with an average management score of 2.53."
Membaca tulisan tersebut, saya ada yang sependapat, ada yang tidak. Temuan tentang kompetisi mendorong peningkatan kualitas praktik manajemen, saya kira memang demikian adanya. Namun, tentang kematian teori-teori manajemen harus diuji kembali -- sekalipun ini adalah topik yang sudah cukup lama. Saya sih lebih setuju dengan Ram Charan yang mengatakan bahwa problem di ranah manajemen lebih pada eksekusi yang tak sesuai dengan rencana-rencana awal. Ram, kini adalah mahaguru manajemen nomor satu versi BusinessWeek.
Yang pasti, The Economist memang asyik dibaca. Dia selalu mencoba menawarkan sudut pandang lain. Contohnya, awal 2005 ketika menunjukkan betapa corporate social responsibility (CSR) adalah hal yang cenderung sia-sia -- pandangan yang agak mengarah pada pendapat Milton Friedman di awal 1970.
So, apapun, selamat berakhir pekan.
Wednesday, December 5, 2007
Happy Birthday Aufa

5 Desember 2003, RS Hermina Depok. Sekitar pkl. 03.30, hadir anakku yang ke-2, seorang laki-laki. Dialah yang kuberi nama Aufa Salman Esfahan. Artinya, orang baik yang menebar keselamatan hingga ke penjuru dunia. Selamat ultah Aufa, be a good boy!
Bakrie dan Ketidakpedulian Kita
Saya senang Franz Magnis Suseno menolak award dari Bakrie Foundation. Namun, tak banyak yang mengambil sikap untuk bertindak tegas seperti ini. Dan tatkala problem ethics (saya tak sekeras untuk menyebut tindakan kriminal atas kasus kehancuran ekologi dan ekosistem di Sidoardjo) ini bertaut dengan ranah ekonomi, kita seringkali benar-benar cuek. Apalagi kalau menyangkut konsumerisme.
Lihatlah, kita tak menghukum Bakrie dengan memboikot produk-produknya. Produk teleponnya bahkan terus melaju. Diserbu para pengguna, yang mungkin tak tahu atau juga memang tak peduli betapa sang pemiliknya punya persoalan sosial dan lingkungan.
Dan Bakrie sendiri (Aburizal), oh la la, selain menantang meminta pembuktian pihaknya telah melakukan kejahatan lingkungan, tampaknya juga terus melaju. Belum lama ini dia mengeluarkan kumpulan tulisannya tentang kesejahteraan sosial. Muantap... Entah apa yang ditulisnya. Saya sudah sedih melihat korban Lapindo. Saya tak mau baca itu.
Oh ya, di luar aktivitas bisnisnya yang kuenceng, keluarga Bakrie juga kian aktif di pendidikan. Meniru keluarga Putera Sampoerna dengan Sampoerna Foundation yang berkolaborasi dengan MM ITB, Bakrie juga meluncurkan Bakrie School of Management. Saya nggak tahu, bagaimana nanti sekolah itu membahas problem tanggung jawab sosial perusahaan.
Yang pasti, Bakrie bisa seperti ini karena masyarakat juga banyak yang tak peduli. Kita tak peduli.