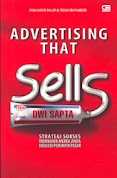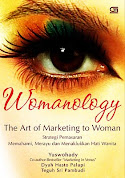Potensinya yang hebat seharusnya bisa membuatnya seperti Dubai. Apa saja langkah yang bisa dilakukan agar membuatnya kian berkembang?
Teguh S. Pambudi
Kalimantan Timur sebagai provinsi terkaya di Tanah Air, kiranya tak bisa didebat lagi. Bahkan, “Dompet Republik ini ada di Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak. Pernyataan Gubernur Kaltim ini, pastinya bukan seloroh di siang bolong. Pada 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai Rp 315,02 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,82%. Provinsi yang luasnya 1,5 kali Jawa itu (198.441,17 km2) memang aduhai. “Dompet republik” itu menyetor ke kas negara mencapai Rp 212 triliun setiap tahunnya. Luar biasa!
Hanya saja, karena sky is the limit, maka orang pun boleh bertanya dan berandai-andai: apakah Kaltim bisa bergerak lebih hebat lagi? Seperti Dubai, misalnya. Atau, Singapura. Dan kalau memang ingin seperti itu, bagaimana caranya?
Bicara potensi, Bambang PS Brodjonegoro, ahli otonomi daerah dan guru besar Universitas Indonesia, mengakui bahwa provinsi yang beribukota di Samarinda ini memiliki potensi paling besar di Indonesia. “Bisa dilihat dengan melimpahnya tambang batu bara, minyak dan gas bumi, hingga hasil hutan,” katanya. Kontribusi terbesar PDRB memang berasal dari sektor pertambangan, yakni sebesar 44,16%. Tapi, Kaltim juga memiliki areal perhutanan yang sangat luas, mencapai 21,14 juta ha. Untuk membuat Kaltim yang lebih hebat dari sekarang, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konteks pembangunan wilayah ini. “Mau diarahkan ke mana? Apakah hanya bisa memanfaatkan uang dari SDA yang ada, atau mengolah SDA tersebut?,” tandas Bambang. Menurutnya, hal ini akan sangat menentukan masa depan Kaltim.
Faroek punya jawaban akan ke mana provinsi yang dipimpinnya bergerak. Tapi, lontaran Bambang adalah contoh dari kritik yang memang mengalir menyoroti bagaimana Kaltim berjalan sejauh ini.
Kaltim yang sekarang berderap, kendati penuh puji, juga dilumuri masalah. Pasalnya, di balik kemilau angka-angka kehebatannya, tersimpan kepiluan. Data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa dari sekitar 3,1 juta jiwa dan dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 26,69 juta, jumlah penduduk miskin di provinsi kaya raya itu mencapai 324.800 jiwa. Dari data tersebut, Kutai Kartanagara ada di posisi pertama dengan 63.500 jiwa, lalu Samarinda (38.200), diikuti Kutai Timur (31.700). Tiga provinsi itu adalah sumbu-sumbu pertumbuhan.
Ada banyak analisis yang mencoba mengurai hal ini. Pendekatan capital investment menyatakan bahwa Kaltim kekurangan investasi untuk membangun dirinya. Dengan kontribusi sebesar Rp 212 triliun kepada negara, yang diterima provinsi itu hanya Rp 24 triliun sebagai modal pembangunan. Kaltim benar-benar termehek-mehek untuk menggenjot pembangunan. Akibatnya, infrastruktur pun terseok-seok. Bukan hanya jalan yang buruk, pemadaman listrik menjadi menu biasa. Maklum, pembangkit listrik di provinsi ini umumnya sudah berusia lanjut: 15-25 tahun, sehingga acap melakukan pemadaman bergilir lantaran daya dukung yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Faroek serta pejabat eksekutif Kaltim lainnya sering menyuarakan “ketidakadilan” ini: menyumbang banyak, tapi menerima sedikit. Koor yang juga kerap terlantun dari lembaga legislatif provinsi itu.
Sementara itu, pendekatan competitive strategy mengritik industri yang sementara ini muncul. Kaltim memang kaya sumber daya alam (SDA), atau biasa disebut resource-rich. Minyak, gas, batu bara merupakan komoditas yang membuat provinsi itu memiliki keunggulan komparatif dibanding provinsi yang tidak kaya SDA (resource-poor). Namun, industri yang ada baru tahap primary industry, tahap awal yang hanya mengambil kekayaan dari perut bumi untuk kemudian menjualnya. Belum dihasilkan industri-industri pengolah (smelter) yang akan mengubah kekayaan bumi menjadi aneka ragam produk turunan untuk dimanfaatkan industri di hilir. Dari hasil penjualan kekayaan alam inilah yang kemudian masuk ke kas Kaltim lewat aneka royalti, yang kemudian mengalir ke kas negara.
Industri pertambangan yang capital intensive ini, yang pandai mengekspor barang mentah ini, tidak terhubung (linked) dengan industri-industri lokal yang dibutuhkan masyarakat setempat. Industri energi ini tak bisa menjadi prime mover (penggerak mula) untuk mendukung industri-industri lainnya (industri pertanian, guna menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat; industri barang-barang modal seperti mesin; dan industri barang konsumsi). Padahal, kalau rantai industri ini terjadi, antara bagian hulu (primary product seperti pertambangan) dengan hilir (industri turunannya, termasuk industri lokal), maka akan tercipta multiplier effect yang besar. Kritik lain, Kaltim juga belum memaksimalkan potensi SDA dari sektor lain, seperti pertanian.
Sesungguhnya, pola di atas (hanya mengekspor barang mentah) juga berlaku di hampir seluruh provinsi di Tanah Air yang resource-rich. Di bagian hulu mengekspor untuk kemudian bagian hilir (industri-industri lokal) mengimpor dalam bentuk produk turunan yang harganya lebih mahal karena adanya penambahan nilai di dalamnya (value added). Sebuah rantai industri yang sungguh-sungguh pendek. Dan sesungguhnya, Indonesia sudah banyak kehilangan momentum karena primary product yang diekspor itu tidak akan pernah terbarukan lagi.
Faroek menyadari hal tersebut. Karena itulah dia berupaya membuat lompatan untuk provinsinya. Dan lantaran pertambangan adalah non renewable resources, dia akan merevitalisasi pertanian. “Kaltim harus menyiapkan lokomotif ekonomi yang baru,” katanya. Konkritnya, agribisnis akan menjadi tumpuan. Untuk itu, dia telah menyiapkan kebijakan pengembangan industri pertanian dengan konsep Integrated Agricultural Industrial Approach. Terdiri dari integrated farming, integrated rice processing, down stream industry, dan management and empowerment. “Kami akan memoles sektor ini agar investor semakin berdatangan,” tandasnya.
Untuk lahan pertanian, Kaltim memang memiliki banyak lahan potensial. Lahan sawah mencapai 205,100 ha dan bukan sawah 22,65 juta ha. Dari luas potensi lahan sawah tersebut, yang ditanami padi setahun dua kali mencapai 35,9 ribu ha dan ditanami sekali seluas 53,7 ribu ha. Sedangkan lahan yang tidak diusahakan seluas 104,265 ha, dan tidak ditanami seluas 25,2 ribu ha.
Sementara itu, Kaltim juga luar biasa. Ia memiliki potensi lahan kering seluas 5.324.488 ha yang terletak di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Dari jumlah itu, seluas 4,25 juta ha lahannya cocok untuk komoditi perkebunan (termasuk kelapa sawit). Hingga 2008, yang telah dimanfaatkan baru seluas 528.848 ha untuk pengembangan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao dan aneka tanaman lainnya. Sementara sisanya (3.73 juta ha), belum dikembangkan.
Selain cetak biru pertanian, Faroek juga tak meninggalkan industri energi, serta berupaya mengembangkan industri-industri lainnya. Dia membuat pembangunan kawasan industri di tiga area, meliputi; Bontang (Bontang Industri Estate), Banjarmasin, dan Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau).
Untuk menggenjot pengembangan industri itulah dia berupaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Sedikitnya, jalan sepanjang 1902 km akan dibangunnya di beberapa lokasi. Lalu, jalan kereta api, dan pelabuhan Maloy yang menjadi pusat keluarnya (outlet) crude palm oil (CPO) di Kalimantan. Tak lupa, dia juga akan memperlebar Bandara Sepinggan. Sebagai bandara tersibuk keempat di Indonesia, daya tampungnya sudah tidak memungkinkan. Landasan pacu (runway) akan direntang dari 2.500 m menjadi 3.100 m. Sepinggan terletak di Balikpapan yang terkenal sebagai kota bisnis. Di kota ini, bangunan-bangunan tinggi menjulang, berdampngan dengan hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel berbintang. Balikpapan adalah tempat perusahaan tambang besar berkantor seperti Pertamina, Total, Unocal dan Chevron.
Rencananya, seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi tolak punggung untuk transportasi hasil SDA, atau menghubungkan pusat pertumbuhan. Misalnya, rel yang menghubungkan Kutai Barat dan Balikpapan. Rel ini khusus untuk mengangkut batu bara, CPO, karet, kayu, dan dan cokelat.
Karena menggejot infrastruktur itu pula, Faroek berikhtiar menggaet dana, baik dari pemerintah pusat, maupun investor dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, diantaranya yang akan masuk adalah Ras-Al Khaimah, salah satu emirat dalam Uni Emirat Arab yang akan mengucurkan Rp 18 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Pertanyaannya: apakah langkah-langkah tersebut akan memadai, apalagi menopang menjadi seperti Dubai?
Sesungguhnya, dengan kekayaan potensi SDA yang luar biasa, Kaltim punya segalanya untuk melebihi Dubai, dan Singapura, dua negara kota (city state)yang luar biasa itu. Dubai tidak kaya akan SDA, sementara Singapura adalah benar-benar resource-poor yang pasir pun beli dari negara lain. Sejauh ini, langkah Kaltim untuk seperti Dubai – atau Singapura – bisa dikatakan sudah berada di jalurnya dengan berdirinya pusat-pusat pertumbuhan (growth area) di tiga kawasan industri (Bontang).
Namun, untuk menjadi seperti Dubai, sesungguhnya ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan. Pusat-pusat pertumbuhan di tiga kawasan industri itu, adalah semacam cluster, yang telah ditempuh Dubai – dan sebelumnya Singapura, juga Korea Selatan. Tapi, kritik yang sejauh ini meluncur adalah Faroek belum membuat industri yang terhubung satu sama lain, dan masih bertumpu pada energi. Di Bontang, misalnya, yang terbangun adalah lebih banyak industri kimia.
Dubai tumbuh dengan caranya tersendiri. Didukung stabilitas pemerintahan yang kuat, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mendirikan infrastruktur serta mengundang investor untuk menjadikan Dubai sebagai financial hub dan pusat industri manufaktur, sekaligus menyediakan properti serta tempat-tempat pariwisata sebagai wahana leisure, termasuk juga ajang pertandingan olahraga dunia. Al Maktoum bukan hanya mengundang pebisnis untuk datang, orang biasa pun diundangnya. Karena itu, kulturnya pun dibuat menjadi sangat fleksibel. “Semua orang ke Dubai karena di sana bebas. Semua orang merasa nyaman di sana. Orang bule juga bebas dan merasa nyaman. Orang berbikini dan yang pakai burqa bisa hidup berdampingan,” ujar Hermawan Kartajaya dari MarkPlus&Co. sambil tertawa.
Jelas tidaklah keliru bila Kaltim membuat industri yang memanfaatkan kekayaan SDA-nya. Namun, dengan kekayaan SDA-nya tersebut, sudah selayaknya provinsi ini tidak semata bergerak di fase primary dan menjualnya sebagai produk komoditas, tapi melangkah pada penciptaan industri-industri manufaktur serta industri pengolahan yang bisa memanfaatkan primary product (hasil tambang), baik dari Kaltim atau tetangganya di bumi Kalimantan, atau pulau-pulau kaya tambang terdekat seperti Sumatera, Sulawesi dan Irian. Faktor proximity (kedekatan) dengan lahan-lahan tambang sebagai bahan baku mestinya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan multiplier effect yang besar. Rantai industri di Kaltim mestinya bisa lebih panjang.
Tentang hal ini, Kaltim mestinya tak boleh kalah dari Dubai yang bahkan sudah membuat Dubai Alumunium. Ini merupakan smelter terbesar di dunia di luar Rusia yang memproduksi billet serta foundry alloy dengan kapasitas produksi 659 ribu ton setahun. Selain alumunium, Dubai Alumunium juga memproduksi baja sebanyak 400 ribu ton setahun yang dapat memenuhi 25% kebutuhan dalam negeri Uni Emirate Arab yang terus mengenjot sektor properti, dan sisanya diekspor ke seluruh dunia. Dari mana mereka mendapat bahan baku yang bisa diubah menjadi lebih dari 10 produk turunan itu? Jelas dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi penghasil timah nomor 2 di dunia. Kalau Dubai bisa, mengapa Kaltim tidak? Faroek bisa mengundang investor melakukan hal ini. Dia bisa memilih akan mengembang rantai industri yang feasible untuk Kaltim.
Intinya, Kaltim sudah sepatutnya membuat cluster yang di dalamnya menciptakan rantai industri yang panjang. Bukan yang rantainya pendek, menggali dari perut bumi lalu mengekspor dalam kondisi mentah. Dan tentang ini, Faroek, serta juga kepala daerah lain, punya legalitas kuat lewat UU Mineral Batu Bara No. 4/2009 yang baru disahkah Januari 2009 yang mewajibkan produsen bahan tambang mengolahnya lebih dahulu di dalam negeri. Dalam konteks membuat rantai industri yang lebih panjang, Faroek telah melangkah lebih maju dengan rencana membuat industri pengolahan kelapa sawit sehingga menghasilkan sejumlah produk turunan ketimbang hanya CPO. Dengan Kutai Timur sebagai pusat CPO di Kalimantan, ada 7 perusahaan nasional berminat untuk bekerja sama dalam pengembangan kelapa sawit di Kaltim.
Kaltim jelas bukan Dubai. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Tapi untuk urusan cara menjadi hebat, pembangunan berbasis SDA di Kaltim dengan rantai industri yang panjang akan lebih hebat juga bila ditunjang dengan pendekatan pembangunan berbasis SDM yang unggul. Dubai meniru Singapura dalam urusan mengumpulkan orang-orang terbaik – Singapura malah terhitung paling rakus mengumpulkan manusia terunggul di muka bumi dengan imbalan setinggi-tingginya. Untuk urusan ini, Kaltim termasuk sudah cukup bagus. Menurut Bambang PS Brodjonegoro, Kaltim termasuk lima besar jika dilihat dari indeks kualitas SDM di Indonesia. "Sudah punya modal manusianya, tinggal bagaimana mengoptimalkan termasuk tidak perlu segan-segan menarik orang dari daerah lain. Tidak mungkin berdiri sendiri karena butuh bantuan," ujar Bambang. Lantas, bagaimana rencana Faroek tentang hal ini?
“Saya mengundang profesional untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di Kaltim. Sebentar lagi akan ada iklan yang mengundang profesional untuk kerja di Kaltim. Ha… ha...,” jelas lelaki berambut putih ini.
Di luar pengembangan industri berbasis SDA dan SDM ini, belajar dari Dubai, aspek branding juga tak kalah penting bila ingin melesat. Untuk mem-branding-kan Kaltim, menurut Sumardy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari apa sebenarnya potensi utama Kaltim yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Potensi itu yang kemudian ditonjolkan untuk di-branding di dalam maupun di luar negeri. “Seperti kita lihat, di dekat Kalimantan ada Sulawesi, di mana Makassar tampak juga ingin menjadi daerah yang menjadi sentra pertumbuhan,” jelas pengamat pemasaran dari Octobrand. Artinya, Kaltim mesti piawai mencari positioning dalam konteks ini.
Last but not least, belajar dari Dubai – begitu juga Singapura – diperlukan konsistensi serta persistensi baik politik, sosial dan budaya untuk mengeksekusi seluruh rencana karena sesungguhnya mereka perlu waktu puluhan tahun hingga ke posisi sekarang. Tanpa hal-hal itu, “Dompet Republik” ini sulit untuk berkembang dan lebih hebat dari sekarang. ***
Boks
Dubai,
Buah Visi Para Pemimpin
Pada dekade 1990-an, ada tiga fastest growing cities di dunia, yakni Dublin, Las Vegas serta Dubai. Nama terakhir yang menyusul belakangan masuk di kategori itu, justru sekarang yang paling berkilau. Dubai yang merupakan salah satu dari 7 emirat di Uni Emirat Arab (UEA) kini menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah dengan perkembangan yang tak pernah terkira sebelumnya. Hari ini Dubai adalah trading, business and increasingly financial hub di Teluk Persia. Ia melampaui Abu Dhabi yang nota bene adalah ibu kota Kesultanan Teluk itu.
Sukses Dubai tak bisa dilepaskan dari kesolidan UEA. Sejak menyatakan menjadi satu negara hasil gabungan 7 emirat pada 1971, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan memimpin UEA relatif tanpa gejolak, dan terpenting, proaktif menggenjot pembangunan. Boom minyak membuat UEA dari desert kingdom menjadi modern metropolis. Sheikh Zayed sendiri adalah Emir Abu Dhabi, sahabat karib Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Emir Dubai. Sheikh Zayed menjadi Presiden UEA sejak 1971 hingga tahun wafatnya, 2004.
Sebagai penguasa Dubai, Sheikh Rashid membangun wilayahnya sejak ladang minyak ditemukan di daerah itu pada tahun 1966. Memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak, dia menggenjot pembangunan infrastruktur. Sejak awal 1967, dia mendorong pembangunan skala besar besaran meliputi bangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan telekomunikasi modern serta bandar udara internasional.
Sheikh Rashid mangkat pada tahun 1981. Setelah itu, tampuk Dubai dipegang anak sulungnya, Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Di tangannya, modernisasi Dubai terus dilanjutkan. Dubai kian dipoles. Dia mendorong Pemerintah Dubai dan keluarga-keluarga berpengaruh di wilayah itu untuk berinvestasi kepada infrastruktur serta merentang rencana-rencana yang ambisius. Kepemimpinan yang stabil, menurut para analis membuat keputusan bisa cepat diambil dalam membangun infrastruktur. Ada istilah yang mengatakan bahwa keputusan “Bangun di sana, bangun di sini” bisa dilakukan Sheikh Maktoum karena tiadanya tentangan.
Maka berdirilah bangunan-bangunan fenomenal seperti Burj Al Arab, Emirates Towers, Burj Dubai, dan Dubai International Airport yang dibangun senilai US$ 4,2 miliar. Terpenting dari itu adalah bangunan untuk menyedot korporasi serta investor kelas dunia seperti Dubai International Financial Centre serta Dubai Metals and Commodities Centre.
Visi Sheikh Maktoum memang menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan dan ekonomi dunia, juga pusat pariwisata. Agar pariwisata kian kencang, dia membuat kebijakan yang mengijinkan orang asing memiliki properti di Dubai. Maka berdirilah kawasan residensial Dubai Marina yang mewah, serta deretan pertokoan seperti Mall of the Emirates.
Namun, sang Sheikh pun bervisi ke luar. Karena itulah dia membangun apa yang sering disebut sebagai Dubai Inc. yang di dalamnya terdiri dari sejumlah perusahaan dalam 4 divisi. Dubai Holding menjadi induk dari Dubai Inc. Dalam naungannya berdiri: Jumeirah Group (membuat hotel), Dubai Property (membangun kota-kota baru), Media Properties (media), dan ujung tombak investasi mancanegara, Dubai International Capital. Diantara anak usaha yang terkenal adalah maskapai Emirates yang menandingi Singapore Airlines. Dan seperti halnya Temasek yang jadi jantung Singapore Inc., Dubai Inc. tak henti berekspansi ke tempat-tempat yang dianggap menguntungkan.
Wafat pada 2006, Sheikh Maktoum digantikan adiknya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang oleh pers Barat disebut Sheik Mo dan diyakini justru merupakan arsitek ekonomi Dubai yang sesungguhnya di balik sang kakak.
Apapun, Dubai kini terus berpendar. GDP-nya mencapai US$ 37 miliar pada tahun 2005, dan tumbuh double digit. Tahun 2008, GDP-nya tumbuh di kisaran 13-16%. Dengan portofolio bisnis yang ada, sumber-sumber pemasukan tidak lagi bertumpu pada minyak yang ditaksir akan sama sekali habis pada 20 tahun mendatang. Minyak dan gas hanya menyumbang 6%. Selebihnya datang dari perdagangan, real estate, jasa keuangan dan pariwisata. Setiap tahun, sedikitnya 7 juta pengunjung mampir ke Dubai, jauh melebihi warga Dubai yang kurang dari 2 juta jiwa.
“Perkembangan ekonomi Dubai yang luar biasa merupakan buah dari visi serta kebijakan progresif keluarga Al Maktoum yang fokus pada pertumbuhan,” ujar Mohamed Ali Alabbar, Dirjen Departemen Pengembangan Ekonomi Pemerintah Dubai, yang juga merangkap Chairman Emaar Properties.
Ya, sesungguhnya Dubai memang tidak dibangun dalam semalam. Ketika keluarga Al Maktoun mulai bermukim di Dubai pada 1883, daerah itu awalnya tempat perdagangan ikan, mutiara serta hasil laut lainnya.
Friday, May 22, 2009
Tuesday, May 19, 2009
Pemerintah dan Merek Orisinal
Banyak merek orisinal yang tumbuh dengan dukungan pemerintah. Namun, mentalitas masyarakat pun berperan dalam melahirkan merek yang menjadi tuan di negeri sendiri dan bermain di level internasional.
Teguh S. Pambudi
Siapa tak kenal Apple, Adidas, Starbucks? Bahkan sosok Donald Trump atau David Beckham adalah brand kelas dunia. Mereka menghiasi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan dari yang sifatnya primer hingga tersier.
Di pentas global, sungguh banyak merek yang seperti itu (Apple dkk.): lahir dan berkembang dengan cara yang natural, yang tumbuh identik dengan dirinya sendiri, baik personal maupun korporat. Namun, sesungguhnya tak sedikit pula merek yang diidentikkan dengan negara tempatnya berasal (origin) sehingga peran pemerintahnya pun disebut-sebut ketika satu atau beberapa merek tumbuh mengesankan. Pemerintah negara yang bersangkutan dipandang sebagai promotor di balik lahirnya merek-merek itu.
Yang paling sering dirujuk dalam konteks ini adalah Jepang. Lihatlah Toyota, Suzuki dan Honda sebagai perwakilan dari jalur otomotif, atau Sony, Toshiba dan Panasonic dari lini elektronik, kerap dikaitkan sebagai Japanese brands. Bukan hanya itu, bahkan fantastic Japanese brands. Merek-merek yang fantastis! Dan asosiasi yang muncul dari made in Japan itu pun bukan main-main: kualitas sekaligus keterandalan. Tak heran, banyak produk – terutama elektronik – yang di Indonesia kemudian diembel-embeli dengan kata “teknologi Jepang” sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu produk punya kualitas tinggi. Atau, setidaknya diberi merek yang berbau Jepang. Sebuah langkah cerdik secara branding, tapi miskin rasa percaya diri.
Hal yang sejenis terjadi pada produk Korea Selatan seperti Samsung, LG atau Hyundai. Dengan porsinya tersendiri, mereka juga dipersepsikan sebagai produk yang oke punya karena kualitasnya terjaga. Produk-produk itu bukan hanya menjadi raja di negeri sendiri tapi juga sukses di panggung global.
Jepang dan Kor-Sel memang tergolong negara yang sangat mendorong mentasnya merek-merek asli dari negerinya. Jepang, contohnya. Bisa dikatakan, Japanese brands dibentuk sebagai hasil dari strategi nasional selepas Perang Dunia II. Dihadapkan pada pembatasan di sektor militer, Pemerintah Jepang tak punya pilihan selain memperkuat sektor ekonomi. Mereka menopang bisnis perusahaan-perusahaannya dalam mengembangkan produk dan mereknya, termasuk hingga ke level global. Selain menyediakan infrastruktur untuk produksi, Pemerintah Negeri Matahari Terbit pun menopang investasi uang, waktu dan energi untuk menghasilkan kualitas papan atas agar produk-produknya bisa masuk ke pasar dunia, khususnya Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi sehingga kini, ketika pabrikan mobil Detroit diterjang badai kebangkrutan, Toyota dan pabrikan otomotif lainnya dari Jepang justru masih tegar sekalipun merugi.
Berbeda dari Jepang, merek-merek dari Kor-Sel yang kini tumbuh di pentas global merupakan hasil strategi korporat yang didorong koneksitas milik para chaebol dengan pihak penguasa. Seperti jaringan keiretsu Jepang, para chaebol ini membentuk merek-mereknya dalam rangka ekspor ke pasar internasional, khususnya negara maju di Eropa dan AS.
Cara yang ditempuh kedua negara itu, sekarang tengah coba dilakoni negara lain yang juga ingin merek orisinal dari perusahaannya kian kinclong di panggung internasional. Rusia, ambil contoh. Tak seperti Jepang atau Kor-Sel yang bermain di sektor mass consumer product, Pemerintah Rusia mendukung para oligarki berinvestasi besar-besaran di sektor utilitas yang sifatnya business to business seperti gas dan minyak. Tentu ada yang tidak setuju dengan Pemerintah Rusia yang menopang para oligarki mengembangkan bisnisnya. Yang jelas, cara itulah yang ditempuh sehingga memunculkan nama Gazprom atau Lukoil di panggung global. Gazprom misalnya, kini memasok sepertiga kebutuhan gas Eropa. Dan salah seorang petingginya, Alexander Medvedev merupakan pentolan politik Rusia.
Di luar Rusia, negara lain yang kian peduli nasib original brand-nya adalah India dan Cina. Di kalangan pelaku bisnis India, muncul kerisauan bahwa made in India sering diasosiasikan dengan kualitas rendah dan tidak efisien. Mereka ingin sekali seperti Italia, umpamanya, yang diasosiasikan dan diidentifikasikan sebagai produk dengan sentuhan seni dan desain yang ciamik. Bvlgari atau Armani mewakili ini. Begitu pula dengan Ferrari atau Maserati yang melambangkan produk berkualitas super.
Sejauh ini, India cukup berhasil melahirkan merek yang identik dengan teknologi informasi seperti Wipro atau Infosys. Mereka pun punya Bajaj dan Tata yang mulai dapat pengakuan di pentas global. Namun, Pemerintah India masih terus mencari formula yang pas agar merek lain dari negerinya kian moncer. Meniru Pemerintah Jepang yang terus mendorong perusahaannya go global, Pemerintah India beserta kalangan bisnisnya bahu-membahu mendirikan India Brand Equity Foundation (IBEF) yang berupaya mempromosikan merek-merek dari negeri yang kebetulan sedang dapat momentum cukup bagus untuk mengatrol citra di pentas internasional dengan kemenangan Slumdog Millionaire di acara Academy Award lalu. “Tugas kami membangun persepsi global tentang India, lalu menciptakan buzz (pembicaraan),” ujar CEO IBEF, Ajay Khanna, beberapa waktu lalu.
Lain India, lain pula Cina. Sejak empat tahun terakhir, merek-merek dari Negeri Tirai Bambu mencoba terus merangsek pasar global. Memang ada hambatan untuk melompat ke level internasional karena seperti halnya India, made in China identik atau diasosiasikan sebagai merek murah sehingga kualitasnya pun jelek. Tak mengherankan, produk consumer mass yang mereka lemparkan baik di telepon seluler, elektronik, maupun otomotif dipandang sebelah mata di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Produk mereka bahkan dianggap masih kalah dibanding yang lahir dari tanah Formosa, Taiwan, yang dipandang lebih hi-tech dan bermutu tinggi. Dengan strategi menguatkan R&D, Pemerintah Taiwan sejak 1980-an mendorong perusahaan-perusahaannya mengembangkan teknologi setelah kenyang menjadi basis produksi bagi pabrikan asing. Kini, made in Taiwan adalah citarasa teknologi bermutu tinggi. Sejumlah produk yang tak bisa disangkal lagi adalah Acer, BenQ, Lite-On, Transcend, dan HTC.
Kendati tertinggal dibanding Taiwan, perusahaan Cina tak henti mencoba untuk bermain di level tertinggi. Ada yang melakukannya dengan cara akuisisi seperti yang dilakukan Legend Computer dengan membeli divisi bisnis PC milik IBM yang kemudian bersalin rupa jadi Lenovo, atau TCL yang mengambil RCA dari Thomson. Toh, banyak pula yang didorong Pemerintah Cina untuk terus berekspansi ke mancanegara secara organik seperti Haier (pabrikan home aplliances), Air China, China Mobile, pemain jasa telekomunikasi seperti ZTE, Tsingtao Brewery, ChangYu dan Moutai (minuman keras), Ping An (asuransi jiwa), serta pemain otomotif DongFeng Motors. Pada saat Olimpiade lalu, mereka bahkan didorong Pemerintah Cina untuk kencang berpromosi agar makin dikenal masyarakat global. Pemerintah Cina bahkan terang-terangan mengaku ingin mengikuti jejak Kor-Sel yang merek-mereknya – terutama Samsung – kian ngetop setelah mensponsori Olimpiade Seoul 1988.
Serbuan merek dari Cina sebenarnya tinggal menunggu waktu seiring upaya mereka memperbaiki citra made in China yang dipandang kualitasnya memble. Huawei, umpamanya, kini terus aktif menggelontorkan dana buat riset dan pengembangan produk dengan target menumbangkan pemain global seperti Cisco Systems. Menariknya, dalam analisis Prof. L.D. Mago dari Indian Institute of Foreign Trade, serbuan mereka ini kerap dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak asing lainnya atau perusahaan tempat mereka berekspansi. Mereka juga, disebutkan Mago, cenderung memilih cara evolusi dan menghindari agresivitas yang kental dengan trial and error. Di Indonesia, Huawei dan ZTE aktif memasarkan produknya dengan menggandeng pemain telekomunikasi seperti Indosat.
Perihal peran pemerintah dalam mendorong merek-merek yang lahir dari negerinya ke pentas global, rasanya tak usah jauh-jauh mengambil contoh, jiran kita yakni Thailand aktif pula melakukannya. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu aktif mendorong munculnya resto makanan Thailand di seluruh dunia. Dalam upaya itu, flag carrier-nya, Thai Airways pun terlibat aktif membantu proses pengiriman bahan makanan dari Thailand termasuk pemasarannya.
Membangun merek global sesungguhnya bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Peran pemerintah memang penting dengan mendukungnya dari sisi penyediaan infrastruktur, regulasi yang fair dan kondusif, serta koneksitas (perluasan pasar). Namun, menyerahkan pada pemerintah semata jelaslah tidak fair. Peran pemerintah yang proporsional dalam konteks ini, belajar dari Jepang atau Kor-Sel selain menciptakan regulasi yang mendorong perusahaan mereka bisa bersaing di pentas global, juga penciptaan infrastruktur yang andal. Di luar peran pemerintah, sesungguhnya peran masyarakat itu sendiri sangatlah penting. Mentalitas mencintai produk dalam negeri juga berperan signifikan. Artinya, ada keterhubungan (link) yang kuat antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Keterhubungan yang sifatnya sinergis, tidak semata politis (didukung kebijakan pemerintah) tapi juga kultural.
Ambil contoh Jepang. Ke mana pun orang-orang Jepang melancong, biasanya mereka akan berupaya menggunakan hotel atau penginapan yang dimiliki orang dari negeri sendiri. Hotel Nikko, misalnya. Sementara itu, orang Kor-Sel terkenal militan untuk menggunakan produk buatan negerinya sendiri. Di jalan-jalan Kor-Sel, niscaya sangat sulit menemukan produk otomotif dari Jepang yang memang sangat mereka benci lantaran pernah menjajah negeri itu. Orang-orang Dae Han Min Guk (begitu orang-orang Kor-Sel menyebut dirinya) lebih mencintai Hyundai di otomotif, atau Samsung dan LG di elektronik. Mereka mencintai dan memberi kesempatan pada produk dalam negerinya itu untuk terus memperbaiki diri. Dan sikap ini berperan besar bagi tumbuhnya merek-merek tersebut. Sebuah kultur yang justru masih sulit dijumpai di Indonesia.
Berbicara kultur menggunakan original brand, jangankan negara-negara Asia yang memang memerlukan mental cinta produk dalam negeri untuk mengejar ketertinggalan ekonomi pasca Perang Dunia II, di Inggris ada cerita legendaris yang masih terkenang hingga kini seputar mentalitas menggunakan produk negeri sendiri. Cerita itu adalah tentang mendiang Lady Diana yang diprotes masyarakat Inggris lantaran mengendarai BMW, bukan Jaguar atau Rolls Royce yang buatan anak Inggris. Memang banyak orang setempat yang lebih memilih produk otomotif non-Inggris, tapi sebagai figur yang mewakili Inggris, diharapkan wanita yang tewas mengenaskan di Prancis itu menggunakan produk asli dari negerinya.
Pertanyaannya kini: mengapa original brand penting bagi sebuah negara?
“Setiap bangsa atau negara punya original brand, dan ketika merek-merek dari suatu negara itu disukai dan dipercayai, maka masyarakat dunia akan membeli produk dan jasa dari negara itu,” ujar Mago.
Indonesia, seperti dicanangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berupaya mengantarkan 200 merek nasional go global tahun ini dengan bertumpu pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Jelas ini merupakan inisiatif yang menarik dan patut diapresiasi. Namun, belajar dari negara-negara lain, Pemerintah RI seyogyanya juga berupaya menciptakan asosiasi yang clear dan interesting tentang apa yang dimaksud dengan made in Indonesia itu sendiri. Pemerintah dan kalangan bisnis mesti bersatu dalam hal ini.
Barangkali Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya meniru pemerintah negara lain yang sangat serius dalam membangun merek, termasuk untuk negaranya. Seperti dikutip LA Times, 3 Mei 2009, Presiden Kor-Sel, Lee Myung-bak sangat marah begitu mengetahui negaranya hanya nomor 33 di Global Brand Index yang baru saja keluar. Kor-Sel berada di bawah Polandia dan Republik Cek yang ekonominya lebih tertinggal – nomor satu dipegang Jerman. Rupanya, Kor-Sel masih dipersepsikan negatif karena dekat dengan Kor-Ut. Beruntung, merek-merek dari negara itu seperti Samsung, LG dan Hyundai sudah masuk dalam BusinessWeek Global Brands dan kian ngetop. Toh, Pemerintah Kor-Sel tak berdiam diri. Meresponsnya, Lee membentuk Presidential Council on Nation Branding. Targetnya: bergerak ke posisi 15 di tahun 2013. Dan kini mereka tengah membangun strategi ke arah itu.
Seperti disinggung di atas, di luar peran pemerintah, masyarakat pun harus punya mentalitas cinta produk dalam negeri yang pada gilirannya mesti direspons pelaku pasar dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Dan kalangan pejabat sebagai representasi negara, juga harus lebih sering menggunakan produk dalam negeri dan memperkenalkannya di mancanegara. Adalah dagelan yang tak lucu ketika salah seorang menteri SBY dalam suatu kesempatan mengaku sulit menemukan sepatu produksi dalam negeri. Sungguh sebuah ironi yang mestinya tak pernah terjadi.
Teguh S. Pambudi
Siapa tak kenal Apple, Adidas, Starbucks? Bahkan sosok Donald Trump atau David Beckham adalah brand kelas dunia. Mereka menghiasi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan dari yang sifatnya primer hingga tersier.
Di pentas global, sungguh banyak merek yang seperti itu (Apple dkk.): lahir dan berkembang dengan cara yang natural, yang tumbuh identik dengan dirinya sendiri, baik personal maupun korporat. Namun, sesungguhnya tak sedikit pula merek yang diidentikkan dengan negara tempatnya berasal (origin) sehingga peran pemerintahnya pun disebut-sebut ketika satu atau beberapa merek tumbuh mengesankan. Pemerintah negara yang bersangkutan dipandang sebagai promotor di balik lahirnya merek-merek itu.
Yang paling sering dirujuk dalam konteks ini adalah Jepang. Lihatlah Toyota, Suzuki dan Honda sebagai perwakilan dari jalur otomotif, atau Sony, Toshiba dan Panasonic dari lini elektronik, kerap dikaitkan sebagai Japanese brands. Bukan hanya itu, bahkan fantastic Japanese brands. Merek-merek yang fantastis! Dan asosiasi yang muncul dari made in Japan itu pun bukan main-main: kualitas sekaligus keterandalan. Tak heran, banyak produk – terutama elektronik – yang di Indonesia kemudian diembel-embeli dengan kata “teknologi Jepang” sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu produk punya kualitas tinggi. Atau, setidaknya diberi merek yang berbau Jepang. Sebuah langkah cerdik secara branding, tapi miskin rasa percaya diri.
Hal yang sejenis terjadi pada produk Korea Selatan seperti Samsung, LG atau Hyundai. Dengan porsinya tersendiri, mereka juga dipersepsikan sebagai produk yang oke punya karena kualitasnya terjaga. Produk-produk itu bukan hanya menjadi raja di negeri sendiri tapi juga sukses di panggung global.
Jepang dan Kor-Sel memang tergolong negara yang sangat mendorong mentasnya merek-merek asli dari negerinya. Jepang, contohnya. Bisa dikatakan, Japanese brands dibentuk sebagai hasil dari strategi nasional selepas Perang Dunia II. Dihadapkan pada pembatasan di sektor militer, Pemerintah Jepang tak punya pilihan selain memperkuat sektor ekonomi. Mereka menopang bisnis perusahaan-perusahaannya dalam mengembangkan produk dan mereknya, termasuk hingga ke level global. Selain menyediakan infrastruktur untuk produksi, Pemerintah Negeri Matahari Terbit pun menopang investasi uang, waktu dan energi untuk menghasilkan kualitas papan atas agar produk-produknya bisa masuk ke pasar dunia, khususnya Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi sehingga kini, ketika pabrikan mobil Detroit diterjang badai kebangkrutan, Toyota dan pabrikan otomotif lainnya dari Jepang justru masih tegar sekalipun merugi.
Berbeda dari Jepang, merek-merek dari Kor-Sel yang kini tumbuh di pentas global merupakan hasil strategi korporat yang didorong koneksitas milik para chaebol dengan pihak penguasa. Seperti jaringan keiretsu Jepang, para chaebol ini membentuk merek-mereknya dalam rangka ekspor ke pasar internasional, khususnya negara maju di Eropa dan AS.
Cara yang ditempuh kedua negara itu, sekarang tengah coba dilakoni negara lain yang juga ingin merek orisinal dari perusahaannya kian kinclong di panggung internasional. Rusia, ambil contoh. Tak seperti Jepang atau Kor-Sel yang bermain di sektor mass consumer product, Pemerintah Rusia mendukung para oligarki berinvestasi besar-besaran di sektor utilitas yang sifatnya business to business seperti gas dan minyak. Tentu ada yang tidak setuju dengan Pemerintah Rusia yang menopang para oligarki mengembangkan bisnisnya. Yang jelas, cara itulah yang ditempuh sehingga memunculkan nama Gazprom atau Lukoil di panggung global. Gazprom misalnya, kini memasok sepertiga kebutuhan gas Eropa. Dan salah seorang petingginya, Alexander Medvedev merupakan pentolan politik Rusia.
Di luar Rusia, negara lain yang kian peduli nasib original brand-nya adalah India dan Cina. Di kalangan pelaku bisnis India, muncul kerisauan bahwa made in India sering diasosiasikan dengan kualitas rendah dan tidak efisien. Mereka ingin sekali seperti Italia, umpamanya, yang diasosiasikan dan diidentifikasikan sebagai produk dengan sentuhan seni dan desain yang ciamik. Bvlgari atau Armani mewakili ini. Begitu pula dengan Ferrari atau Maserati yang melambangkan produk berkualitas super.
Sejauh ini, India cukup berhasil melahirkan merek yang identik dengan teknologi informasi seperti Wipro atau Infosys. Mereka pun punya Bajaj dan Tata yang mulai dapat pengakuan di pentas global. Namun, Pemerintah India masih terus mencari formula yang pas agar merek lain dari negerinya kian moncer. Meniru Pemerintah Jepang yang terus mendorong perusahaannya go global, Pemerintah India beserta kalangan bisnisnya bahu-membahu mendirikan India Brand Equity Foundation (IBEF) yang berupaya mempromosikan merek-merek dari negeri yang kebetulan sedang dapat momentum cukup bagus untuk mengatrol citra di pentas internasional dengan kemenangan Slumdog Millionaire di acara Academy Award lalu. “Tugas kami membangun persepsi global tentang India, lalu menciptakan buzz (pembicaraan),” ujar CEO IBEF, Ajay Khanna, beberapa waktu lalu.
Lain India, lain pula Cina. Sejak empat tahun terakhir, merek-merek dari Negeri Tirai Bambu mencoba terus merangsek pasar global. Memang ada hambatan untuk melompat ke level internasional karena seperti halnya India, made in China identik atau diasosiasikan sebagai merek murah sehingga kualitasnya pun jelek. Tak mengherankan, produk consumer mass yang mereka lemparkan baik di telepon seluler, elektronik, maupun otomotif dipandang sebelah mata di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Produk mereka bahkan dianggap masih kalah dibanding yang lahir dari tanah Formosa, Taiwan, yang dipandang lebih hi-tech dan bermutu tinggi. Dengan strategi menguatkan R&D, Pemerintah Taiwan sejak 1980-an mendorong perusahaan-perusahaannya mengembangkan teknologi setelah kenyang menjadi basis produksi bagi pabrikan asing. Kini, made in Taiwan adalah citarasa teknologi bermutu tinggi. Sejumlah produk yang tak bisa disangkal lagi adalah Acer, BenQ, Lite-On, Transcend, dan HTC.
Kendati tertinggal dibanding Taiwan, perusahaan Cina tak henti mencoba untuk bermain di level tertinggi. Ada yang melakukannya dengan cara akuisisi seperti yang dilakukan Legend Computer dengan membeli divisi bisnis PC milik IBM yang kemudian bersalin rupa jadi Lenovo, atau TCL yang mengambil RCA dari Thomson. Toh, banyak pula yang didorong Pemerintah Cina untuk terus berekspansi ke mancanegara secara organik seperti Haier (pabrikan home aplliances), Air China, China Mobile, pemain jasa telekomunikasi seperti ZTE, Tsingtao Brewery, ChangYu dan Moutai (minuman keras), Ping An (asuransi jiwa), serta pemain otomotif DongFeng Motors. Pada saat Olimpiade lalu, mereka bahkan didorong Pemerintah Cina untuk kencang berpromosi agar makin dikenal masyarakat global. Pemerintah Cina bahkan terang-terangan mengaku ingin mengikuti jejak Kor-Sel yang merek-mereknya – terutama Samsung – kian ngetop setelah mensponsori Olimpiade Seoul 1988.
Serbuan merek dari Cina sebenarnya tinggal menunggu waktu seiring upaya mereka memperbaiki citra made in China yang dipandang kualitasnya memble. Huawei, umpamanya, kini terus aktif menggelontorkan dana buat riset dan pengembangan produk dengan target menumbangkan pemain global seperti Cisco Systems. Menariknya, dalam analisis Prof. L.D. Mago dari Indian Institute of Foreign Trade, serbuan mereka ini kerap dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak asing lainnya atau perusahaan tempat mereka berekspansi. Mereka juga, disebutkan Mago, cenderung memilih cara evolusi dan menghindari agresivitas yang kental dengan trial and error. Di Indonesia, Huawei dan ZTE aktif memasarkan produknya dengan menggandeng pemain telekomunikasi seperti Indosat.
Perihal peran pemerintah dalam mendorong merek-merek yang lahir dari negerinya ke pentas global, rasanya tak usah jauh-jauh mengambil contoh, jiran kita yakni Thailand aktif pula melakukannya. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu aktif mendorong munculnya resto makanan Thailand di seluruh dunia. Dalam upaya itu, flag carrier-nya, Thai Airways pun terlibat aktif membantu proses pengiriman bahan makanan dari Thailand termasuk pemasarannya.
Membangun merek global sesungguhnya bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Peran pemerintah memang penting dengan mendukungnya dari sisi penyediaan infrastruktur, regulasi yang fair dan kondusif, serta koneksitas (perluasan pasar). Namun, menyerahkan pada pemerintah semata jelaslah tidak fair. Peran pemerintah yang proporsional dalam konteks ini, belajar dari Jepang atau Kor-Sel selain menciptakan regulasi yang mendorong perusahaan mereka bisa bersaing di pentas global, juga penciptaan infrastruktur yang andal. Di luar peran pemerintah, sesungguhnya peran masyarakat itu sendiri sangatlah penting. Mentalitas mencintai produk dalam negeri juga berperan signifikan. Artinya, ada keterhubungan (link) yang kuat antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Keterhubungan yang sifatnya sinergis, tidak semata politis (didukung kebijakan pemerintah) tapi juga kultural.
Ambil contoh Jepang. Ke mana pun orang-orang Jepang melancong, biasanya mereka akan berupaya menggunakan hotel atau penginapan yang dimiliki orang dari negeri sendiri. Hotel Nikko, misalnya. Sementara itu, orang Kor-Sel terkenal militan untuk menggunakan produk buatan negerinya sendiri. Di jalan-jalan Kor-Sel, niscaya sangat sulit menemukan produk otomotif dari Jepang yang memang sangat mereka benci lantaran pernah menjajah negeri itu. Orang-orang Dae Han Min Guk (begitu orang-orang Kor-Sel menyebut dirinya) lebih mencintai Hyundai di otomotif, atau Samsung dan LG di elektronik. Mereka mencintai dan memberi kesempatan pada produk dalam negerinya itu untuk terus memperbaiki diri. Dan sikap ini berperan besar bagi tumbuhnya merek-merek tersebut. Sebuah kultur yang justru masih sulit dijumpai di Indonesia.
Berbicara kultur menggunakan original brand, jangankan negara-negara Asia yang memang memerlukan mental cinta produk dalam negeri untuk mengejar ketertinggalan ekonomi pasca Perang Dunia II, di Inggris ada cerita legendaris yang masih terkenang hingga kini seputar mentalitas menggunakan produk negeri sendiri. Cerita itu adalah tentang mendiang Lady Diana yang diprotes masyarakat Inggris lantaran mengendarai BMW, bukan Jaguar atau Rolls Royce yang buatan anak Inggris. Memang banyak orang setempat yang lebih memilih produk otomotif non-Inggris, tapi sebagai figur yang mewakili Inggris, diharapkan wanita yang tewas mengenaskan di Prancis itu menggunakan produk asli dari negerinya.
Pertanyaannya kini: mengapa original brand penting bagi sebuah negara?
“Setiap bangsa atau negara punya original brand, dan ketika merek-merek dari suatu negara itu disukai dan dipercayai, maka masyarakat dunia akan membeli produk dan jasa dari negara itu,” ujar Mago.
Indonesia, seperti dicanangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berupaya mengantarkan 200 merek nasional go global tahun ini dengan bertumpu pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Jelas ini merupakan inisiatif yang menarik dan patut diapresiasi. Namun, belajar dari negara-negara lain, Pemerintah RI seyogyanya juga berupaya menciptakan asosiasi yang clear dan interesting tentang apa yang dimaksud dengan made in Indonesia itu sendiri. Pemerintah dan kalangan bisnis mesti bersatu dalam hal ini.
Barangkali Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya meniru pemerintah negara lain yang sangat serius dalam membangun merek, termasuk untuk negaranya. Seperti dikutip LA Times, 3 Mei 2009, Presiden Kor-Sel, Lee Myung-bak sangat marah begitu mengetahui negaranya hanya nomor 33 di Global Brand Index yang baru saja keluar. Kor-Sel berada di bawah Polandia dan Republik Cek yang ekonominya lebih tertinggal – nomor satu dipegang Jerman. Rupanya, Kor-Sel masih dipersepsikan negatif karena dekat dengan Kor-Ut. Beruntung, merek-merek dari negara itu seperti Samsung, LG dan Hyundai sudah masuk dalam BusinessWeek Global Brands dan kian ngetop. Toh, Pemerintah Kor-Sel tak berdiam diri. Meresponsnya, Lee membentuk Presidential Council on Nation Branding. Targetnya: bergerak ke posisi 15 di tahun 2013. Dan kini mereka tengah membangun strategi ke arah itu.
Seperti disinggung di atas, di luar peran pemerintah, masyarakat pun harus punya mentalitas cinta produk dalam negeri yang pada gilirannya mesti direspons pelaku pasar dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Dan kalangan pejabat sebagai representasi negara, juga harus lebih sering menggunakan produk dalam negeri dan memperkenalkannya di mancanegara. Adalah dagelan yang tak lucu ketika salah seorang menteri SBY dalam suatu kesempatan mengaku sulit menemukan sepatu produksi dalam negeri. Sungguh sebuah ironi yang mestinya tak pernah terjadi.
Labels:
Marketing