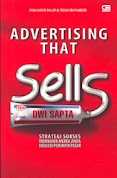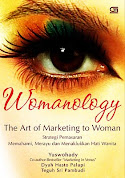Sejumlah figur kelas dunia tampil menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Dari mereka ada pelajaran: jangan terlalu memuja intelegensia dan bakat.
Teguh S. Pambudi
Banyak orang masih meributkan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa: Diego Armando Maradona, atau Edison Arantes do Nascimento alias Pele? Tapi di jagat tenis, tak ada keraguan untuk menyematkan predikat the Greatest Tennis Player Of All Time pada seorang pria kelahiran Basel, Swiss, 8 Agustus 1981 bernama Roger Federer yang sejauh ini telah menyabet 15 gelar grand slam dan diprediksi masih akan terus menambah koleksinya. Begitu pula tak ada perdebatan untuk menahbiskan sosok yang sesungguhnya layak mendapat sebutan Greatest Of Them All. Anda tahu siapa? Ya, Si Mulut Besar, Muhammad Ali.
Hidup mereka, di mata sebagian orang mungkin terlihat nikmat. Penuh bakat dan bergelimang sukses – sekalipun Ali didera Parkinson. Hal yang sama juga terlihat pada orang-orang di panggung bisnis macam Steve Jobs, duo pendiri Google (Larry Page dan Sergey Brin), sang fenomenal, Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), serta Jack Dorsey, pembuat Twitter. Mereka adalah orang-orang hebat. Dan jauh sebelum mereka, banyak orang-orang hebat di jamannya masing-masing. Ford dan Toyoda di otomotif, Matsushita dan Bill Hewlett-Dave Packard di elektronik, bahkan Ruth Handler si pencipta Barbie dan Mattel Inc. Nama-nama terakhir bahkan sering disebut sebagai “suvenir di abad-20” lantaran saking besarnya kontribusi yang diberikan.
Bagaimana mereka bisa sehebat itu?
Mereka memang dikaruniai kecerdasan serta bakat yang luar biasa. Tapi dalam kacamata Malcolm Gladwell, bakat serta intelejensia bukanlah segalanya. Mereka bisa menjadi kaum outlier, orang-orang hebat nan sukses itu, lantaran bantuan orang-orang sekitarnya sehingga bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dalam bahasa Gladwell, dan itu yang diyakininya, "People don't rise from nothing. We do owe something to parentage and patronage". Betul, dua “P” itulah, parentage and patronage yang memegang peranan. Faktor pengasuhan serta patronaselah yang berperan signifikan dalam membentuk seseorang menjadi “somebody” atau tidak sama sekali.
Tulisan si kribo Gladwell, mendapat dukungan Geoff Colvin lewat bukunya yang juga inspiratif, Talent is Overrated. Ya, bakat memang karunia yang distingtif pada manusia-manusia istimewa – bahkan sejatinya bakat itu ada pada tiap manusia. Tapi, sarannya, hendaknya orang tak terlalu menilai tinggi (overrated) sekaligus memuja-muji atas sesuatu yang disebut bakat karena banyak faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya seseorang. Dengan kata lain: bakat memang perlu, tapi itu tidak mutlak mengangkat nasib seseorang ke derajat yang lebih tinggi.
Dan rasanya, itu benar adanya. Anda tahu Lionel Andres Messi, sang penerus Maradona? Pemain Terbaik UEFA 2009 yang juga berpeluang besar meraih Ballon d'Or (Bola Emas) 2009 ini mungkin hanya menjadi seorang anak biasa di Rosario, Argentina bila para pemandu bakat dari FC Barcelona (Spanyol) tak bisa membujuk kedua orang tuanya untuk membawanya ke Barcelona dan memberinya suntikan hormon agar badannya tidak boncel.
Bocah kelahiran 24 Juni 1987 ini memang dikarunia bakat luar biasa. Bermain sepakbola sejak usia 5 tahun untuk klub Grandoli yang dilatih ayahnya, Jorge Messi, si bocah jenius ini kemudian pindah ke Newell’s Old Boy di tahun 1995. Malang tak bisa ditolak, saat usianya 11 tahun, dokter mendiagnosis anak ini mengidap apa yang disebut “growth hormone deficiency”. Tubuh Messi akan sulit berkembang karena defisiensi hormon pertumbuhan. Tinggi badannya divonis tak bisa melewati 140 cm. Mendekati setinggi itu pun sudah untung.
River Plate, salah satu klub besar Argentina yang juga pesaing Newell’s Old Boy, awalnya berniat mengambil persoalan ini. Rencananya: Messi ditarik ke klub itu dan diberikan treatment khusus. Tapi, biaya terapi hormon yang sebesar US$ 900 per bulan membuat manajemen River Plate mengurungkan niat. Mereka masih pikir-pikir untuk investasi yang tingkat pengembaliannya masih samar buat bocah 11 tahun. Buntutnya, nasib Messi pun menjadi ikut-ikutan tidak jelas.
Charles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona yang mencium bakat besar di Rosario segera bertindak. Dari Spanyol dia datang ke Rosario. Dia menawari Messi pengobatan bila keluarganya bersedia pindah ke wilayah Catalan, tempat Barcelona bermarkas. Dan begitulah cerita tentang anak jenius itu dirajut. Messi bergabung dengan klub Barcelona, dilatih hingga puluhan ribu jam di La Masia (Akademi Barcelona), diberikan suntikan hormon hingga akhirnya kini seperti yang dikenal dunia: Messi yang memberi banyak gelar pada Barcelona, Messi yang dipatok harga jualnya 70 juta pound, Messi sang Mesiah dengan tinggi 169 cm.
Messi jelas punya bakat yang dipertunjukkannya saat meliuk-liuk melewati lawan serta menjaringkan si kulit bundar. Namun, faktor orang tua, patron yang bernama Rexach serta manajemen Barcelona memegang peranan dalam menciptakan lingkungan yang membuat seluruh bakatnya berkembang maksimal. Messi sungguh beruntung mendapatkan itu semua. Akan tetapi, anak Rosario itu sendiri juga berperan besar, khususnya dalam membangun mentalitas juara. Mentalitas untuk melewati titik “kutukan” 140 cm dengan kesabaran menerima suntikan hormon secara berkala. Mentalitas untuk belajar menendang dan menaikkan jam terbang dalam urusan melatih dribling kaki kirinya yang luar biasa dan paket skill lainnya mulai dari mengoper hingga mencetak gol. Melihat semua yang terjadi, mungkin orang layak menerung: apa jadinya bakat Messi bila tak ditunjang dengan lingkungan serta mentalitas seperti itu?
Billy Jean King, sang legenda tennis dari AS pernah bilang dengan nada serius, “pressure is privileged”. Tekanan hanya datang pada orang-orang tertentu. Ya, tekanan adalah privilese, tidak datang pada setiap orang. Hanya para juara bermental baja yang sanggup menghadapinya. Dan di jagat tenis, kini Roger Federer adalah orangnya. 15 gelar grand slam koleksinya (6 gelar Wimbledon, 5 kali AS Terbuka, 3 gelar Australia Terbuka, dan satu dari Perancis Terbuka) akan sulit disamai para petenis manapun, terlebih mengingat usianya yang secara matematis masih panjang untuk mengejar tambahan raihan trofi. Dalam sejarah tenis, Federer adalah yang terbanyak masuk final grand slam, 21 kali. Terakhir, dia kalah atas Juan Martin Del Potro di final AS Terbuka, 15 September 2009. Dan dalam urusan uang, lelaki murah senyum ini juga jagonya: ditaksir lebih dari US$ 50,7 juta telah dikantunginya.
Menatap sepak terjang Federer adalah seperti melihat kesempurnaan. Namun, jelas sangat keliru bila melihat posisi berikut seluruh raihan petenis yang dijuluki Federer Express itu hanya dengan cara mengukurnya dari sisi bakat. Pencapaian Federer adalah buah dari lingkungan kondusif yang diberikan orang tuanya, Robert Federer dan Lynette Du Rand. Juga keseriusannya sendiri untuk terus mengasah jam terbang: memukul bola dengan segala jenis gaya, dan di atas segala jenis lapangan.
Mulai belajar tenis di usia 6 tahun, pada usia 12 tahun, Federer yang juga berbakat pada sepakbola dan fans berat FC Basel, akhirnya menyatakan pada orang tuanya bahwa dia memutuskan tenis sebagai masa depannya. Mendapat restu orang tua, Federer kemudian menempa diri. Dia tak henti berlatih, bahkan dengan porsi yang tinggi, minimal 4-6 jam sehari. Kelak, kebiasaan ini tak pernah hilang dari dirinya. Lelaki setingi 1,85 m itu bahkan mengaku hanya libur berlatih selama dua hari ketika menemani istrinya, Miroslava Vavrinec melahirkan anak kembar mereka, Charlene Riva dan Myla Rose, Juli 2009. Setelah itu, dia kembali berlatih, mengasah dan mempertajam seluruh kekuatan pukulannya.
Tak pelak, latihan spartan inilah yang kemudian menjadi dasar kekuatannya sehingga Jimmy Connors, mantan petenis top AS memujinya habis-habisan. "Di era spesialis seperti sekarang, Anda mungkin jago di clay court, spesialis lapangan rumput, kampiun hard court, atau ... Anda adalah Roger Federer," katanya. Masudnya?
Tak seperti pemain lainnya yang cuma piawai pada lapangan tertentu, Federer jago semua jenis lapangan turnamen besar, khususnya grand slam. Karena itu dia dijuluki “an all-court player”. Lapangan apapun, disikatnya!
Ada banyak cerita tentang outlier dari jagat olahraga. Namun, pesan yang mereka kirim adalah sama: bakat mereka berkembang sempurna di lingkungan yang bisa memaksimalkannya sehingga dapat menjadi persona-persona nan hebat. Contoh dari dunia sepakbola adalah bakat-bakat terbaik dari Afrika, Amerika Latin dan Asia yang mencorong di Eropa karena lingkungan di Benua Biru itu kondusif, terutama dengan adanya sistem kompetisi serta liga yang profesional, juga pelatih-pelatih bertangan dingin.
Di sejumlah negara Afrika, terutama, bakat-bakat itu terancam hanya akan tergerus usia dan tersia-siakan karena persoalan-persoalan non teknis serta politis, seperti perang, kemiskinan, dan kelaparan. Begitu pula dengan bakat yang tersia-sia di sejumlah negara Asia yang liganya sangat tidak profesional. Faktor lingkungan yang kondusif untuk menyemai bakat ini penting karena fakta membuktikan betapa negara-negara Asia dengan sistem kompetisi yang profesional seperti Jepang dan Korea Selatan mampu menghasilkan pemain-pemain hebat melebihi negara-negara Asia lainnya yang sistem kompetisinya amburadul.
Dari jagat profesional di dunia bisnis, hal serupa juga sering terjadi: bahwa bakat tidaklah selalu berperan paling dominan dalam kesuksesan.
Pertengahan 1978. Di markas besar Procter & Gamble di Cincinnati, AS, dua anak muda berusia 22 tahun yang baru saja lulus sedang asyik mencorat-coret memo bisnis. Keduanya tengah ditugaskan menjual adonan brownies Duncan Hines. Keduanya cerdas, yang satu dari Harvard, yang satunya dari Dartmouth College. Keduanya karyawan baru di P&G. Keduanya berada di ruang yang sama.
Saat itu tak ada yang menonjol dibanding rekrutmen baru P&G lainnya. Tapi, apa yang membuat keduanya kelak berbeda dibanding rekan-rekan seangkatan adalah keduanya penuh dengan ambisi di samping bakat bisnis yang besar. Tahukah Anda siapa mereka?
Mereka adalah Jeffrey Robert Immelt dan Steven Anthony Ballmer yang sebelum menginjak usia 50 tahun telah menjadi CEO dari dua perusahaan raksasa dunia, General Electric dan Microsoft. Apa yang membuat keduanya hebat, selain penuh dengan ambisi dan bakat kepemimpinan, juga keberuntungan mendapat patron yang luar biasa. Ballmer mendapat mitra yang hebat dalam diri Bill Gates ketika memutuskan bergabung dengan Microsoft pada tahun 1980, sementara Jeffrey Immelt yang bergabung dengan GE pada 1982 sangat beruntung karena digembleng patron terbesarnya yang juga seorang legenda bisnis, Jack Welch. Bila tak bertemu dua titan tersebut, mungkin mereka hanyalah orang-orang biasa. Atau, kalaupun hebat, belum tentu seperti sekarang. Keduanya, Gates dan Welch, berpengaruh sangat besar dalam membentuk jalan sehingga mereka bisa duduk di kursi yang sangat tinggi ini.
Memang, hidup tampak jauh lebih nikmat bagi mereka yang penuh bakat. Mereka punya lebih banyak pilihan, punya lebih peluang untuk sukses. Tapi, tunggu dulu, sebagaimana ditulis Gladwell dan Colvin: sebetulnya tidak ada masalah dengan apa yang Anda miliki ketika dilahirkan karena sukses besar tersedia bagi siapa saja yang bersedia untuk terus mengasah diri, melatih mental, mencari lingkungan yang kondusif, berada dalam jejaring yang positif, dan… tentu saja memiliki keberuntungan.
Jack Welch yang dijuluki Manajer Abad 20, misalnya, tak menunjukkan minatnya pada bisnis hingga usia pertengahan 20-an. Dengan gelar doktor rekayasa kimia, dia baru bersentuhan dengan dunia bisnis pada usia 25 tahun. Itupun setelah dia memutuskan bekerja di bagian pengembangan kimia di General Electric dan mengabaikan kemungkinan bekerja di universitas Syracuse serta West Virigia. Tapi kesediaannya untuk belajar membuatnya menjadi outlier di kalangan profesional bisnis, yang mengundang kekaguman hingga kini.
Bakat memang karunia. Tapi sebagaimana juga ditulis Colvin, “para ilmuwan hingga kini belum bisa menemukan atau mengidentifikasi gen yang membawa bakat tertentu seperti gen pemain piano, gen investasi, atau gen akuntansi”. Apa yang bisa membuat sukses seseorang, yang disebut Gladwell sebagai 10 ribu jam terbang, menurut Colvin adalah "deliberate practice". Ini bukan sekedar frekuensi atau lamanya sebuah latihan, tapi istilah untuk sebuah latihan atau praktik yang dilakukan secara konsisten guna meningkatkan performa. Jadi, pendekatannya adalah kualitas, bukan kuantitas. Dalam konteks ini, para maestro yang telah melakukannya sejak dini dan disebut sebagai contoh terbaik adalah Tiger Woods, Pablo Picasso serta Wolfgang Amadeus Mozart.
Tentu tak semua orang dapat keberuntungan melatih satu bakat atau keahlian tertentu pada usia yang sangat dini. Namun, praktik yang konsisten ini sangat penting karena begitu satu kesempatan datang, level performa tertentu telah dimiliki. Alhasil, deliberate practice adalah kunci penting untuk menjemput sukses, the key when opportunity comes. Hanya saja, seperti juga telah disinggung Jean King, deliberate practice memerlukan sikap mental yang kuat karena latihan yang konsisten kerap kali tidak mudah, penuh cobaan. “It's highly demanding mentally,” tulis Colvin.
Selain mental, deliberate practice juga membutuhkan upaya untuk fokus dan konsentrasi tinggi. Itu artinya membutuhkan daya tahan pikiran. Federer menjadi maestro karena ketahanannya untuk tetap fokus memukul bola di tengah segala tekanan saat bermain. Dia juga jarang terlihat emosional ketika dalam posisi tertinggal. Saking hebatnya dia bermain, sampai-sampai banyak artikel bermunculan hanya dengan satu topik: bagaimana mengalahkan Federer yang selalu tampil prima?
Tentang pentingnya kekuatan fokus dalam deliberate practice dialami Nathan Mironovich Milstein, salah seorang dari pemain biola terbaik abad 20. Milstein yang kelahiran Odessa (Ukraina) adalah murid dari guru terkenal, Leopold Auer di St. Pertersburg. Suatu waktu, sehabis berlatih, Milstein bertanya pada gurunya: apakah latihannya sudah memadai? Auer menjawab singkat, tapi dalam, “Berlatihlah dengan jari-jarimu, maka kamu akan butuh sehari penuh. Sebaliknya, berlatihlah dengan pikiranmu, maka kamu cuma butuh 1,5 jam saja”. Apa yang dimaksudkan Auer adalah jika Anda benar-benar berlatih dengan menggunakan pikiran sepenuhnya, alias konsentrasi, maka 1,5 jam sudah memadai untuk memupuk kompetensi diri. Ingat, memupuk, yang artinya melakukannya secara berkesinambungan.
Yang menarik, Colvin kemudian menarik aspek kesuksesan individu ini untuk kemudian meletakkannya dalam konteks korporasi. Menurutnya, perusahaan yang hebat, adalah mereka yang juga bisa membuat bakat-bakat yang ada di dalamnya tumbuh berkembang dengan baik. Itu artinya, perusahaan perlu menciptakan iklim yang kondusif seperti budaya mentoring, coaching, dan kebiasaan membangun karir dengan pemberian tugas yang membangun potensi diri karyawan. Meminjam Gladwell, budaya kondusif di atas tak ubahnya menciptakan pola pengasuhan (parentage) yang tepat sehingga potensi-potensi terbaik bisa terasah. Apple, Google, serta Intuit adalah segelintir perusahaan yang bisa menciptakan iklim seperti itu.
Repotnya, tandas Colvin, banyak perusahaan mengabaikan faktor fundamental tersebut. Padahal, boleh jadi akan banyak outlier dalam tubuh suatu perusahaan begitu kultur tersebut dibangun. Outlier yang berwujud para profesional pilihan macam Ballmer atau Immelt, atau orang-orang sekreatif Steve Jobs. Orang-orang yang dijuluki the great man on their job.
Monday, September 28, 2009
Tuesday, September 15, 2009
Gonjang-ganjing Leadership Global
Krisis finansial tak hanya mengakibatkan CEO berguguran, tetapi juga membuat nilai-nilai kepemimpinan di kancah bisnis global digugat. Apa yang sebenarnya terjadi?
Teguh S. Pambudi
25 November 2008. Barbara Kellerman mengeluarkan catatan menarik dalam tulisannya, Leadership Malpractice. Pada tulisan yang dimuat di Harvard Business Online itu, pengajar Public Leadership di John F. Kennedy School of Government itu mencatat bahwa dalam 9 bulan pertama di tahun 2008, sedikitnya ada 1.132 CEO di sejumlah negara yang terpental dari posisinya, atau diminta untuk segera hengkang. Tekanan krisis membuat mereka rontok, atau dirontokkan karena dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial.
Angka yang dikutip Kellerman mungkin terbilang fantastis. Namun, Booz & Company, dalam surveinya yang dirilis 26 Mei 2009 mencatat bahwa turnover CEO memang meningkat: dari 13,8% menjadi 14,4% di tahun 2008. Dalam laporannya bertajuk CEO Succession 2008 itu, sedikitnya tercatat 361 suksesi di antara 2.500 perusahaan publik papan atas global di tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 180 CEO dilengserkan karena memang telah direncanakan sebelumnya (pensiun, sakit), 54 CEO diganti karena terjadi merger-akuisisi, dan hanya 127 orang yang dipaksa mundur karena kinerja yang buruk serta persoalan etika.
Sejak krisis finansial meledak, pembahasan tentang peran para leader di panggung bisnis global memang kian mengemuka. Umumnya mengerucut pada hal berikut: apa yang terjadi sehingga leader justru menjadikan kondisi memburuk? Tidakkah cukup kasus Enron dan WorldComm mengajarkan betapa leadership yang buruk membuat malapetaka besar?
“Ada ingredient yang hilang,” cetus Rick Wartzman, Direktur Drucker Institute at Claremont Graduate University. Menurut hematnya, dengan mengutip Drucker, the true leader adalah mereka yang membawa tanggung jawab, konsistensi, dan sense yang tajam untuk semua hal yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di Wall Street yang kemudian mengguncang dunia, menurut Wartzman, menunjukkan mereka kehilangan itu semua. Sebagai leader, mereka yang mestinya penuh tanggung jawab dalam bertindak, justru dengan seenaknya berperilaku, mempermainkan kuasa yang mereka punya.
Yang membuat publik makin kesal, tulis Wartzman, sejumlah CEO sepertinya tidak mau disalahkan sekaligus menanggung beban atas ulahnya yang menjengkelkan itu. Mantan petinggi Lehman Brothers dan American International Group (AIG), ketika berbicara di Capitol Hill menuduh bahwa kekacauan finansial terjadi di luar diri dan institusi mereka. Dengan gagahnya, mereka justru menuding kalangan pasar modal, short-seller, juga regulator yang menimbulkan malapetaka ini semua. “Kalau melihat saat saya jadi CEO,” tukas Robert Willumstad, “saya tidak percaya AIG berbuat sesuatu yang aneh-aneh.” Begitu kata mantan CEO AIG ini. “Ya, kami sama-sama prudent,” tukas Richard Fuld, Chairman merangkap CEO Lehman Brothers dengan enteng.
“The leader's first task is to be the trumpet that sounds a clear sound.” Demikian Peter F. Drucker pernah menulis. “Effective leadership – and again this is very old wisdom – is not based on being clever; it is based primarily on being consistent,” lanjutnya.
Jelas, perilaku yang didemonstrasikan Fuld dan Willumstald itu, tak ayal mengundang kegeraman banyak pihak. “Mereka adalah teroris keuangan,” kata Max Keiser, kolomnis di Huffington Post, media online yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Wajar saja dia gusar. Keiser mewakili perasaan publik yang menyaksikan jutaan pekerjaan hilang dan kebanyakan tak pernah kembali. Begitu pula dengan triliunan dolar yang… wuzzz… menguap entah ke mana.
Alhasil, flawed leadership (kepemimpinan yang cacat), leadership malpractice adalah sinisme terhadap para business leader di Barat hari-hari ini. Mereka marah. Geram. Gusar.
Menariknya, di tengah sorotan demikian, kalangan sekolah bisnis pun tak luput dari sinisme. Banyak orang percaya bahwa pendidikan manajemen telah menyumbang pada kegagalan sistemik atas kepemimpinan bisnis yang mengantar ke krisis keuangan. Satu tulisan di Harvard Business Review (Juni 2009) mencatat dengan baik kejengkelan tersebut. Berjudul The Buck Stops (and Starts) at Business School, Joel M. Podolny mencatat bahwa dia marah karena tiadanya perhatian pada apa yang disebut ethics and value-based leadership di sekolah-sekolah bisnis.
Vice President Apple University in Cupertino, Kalifornia ini merespons sejumlah surat yang dimuat di New York Times, edisi 3 Maret 2009. Surat yang masuk itu membuat tekanan agar sekolah bisnis juga mengajarkan humanities. Mereka menyatakan bahwa dengan mempelajari seni, sejarah budaya, sastra, filsafat, dan juga agama, akan membuat orang mengembangkan daya nalar yang dipenuhi moralitas. Apa yang diajarkan sekolah bisnis masa kini adalah melahirkan pemimpin bisnis yang berpikir pendek, sekadar dimensi bisnis, dan mengambil keputusan hanya atas pertimbangan keuntungan. Bagi Podolny, seperti disinggung di atas, lebih tepatnya karena kurang aktifnya pengajaran perihal ethics and value-based leadership.
Gayung pun bersambut. Pemikiran tentang perlunya kurikulum Rethinking C-school demi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas secara intelektual-moral-spiritual memang dirasa semakin mendesak (BusinessWeek, 30 Juli 2009). Tak heran, sejak Agustus 2009, dunia sekolah bisnis di Barat mengalami banyak perubahan. Sejumlah kelas bukan lagi mengajarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi – berikut penyebab munculnya krisis – atau tentang manajemen risiko, tetapi juga menitikberatkan pada etika. Bahkan, pelajaran seputar hal tersebut diprediksi akan memainkan porsi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gonjang-ganjing yang menyoroti pemimpin bisnis, menariknya bukan cuma membuat kalangan sekolah bisnis “dihajar” habis-habisan. Yang cukup menggelitik, sejumlah pakar leadership pun kini kian mempertanyakan nilai-nilai kepemimpinan Barat yang dipandang tidak bisa menolong dari kondisi bisnis yang memburuk, malah membuat semakin parah.
Salah satu gerakan yang muncul adalah upaya melirik moral leadership dari Cina dan berharap ada sesuatu di sana yang bisa membantu dunia kepemimpinan dan bisnis secara keseluruhan dari nilai-nilai Konfusianisme. “Kerakusan eksekutif dan sistem keyakinan yang salah dalam sistem kapitalisme modern membuat ini terjadi. Barat telah kehilangan basis moralnya,” sebagaimana dikutip BusinessWeek (15 Mei 2009).
Faktanya, pemerhati kepemimpinan dan para profesional Cina itu sendiri kini memang tengah aktif-aktifnya menggali nilai kepemimpinan bisnis dari nilai tradisional mereka. Mereka yang ada di pusat bisnis seperti Shanghai dan Beijing, disebut-sebut semakin tidak percaya nilai kepemimpinan Barat yang terbukti berkali-kali memunculkan krisis dan skandal. Bahkan, seperti juga gugatan yang muncul di Barat, mereka mempertanyakan ajaran Adam Smith tentang the invisible hand di pasar, yang ternyata membuat para pemimpin pasar bertindak seliar-liarnya.
Pemerintah Cina sendiri, jauh sebelum krisis meledak, sudah mendorong kalangan swasta untuk mencari moral leadership dari leluhurnya. Tahun 2006, Pemerintah Cina mendorong digelarnya the World Buddhist Forum di Hangzhou yang salah satunya mencari nilai kepemimpinan bisnis. Selain dari Buddha, mereka juga mencari nilai-nilai dari Konfusianisme dan Taoisme untuk menjadi vitamin bagi kalangan pemimpin bisnis.
Konferensi itu akhirnya menetaskan Deklarasi Putuoshan. Bunyinya: “Setiap orang bertanggung jawab pada keharmonisan dunia, yang dimulai dari pikirannya.” Deklarasi itu benar-benar menohok. Meminta agar orang, terutama pemimpin bisnis, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga dunia global. Dan itu harus dimulai dari pikirannya.
Deklarasi itu muncul sebelum krisis meledak. Setelah krisis datang mengentak, keinginan untuk kian menggali nilai-nilai dari Cina, apakah Konfusius atau Tao, terus menggelinding. Percakapan di kalangan wirausaha Cina, pemimpin korporasi, dan akademisi mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar mencari kompas moral yang bisa digunakan di tengah kegaduhan nilai kepemimpinan Barat yang ternyata keropos. Mereka mencari nilai kepemimpinan yang telah tercerabut dari akar budaya mereka. Baik karena pengaruh revolusi kebudayaan Mao Zedong maupun hasil interaksi dengan Barat.
Dalam konteks pencarian ini, memang banyak kalangan yang meragukan apakah nilai kepemimpinan Cina sanggup mengatasi persoalan di dunia bisnis global. Mereka ragu bukan lantaran Cina baru tahap menjadi aktor ekonomi global. Mereka ragu dengan menyoroti bahwa negeri itu terhitung tempat berbisnis dengan sistem yang dikeluhkan masih kurang transparan dan nepotisme. Apa bisa negeri ini menawarkan sesuatu sementara sistem mereka sendiri juga bermasalah? Apa yang bisa diharapkan sementara pemerintah mereka masih kerja keras memberangus korupsi?
Keraguan yang masuk akal. Namun, yang meyakini pun tidak sedikit. Asumsinya, terlepas dari Pemerintah Cina sendiri menghadapi persoalan, nilai Konfusianisme dan Taoisme dapat diadopsi secara universal. Di antara nilai Konfusianisme yang kini relevan adalah unselfishness, careful thinking dan careful acting.
Terlepas dari pro dan kontra pencarian terhadap nilai kepemimpinan Cina, pesan yang sesungguhnya ditangkap dari gonjang-ganjing kepemimpinan global saat ini bahwa sesungguhnya nilai-nilai atau kebijakan lokal ada dalam setiap masyarakat, di mana pun di dunia ini. Terkait dengan Indonesia, kinilah saatnya kembali menggali nilai-nilai kepemimpinan yang sudah dimiliki, yang sesungguhnya sangat luhur bila diaplikasikan.
Teguh S. Pambudi
25 November 2008. Barbara Kellerman mengeluarkan catatan menarik dalam tulisannya, Leadership Malpractice. Pada tulisan yang dimuat di Harvard Business Online itu, pengajar Public Leadership di John F. Kennedy School of Government itu mencatat bahwa dalam 9 bulan pertama di tahun 2008, sedikitnya ada 1.132 CEO di sejumlah negara yang terpental dari posisinya, atau diminta untuk segera hengkang. Tekanan krisis membuat mereka rontok, atau dirontokkan karena dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial.
Angka yang dikutip Kellerman mungkin terbilang fantastis. Namun, Booz & Company, dalam surveinya yang dirilis 26 Mei 2009 mencatat bahwa turnover CEO memang meningkat: dari 13,8% menjadi 14,4% di tahun 2008. Dalam laporannya bertajuk CEO Succession 2008 itu, sedikitnya tercatat 361 suksesi di antara 2.500 perusahaan publik papan atas global di tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 180 CEO dilengserkan karena memang telah direncanakan sebelumnya (pensiun, sakit), 54 CEO diganti karena terjadi merger-akuisisi, dan hanya 127 orang yang dipaksa mundur karena kinerja yang buruk serta persoalan etika.
Sejak krisis finansial meledak, pembahasan tentang peran para leader di panggung bisnis global memang kian mengemuka. Umumnya mengerucut pada hal berikut: apa yang terjadi sehingga leader justru menjadikan kondisi memburuk? Tidakkah cukup kasus Enron dan WorldComm mengajarkan betapa leadership yang buruk membuat malapetaka besar?
“Ada ingredient yang hilang,” cetus Rick Wartzman, Direktur Drucker Institute at Claremont Graduate University. Menurut hematnya, dengan mengutip Drucker, the true leader adalah mereka yang membawa tanggung jawab, konsistensi, dan sense yang tajam untuk semua hal yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di Wall Street yang kemudian mengguncang dunia, menurut Wartzman, menunjukkan mereka kehilangan itu semua. Sebagai leader, mereka yang mestinya penuh tanggung jawab dalam bertindak, justru dengan seenaknya berperilaku, mempermainkan kuasa yang mereka punya.
Yang membuat publik makin kesal, tulis Wartzman, sejumlah CEO sepertinya tidak mau disalahkan sekaligus menanggung beban atas ulahnya yang menjengkelkan itu. Mantan petinggi Lehman Brothers dan American International Group (AIG), ketika berbicara di Capitol Hill menuduh bahwa kekacauan finansial terjadi di luar diri dan institusi mereka. Dengan gagahnya, mereka justru menuding kalangan pasar modal, short-seller, juga regulator yang menimbulkan malapetaka ini semua. “Kalau melihat saat saya jadi CEO,” tukas Robert Willumstad, “saya tidak percaya AIG berbuat sesuatu yang aneh-aneh.” Begitu kata mantan CEO AIG ini. “Ya, kami sama-sama prudent,” tukas Richard Fuld, Chairman merangkap CEO Lehman Brothers dengan enteng.
“The leader's first task is to be the trumpet that sounds a clear sound.” Demikian Peter F. Drucker pernah menulis. “Effective leadership – and again this is very old wisdom – is not based on being clever; it is based primarily on being consistent,” lanjutnya.
Jelas, perilaku yang didemonstrasikan Fuld dan Willumstald itu, tak ayal mengundang kegeraman banyak pihak. “Mereka adalah teroris keuangan,” kata Max Keiser, kolomnis di Huffington Post, media online yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Wajar saja dia gusar. Keiser mewakili perasaan publik yang menyaksikan jutaan pekerjaan hilang dan kebanyakan tak pernah kembali. Begitu pula dengan triliunan dolar yang… wuzzz… menguap entah ke mana.
Alhasil, flawed leadership (kepemimpinan yang cacat), leadership malpractice adalah sinisme terhadap para business leader di Barat hari-hari ini. Mereka marah. Geram. Gusar.
Menariknya, di tengah sorotan demikian, kalangan sekolah bisnis pun tak luput dari sinisme. Banyak orang percaya bahwa pendidikan manajemen telah menyumbang pada kegagalan sistemik atas kepemimpinan bisnis yang mengantar ke krisis keuangan. Satu tulisan di Harvard Business Review (Juni 2009) mencatat dengan baik kejengkelan tersebut. Berjudul The Buck Stops (and Starts) at Business School, Joel M. Podolny mencatat bahwa dia marah karena tiadanya perhatian pada apa yang disebut ethics and value-based leadership di sekolah-sekolah bisnis.
Vice President Apple University in Cupertino, Kalifornia ini merespons sejumlah surat yang dimuat di New York Times, edisi 3 Maret 2009. Surat yang masuk itu membuat tekanan agar sekolah bisnis juga mengajarkan humanities. Mereka menyatakan bahwa dengan mempelajari seni, sejarah budaya, sastra, filsafat, dan juga agama, akan membuat orang mengembangkan daya nalar yang dipenuhi moralitas. Apa yang diajarkan sekolah bisnis masa kini adalah melahirkan pemimpin bisnis yang berpikir pendek, sekadar dimensi bisnis, dan mengambil keputusan hanya atas pertimbangan keuntungan. Bagi Podolny, seperti disinggung di atas, lebih tepatnya karena kurang aktifnya pengajaran perihal ethics and value-based leadership.
Gayung pun bersambut. Pemikiran tentang perlunya kurikulum Rethinking C-school demi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas secara intelektual-moral-spiritual memang dirasa semakin mendesak (BusinessWeek, 30 Juli 2009). Tak heran, sejak Agustus 2009, dunia sekolah bisnis di Barat mengalami banyak perubahan. Sejumlah kelas bukan lagi mengajarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi – berikut penyebab munculnya krisis – atau tentang manajemen risiko, tetapi juga menitikberatkan pada etika. Bahkan, pelajaran seputar hal tersebut diprediksi akan memainkan porsi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gonjang-ganjing yang menyoroti pemimpin bisnis, menariknya bukan cuma membuat kalangan sekolah bisnis “dihajar” habis-habisan. Yang cukup menggelitik, sejumlah pakar leadership pun kini kian mempertanyakan nilai-nilai kepemimpinan Barat yang dipandang tidak bisa menolong dari kondisi bisnis yang memburuk, malah membuat semakin parah.
Salah satu gerakan yang muncul adalah upaya melirik moral leadership dari Cina dan berharap ada sesuatu di sana yang bisa membantu dunia kepemimpinan dan bisnis secara keseluruhan dari nilai-nilai Konfusianisme. “Kerakusan eksekutif dan sistem keyakinan yang salah dalam sistem kapitalisme modern membuat ini terjadi. Barat telah kehilangan basis moralnya,” sebagaimana dikutip BusinessWeek (15 Mei 2009).
Faktanya, pemerhati kepemimpinan dan para profesional Cina itu sendiri kini memang tengah aktif-aktifnya menggali nilai kepemimpinan bisnis dari nilai tradisional mereka. Mereka yang ada di pusat bisnis seperti Shanghai dan Beijing, disebut-sebut semakin tidak percaya nilai kepemimpinan Barat yang terbukti berkali-kali memunculkan krisis dan skandal. Bahkan, seperti juga gugatan yang muncul di Barat, mereka mempertanyakan ajaran Adam Smith tentang the invisible hand di pasar, yang ternyata membuat para pemimpin pasar bertindak seliar-liarnya.
Pemerintah Cina sendiri, jauh sebelum krisis meledak, sudah mendorong kalangan swasta untuk mencari moral leadership dari leluhurnya. Tahun 2006, Pemerintah Cina mendorong digelarnya the World Buddhist Forum di Hangzhou yang salah satunya mencari nilai kepemimpinan bisnis. Selain dari Buddha, mereka juga mencari nilai-nilai dari Konfusianisme dan Taoisme untuk menjadi vitamin bagi kalangan pemimpin bisnis.
Konferensi itu akhirnya menetaskan Deklarasi Putuoshan. Bunyinya: “Setiap orang bertanggung jawab pada keharmonisan dunia, yang dimulai dari pikirannya.” Deklarasi itu benar-benar menohok. Meminta agar orang, terutama pemimpin bisnis, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga dunia global. Dan itu harus dimulai dari pikirannya.
Deklarasi itu muncul sebelum krisis meledak. Setelah krisis datang mengentak, keinginan untuk kian menggali nilai-nilai dari Cina, apakah Konfusius atau Tao, terus menggelinding. Percakapan di kalangan wirausaha Cina, pemimpin korporasi, dan akademisi mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar mencari kompas moral yang bisa digunakan di tengah kegaduhan nilai kepemimpinan Barat yang ternyata keropos. Mereka mencari nilai kepemimpinan yang telah tercerabut dari akar budaya mereka. Baik karena pengaruh revolusi kebudayaan Mao Zedong maupun hasil interaksi dengan Barat.
Dalam konteks pencarian ini, memang banyak kalangan yang meragukan apakah nilai kepemimpinan Cina sanggup mengatasi persoalan di dunia bisnis global. Mereka ragu bukan lantaran Cina baru tahap menjadi aktor ekonomi global. Mereka ragu dengan menyoroti bahwa negeri itu terhitung tempat berbisnis dengan sistem yang dikeluhkan masih kurang transparan dan nepotisme. Apa bisa negeri ini menawarkan sesuatu sementara sistem mereka sendiri juga bermasalah? Apa yang bisa diharapkan sementara pemerintah mereka masih kerja keras memberangus korupsi?
Keraguan yang masuk akal. Namun, yang meyakini pun tidak sedikit. Asumsinya, terlepas dari Pemerintah Cina sendiri menghadapi persoalan, nilai Konfusianisme dan Taoisme dapat diadopsi secara universal. Di antara nilai Konfusianisme yang kini relevan adalah unselfishness, careful thinking dan careful acting.
Terlepas dari pro dan kontra pencarian terhadap nilai kepemimpinan Cina, pesan yang sesungguhnya ditangkap dari gonjang-ganjing kepemimpinan global saat ini bahwa sesungguhnya nilai-nilai atau kebijakan lokal ada dalam setiap masyarakat, di mana pun di dunia ini. Terkait dengan Indonesia, kinilah saatnya kembali menggali nilai-nilai kepemimpinan yang sudah dimiliki, yang sesungguhnya sangat luhur bila diaplikasikan.
Labels:
Leadership