Krisis finansial tak hanya mengakibatkan CEO berguguran, tetapi juga membuat nilai-nilai kepemimpinan di kancah bisnis global digugat. Apa yang sebenarnya terjadi?
Teguh S. Pambudi
25 November 2008. Barbara Kellerman mengeluarkan catatan menarik dalam tulisannya, Leadership Malpractice. Pada tulisan yang dimuat di Harvard Business Online itu, pengajar Public Leadership di John F. Kennedy School of Government itu mencatat bahwa dalam 9 bulan pertama di tahun 2008, sedikitnya ada 1.132 CEO di sejumlah negara yang terpental dari posisinya, atau diminta untuk segera hengkang. Tekanan krisis membuat mereka rontok, atau dirontokkan karena dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial.
Angka yang dikutip Kellerman mungkin terbilang fantastis. Namun, Booz & Company, dalam surveinya yang dirilis 26 Mei 2009 mencatat bahwa turnover CEO memang meningkat: dari 13,8% menjadi 14,4% di tahun 2008. Dalam laporannya bertajuk CEO Succession 2008 itu, sedikitnya tercatat 361 suksesi di antara 2.500 perusahaan publik papan atas global di tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 180 CEO dilengserkan karena memang telah direncanakan sebelumnya (pensiun, sakit), 54 CEO diganti karena terjadi merger-akuisisi, dan hanya 127 orang yang dipaksa mundur karena kinerja yang buruk serta persoalan etika.
Sejak krisis finansial meledak, pembahasan tentang peran para leader di panggung bisnis global memang kian mengemuka. Umumnya mengerucut pada hal berikut: apa yang terjadi sehingga leader justru menjadikan kondisi memburuk? Tidakkah cukup kasus Enron dan WorldComm mengajarkan betapa leadership yang buruk membuat malapetaka besar?
“Ada ingredient yang hilang,” cetus Rick Wartzman, Direktur Drucker Institute at Claremont Graduate University. Menurut hematnya, dengan mengutip Drucker, the true leader adalah mereka yang membawa tanggung jawab, konsistensi, dan sense yang tajam untuk semua hal yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di Wall Street yang kemudian mengguncang dunia, menurut Wartzman, menunjukkan mereka kehilangan itu semua. Sebagai leader, mereka yang mestinya penuh tanggung jawab dalam bertindak, justru dengan seenaknya berperilaku, mempermainkan kuasa yang mereka punya.
Yang membuat publik makin kesal, tulis Wartzman, sejumlah CEO sepertinya tidak mau disalahkan sekaligus menanggung beban atas ulahnya yang menjengkelkan itu. Mantan petinggi Lehman Brothers dan American International Group (AIG), ketika berbicara di Capitol Hill menuduh bahwa kekacauan finansial terjadi di luar diri dan institusi mereka. Dengan gagahnya, mereka justru menuding kalangan pasar modal, short-seller, juga regulator yang menimbulkan malapetaka ini semua. “Kalau melihat saat saya jadi CEO,” tukas Robert Willumstad, “saya tidak percaya AIG berbuat sesuatu yang aneh-aneh.” Begitu kata mantan CEO AIG ini. “Ya, kami sama-sama prudent,” tukas Richard Fuld, Chairman merangkap CEO Lehman Brothers dengan enteng.
“The leader's first task is to be the trumpet that sounds a clear sound.” Demikian Peter F. Drucker pernah menulis. “Effective leadership – and again this is very old wisdom – is not based on being clever; it is based primarily on being consistent,” lanjutnya.
Jelas, perilaku yang didemonstrasikan Fuld dan Willumstald itu, tak ayal mengundang kegeraman banyak pihak. “Mereka adalah teroris keuangan,” kata Max Keiser, kolomnis di Huffington Post, media online yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Wajar saja dia gusar. Keiser mewakili perasaan publik yang menyaksikan jutaan pekerjaan hilang dan kebanyakan tak pernah kembali. Begitu pula dengan triliunan dolar yang… wuzzz… menguap entah ke mana.
Alhasil, flawed leadership (kepemimpinan yang cacat), leadership malpractice adalah sinisme terhadap para business leader di Barat hari-hari ini. Mereka marah. Geram. Gusar.
Menariknya, di tengah sorotan demikian, kalangan sekolah bisnis pun tak luput dari sinisme. Banyak orang percaya bahwa pendidikan manajemen telah menyumbang pada kegagalan sistemik atas kepemimpinan bisnis yang mengantar ke krisis keuangan. Satu tulisan di Harvard Business Review (Juni 2009) mencatat dengan baik kejengkelan tersebut. Berjudul The Buck Stops (and Starts) at Business School, Joel M. Podolny mencatat bahwa dia marah karena tiadanya perhatian pada apa yang disebut ethics and value-based leadership di sekolah-sekolah bisnis.
Vice President Apple University in Cupertino, Kalifornia ini merespons sejumlah surat yang dimuat di New York Times, edisi 3 Maret 2009. Surat yang masuk itu membuat tekanan agar sekolah bisnis juga mengajarkan humanities. Mereka menyatakan bahwa dengan mempelajari seni, sejarah budaya, sastra, filsafat, dan juga agama, akan membuat orang mengembangkan daya nalar yang dipenuhi moralitas. Apa yang diajarkan sekolah bisnis masa kini adalah melahirkan pemimpin bisnis yang berpikir pendek, sekadar dimensi bisnis, dan mengambil keputusan hanya atas pertimbangan keuntungan. Bagi Podolny, seperti disinggung di atas, lebih tepatnya karena kurang aktifnya pengajaran perihal ethics and value-based leadership.
Gayung pun bersambut. Pemikiran tentang perlunya kurikulum Rethinking C-school demi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas secara intelektual-moral-spiritual memang dirasa semakin mendesak (BusinessWeek, 30 Juli 2009). Tak heran, sejak Agustus 2009, dunia sekolah bisnis di Barat mengalami banyak perubahan. Sejumlah kelas bukan lagi mengajarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi – berikut penyebab munculnya krisis – atau tentang manajemen risiko, tetapi juga menitikberatkan pada etika. Bahkan, pelajaran seputar hal tersebut diprediksi akan memainkan porsi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gonjang-ganjing yang menyoroti pemimpin bisnis, menariknya bukan cuma membuat kalangan sekolah bisnis “dihajar” habis-habisan. Yang cukup menggelitik, sejumlah pakar leadership pun kini kian mempertanyakan nilai-nilai kepemimpinan Barat yang dipandang tidak bisa menolong dari kondisi bisnis yang memburuk, malah membuat semakin parah.
Salah satu gerakan yang muncul adalah upaya melirik moral leadership dari Cina dan berharap ada sesuatu di sana yang bisa membantu dunia kepemimpinan dan bisnis secara keseluruhan dari nilai-nilai Konfusianisme. “Kerakusan eksekutif dan sistem keyakinan yang salah dalam sistem kapitalisme modern membuat ini terjadi. Barat telah kehilangan basis moralnya,” sebagaimana dikutip BusinessWeek (15 Mei 2009).
Faktanya, pemerhati kepemimpinan dan para profesional Cina itu sendiri kini memang tengah aktif-aktifnya menggali nilai kepemimpinan bisnis dari nilai tradisional mereka. Mereka yang ada di pusat bisnis seperti Shanghai dan Beijing, disebut-sebut semakin tidak percaya nilai kepemimpinan Barat yang terbukti berkali-kali memunculkan krisis dan skandal. Bahkan, seperti juga gugatan yang muncul di Barat, mereka mempertanyakan ajaran Adam Smith tentang the invisible hand di pasar, yang ternyata membuat para pemimpin pasar bertindak seliar-liarnya.
Pemerintah Cina sendiri, jauh sebelum krisis meledak, sudah mendorong kalangan swasta untuk mencari moral leadership dari leluhurnya. Tahun 2006, Pemerintah Cina mendorong digelarnya the World Buddhist Forum di Hangzhou yang salah satunya mencari nilai kepemimpinan bisnis. Selain dari Buddha, mereka juga mencari nilai-nilai dari Konfusianisme dan Taoisme untuk menjadi vitamin bagi kalangan pemimpin bisnis.
Konferensi itu akhirnya menetaskan Deklarasi Putuoshan. Bunyinya: “Setiap orang bertanggung jawab pada keharmonisan dunia, yang dimulai dari pikirannya.” Deklarasi itu benar-benar menohok. Meminta agar orang, terutama pemimpin bisnis, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga dunia global. Dan itu harus dimulai dari pikirannya.
Deklarasi itu muncul sebelum krisis meledak. Setelah krisis datang mengentak, keinginan untuk kian menggali nilai-nilai dari Cina, apakah Konfusius atau Tao, terus menggelinding. Percakapan di kalangan wirausaha Cina, pemimpin korporasi, dan akademisi mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar mencari kompas moral yang bisa digunakan di tengah kegaduhan nilai kepemimpinan Barat yang ternyata keropos. Mereka mencari nilai kepemimpinan yang telah tercerabut dari akar budaya mereka. Baik karena pengaruh revolusi kebudayaan Mao Zedong maupun hasil interaksi dengan Barat.
Dalam konteks pencarian ini, memang banyak kalangan yang meragukan apakah nilai kepemimpinan Cina sanggup mengatasi persoalan di dunia bisnis global. Mereka ragu bukan lantaran Cina baru tahap menjadi aktor ekonomi global. Mereka ragu dengan menyoroti bahwa negeri itu terhitung tempat berbisnis dengan sistem yang dikeluhkan masih kurang transparan dan nepotisme. Apa bisa negeri ini menawarkan sesuatu sementara sistem mereka sendiri juga bermasalah? Apa yang bisa diharapkan sementara pemerintah mereka masih kerja keras memberangus korupsi?
Keraguan yang masuk akal. Namun, yang meyakini pun tidak sedikit. Asumsinya, terlepas dari Pemerintah Cina sendiri menghadapi persoalan, nilai Konfusianisme dan Taoisme dapat diadopsi secara universal. Di antara nilai Konfusianisme yang kini relevan adalah unselfishness, careful thinking dan careful acting.
Terlepas dari pro dan kontra pencarian terhadap nilai kepemimpinan Cina, pesan yang sesungguhnya ditangkap dari gonjang-ganjing kepemimpinan global saat ini bahwa sesungguhnya nilai-nilai atau kebijakan lokal ada dalam setiap masyarakat, di mana pun di dunia ini. Terkait dengan Indonesia, kinilah saatnya kembali menggali nilai-nilai kepemimpinan yang sudah dimiliki, yang sesungguhnya sangat luhur bila diaplikasikan.
skip to main |
skip to sidebar

Catatan ringan dari Taman Tanah Abang III
Come on
Follow me @teguhspambudi
Calendare
Time is ...
Welcome
Salam. Blog ini dihadirkan di tengah Taman Tanah Abang III. Celoteh ringan di sela pekerjaan. Sebagian dimuat di SWA. Sebagian tercurah begitu saja.
About Me
From Zero to Growth

Categories
- Creative Economy (33)
- CSR (3)
- Diaspora (2)
- Digital Technology (11)
- Entrepreneur (26)
- Entrepreneurship (24)
- Family Business (7)
- Green Business (1)
- HR (4)
- Leadership (44)
- Life (12)
- Live (3)
- Macroeco (6)
- Management (21)
- Marketing (28)
- Social Entrepreneur (8)
- Social Media (4)
- Strategy (34)
- Sustainability Development (2)
- Technopreneur (12)
- Women Leadership (7)



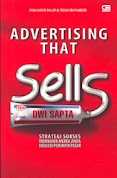
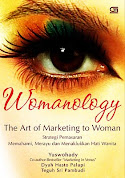












0 comments:
Post a Comment