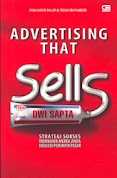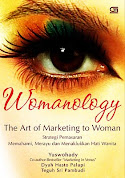Bila tak sanggup membangun, maka ambillah sainganmu. Itulah yang
dipraktikkan raksasa dari Tokyo terhadap saingannya di London.
MENANG BERBURU
Ini
bukan suasana kemenangan tim sepakbola Jepang atas Jerman. Namun, begitulah aura
yang meruar di Imperial Hotel Tokyo pada 24 Juli 2015 ketika para pemimpin
Nikkei Inc., perusahaan media terbesar Jepang duduk manis mengumbar senyum di
hadapan para jurnalis. Dengan gembiranya mereka mengumumkan berita penting: akuisisi
kelompok usaha surat kabar berpengaruh dari tanah Inggris Raya, Financial Times (FT) Group, pemilik
surat kabar ternama, Financial Times.
Lho, apa hubungannya dengan Jerman?
Secara
mengejutkan, Nikkei mengalahkan Axel Springer, konglomerat media dari Jerman,
pemilik sejumlah koran dan tabloid bergengsi: Bild, Die Welt dan Fakt.
Jauh sebelum Nikkei jadi pemenang, sejatinya Springer-lah yang bernegosiasi
dengan Pearson, pemilik FT Group. Selama setahun penuh, dari Berlin mereka membelah
udara, terbang ke London, duduk bernegosiasi mencari kesepakatan harga.
Awal
negosiasi, Springer datang dengan tawaran US$ 930 juta. Pearson menolak dengan
sopan. Lalu Springer menaikkan tawarannya menjadi US$ 1,16 miliar. Lagi, konglomerat
media serta pendidikan di Inggris itu kembali menggeleng. Dua pihak ini pun terus
bernegosiasi dengan alotnya.
Sebenarnya
tak hanya Springer yang memburu FT Group. Pemain top lainnya di industri media,
Bloomberg serta Thomson Reuters juga ikut perburuan. Tapi raksasa Jerman itulah
yang paling serius mendekati Pearson. Bak serigala yang begitu lapar hendak
memangsa korbannya, ia aktif merangsek.
Tak
perlu heran jika FT Group -- khususnya surat kabarnya -- menjadi incaran
media-media besar. Koran FT – yang sering disebut the salmon newspaper
(karena kertasnya berwarna kuning salmon) – memang ibarat bunga cantik nan
menawan, yang membuat gatal tangan untuk memetiknya. Terlebih di era berita
digital seperti saat ini yang membuat banyak media cetak kelimpungan tak tahu
arah yang dituju.
Diantara surat
kabar kelas dunia, FT memang terbilang sukses di ranah cetak dan online. Total
sirkulasi cetak serta digitalnya meningkat lebih dari 30% selama 5 tahun terakhir
menjadi 737 ribu pelanggan.
Dari total
peningkatan sirkulasi itu, area digital menjadi primadonanya. Pelanggan situs FT.com
tumbuh 21% di tahun 2014 menjadi hampir 504 ribu. Secara total, kanal digital
menyumbang 70% dari total pembaca berbayar FT. Prosentase
sumbangannya ini melejit dari posisi 24% pada 5 tahun lalu.
Menariknya,
dengan data seperti itu, kinerja keuangan FT Group pun ikut cantik. Tahun 2014 mereka
menyumbang penjualan senilai US$ 511 juta dan US$ 36,7 juta laba operasi ke
Pearson. Hebatnya, angka sebesar itu sebagian besar datang dari jalur penjualan
konten, bukan lagi iklan seperti yang masih terjadi pada media lain.
Inilah
yang membuat banyak pihak tergiur untuk menyunting sang primadona. Dan Springer
menjadi yang terdepan sampai kemudian disalip Nikkei pada 15 menit terakhir
sebelum tawaran resmi ditutup.
Ya,
akuisisi FT Group oleh Nikkei tak ubahnya sebuah drama sinetron. Bila di
lapangan hijau, mirip sebuah gol di injury time yang menjadi pemisah
antara pemenang dan pecundang. Kejadiannya; sementara negosiasi dengan Springer
mentok di jalan, Pearson menerima tawaran Nikkei di pintu yang berbeda. Dari
Tokyo, jajaran penting Nikkei menjejak London menawarkan proposal.
 |
| Financial Times, gadis cantik yang dipinang Nikkei |
Tak
perlu berlama-lama seperti saat menghadapi pewakilan Springer, setelah 5 minggu
bernegosiasi, Pearson dengan tangan terbuka menerima mahar dari raksasa Jepang
itu di angka US $1,3 miliar yang dibayar tunai. Yang menjadi drama adalah
kesepakatan “pernikahan” itu hanya terjadi 15 menit sebelum Springer datang kembali
dengan tawaran baru yang lebih tinggi dari angka sebelumnya.
Itulah
sebabnya para petinggi Nikkei bersorak. Mereka menyingkirkan pemain Jerman yang
sudah lebih lama merayu Pearson, yang akhirnya cuma melongo dan gigit jari.
Sungguh,
ini peristiwa hebat di dunia media. Lazimnya, media Barat diambil sesama pemain
dari Barat. Atau setidaknya media berbahasa Inggris. Bukan dari dunia belahan
Timur. Dalam sepuluh tahun terakhir, akuisisi media besar di belahan Barat
dilakukan sesama pemain dari Barat seperti tertera di tabel (Akuisisi Media Raksasa 10 Tahun Terakhir).
Uniknya,
bukan orang Jerman yang terluka dengan pembelian ini.
Dulu, Dame Marjorie
Scardino, mantan CEO Pearson selalu melemparkan kalimat yang keras pada ide
penjualan koran berwarna salmon itu. “Langkahi dulu mayatku,” kata wanita berkacamata
ini dengan berapi-api. Tekat semacam itulah yang melindungi FT dan kelompoknya dari
terkaman sejumlah pihak yang telah lama ingin mencaploknya.
Sementara di Tokyo petinggi Nikkei berpesta, di London ada
kemarahan yang meluap. Pengambilalihan FT Group kontan menambah gerundelan di tanah Inggris
Raya. Omelan yang benuansa nasionalisme. Maklum, jagoan mereka, satu persatu
jatuh dalam pelukan asing. Sebelumnya, Jaguar Land Rover (ke perusahaan India), Asda (AS), Aga (AS),
Boots (Italia), Rolls-Royce (Jerman), Weetabix (China), Cadbury (AS), Camelot
(Kanada), Raleigh (Belanda), Branston Pickle (Jepang), Newcastle Brown Ale
(Belanda dan Denmark), bahkan klub-klub sepakbola ternama seperti Manchester
United, Liverpool dan Arsenal pun jatuh ke pelukan orang AS, sementara
Manchester City milik lelaki-lelaki bersurban dari Uni Emirates, dan Chelsea
punya taipan Rusia.
Penjualan
FT Group sungguh menimbulkan pertanyaan tersendiri. Selama 60 tahun di bawah
naungan Pearson, kelompok media ini sejatinya telah menambah kekokohan bisnis sang
induk. Bahkan menjadi pilarnya. Lantas, mengapa dijual?
Zaman
memang telah berubah. John Fallon, CEO Pearson mengambil sikap berbeda
dibanding para pendahulunya, apalagi Scardino. Penjualan FT Group, katanya
adalah untuk membuat Pearson lebih fokus di pendidikan. Di era mobile serta
gemuruh media sosial seperti sekarang, rumah bernaung yang paling baik buat kelompok
FT, katanya, adalah perusahaan seperti Nikkei.
Pernyataan
ini sebenarnya agak ambigu, terutama dilihat dari sisi jurnalistik. Di kancah
global, koran FT dikenal sebagai media yang otoritatif, berintegritas dan
akurat. Sementara Nikkei dikenal sebagai koran yang konservatif, yang cenderung
lebih menjadi corong kepentingan Japan Inc. ketimbang publik sehingga memoles
berita korporasi Jepang dengan cantik. Kritikan keras kerap dilemparkan pada
surat kabar ini yang dituding ogah-ogahan membongkar praktik tidak sedap
kalangan dunia usaha Jepang. Diantaranya, skandal akuntasi Olympus di tahun
2011. Bukan Nikkei yang membongkar borok besar di tanah airnya itu, justru FT
lah yang mengungkap bau busuknya.
Alhasil,
sangat terang-benderang: alasan ekonomilah yang menjadi penyebab utama
dilepasnya FT Group. Ken Doctor, analis yang menulis berita bisnis di situsnya, Newsonomics.com,
mencatat bahwa Nikkei membayar 40 kali laba kelompok FT, setara dengan valuasi
yang dibayar Rupert Murdoch ketika membeli Dow Jones dan koran utamanya, The
Wall Street Journal. FT Group yang dijual ke Nikkei, di dalamnya termasuk surat kabar
edisi cetak (FT), FT.com, How to Spend It, FT Labs, FTChinese,
The Banker, Investors Chronicle, MandateWire, Money-Media, dan Medley
Global Advisors.
Dengan
uang belasan triliun rupiah itu, Pearson ditengarai akan punya bekal untuk
membenahi sejumlah bisnisnya di area pendidikan. Dan itu diakui John Fallon. “Pearson akan 100% fokus pada
pendidikan global,” katanya. Bisnis Pearson yang diantaranya menjalankan pusat uji GMAT dan
ujian lainnya secara global di samping punya sekolah serta penerbitan buku memang
tengah tertekan. Bisnis buku teksnya, umpamanya, terancam gelombang migrasi ke e-book
dan sumber online lainnya. Pendapatannya tahun lalu turun 4% menjadi US$
7,6 miliar.
Inilah
yang menjadi dasar Fallon untuk mengambil keputusan yang dulunya seakan hal
yang tabu. Yang pasti, ada yang mengatakan akuisisi ini adalah pernikahan dua
raksasa. Faktanya memang demikian. Keduanya punya kesamaan: surat kabar bisnis
dan keuangan. Keduanya juga pemain besar serta punya pengaruh di dunia pasar
modal dengan menerbitkan indeks pasar modal. FT bertanggung jawab untuk FTSE
atau yang biasa disebut indeks ‘Footsie’ untuk 100 saham utama di Inggris.
Sementara Nikkei punya Nikkei indeks 225 untuk perusahaan Jepang papan atas.
STRATEGI PENTING
Namun,
uang tunai US
$1,3 miliar yang dikucurkan Nikkei, dipandang lebih menguntungkan raksasa Jepang
itu. Kemenangan di detik-detik akhir ini bukan hanya mendatangkan tepuk tangan
buat Nikkei. Makna akuisisi lebih dari itu. Lebih dari sekadar pembelian sebuah
surat kabar. Ini adalah ejawantah sebuah strategi penting.
Nihon Keizai Shimbun, yang berarti surat kabar ekonomi
Jepang, yang kemudian disingkat menjadi Nikkei, keberadaannya jauh lebih senior
dibanding pemain dari Inggris itu. Nikkei berdiri tahun 1876 sementara koran FT
tahun 1888. Dari segi pendapatan, koran yang awal mulanya adalah tabloid internal
milik Mitsui & Company ini juga lebih besar. Tahun lalu meraup US$ 2,4
miliar dengan laba operasinya tiga kali lipat FT.
Namun, ada keadaan yang membuat Nikkei merasa harus “menikahi”
FT Group. Tidak lain dan tidak bukan adalah kemampuan pemain dari Inggris itu,
terutama untuk divisi surat kabarnya dalam berselancar di era digital seperti
disinggung di atas. Inilah kemampuan yang tidak dimiliki Nikkei.
Sementara
FT Group sudah lebih dulu mengarungi era digital dengan mendirikan FT.com
sebagai pelopor untuk layanan berita berbayar, Nikkei justru berjalan bak siput.
Layanan online-nya baru dimulainya tahun 2010. Di tahun 2013, mereka
lalu meluncurkan Nikkei Asian Review (asia.nikkei.com) yang berbahasa
Inggris. Ini menggantikan situs bahasa Inggris sebelumnya, nikkei.com
dan Asia Weekly. Nikkei.com kini berbahasa Jepang.
Alhasil, dalam konteks menghadapi perubahan besar akibat
gelombang berita digital, Nikkei bisa disebut kejatuhan durian. Telah lama jagoan dari Jepang itu ingin
melebarkan sayap online-nya, berseluncur di medan digital. Akuisisi ini jelas
akan memperkuat cengkeramaannya di era transformasi digital yang begitu dahsyat
seperti sekarang.
Ya,
akuisisi ini terjadi pada masa transformasi dan perubahan besar di industri
media cetak. Secara tradisional, berpuluh-puluh tahun sudah industri surat
kabar menyandarkan pendapatan dari cetak dan iklan. Datangnya era internet,
ponsel, serta tablet telah menciptakan suasana sulit bagi industri. Seiring
kian banyaknya orang mendapat berita dari sumber online, permintaan untuk edisi
cetak kian menurun. Konsekuensinya, pendapatan iklan cetak pun merosot. Di AS,
misalnya. Dalam 10 tahun terakhir, industri surat kabar Negeri Abang Sam telah
kehilangan pendapatan dari iklan cetak: melorot dari US$ 60 juta menjadi US$ 30
juta.
Di tengah disrupsi
besar seperti ini, FT
– terutama surat kabarnya –, justru telah menjadi simbol sukses. Mereka sendiri
sebenarnya mengakui beratnya efek digital bagi iklan cetak. “Iklan cetak terus
menurun,” begitu tertulis di laporan tahunan FT Group 2014. Namun, seperti
disebut di atas, konstribusi pelanggan digitalnya terus melejit. Pertanyaannya:
bagaimana mereka bisa melakukan itu?
Ini
adalah buah dari strategi yang jitu. Di tahun 2001, FT memperkenalkan model
langganan online. Pelanggan diminta untuk membayar konten yang bernilai.
Tahun 2007, FT sedikit melakukan perubahan pada model ini. Caranya: memberikan
kontrol kepada pelanggan. Model baru ini memungkinkan member mendapatkan
kuota dan bebas mengaturnya sendiri sehingga bisa mendapat konten gratis serta
mengunduh artikel yang diinginkan. Nanti, bila kuota habis, barulah disyaratkan
berlangganan. Cara ini sukses besar. FT pun menjadi pemimpin pasar dalam
mencari pendapatan online serta membesarkan jumlah pembaca dengan men-charge
konten.
Tahun
2007 juga menjadi saat monumental bagi FT. Mereka mengguncang praktik di
industri dengan menjual konten bersifat bulk kepada para aggregator,
yang kemudian menjualnya pada end user. Dengan pola ini, pelanggan
mengakses konten melalui aggregator yang terdaftar di FT.com. Hal ini
membuat manajemen FT bisa memahami perilaku pelanggan sehingga bisa melayaninya
lebih baik.
Langkah
ini akhirnya membuat koran FT mampu melakukan transformasi besar: bergerak dari
model pendapatan lewat langganan cetak dan iklan menjadi jalur konten online
berbayar. Ia mampu bertransformasi dari bisnis surat kabar cetak menjadi bisnis
media digital. Ia sukses sementara yang lainnya tengah bergelut.
“FT
adalah pemimpin dalam urusan mengelola pelanggan digital,” puji guru besar
manajemen Wharton, Emilie Feldman. FT, dia melanjutkan, telah menunjukkan
kesuksesan dalam mengonversi “pembaca” digital menjadi “pelanggan” ketika
mereka kehabisan kuota atau membaca artikel.
Kesuksesan
FT membesarkan basis pembaca digital yang berlangganan di tengah penurunan
pendapatan iklan, ungkap Ken Doctor, adalah hal menarik. Menurutnya, The New
York Times sekarang meraih lebih dari US$ 6 dari setiap US$ 10 yang dibayar
pembacanya. The New York Times sendiri, katanya meniru model FT yang
sudah lebih dulu melakukannya. “Ini sangatlah penting di dunia di mana
periklanan berubah dahsyat dan Google serta Facebook mendominasi,” tulis Doctor
yang juga menjadi kontributor Nieman Journalism Lab Harvard University.
Berbeda
dengan FT, selain lambat, Nikkei pun tertatih-tatih melakukan transformasi
digitalnya. Padahal, kemampuan ini sangat dibutuhkan
mengingat Jepang pun tak steril dari gelombang besar perubahan industri media. Maklum, di Negeri
Matahari Terbit, sirkulasi cetak juga terus melambat terkena hantaman media online.
Nikkei sendiri masih bergantung pada kertas dan tinta. Dari 2,7 juta pelanggannya,
hanya 430 ribu yang mengakses produk digitalnya. Bandingkan dengan FT
yang punya 504 ribu pembayar layanan digital dari 737 ribu pelanggan.
Selain
tertatih, Nikkei juga kurang sukses melakukan transformasi digital. Layanan online-nya di tahun 2010 berikut peluncuran asia.nikkei.com di tahun 2013 tak seperti
yang diharapkan. Tak bisa disebut gagal total, memang. Tapi sangat lelet.
Alhasil, bagi
perusahaan seperti Nikkei yang ingin melebarkan pasar global dan berselancar di
era digital, pilihannya cuma dua: build, terus membangun yang ada, yang
menjengkelkan karena lambat dan tak sukses, atau buy, membeli yang sudah
mapan dan terbukti sukses. Akhirnya Nikkei pun memilih jalan yang kedua.
“Nikkei memang sudah lama ingin go-global. Tapi
mereka tak pernah berhasil. Padahal, jika Anda ingin menjadi pemain global,
maka Anda harus punya jangkauan global. Pilihannya, pada akhirnya membeli
sesuatu yang sudah mengglobal,” ujar Yoshikazu Mikami, guru besar kajian media Mejiro
University di Tokyo memuji langkah Nikkei.
Manajemen Nikkei sendiri mengakui langkah akuisisi ini
benar-benar bagian penting dari strategi transformasi digitalnya. Pertumbuhan kami,
ujar Chairman Nikei, Tsuneo Kita, terletak pada dua sumbu: digital dan
global. Itulah sebabnya mereka bersorak setelah mengambil FT. Sebab, dengan mencaplok FT Group, bukan
hanya berarti Nikkei telah memiliki senjata yang tangguh untuk bermain global,
melainkan juga papan seluncur yang kuat untuk menunggangi gelombang perubahan
digital dunia surat kabar dan penerbitan.
Mari
kita lihat lebih dekat, dari sumbu global, Nikkei punya tambahan amunisi baru: dengan
sebarannya yang masif, FT berkekuatan sekurangnya 500 wartawan di lebih dari 50 lokasi di
dunia. “Nikkei
jelas-jelas membeli pertumbuhan di luar, sementara di dalam negerinya pasar
terus menciut,” ujar Feldman. Di sisi lain, Nikkei juga bisa menolong FT
menggenjot pendapatannya di Asia, wilayah yang tumbuh pesat, yang terus diintai
media global. “Dengan akuisisi ini, bisa menolong pertumbuhan FT,” kupas Doctor.
Lalu,
dari sumbu digital, pembelian
Nikkei atas FT adalah membeli pengaruh sekaligus langkah strategis untuk
memenangkan era digital. Nikkei bisa belajar dari
FT bagaimana melakukan transformasi digital sehingga mampu mencetak uang lebih
banyak dari sistem pelanggan berbayar ketimbang iklan.
Naotoshi
Okada, President Okada mengakui pihaknya akan belajar banyak dari kekuatan FT
di berita digital, termasuk dalam hal customer management system. Pelanggan
digital Nikkei dan FT sendiri akan menjadi 934 ribu. Berada di belakang 1 juta pelanggan
digital New York Times.
Keuntungan
ini adalah competitive advantage yang pantas membuat Nikkei bersuka
cita. Namun lebih dari itu, dengan mengambil FT Group yang sukses di ranah
digital, Nikkei sejatinya tengah memeluk masa depan. Mengapa?
Kesepakatan
ini memberi pijakan di tengah kian menggembungnya generasi millennial.
“Fenomena
besar di berita digital adalah fokus pada millennial,” ujar Doctor. “Generasi
millennial lebih besar ketimbang baby boom. Anda mengombinasikannya
dengan bisnis berita dan Anda punya jutaan orang muda. Ini adalah target utama
perusahaan berita,” kata pengarang Newsonomics:
Twelve New Trends That Will Shape the News You Get itu.
Tentu
saja ini peluang yang begitu besar yang dimiliki Nikkei. Namun apakah mereka mampu
memanfaatkannya, semuanya akan bergantung pada seberapa sanggup mereka
menyinergikan aset-aset yang ada. Yang pasti, Nikkei telah memiliki kendaraan
untuk berselancar di medan digital yang begitu dahsyat. ***
Akuisisi Media Raksasa 10 Tahun Terakhir
|
Tahun
|
Perusahaan Media
|
Pembeli
|
Harga Jual
|
|
2007
|
Dow Jones & Company (AS), penerbit The Wall Street
Journal
|
Media group News Corp
|
US$ 5 miliar
|
|
2007
|
Tribune Company (AS), penerbit Los Angeles Times
|
Sam Zell
|
US$ 8,2 miliar
|
|
2008
|
Reuters Group (Inggris)
|
Thomson Corporation
|
US$ 17 miliar
|
|
2010
|
Le Monde (Perancis)
|
Matthieu
Pigasse, Pierre Bergé, dan Xavier Niel
|
US$ 125,4 juta
|
|
2011
|
Huffington Post (AS)
|
AOL
|
US$ 315 juta
|
|
2013
|
Boston Globe (AS)
|
John W. Henry, pemilik Boston Red Sox
|
US$ 70 juta
|
|
2013
|
Washington Post (AS)
|
Jeff Bezos, pendiri Amazon
|
US$ 250 juta
|
|
2015
|
Financial Times (Inggris)
|
Nikkei
|
US$ 1,3 miliar
|
iNSIGHT
----------------------------------------------------------------------------------------------
Strategi Digital
Nikkei
Menyadari
disrupsi digital terus mengancam industri media dan penerbitan, Nikkei mencoba
melakukan transformasi digital. Langkahnya:
v
Tahun 2010: meluncurkan layanan online, nikkei.com,
berbahasa Inggris
v
Tahun 2013: meluncurkan Nikkei
Asian Review lewat laman asia.nikkei.com. Berbahasa Inggris, situs ini menggantikan nikkei.com
Selain
terlambat, langkah ini pun tertatih-tatih. Nikkei masih bergantung pada kertas dan tinta.
Kinerjanya pun tak memuaskan:
v
Dari 2,7 juta pelanggannya, hanya 430 ribu yang
mengakses produk digitalnya.
Karena
membangun (build) sendiri kurang sukses, maka membeli (buy)
adalah jalan paling rasional untuk cepat bertransformasi. Akhirnya, langkah
terakhir diayunkan:
v
Tahun 2015: membeli Financial Times Group yang
sukses di ranah digital
Harapan
lewat strategi ini, merengkuh dua sumbu pertumbuhan sekaligus:
v
Sumbu global: jangkauan Nikkei akan semakin
mengglobal, bersinergi dengan FT
v
Sumbu digital: Nikkei akan belajar
mentransformasi diri, mengoversi pembaca menjadi pelanggan digital, menggeber
pendapatan konten online, dan meraih pembaca generasi millennial