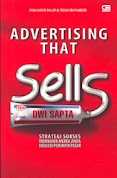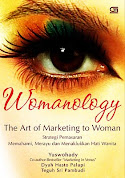Sudah
beberapa pekan ini ada hal yang menarik perhatian saya. Awalnya adalah berita di
pertengahan Mei 2012 bahwa jumlah wirausahawan di Indonesia melonjak tajam dari
0,24% menjadi 1,56% dari jumlah penduduk. Kemenkop bahkan optimistis tahun 2014
pertumbuhan wirausaha ke titik ideal (minimal 2%) dapat tercapai. BPS merilis
jumlah penduduk kita 237,6 juta (2011).
Berita ini menarik. Karena itu berarti,
dengan mengambil pendapat David
McClelland, terbuka sudah jalan kemakmuran. Sudah lama sosiolog itu
mengeluarkan pendapat yang ditupkan di banyak tempat: suatu negara bisa menjadi
makmur bila jumlah entrepreneur
sedikitnya mencapai 2% dari jumlah penduduknya. Asumsinya sederhana: putaran kapital
yang digulirkan satu orang akan berefek ganda untuk mengerek taraf kehidupan
orang sekitarnya. Satu pengusaha menghidupi banyak orang. Semakin banyak
pengusaha, semakin banyak orang yang terkena imbasnya.
Tapi
bukan hanya pendapat McLelland yang menarik. Saat mengedit tulisan seorang
redaktur SWA (Sdr. Sudarmadi) tentang
menjamurnya sekolah entrepreneur di
Indonesia, saya membaca keterangan-keterangan yang menggelitik. Apa saja?
Pertama: sejumlah pelaku bisnis menangkap peluang orang yang ingin berwirausaha dengan mendirikan sekolah entrepreneur. Diantaranya: Purdie Chandra (Grup Primagama) mendirikan
Entrepreneur University; Ciputra
mendirikan Universitas Ciputra Entrepreneur Center (UCEC); A. Khoerussalim dengan Entrepreneur College; Wuryanano membuka Swastika Prima Entrepreneur
College; Jaya
Setiabudi menggelar Young Entrepreneur Academy (YEA); LP3I dengan Rumah Entrepreneur; juga Rhenald Kasali yang mengibarkan Rhenald Kasali School for
Entrepreneurs (RKSE) bekerjasama dengan Cak Eko (pemilik Bakso Malang) dan Sunaryo Suhardi. Meski
berbeda nama, intinya mereka semua menawarkan program pelatihan kewirausahaan,
dengan metodenya masing-masing. Malahan kalangan perguruan tinggi umum pun juga
memperkuat kurikulumnya dengan mata kuliah entrepreneruship
seperti di Prasetiya
Mulya serta Universitas Bakrie. Di Prasetiya Mulya, kurikulum kewirausahaan diberikan selama 8
semestrer, dan mata kuliah itu disebut sebagai anchor subject.
Sekolah-sekolah itu cukup laris. Di RKSE misalnya, berdiri 2009, kini sudah mencetak 1000 alumni.
Swastika menerima sekitar 400 murid pertahun. YEA sekitar 220 murid sejak berdiri tahun 2007. Adapun UCEC melahirkan 8.500 alumni sejak 2007.
Fakta ini
menarik, dikaitkan dengan keterangan kedua.
Menurut salah seorang pengurus sekolah itu, pihaknya mengembangkan kewirausahaan karena Indonesia butuh generasi “pendobrak”
yang mampu mengolah sumberdaya menjadi sesuatu yang bernilai dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. "Mereka adalah para entrepreneur yang kami definisikan sebagai educated entrepreneur untuk membedakan dengan street
entrepreneur," katanya.
Educated entrepreneur. Bukan street entrepreneur.
Ini adalah jalan untuk mengejar titik 2%.
Ini istilah
yang menarik, sekaligus menunjukkan keyakinan bahwa mereka punya jawaban untuk
pertanyaan yang sering muncul: apakah entrepreneur
itu terlahir (born) atau diciptakan (made)?
Sekolah wirausaha
beserta kurikulumnya adalah jawaban bahwa entrepreneur bukan dilahiran, tapi
dibentuk. Di kampus, anak-anak muda itu, mahasiswa itu, dibekali soft
skills dan hard skills yang diasumsikan mendukung entrepreneurship.
Di titik
ini, saya pun teringat Josh Lerner.
Model Pengembangan Entrepreneur
Bicara
tentang mencetak entrepreneur,
Amerika Serikat adalah ”biangnya”. Negeri Abang Sam ini adalah apa yang disebut
sebagai ”beacon of entrepreneurialism”.
Antara 1996 hingga 2004, di negeri ini tercipta rata-rata 550.000 bisnis kecil
setiap bulannya. Banyak dari bisnis itu kemudian bergerak membesar, dan banyak
juga yang tumbang. Di
tengah dinamika yang ada, di AS, perusahaan start-ups
telah berjasa untuk hampir semua penciptaan lapangan kerja.
Menyadari pentingnya startup dan entrepreneur dalam skala kecil sekalipun dalam mendorong
perekonomian, maka pemerintah di banyak negara, berupaya memainkan peran
penting dalam memicu entrepreneurship.
Banyak dari apa yang disebut great
entrepreneurial hubs di dunia, sejak dari Bangalore hingga Guangdong,
merupakan buah tangan intervensi pemerintah. Di AS, misalnya, selain
menyediakan infrastruktur yang vital, termasuk lewat pendidikan, pemerintah
juga berperan mendorong entrepreneurship
itu sendiri. Silicon Valley tercipta ketika Pentagon menginginkan sejumlah
produk, yang akhirnya malah memicu kelahiran para entrepreneur teknologi di lembah itu.
Namun, mereplikasi kesuksesan AS di
lebah Silikon tidaklah mudah. Jalan menciptakan kewirausahaan dengan bantuan
pemerintah, tidak selamanya berakhir dengan cerita indah. Di jiran kita,
Malaysia, upaya massif kompleks Bio Valley, yang dibuka pemerintah Malaysia
pada tahun 2005 dengan nilai US$ 150 juta, kini diolok-olok sebagai “Valley of the Bio Ghost” karena gagal
total. Di Dubai, entrepreneurial hub
juga telah gagal. Adapun pemerintah Australia tidak lagi menunjukkan minat ambisiusnya
untuk program BITS (Building on
Information Technology Strength) lantaran tidak berhasil.
Josh Lerner dengan jitu mengamati
fenomena ini. Dalam bukunya, Boulevard of
Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital
Have Failed—and What to Do About it (2009), guru besar Harvard Business
School itu mencatat beberapa common
failures dalam mendorong entrepreneurship.
Salah satunya, katanya, banyak negara dikuasai ambisi tanpa melihat comparative advantages yang ada di
negara tersebut. Sekalipun Malaysia hanya punya sedikit ahli biologi, para
politisinya memutuskan untuk membangun BioValley di atas kegagalan
Entertainment Village, upaya lain menciptakan Malaysian Hollywood. Terlalu
banyak politisi, ungkap Lerner yang memperlakukan entrepreneurship sebagai “gravy
train”, tanpa kerja keras tapi berharap uang mudah didapatkan.
Kebanyakan
kekeliruan yang dibuat para politisi terkait mendorong entrepreneurship adalah mengasumsikan hanya ada satu model klaster
kewirausahaan yang sukses. Faktanya, Silicon Valey tak akan pernah sukses tanpa
dua universitas kelas dunia, Stanford dan Berkeley, serta pusat keuangan kelas
dunia, San Fransisco. Itu sering dilupakan.
Dalam contoh klasik kesuksesan model
Silicon Valley, Global Entrepreneurship Monitor (GEM), joint venture antara London Business School dan Babson College
mengidentifikasi tiga ekologi wirausahawan sukses. Pertama, adalah anchor-firm model. Alfred Marshall,
salah seorang ahli ekonomi yang pertama-tama menulis tentang entrepreneurship menyatakan bahwa entrepreneur sukses adalah seperti pohon
di sebuah hutan, menjulang dibanding tetangga-tetangganya, dan mengambil cahaya
dan udara. Kemudian, pohon-pohon besar itu menghasilkan pohon-pohon lain.
Mereka men-spin-off anak usaha,
memberikan pengalaman pada karyawan yang memutuskan ingin berjalan sendiri, dan
mengasuh lusinan pemasok.
Segitiga riset di North Carolina
merupakan eksponen sukses dari model anchor-firm.
Di sini terlibat IBM, Alcatel, dan Union Carbide yang kemudian menarik banyak
operator kecil. Hindustan Unilever, adalah contoh lainnya. Raksasa consumer goods di India ini
memperkerjakan 45 ribu wanita di seluruh India, dan memasarkan produknya ke 150
juta konsumen di area pedesaan. Para saleswomen
ini tak semata mencari uang, mereka juga belajar tentang produk, harga, dan
pemasaran, mengirim gelombang kewirausahaan di daerah-daerah pedesaan India.
Model kedua, driven by crisis. Orang menjadi entrepreneur
ketika ekonomi berhenti memasok pekerjaan. Ini terjadi di wilayah San Diego di
tahun 1990-an ketika Perang Dingin berakhir membuat ratusan ilmuwan militer
tidak memiliki pekerjaan. Perusahaan start-up
setempat seperti Qualcomm membetot mereka dan memperkerjakannya.
Model ketiga adalah the local-hero model, yakni seorang entrepreneur setempat melihat peluang, memulai bisnis, dan
mengubahnya menjadi perusahaan raksasa. Ketika Earl Bakken mendirikan Medtronic
di Minneapolis pada 1949, dia menciptakan industri lokal menjadi sebuah
perusahaan. Setelah mengembangkan alat pacu jantung yang pertama, Medtronic
tumbuh menjadi perusahaan medical-technology
terbesar di dunia, melahirkan sejumlah perusahaan lain.
Tak ada model yang paling hebat karena
masing-masing memiliki causa, atau
penyebabnya sendiri. Terpenting adalah melihat efek yang dihasilkannya. Semakin
banyak entrepreneur dilahirkan,
tentunya akan semakin baik. Semakin banyak “virus” yang terinkubasi, maka
pertumbuhan ekonomi akan semakin hangat, dan karenanya bergulir semakin
kencang.
Sekarang, kembali ke Indonesia. Apa model
yang kita miliki untuk pengembangan entrepreneur?
Sudah adakah jalan yang akan ditempuh?
Mentor Mindset dan Mental
Saya mendukung
pernyataan bahwa sekolah memberikan topangan pengetahuan untuk menjadi pebisnis.
Sebab, di sekolah-sekolah entrepreneur itu biasanya memang diajarkan beberapa materi
terkait kewirausahaan seperti pembuatan rencana bisis, cara menarik investor, mengontrol usaha, pengaturan cash flow dan fund raising. Sekolah-sekolah itu juga menyaratkan tugas akhir berupa pembuatan proyek bisnis.
Namun, poin
dari Lerner adalah bahwa menjadi wirausahawan itu berarti berada dalam sebuah
ekosistem tersendiri. Rasanya kita belum punya model pengembangan yang baik
secara nasional, yang di dalamnya tergambar ekosistem yang jelas. Beruntung, masih
ada perusahaan yang mau bertindak sebagai anchor-firm atau the local-hero dalam kapasitasnya
masing-masing. Contoh anchor-firm
adalah yayasan-yayasan korporasi yang membina mitra usaha kecil untuk menjadi
bagian dari komponen supply-chain
dalam proses produksinya. Akan tetapi, jumlahnya belumlah banyak. Kebanyakan model
yang ada adalah para entrepreneur
tumbuh dengan kaki dan tangannya sendiri. Seruduk sana, tubruk sini.
Tentu tak ada
yang salah bila ingin tumbuh seperti itu, dengan kaki dan tangannya sendiri. Dengan
catatan: itu bisa membuat mereka tangguh. Persoalannya, pada banyak kasus, apa
yang dibutuhkan entrepreneur adalah
mentor-mentor. Bukan hanya dalam urusan intelektual, tentang menjalankan bisnis,
atau bantuan kepada akses permodal, tapi juga mindset dan mental.
2M (mindset dan mental) ini bukan
perkara enteng. Banyak pebisnis yang tumbuh besar tak bisa dilepaskan dari mindset dan mental pengelolanya yang
merujuk Carol Dweck disebut sebagai “Growth Mindset”. Dalam bukunya yang
fenomenal
dan laris manis, “Mindset : The
New Psychology of Success” (2006), psikolog sosial dari Standford
University
ini mengintroduksi
konsep “growth
mindset” dan “fixed mindset”. Apa beda
keduanya?
Orang-orang yang memiliki “fixed mindset” adalah mereka
yang semata-mata mengandalkan talenta yang dimilikinya dan sangat berfokus kepada “hasil” (result). “Hasil” akan menjadi ukuran
pencapaian mereka. Oang-orang
seperti ini juga berkarakter menolak tantangan-tantangan baru dan menganggap bahwa
kerja keras adalah sia-sia. Mereka pun tak suka dengan kritik. Selalu merasa
hebat dan paling benar.
Adapun mereka yang memiliki “growth mindset” adalah
orang-orang yang tidak membatasi dirinya pada talenta miliknya. Mereka lebih mengandalkan keberanian bertindak dan upaya untuk terus tumbuh. Orang-orang seperti ini lebih peduli pada
usaha yang mereka lakukan beserta proses pencapaiannya, ketimbang
hasil akhir semata. Bagi orang tipe ini, hasil (result)
tetaplah penting, tapi hanya indikator semata, bukan target yang hendak mati-matian diburu. Tak heran, mereka selalu menyenangi
tantangan-tantangan baru.
Sekolah-sekolah bisnis, buat saya adalah
mentor intelektual. Tapi bisnis bukan sekedar itu.
Bicara tentang kewirausahaan, atau lebih
spesifik menyoal “educated entrepreneur”
dan “street entrepreneur”, sekitar 2
tahun lalu, Saras Sarasvathy, Associate
Professor dari Darden School of Business, University of Virginia, AS
mengangkat topik yang disebut sebagai “entrepreneurial
method”. Ini adalah semacam jalan menjadi seorang pebisnis.
Sarasvathy mengambil perumpamaan orang
yang memasak. Cara yang pertama adalah ingin memasak sesuatu dan kemudian
mencari resep tentang masakan tersebut, lalu mencari bahan-bahannya. Cara yang
lain adalah langsung pergi ke dapur, membuka kulkas, lalu memasak berdasarkan
bahan-bahan yang ada. Mana yang lebih baik?
Pada akhirnya, semua akan bergantung
pada bagaimana cara kita memasak, pada cara meramu bahan, yang tentunya semua itu
diperoleh berdasarkan latihan dan pengalaman, yang itu juga tak akan bisa
dilepaskan dari kedisiplinan. Dalam bahasa bisnis, meramu bahan serta bumbu
masak di dapur adalah organizing dan managing capital.
Ide besar yang diungkap di sini adalah bahwa
semua orang bisa belajar dan diajari untuk menjadi entrepreneur. Namun fakta menunjukkan setiap perusahaan raksasa,
pada mulanya berangkat dari perusahaan kecil, yang bahkan seringkali dimulai
oleh orang biasa, ordinary people. Bahkan
tak sedikit yang berangkat dari ibu rumah tangga. Mereka menjadi orang luar
biasa karena kemampuannya mengelola kapitalnya sehingga mampu tumbuh
berkembang. Dan kembali, hal ini banyak berpulang pada mindset dan mental, juga kedisiplinan.
Jadi, bagaimanapun,
kewirausahaan bukanlah semata silabus di atas kertas yang dipelajari di ruang
ber-AC nan sejuk. Selain otak encer, wirausaha juga butuh kekuatan 2M yang
seringkali tak tercakup dalam kurikulum.
Di sinilah kita
butuh semakin banyak anchor-firm atau the local-hero dengan mempertimbangkan comparative
advantages
yang ada di Indonesia (untuk urusan ini
mesti dicari apa keunggulan komparatifnya – bukan sekedar upah murah atau
komoditas alam). Jangan berharap pada model driven
by crisis
karena itu tak sustainable. Mengapa anchor-firm atau the local-hero yang dibutuhkan?
Perusahaan-perusahaan
baru (startup), terutama yang
inovatif, merupakan
mesin yang efisien untuk penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan jangka
panjang. Dengan cara menolong small
entrepreneurs tumbuh berkembang, menurut Bank Dunia, maka terdoronglah
pertumbuhan. Demikian pernah dinyatakan The
Economist, 29 Oktober 2009.
Jadi, partisipasi
aktif dunia bisnis dan para pengusaha yang sudah besar untuk terlibat dalam proses
pemagangan serta pematangan calon-calon wirausaha adalah syarat besar untuk
mengejar angka 2%. Bila tidak, hal itu akan sulit dicapai. Tapi, wirausahawan
juga tak boleh cengeng. Tak boleh terlalu berharap cepat membesar dengan sekali
mendayung.
Sekian dulu
catatan tentang entrepreneurship ini.
Bila
ada kesempatan, saya akan menulis tentang bagaimana pengembangan entrepreneur di sebuah negara yang
seringkali sensitif dibicarakan: Israel. Sebab, suka ataupun tidak, negeri ini
adalah one of the best startup nation.
***