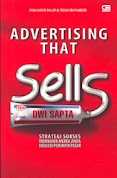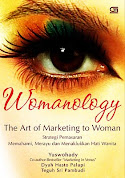Setelah
dihebohkan soal skripsi, tesis dan disertasi yang super singkat sehingga
terindikasi joki, bahkan plagiat, kita dihebohkan seorang Dwi Hartanto yang
sempat dijuluki the Next Habibie. Di balik rasa kasihan terhadap
orang ini, ada keheranan (juga terbersit kekaguman) bagaimana dia bisa
mengelabui begitu banyak orang top. Aje gile, kata orang Betawi.
Membaca berita-berita itu, dan khusus tentang DH, kontan saya
teringat liputan National Geographic,
Juni lalu dengan judul keren: Ada Dusta di Antara Kita. Biar lebih
singkat, berikut saya kutip isinya secara bebas:
Begini...
Tahun 1989, Princeton University menyambut angkatan baru, termasuk seorang pemuda bernama Alexi Indris-Santana. Kisah hidupnya dinilai sangat memikat oleh komite penerimaan mahasiswa baru sehingga dia diterima setelah melamar ke kampus sebagai self-taught orphan. Bayangkan, dia hampir tak pernah mengenyam sekolah formal. Hampir seluruh masa remajanya dilewati dalam kesendirian. Hidup di alam bebas di Utah, menggembala ternak, pelihara kambing, dan membaca filsafat. Berlari di Gurun Mojave, dia berlatih jadi pelari jarak jauh. Pokoknya keren deh...
Tahun 1989, Princeton University menyambut angkatan baru, termasuk seorang pemuda bernama Alexi Indris-Santana. Kisah hidupnya dinilai sangat memikat oleh komite penerimaan mahasiswa baru sehingga dia diterima setelah melamar ke kampus sebagai self-taught orphan. Bayangkan, dia hampir tak pernah mengenyam sekolah formal. Hampir seluruh masa remajanya dilewati dalam kesendirian. Hidup di alam bebas di Utah, menggembala ternak, pelihara kambing, dan membaca filsafat. Berlari di Gurun Mojave, dia berlatih jadi pelari jarak jauh. Pokoknya keren deh...
Di kampus, Alexi segera jadi bintang. Atlet pelari yang secara
akademis juga berprestasi. Nilai A diraihnya, di hampir setiap mata kuliah.
Sikap pendiamnya serta latar belakangnya yang tak lazim memberi nilai tambah:
jadi kian misterius. Waktu teman sekamarnya bertanya tentang tempat tidurnya
yang rapi jali, dia menjawab tidur di lantai. Hmm... jawaban itu ditelan sang
kawan karena sepanjang hidupnya Alexi mengaku hidup di alam sehingga tidak suka
tempat tidur.
Waktu berlalu. Tapi sepandai-pandainya tupai meloncat, dia jatuh
juga. Kisah Alexi adalah isapan jempol belaka. 18 bulan setelah masuk kuliah,
seorang perempuan (Reene Pacheco) mengenalinya sebagai Jay Mitchell Huntsman,
kawannya di SMA Palo Alto, California, enam tahun sebelumnya. Tapi itu juga
bukan nama aslinya. Lho?
Ya, dia sebenarnya adalah James Hogue, lelaki kelahiran 22
Oktober 1959 yang pernah dipenjara di Utah karena memiliki peralatan serta
onderdil sepeda curian.
Amerika gempar. Bagaimana bisa seorang berusia 29 tahun, eks napi,
bisa menjadi pemuda 19 tahun dan masuk Princeton, kampus yang identik dengan
Einstein???
Alexi pun dicyduk (hehehe...istilah kekiniannya) dari Princeton.
 |
| Foto-foto James Hogue, aka Alexi Santana |
Tahun-tahun setelah itu, Alexi.. eh Hogue ditangkap beberapa
kali dengan dakwaan pencurian serta gonta-ganti identitas. Dia keluar masuk
penjara. Terakhir, Maret 2017, dia kembali didakwa karena pencurian.
Kisah hidupnya pernah ditulis dengan ciamik oleh New Yorker dengan judul The Runner (tahun 2001) --- bisa akses
di sini tautannya: https://www.newyorker.com/magazine/2001/09/03/the-runner.
Juga pernah didokumentasikan dalam film Con
Man oleh Jesse Moss (tahun 2003) dengan sebutan penuh kekaguman: brilliant impostor. Impostor adalah
istilah tentang orang yang berpura-pura menjadi orang lain.
 |
| Film Con Man, dokumentasi James Hogue |
Plagiat, joki, atau apapun bentuk kebohongan di kampus, selalu
menjadi sorotan besar di manapun. Mengapa? Karena dunia kampus adalah dunia
keilmuan yang dianggap, atau seharusnya, jauh dari penipuan. Dunia orang-orang
jujur. Itulah alam bawah sadar kita. Berbeda dengan wilayah, maaf politik dan
bisnis.
Orang-orang yang berkecimpung di dunia politik atau bisnis, suka
ataupun tidak, dianggap dekat dengan hal itu. Di politik bahkan ada anekdot
yang terkenal tentang seorang politisi yang menjanjikan sungai bersih di sebuah
desa, tapi begitu diberi tahu bahwa tak ada sungai di desa itu, dia bilang,
“saya buatkan sungainya”. Atau adagium: politik itu “pagi tempe, sore tahu”. Sementara di bisnis, saking jengkelnya,
seorang menteri ekonomi Orde Baru pernah bilang, “Semua pedagang itu tukang
bohong.” Pokoknya, tak ada nilai-nilai spiritualisme di politik dan bisnis
sehingga kita menganggap wajar bila mereka berbohong.
Bicara soal kebohongan, National
Geographic menulis alasan orang melakukan itu: menutupi kesalahan atau kelakuan buruk adalah alasan terbesar.
Lalu, diikuti “demi keuntungan ekonomi”,
“manfaat selain uang”, “menghindari orang lain”, dan “pencitraan”. Ada alasan-alasan lain,
tapi itulah lima peringkat teratas alasan manusia berbohong.
Sadisnya, karena kebohongan ada di mana-mana, maka ditulis
begini: “Ketidakjujuran adalah bagian
dari diri kita. Jadi tidak keliru jika dikatakan berbohong itu manusiawi.”
Lalu, “Manusia, secara umum memiliki
bakat untuk saling menipu. Ini diduga muncul setelah adanya bahasa.” Karena
dengan bahasa, manusia bisa memanipulasi orang lain tanpa menggunakan fisik untuk
berebut sumber daya.
Hehehehe... Awalnya baca ini agak bikin mengernyit. Tapi
sepertinya memang begitu. Tak heran, kita selalu senang kalau ada film,
tulisan, novel, atau buku berjudul “Pengakuan”... Karena alam bawah sadar kita,
juga relung hati memang mengakui, bahwa kita pun sering berdusta atas alasan
apapun. Iya, khan? Dan Juli lalu muncul buku Everybody Lies tulisan Seth Stephens-Davidowitz yang mengukuhkan
itu. Dia menunjukkan bagaimana kebohongan menjadi bagian kehidupan, dan makin
menjadi-jadi di era internet.
Kembali ke awal tulisan. Membaca berita tentang Bung DH, sedih
juga melihatnya. Tapi saya angkat topi padanya karena dia berani mengakui semua
kebohongannya dan meminta maaf. Berbeda dengan para politisi korup yang pandai
berkelit, yang ... ah... sudahlah, kita tahu semua, yang ujungnya selalu bilang
begini setelah vonis hakim jatuh: “Saya khilaf”. Jarang sekali ada yang meminta
maaf. ***