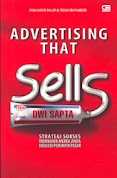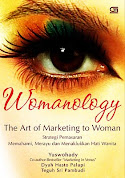Sejumlah negara telah menciptakan
perubahan ekonomi lewat kerjasama dengan kalangan diasporanya. Inisiatif
pemerintah dan kompetensi menjadi kata kunci.
Akhir Maret lalu, pemerintahan di
sub-Sahara Afrika, yakni Ethiopia, Ghana dan Nigeria melakukan terobosan.
Mereka menerbitkan apa yang disebut obligasi diaspora buat warga negara mereka
yang tinggal di mancanegara. Ethiopia, Ghana dan Nigeria memang tergolong
negara-negara yang banyak warganya -- atau setidaknya yang punya pertalian
darah -- telah menetap di sejumlah negara maju. Ketiganya berharap warganya
tersebut akan memborong obligasi. Dalam taksiran Bank Dunia dan
Bank Pembangunan Afrika, obligasi
diaspora ini bisa menyedot dana hingga US$ 1 miliar setahunnya. Keyakinan ini didasarkan pada arus uang
remittance (kiriman) ke Afrika yang tumbuh hampir 4 kali lipat antara 1990-2010 mencapai
US$ 40 miliar di tahun 2011 mengacu data
Bank Dunia dan ADB.
Melihat
potensi yang besar, Mthuli Ncube, Chief Economist ADB bahkan berani
menyarankan satu terobosan pemikiran: dalam rangka meningkatkan akses ke pasar
modal internasional, bank-bank di Afrika bisa menerbitkan obligasi yang dijamin
aliran kiriman uang para diaspora. Bear keyakinan mereka akan sukses.
Bagi
sejumlah negara Afrika, kini memang semakin menguat kesadaran untuk menggunakan
diaspora seperti apa yang dikatakan Steffen Roth yakni sebagai nation’s
capital. Di New York, Boston dan beberapa kota besar di AS, sekarang sudah
menjadi kelaziman digelar acara pertemuan diaspora Afrika untuk membahas apa
yang bisa dikembangkan lebih jauh. Bahkan sudah muncul bebrapa majalah untuk
memfasilitasi orang-orang diaspora Afrika. Diantaranya: www.reconnectafrica.com dan www.diasporabusinessmagazine.com.
Menyimak apa yang dilakukan negara-negara Afrika, dalam
kerangka berpikir Yevgeny Kuznetsov dari World Bank Institute, kegiatan
menghimpun kiriman uang masih berada pada tahap dasar dampak yang diharapkan
dari diaspora. Secara keseluruhan, ada lima dampak diaspora: (1) remittance;
(2) donation; (3) investment; (4) knowledge and innovation
network; dan (5) institutional development and reform. Kiriman uang
dan donasi memang bisa disalurkan untuk dunia bisnis. Namun level 4 dan 5
merupakan tingkatan terbaik yang bisa dimaksimalkan oleh negara dari
diasporanya. Level ini adalah tahap dimana terjadi brain circulation,
sirkulasi pengetahuan dan kompetensi untuk memberikan dampak yang lebih besar
dan berkelanjutan bagi satu negara ketimbang kiriman uang belaka. Lengkapnya
lihat bagan Hierarchy of Diaspora Impact.
Taiwan adalah
salah satu contoh brain circulation
yang baik. Di tahun 1970-an, negara ini adalah daerah pinggiran dalam urusan entrepreneurship dan innovation di dunia. Mereka kemudian
menjadi salah satu pusat inovasi terkemuka di dunia. Rahasianya?
Kemampuan memaksimalkan jaringan diaspora, terutama
dalam urusan optimalisasi pengetahuan serta kompetensi. Sewaktu pemerintah Taiwan
memutuskan mendorong industri venture
capital (VC) di awal tahun 1980-an, mereka bukan
hanya tak memiliki kapabilitas, tapi juga cetak biru untuk melakukannya. Banyak
pihak menentang ide ini lantaran konsep venture capital terdengar asing
dalam praktik bisnis Taiwan di mana anggota keluarga mengontrol seluruh
aktivitas bisnis, khususnya keuangan. Melalui proses interaksi yang intens
antara Pemerintah dengan orang-orang diaspora Taiwan di Silicon Valley,
berdirilah sejumlah institusi seperti Seed Fund yang memberikan bantuan dana
bagi para entrepreneur yang ingin berbisnis di Taiwan.
Pemerintah Taiwan juga mengundang
kalangan diasporanya untuk merelokasi bisnisnya ke Taiwan. Buat mereka, Taiwan
mendirikan sejumlah teknopark agar bisnis berjalan bagus. Salah satunya, pada 15 Desember
1980 dibangunlah Hsinchu Science and Industrial Park yang berdampingan dengan
National Chiao Tung University dan National Tsing Hua University. Taiwan memang ingin membangun seperti Silicon Valley yang
berdampingan dengan Stanford.
Salah satu yang menikmati progam ini adalah
Miin Wu. Datang ke AS di awal 1970-an untuk mengejar gelar sarjana
teknik elektro, Wu akhirnya meraih gelar doktor dari Stanford University pada
tahun 1976. Selepas lulus, Wu melihat ilmu yang digunakannya belum bisa
diimplementasikan di Taiwan. Dia pun bertahan di negeri Abang Sam. Dia merintis
karir di sejumlah perusahaan Silicon Valley, termasuk Siliconix dan Intel. Dia
juga sempat mengecap pengalaman sebagai salah satu pendiri VLSI Technology.
Tahun 1980-an
ekonomi Taiwan berkembang. Wu memutuskan mudik. Tak berapa lama, pada 1989,
perusahaan semikonduktor pertama di Taiwan, Macronix Co. dikibarkannya di
Hsinchu Science and Industrial Park. Wu juga menjadi anggota aktif Silicon
Valley's Monte Jade Science and Technology Association yang membangun hubungan
bisnis antara komunitas teknis di Silicon Valley and Taiwan.
Berkembang
pesat, tahun 1995, Macronix mendaftar di bursa Taiwan, dan setahun kemudian
menjadi perusahaan pertama yang terdaftar di Nasdaq. Berkekuatan lebih dari 4000 karyawan, Macronix kini menjadi salah satu pabrikan dan pemasok integrated
circuits (IC) serta kartu memori terbesar untuk wilayah Asia, Eropa dan AS. Di Hsinchu inilah Wu membangun Macronix.
Kini ratusan perusahaan berdiri di sini, membetot anak-anak Taiwan yang menimba
ilmu di mancanegara.
Pemerhati diaspora, Prof. AnnaLee Saxenian menegaskan
bahwa untuk menciptakan perubahan ekonomi dan institusional yang diharapkan,
maka kalangan diaspora dengan kompetensinya harus berkolaborasi dengan para
pembuat keputusan. Dengan cara ini diharapkan akan ada perubahan yang
inkremental hingga transformasi yang besar.
Saxenian benar. Kunci kesuksesan Taiwan
dalam memaksimalkan diasporanya adalah kerjasama Pemerintah Taiwan dan jaringan
orang-orang diaspora yang kompeten, terutama di Silicon Valley. Para diaspora
menjalankan peran yang disebut Yevgeny Kuznetsov sebagai para “pengungkit ala Archimedes”. Mereka
menginisiasi perubahan, membawa keahlian secara teknis dan kompetensi dalam
urusan industri venture capital.
Belajar dari kesuksesan Taiwan, selain
inisiatif pemerintah, posisi para diaspora juga sangatlah penting. Itulah yang
kemudian ditiru para diaspora Chili. Para diaspora Chili membangun jaringan
yang mereka sebut ChileGlobal, sebuah jaringan internasional yang terdiri dari
para pemilik bisnis dan eksekutif papan atas (lebih dari 100 orang) yang punya
hubungan darah dengan Chili. Jaringan ini dibentuk untuk mereka yang ingin
berkontribusi bagi perekonomian dan pembangunan Chili. Pengelolaan ChileGlobal
dipegang oleh Fundación Imagen de Chile, organisasi nirlaba.
Tentang mereka, bisa diakses di www.chileglobal.net/ atau www.chileglobal.org/english-version/.
Otak di balik ChileGlobal
adalah Ramón L. García. Pada tahun 1997, Ramon yang
seorang wirausahawan di bidang genetika dan bioteknologi mengontak Fundación Chile, organisasi yang berkutat di bidang energi terbarukan.
Ramon yang juga PhD dari University of Iowa adalah CEO
InterLink Biotechnologies, perusahaan yang didirikannya di Princeton tahun 1991. Setelah berdiskusi, Fundación
dan Interlink mendirikan perusahaan baru yang bergerak
dalam bidang penelitian. Mereka mengelola proyek-proyek untuk mentransfer
teknologi ke Chili yang dipandang menjadi titik kunci buat meningkatkan daya
saing, khususnya di sektor agribisnis. Dengan kombinasi pengetahuan Ramon atas
Chile, pendidikan tingginya, pemahamannya atas praktik manajerial, dia sukses
mentransfer teknologi ke negeri tercintanya. Per Januari 2008,
Ramón telah menciptakan 3 perusahaan bioteknologi
bersama Fundación Chile.
Tahun 2005, terilhami oleh inisiatif Ramon, berdirilah
ChileGlobal. Lewat ChileGlobal dibuatlah aneka workshop untuk mendorong hubungan dan mentoring antara
perusahaan startups Chili dengan kalangan diaspora yang sudah sukses. Pihak
Pemerintah Chili turut terlibat dalam mendorong pertemuan ini.
Masih di
tahun yang sama, Pemerintah Meksiko juga tak mau kalah dalam memanfaatkan
diasporanya untuk turut membangun perekonomian. Tahun 2005, mereka mendirikan Mexican
Talent Network yang berupaya menghimpun orang-orang hebat di mancanegara. Mexican
Talent Network bertujuan mendorong kerjasama antara para profesional yang
tinggal di luar negeri untuk membantu proyek pembangunan Meksiko serta
mempropomosikan citra Meksiko di pentas global.
Di luar Taiwan, Chili dan Meksiko, yang cukup maju
dalam memaksimalkan para diaspora adalah Skotlandia lewat programnya GlobalScot.
GlobalScot adalah program yang super
serius yang digalang Pemerintah. Di sini berhimpun jejaring dari lebih 950
orang sukses Skotlandia di seluruh dunia yang saling mentransfer pengetahuan
serta kompetensi untuk mendirikan aneka proyek yang bermanfaat buat negaranya.
Untuk melakukan itu, mereka menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan
yang berdomisili di Skotlandia. Sejak berdiri tahun 2001, GlobalScot kian
berkembang, menghimpun diaspora Skotlandia yang sukses di beragam negara. Mereka
berhimpun di www.sdi.co.uk/globalscot.aspx/.
Peran diaspora memang sangat penting dalam membantu suatu
negara. Di India, PM Manmohan Singh yang lulusan Oxford dan Cambridge memainkan
peran dalam mereformasi perekonomian di awal 1990-an dengan cara menarik para
diaspora India. Fasilitas,
insentif, dan peluang kemitraan dibuka di India buat anak-anak terbaik yang
ingin membangun negerinya. Pemerintah juga mengembangkan
universitas-universitas si seluruh pelosok negeri sebagai
mitra untuk penelitian. Begitu juga dengan
balai latihan, terus dibuat agar kompetensi warga lokal bisa mengimbangi
rekan-rekannya yang baru pulang dari mancanegara atau tetap di luar negeri yang
membutuhkan tenaga-tenaga ahli di India. The
Economist menaksir ada 22 juta diaspora India yang
bila bisa dimaksimalkan akan sangat berpengaruh bagi negeri tersebut.
Menurut Kuznetsov, sesungguhnya diaspora adalah
sumber pertolongan sekaligus sumber daya yang sangat bermanfaat untuk membantu
pembangunan sebuah negara, tidak hanya dari sisi kiriman uang tapi transfer
teknologi dan kompetensi. Persoalannya tinggal bagaimana pemerintah negara
tersebut dan para diasporanya bersinergi positif seperti yang dipraktikkan
Taiwan, India, Chili, Meksiko dan Skotlandia.
Hampir semua negara kini berlomba berkolaborasi
dengan kalangan diasporanya. Bahkan Armenia telah membuat Armenia 2020 yang
berupaya menggerakkan kalangan diasporanya membangun negeri itu hingga tahun
2020. Spesifik dan terdesain. Indonesia tampaknya memang tak boleh tertinggal
gelombang besar ini. ***