Ritel
ini tumbuh melampaui pesaingnya dan menjadi jawara di industrinya. Rahasianya
ada pada struktur dan sistem di dalamnya, yang kemudian akan diadopsi banyak
perusahaan lain.
Ini
adalah sebutan untuk sistem kapitalisme yang menurut Clegg lebih bertanggung
jawab lewat sebuah model: perusahaan yang dikelola karyawannya (employee-owned businesses).
Tak
cukup dengan pernyataan, pada Juli 2012, Clegg bahkan mengapungkan proposal yang
tidak populer di mata kalangan pebisnis. Dia mengusulkan jika 10% saja karyawan
sebuah perusahaan ingin memiliki saham dalam perusahaan tempat mereka bekerja,
maka perusahaan harus merealisasikannya. Atau menolak dengan alasan yang
terperinci dan masuk akal. Peraturan ini rencananya berlaku untuk perusahaan
dengan karyawan lebih dari 250 orang.
Mengapa Clegg, atau Pemerintah Inggris
muncul dengan istilah itu?
Tak sulit menjawabnya. Di tengah resesi
ekonomi, Inggris menghadapi serangkaian skandal korporasi mulai dari perilaku
tak etis kerajaan bisnis Rupert Murdoch
hingga Barclays yang mengguncang dunia finansial. Barclays, kata Clegg,
“Mengingatkan kita bahwa ekonomi sungguh-sungguh membutuhkan suntikan tanggung
jawab, mengontrol kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, sebuah kekuataan
yang berada di lebih banyak tangan.” Lantas, mengapa solusinya “John Lewis
Economy”?
“John Lewis Economy” adalah istilah yang
merujuk pada sebuah jaringan dept store
di Inggris yang fenomenal. Dikatakan fenomenal karena John Lewis memang seperti
anomali. Jaringan berkekuatan 38 gerai di seantero Inggris ini bukan hanya mampu
mempertahankan penjualan yang meroket dalam 10 tahun terakhir, tapi juga tetap
kemilau di tengah resesi yang tengah melanda Eropa. Tahun lalu penjualannya
melonjak 6,4% mencapai US$ 13,48 miliar. Jauh mengungguli Marks & Spences
dan House of Fraser yang masing-masing hanya tumbuh 2% dan 1,5%.
Memang perusahaan ini bukan tak kebal
masalah. Tahun lalu labanya merosot 9%, di posisi US$ 607 juta. Tapi itu lebih karena
banyaknya investasi yang mereka sebar di sejumlah bisnis. Toh secara
keseluruhan kecemerlangan itu tak tertahankan: penjualan terus melesat. Mengapa
bisa demikian?
Inilah yang kemudian menjadi alasan
Clegg untuk melemparkan gagasannya ke pelaku bisnis. Di samping produknya yang
bersaing, senjata terbesar John Lewis adalah struktur yang tidak lazim pada
perusahaan modern: 100% sahamnya dimiliki 81 ribu karyawannya!
Tentu saja ini terdengar tak lazim.
Porsi kepemilikan di John Lewis ini otomatis lebih besar ketimbang perusahaan
publik.
Dirunut ke belakang, sistem ini
merupakan hasil proses yang panjang. Didirikan
oleh John Lewis di London pada tahun 1864, toko ini tumbuh cepat menjadi dept store yang sukses. Ketika pemikiran
komunisme tumbuh cepat di awal abad 20, John Spedan Lewis, anak sang pendiri,
mulai merasa takut masa depan toko milik ayahnya. Pasalnya, apa yang diperoleh
sang ayah, saudaranya dan dia sendiri jauh melebihi gaji karyawan. Pikirnya,
ini merupakan potensi masalah besar di kemudian hari.
Ketika
ayahnya meninggal pada 1928, Spedan mengambil alih pengendalian. Dia pun segera
membuat terobosan penting dalam operasional perusahaan: skema bagi hasil. Jadi
ketika perusahaan berkinerja baik, selain ada hasil laba, karyawan juga mengantungi
bonus ekstra. Dua dekade kemudian, pada tahun 1950, Spedan membuat terobosan
lanjutan: menyerahkan kepemilikan penuh pada karyawan.
Sistem
yang dibuat Spedan sangat khas. Karyawan John Lewis tidak memilik saham secara
individual. Mereka memiliki wadah, sebuah trust
yang mengelola saham karyawan. Setiap gerai memiliki forum karyawan yang
memilih perwakilan yang kemudian berujung pada 14 orang dewan kemitraan. Dewan
ini rapat rapat 4 kali dalam setahun. Dalam forum itu, ketua baru bisa dipilih
kapan saja. “Itulah the real power,”
kata Charlie Mayfield (47 tahun), yang mengetuai dewan kemitraan ini.
Sistem
yang membagi kekuasaan dan bonus ini ternyata membawa manfaat sangat banyak.
Sejumlah penelitian pun dilakukan untuk membedah ritel ini. Manfaat paling
terasa tentu saja sense of belongingness
yang kuat. Karena merasa ini adalah perusahaannya, karyawan memiliki passion yang besar untuk melayani
pelanggan. Apalagi, sistem bonus yang diberikan sangat transparan dan setara. Tahun
lalu, misalnya, prosentase bonus semua karyawan sama, 14% dari gaji tahunan,
atau sekitar gaji selama 7 minggu. Tak terkecuali Mayfield yang juga menjadi
Komisaris John Lewis. Tahun 2011 dia mengantungi US$ 179 ribu. Sebagai
perbandingan, Marc Bolland, CEO Marks & Spencer mendapat bonus US$1,03
juta.
Karena
sistem operasi yang fair, perasaan
tenang bekerja pun lahir sehingga karyawan fokus pada pekerjaan dan perkembangan
perusahaan. Bekerja di John Lewis, ungkap Elizabeth
Dunbar, lebih seperti keluarga daripada karyawan biasa. "Kami saling
melindungi satu sama lain, dan melindungi bisnis,” kata wanita yang berposisi
sebagai stock auditor ini.
Karyawan
John Lewis memang terbilang kompak. Mereka menolak tawaran untuk menjual
perusahaan ke pihak investor di tahun 1999 yang menjanjikan bayaran sekitar US$
150 ribu per karyawan. Karyawan tak mau ada pemilik baru karena khawatir mereka
akan mengubah budaya perusahaan. “Sejak itu, bisnis John Lewis tumbuh menjadi
lebih kuat,” ujar Poynor, seorang analis ritel.
Agar
bisa mempertahankan bonus tahunan yang gemuk, perusahaan pun membuat portfolio
bisnis, mengoperasikan 5 resor hotel, termasuk Brownsea Castle, puri dari abad
16 di sebelah selatan Inggris. Lalu, agar karyawan terpuaskan, mereka bisa
dapat berlibur dan menyalurkan hobi mulai dari ski, snowboarding, berlayar, naik kuda, juga memasak. Dan semuanya
diberi diskon.
Kebahagiaan
karyawan memang sangat diutamakan di John Lewis. Biaya untuk karyawan sungguh tak
kecil. Tahun lalu, manajemen John Lewis membelanjakan sekitar US$ 588 juta
untuk berbagai benefit. Jumlah ini
dua kali lipat lebih banyak ketimbang pesaing utamanya, Marks & Spencer
yang berkekuatan 82 ribu karyawan. Lalu, mengucurkan anggaran 25% lebih banyak dibanding pesaingnya dalam
pengembangan karyawan.
Merunut ke tradisi yang dikembangkan
Spedan, hal itu tidak mengejutkan. Nilai-nilai
yang diwariskan Spedan di perusahaannya memang sangat pro-karyawan:
“kebahagiaan untuk seluruh karyawan”. Begitu slogannya.
Tentu saja itu berbalas. Turnover karyawan, misalnya, sangat
rendah. Sementara turnover di
industri ritel mencapai 50%, di John Lewis hanya 20. "Itu jelas-jelas penghematan biaya,” ujar Joshua
Bamfield, Direktur Centre for Retail
Research Inggris. Manajemen John Lewis sendiri secara tradisi juga berupaya
meminimalisasi pengurangan karyawan, bahkan ketika situasi ekonomi sedang tidak
bagus. Pendek kata, "Model kepemilikan ini menciptakan kondisi yang tepat
untuk sukses,” ujar Mayfield, yang menjadi Komisaris John Lewis sejak 2007.
Ucapan
Mayfield mendapat konfirmasi yang sahih. John Lewis tumbuh 50% lebih cepat
ketimbang perekonomian Inggris. Pelanggannya pun loyal. Dari 80% penjualan John
Lewis, 20% datang dari pelanggannya yang setia.
Keberhasilan
John Lewis memancing sejumlah studi yang kemudian diteorikan. Salah satunya
adalah studi yang digelar Cass Business School di London. Dari hasil studi atas
John Lewis diyakini bahwa employee-owned
businesses jauh lebih unggul ketimbang perusahaan biasa, baik dalam masa
susah maupun senang. Employee-owned businesses
juga lebih menguntungkan, menciptakan pekerjaan lebih cepat ketimbang
perusahaan lain, juga lebih sedikit membutuhkan staf.
Dengan
keunggulan seperti itu, tak heran jika Pemerintah Inggris mendorong model
serupa diterapkan pada perusahaan lain. Pemerintah Inggris yakin perusahaan yang
dimiliki karyawan lebih dinamis dan punya moral yang lebih tinggi. Seharusnya,
kata Nick Clegg, perusahaan mengikuti model John Lewis yang mendistribusikan
laba pada karyawannya. Menurut Clegg, era kapitalisme kroni di mana
kesejahteraan dimonopoli sejumlah orang sehingga berpotensi korup seperti
Rupert Murdoch dan Barclays sudah berakhir.
Kampanye
Deputi PM itu diyakini akan menghadapi banyak tentangan, terutama dari para
pemilik perusahaan. Sejauh ini, hanya 3% perusahaan di Inggris yang sifatnya employee owned. Itu pun tidak 100%
seperti John Lewis yang memang terbilang ekstrim. Prosentase ini masih lebih
sedikit dibanding di AS yang 10%.
Kendati
begitu, sejumlah pihak di Inggris berkeyakinan kebijakan Clegg akan mendapat
pendukungnya, setidaknya di kalangan start-up
yang terus bermunculan. Bahkan, menurut Iain Hasdell, Ketua Employee Ownership
Association di London, ada harapan jumlah perusahaan yang menerapkan model John
Lewis ini akan bertambah, setidaknya sekitar 100 perusahaan. Bila ini
terealisasi, iklim bisnis di Negeri Ratu Elizabeth ini diyakini akan semakin
baik. ***




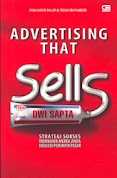
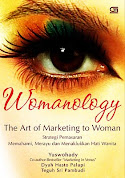













0 comments:
Post a Comment