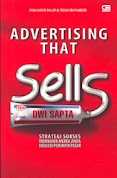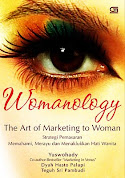Buaian sukses serta perubahan yang lambat diantisipasi
membuat kerugian serta ancaman kebangkrutan datang menyergap. Dua kali periode
transformasi pun harus dijalankan untuk membangun kembali kejayaan yang nyaris
hilang.
MIMPI BURUK
Tahun 2003 adalah mimpi buruk bagi Lego. Betapa tidak, akibat bisnis
yang hancur-hancuran, laci kas mengering. Laporan keuangan pun menampilkan
wajah horornya: rugi US$ 300 juta, dan diproyeksikan meningkat hingga US$ 400
juta di tahun 2004. Ujungnya, bayang-bayang maut menari di depan mata:
kebangkrutan!
Sungguh ini tak pernah terbayang. Satu dekade sebelumnya, upaya
transformasi telah diupayakan setelah stagnasi menghempas mereka. Dimulai tahun
1993, bisnis produsen mainan itu melesu. Penjualan merosot. Mainan menumpuk.
Sementara laju biaya produksi tak bisa dihentikan. Tapi saat itu kerugian tak
terbayangkan. Harapan masih ditebar karena tak ada ceritanya Lego merugi.
Sejarah
Lego memang seperti mayoritas produknya: tumpukan balok yang indah tersusun. Cerita perusahaan ini adalah kisah bisnis yang sukses tahun demi tahun,
terutama selepas Perang Dunia II.
Semuanya bermula sewaktu Ole
Kirk Christiansen
membuat mainan dari kayu di Billund, Denmark, semasa era depresi di tahun 1932. Dia beri nama Lego yang diambil dari bahasa Denmark,
“leg godt” yang terjemahan
bebasnya bisa diartikan “asyik
bermain”.
Selepas
Perang Dunia II, Christiansen membeli
mesin plastic injection molding
dan mencoba-coba apa yang bisa
diperbuatnya
dengan mesin itu. Tahun 1947, dia pun mulai mengembangkan balok-balok mainan
yang kemudian dikenal seperti sekarang, yang perlahan tapi pasti diserbu
anak-anak di seantero jagat.
Lepas dua dekade merintis bisnis, pertumbuhan pesat Lego terjadi di
tahun 1960-1970-an. Di masa itu, apapun produk yang dilempar, diserap pasar,
diserbu bocah-bocah ingusan yang antusias merakit mainan. Benar-benar laris
manis. Lego pun menjelma menjadi salah satu perusahaan raksasa yang disegani.
Namun laiknya roda kehidupan, putaran nasib Lego mulai bergerak ke
bawah. Stagnasi dimulai tahun 1993. Dari sisi pasar, anak-anak yang beranjak tumbuh
dewasa, kian meninggalkan Lego. Sementara anak-anak yang baru tumbuh,
mendapatkan alternatif dari produsen lain yang menggunakan paten Lego yang
telah kadaluwarsa untuk membuat mainan sejenis. Sementara dari sisi produksi,
di tengah para pesaing mengalihdayakan produktivitasnya ke Cina serta negara
lain yang berbiaya rendah, Lego masih berbasis di Denmark yang berongkos mahal.
Semua telah berubah. Dan celakanya, Lego terlambat melakukan perubahan!
KELIRU
Mengatasi keadaan, manajemen Lego berupaya melakukan transformasi. Perusahaan
mesti disegarkan. Dibuat menjadi lebih lincah. Wujudnya, aneka perubahan
dibuat. Serangkaian portofolio produk yang lebih luas dan beragam diluncurkan,
seperti Bionicle (robot peperangan) dan Lego Galidor, boneka yang bisa bicara.
Lalu, mengakuisisi perusahaan mainan di Kalifornia, membuat studio desain di
Italia, membuka banyak Legoland Amusement Parks (taman hiburan), meluncurkan
Lego Education Centre yang menawarkan aktivitas bermain setelah sekolah, juga
membuat Lego Factory, di mana orang bisa membangun Lego secara virtual 3D, juga
beraliansi pemasaran dengan Harry Potter dan Star Wars.
Upaya transformasi yang dilakukan manajemen Lego ini bisa dikatakan
cukup radikal. Mereka tak hanya mendisrupsi model bisnis dengan cara membangun
Lego virtual, tapi juga masuk ke strategi blue
ocean dengan membangun theme park,
area yang diyakini bisa meraih pasar baru. Semua itu dilakukan demi
membangkitkan kejayaan yang rebah lantaran terlambat melakukan perubahan.
Tahun demi tahun pergulatan ini dilakukan sampai seorang konsultan yang
dipekerjakan untuk membantu perusahaan menghadap direksi guna menunjukkan
salahnya jalan yang tengah ditempuh. Dia rupanya resah karena semua yang
digelar ternyata tak berjalan sesuai harapan. Sosok itu adalah Jørgen Vig
Knudstorp
Pada saat menghadap direksi, Knudstorp menyatakan bahwa setelah
menjalankan program transformasi, Lego sesungguhnya duduk di atas bara api. Memang
mereka punya banyak inovasi, karena inovasi menjadi prioritas strategis dalam
upaya transformasi mengingat pasar serta persaingan telah berubah drastis. Namun,
dari serangkaian inovasi yang merombak model dan produk bisnis, ternyata hanya
3 produk yang positif: yang beraliansi dengan Star Wars dan Harry Potter, serta
Bionicle. Tapi itu pun sangat lemah. Bahkan khusus yang terafiliasi dengan Star
Wars dan Harry Potter, produk-produk Lego hanya mencetak laba ketika filmnya
diputar. Bionicles memang lumayan. Permainan ini disukai. Anak-anak juga
meminta orang tuanya membelikan aneka aksesori bernuansa robot. Akan tetapi, secara
keseluruhan, Lego telah terbakar. Kerugian di tahun 2003 yang mencapai US$ 300
juta adalah kerugian pertama dalam sejarah kehidupan “Si Balok dari Denmark”
ini.
Oktober
2004. Untuk membenahi keadaan,
jajaran komisaris melakukan perombakan manajemen. Knudstorp, mantan
konsultan McKinsey diangkat menjadi CEO, menggantikan Kjelf Kirk Kristiansen,
cucu sang pendiri, yang telah menjabat sebagai pemimpin perusahaan itu selama
25 tahun.
Dalam
sejarah Lego, penunjukkan Knudstorp merupakan terobosan besar. Sejak perusahaan
berdiri, pucuk pimpinan tak pernah keluar dari trah keluarga Kristiansen. Namun
sosok Knudstorp memang figur yang unik. Setelah lulus dari Universitas Aarhus,
Denmark, dia merintis karir sebagai Engagement Consultant di McKinsey &
Company sebelum bergabung dengan Lego sebagai Diretur Pengembangan Strategis di
tahun 2001. Dia adalah konsultan di perusahaan. Dengan latar belakangnya dan
posisinya di Lego, doktor ekonomi bisnis ini dipandang akan lebih jernih
membedah persoalan sekalipun saat itu usianya baru menginjak 34 tahun.
Segera
setelah menjadi orang nomor satu yang membawahi 7300 karyawan, Knudstorp
menggelar operasi transformasi Lego selanjutnya. Minggu-minggu pertama menjabat
CEO, dia menghabiskan waktu bersama Kjelf serta anggota direksi lainnya untuk
membedah persoalan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan Knudstorp sangat
menukik: apakah Lego terlalu terdiversifikasi? Apakah biaya menjadi isu besar?
Apakah Lego kehilangan sentuhan dengan pasar yang kian terobsesi dengan video
game, bukan balok mainan?
Diskusi
hangat berlangsung diantara mereka. Masing-masing memaparkan opini berikut hipotesisnya.
Mereka memetakan persoalan. Satu poin terpampang jelas: pada transformasi
1993-2003, manajemen habis-habisan berinovasi untuk membangkitkan perusahaan.
Memang dari sisi inovasi, hasilnya luar biasa. Jumlah komponen produk mainan
yang dibuat meledak dari 2000 menjadi 10 ribu. Balok plastik tak lagi sederhana
seperti dulu, dengan warna-warna dasar. Sangat inovatif dan menarik, tapi
hasilnya amat pahit karena banyak yang tak diserap pasar sehingga tak memberi
nilai bagi perusahaan. Knudstorp pun segera memangkas setengahnya.
Selanjutnya,
di tengah perdebatan, satu hal juga tampak di wajah mereka: penjualan terbesar
datang dari produk mainan non-elektronik. Alhasil, “Saya yakin bahwa meneruskan
permainan di kompetisi yang bukan bisnis inti adalah berisiko,” ungkap
Knudstorp. Maka menurutnya, Lego harus back
to basic. Inovasi yang terlalu berlebihan dan masuk ke aneka bisnis membuat
arah perusahaan bukannya menjadi hebat, malah semrawut. Dari hasil pemetaan itu,
sang CEO beserta jajarannya sepakat bahwa balok mainan adalah masa depan
perusahaan. Karena itu bisnis yang terlihat tak relevan disisihkan. Knudstorp pun melego 70% saham di Legoland kepada Blackstone Group,
meraup US$ 460 juta.
Dengan
memutuskan Lego harus kembali ke khittahnya sebagai produsen balok mainan, Knudstorp
meminta staf intinya melakukan transformasi dari sisi produk. Pada sisi desain,
dia meminta para desainer menata ulang produk-produk. Hasil telaahan masalah
menunjukkan: hanya 30 produk yang menyumbang 80% pendapatan perusahaan. Yang
lainnya tak memberi nilai tambah dan tidak diproduksi lagi, menumpuk di gudang.
Knudstorp
ingin para desainernya merancang produk yang sesuai pasar, termasuk juga melihat
apa saja produk yang bisa dibangkitkan kembali, dikemas dengan lebih segar dan
sesuai selera mutakhir. Maka produk-produk legendaris dihidupkan lagi, seperti
model mobil pemadam kebakaran. Model itu dinilai masih oke untuk diperbarui. Begitu
juga dengan Lego Mindstorms yang sempat menjadi produk laris.
Tapi
Knudstorp juga mengingatkan para desainer untuk memikirkan aspek harga bahan
dasar, atau biaya produksi. Dia meyakinkan para desainernya bahwa kreativitas sebebas-bebasnya
tidak tepat untuk pasar mainan global di mana tekanan biaya sangat berperan
dalam keberlanjutan usaha. Knudstorp menunjukkan ada mainan yang hanya butuh
sedikit resin, tapi membeli berton-ton resin senilai puluhan ribu Euro yang
akhirnya mubazir.
Yang
menarik adalah dari sisi inovasi produk. Knudstorp percaya inovasi tetap
diperlukan. Sebab itu, secara internal, dia memberikan kebebasan pada tiap orang dari tenaga penjualan hingga staf
kantor pusat kapabilitas untuk menciptakan serta mengusulkan jalan baru untuk pertumbuhan
lewat inovasi produk. Lalu, dia juga percaya suara dari pasar harus benar-benar
diperhatikan dan diseleksi. Maka dalam upaya memunculkan produk unggulan, Lego mengembangkan model crowd-sourcing. Sekitar 100 orang penggemar fanatik dimintai bantuan untuk mengembangkan
produk. Knudstorp juga membuat Cuusoo, situs crowd-sourcing.
SIRKULASI HOLISTIK
“Dari
perspektif saya, supply chain adalah sistem sirkulasi. Anda harus
membenahinya,” kata Knudstorp. Ide pengembangan produk dan inovasi merupakan
bagian dari sirkulasi itu. Namun berbeda dengan satu dekade sebelumnya. Model
inovasi yang kini diberlakukan tak lagi sama. Menyadari banjir ide akan muncul
sewaktu-waktu, Knudstorp pun melakukan langkah-langkah sistematis. Untuk
mengelola crowd-sourcing, dia
menerapkan pola crowd-control. Ada karyawan yang
ditugaskan mengelola komunitas
fans fanatik. Juga ada
licensing development group, yang menciptakan panduan untuk para
mitra dalam membuat
produk Legok.
Dan di situs Cuusoo, satu produk baru
akan dibuat jika 10 ribu orang memilihnya.
Di
atas semuanya, poin yang sangat berbeda dibanding fase transformasi sebelumnya
adalah Knudstorp mengembangkan
matrik inovasi untuk menakar potensi dan risiko sebuah inovasi. Dengan matriks
ini, perusahaan bisa mengukur bagaimana inovasi harus dibangun, di mana harus berinvestasi,
dan bagaimana proyeksi hasil
akhir.
Di
tangan Knudstorp, organisasi dan inovasi memang
menjadi lebih terstruktur. Tentu
saja ini tak terlepas dari pengalaman buruk Lego dekade 1993-2003. Bagi Knudstorp, ide tetap harus
ditata. Orang dalam boleh mengusulkan ide. Begitu juga orang luar. Namun semua
akan ditakar lewat matriks inovasi.
Akan
tetapi, ide hanyalah satu titik dalam sirkulasi supply chain versi
Knudstorp. Dia beserta timnya melihat persoalan secara holistik, menganalisis
setiap aspek mulai dari sumber bahan baku, hingga manufaktur dan distribusi.
“Saya
kira, kesalahan yang sering diperbuat perusahaan adalah mendekati aspek supply
chain dengan melihatnya sebagai satu topik, inovasi sebagai hal lain,
begitu juga dengan kualitas produk. Padahal, cara terbaik adalah melihatnya
sebagai sesuatu yang saling terhubung satu sama lain,” ujar Knudstorp.
Tak
heran, mengimbangi perubahan di sisi produk, manajemen Lego membenahi sisi
operasi. Efisiensi digenjot total. Mereka melakukan renegosiasi dengan lebih
dari 11 ribu pemasok (lebih banyak dari pemasok Boeing untuk membuat pesawat)
untuk mendapatkan harga terbaik. Knudstorp juga memindahkan kantor ke dekat
pabrik. Lalu produksi balok mainan dialihdayakan ke pabrik yang lebih murah di Hungaria,
Kladno (Republik Ceko), Cina serta Meksiko. Mereka pun mengkaji ulang proses produksi agar produk
meluncur tepat pada waktunya. Dan di ujung proses, pada sisi distribusi,
Lego menutup 5 pusat distribusi di Denmark, Jerman serta Prancis. Sebagai
gantinya, mereka membuat sebuah pusat distribusi di Republik Ceko yang
dioperasikan oleh DHL.
Untuk
mendorong transformasi berjalan baik dan sesuai harapan, Knudstorp aktif
mengumpulkan para eksekutifnya. Dia membuat sebuah war room guna
mengkaji, mendiskusikan serta mengembangkan strategi. Adapun di level para planners
serta perwakilan penjualan, logistik, TI dan manufaktur, dia meminta mereka
mengoordinasi perubahan di level operasi.
Knudstorp
seringkali mengunjungi war room, mengecek pekerjaan para eksekutifnya.
Dan manakala dia melihat ada pekerjaan yang belum terselesaikan, dia akan
menanyakan langsung mengapa itu terjadi. “This is still here?” adalah
pertanyaan yang sering diajukannya begitu melihat satu persoalan masih menempel
di papan tulis. Knudstorp memang tipikal bos yang demanding.
Proses
transformasi memang melelahkan. Terutama bagi Knudstorp yang sering terjun
langsung ke lapangan. Namun hasil seluruh transformasi yang digerakannya sangat
memuaskan. Sejak 2004, langkah-langkah transformasi yang digelar sudah
menyelamatkan lebih dari US$ 67 juta. Tahun 2005, laba kembali diraih, sebesar
US$ 72 juta. Sejak tahun 2009, penjualan tumbuh 24% pertahun, dan
labanya tumbuh 41%. Karyawan bertambah
hingga 10 ribu orang. Memang Lego tidak lagi secara teratur masuk perusahaan
paling inovatif di dunia seperti dulu, tapi ia tumbuh mantap melewati
pesaingnya seperti Hasbro dan Mattel.
Di
atas itu semua, Knudstorp mengungkap bahwa transformasi yang dilakukannya telah
membawa dampak besar bagi perusahaan. Mereka jadi semakin menyadari bahwa
menciptakan produk yang tepat, diijual ke pasar pada saat yang tepat, dan
dengan harga yang tepat sangatlah esensial. “Transformasi yang kami lakukan
membuat Lego menjadi fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi, juga
pengembangan organisasi sebagai tempat bekerja yang lebih kreatif lagi. Itu
adalah sebuah kemewahan,” kata Knudstorp.
Begitulah.
Seperti balok-balok mainan, Knudstorp dan manajemen Lego melakukan
transformasi. Mereka menyusun langkah seperti menata balok satu demi satu agar satu
bentuk bisa dibuat. Mereka merasionalisasi dan merampingkan pengembangan
produk, menata sumber bahan baku, manufaktur dan distribusinya.***