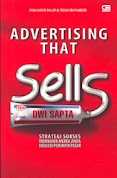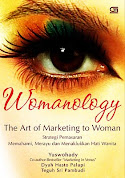Era memperbesar follower telah usai. Tugas mendesak pemimpin adalah creating more leaders.
JUDUL di atas, sepintas mirip iklan produk yang diobral:
“buy one, get three”. Tapi jelas judul di atas bukanlah seperti itu: bahwa bila
kita membeli satu produk, kita akan mendapat bonus. Kata itu saya dapatkan dari
owner sekaligus CEO Adhimix, Edno Windratno. Perusahaan precast nasional yang
urusannya memproduksi beton-beton ini kinerjanya luar biasa. Setelah di-spin
off dari Adhi Karya pada tahun 2002, Adhimix melesat luar biasa. Turnover-nya
yang hanya miliaran rupiah, kini telah mendekati Rp 5 triliun. Padahal,
sebelumnya Adhimix selalu merugi sehingga tidak berkontribusi pada Adhi Karya.
Lantas, apa maksudnya dengan “one get three”?
Yang dimaksudkannya di sini adalah tentang pentingnya peran
seorang pemimpin dalam melahirkan pemimpin-pemimpin di bawahnya,
pemimpin-pemimpin berikutnya, sehingga organisasi berjalan berkesinambungan.
Bukan organisasi yang pemimpinnya lebih besar dari organisasi itu sendiri
sehingga ketika sang pemimpin pergi, organisasi itu pun berantakan.
Seringkali, memang, orang menilai pemimpin dari prestasi,
atau result, yang dibuatnya sekarang. Di organisasi bisnis, prestasi itu berupa
kinerja finansial yang mengesankan, atau target yang jauh terlampaui. Penilaian
seperti itu tentunya tak keliru. Indikator-indikator kuantitatif semacam itu
memang yang paling disorot karena menjadi cerminan sejauh mana yang
bersangkutan telah mampu membawa organisasinya tumbuh.
Akan tetapi, pandangan seperti itu tidak sepenuhnya tepat.
Tugas pemimpin bukan sekedar mencetak angka pertumbuhan bisnis, tapi juga
mencetak pemimpin-pemimpin baru. Leader create leader. Bukan hanya satu, tapi
banyak, setidaknya 3 orang. Itulah yang dimaksud dengan “one get three”. Jadi
dengan demikian, lebih tepatnya adalah “leader create more leaders”. Bahkan bukan sekadar mencetak pemimpin di
bawahnya, tapi kalau bisa mendorong munculnya pemimpin-pemimpin di semua level
yang ada.
Di masa lampau, pendekatan yang sering kali berlaku untuk
menilai kesuksesan pemimpin adalah “berapa banyak orang yang mengikutinya
(followers)”. Entah itu organisasi bisnis, terlebih organisasi sosial. Bila
pengikutnya semakin banyak, maka sukseslah dia.
Era seperti itu kiranya sudah tidak banyak berlaku lagi.
Paradigmanya kian bergeser. Di masa kini dan masa mendatang, saya sepenuhnya
meyakini bahwa para pemimpin juga akan dinilai dari “seberapa banyak pemimpin
yang mereka hasilkan”. Apa maknanya?
Itu artinya, bila diletakkan dalam konteks organisasi
bisnis, kesuksesan pemimpin bukan semata dilihat dari sisi pertumbuhan finansial
(financial growth), tapi juga dilihat dari sejauh mana dia berperan di sisi
ini: melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang lebih berkualitas dibanding dirinya
(human capital growth).
Bagi organisasi yang ingin tumbuh, tumbuh dan terus tumbuh,
paradigma yang terakhir adalah yang paling relevan. Sebab, organisasi yang
ingin terus berkembang, yang ingin “sawah ladangnya kian meluas untuk ditanami
dengan beragam tumbuhan yang menghasilkan”, pastinya ia akan menciptakan atau
merebut peluang demi peluang yang kadang datangnya tak terantisipasi. Seperti
orang yang berada di stasiun, organisasi yang ingin maju akan menghadapi kereta
demi kereta yang datang dengan jadwal tiba-tiba.
Dalam kondisi demikian, tentunya diperlukan para pemimpin.
Dibutuhkan orang-orang yang berkarakter memimpin, yang tahu bagaimana melihat
serta memanfaatkan peluang, dan yang terpenting: berani mengambil keputusan
dengan segala risiko yang terkalkulasikan, sekaligus berani menghadapi
tantangan serta mempertanggungjawabkannya. Para pemimpin ini bukan hanya di
pucuk organisasi, tapi di semua level. Bukan hanya satu orang di satu
departemen atau divisi, tapi berlapis demi lapis.
Bila pemimpin yang ada dalam organisasi tersebut terbilang
sedikit, tidak di semua level, bisa dibayangkan seperti apa organisasi itu akan
bergerak. Boleh jadi organisasi itu hanya akan berjalan di tempat karena
orang-orang yang semestinya berani berinisiatif hanya diam menunggu titah. Cuma
duduk manis karena bersikap sebagai follower yang takut mengambil keputusan.
Melihat perjalanan ke depan, dan keinginan terus berlari
hingga batas yang tak bertepi, semua organisasi dalam skala apapun, sungguh
memerlukan munculnya pemimpin-pemimpin bisnis di semua level. Pemimpin di sini
bukan semata jabatan atau posisi, tapi juga karakter seperti berikut: jiwa
untuk memimpin, mengelola, mempengaruhi, memotivasi dan menginpirasi orang
lain.
Kalau sedemikian penting artinya “one get three” ini, maka
otomatis para pemimpin dituntut harus tahu bagaimana caranya mencetak
pemimpin-pemimpin baru.
Ini memang bukan pekerjaan gampang. Di banyak organisasi,
bahkan bukan cerita baru orang-orang dari luar direkrut besar-besaran untuk
menjadi pemimpin karena minimnya orang-orang dari lingkungan internal yang
berkualifikasi untuk me-lead dan me-manage.
Untuk kebetuhan mendesak, itu mungkin bisa dilakukan. Namun
belakangan banyak yang menyadari bahwa pemimpin yang terbaik biasanya memang
datang dari “ladang” sendiri. Mengapa? Karena yang bersangkutan sudah memahami
seluk-beluk mulai dari values, sistem hingga budaya yang berkembang. Ibarat
petani, dia sudah mengetahui jenis tanaman yang cocok dengan kontur tanah yang
digarapnya berikut kebutuhan airnya.
Akan tetapi, seperti disinggung di atas, sekalipun menyadari
orang lingkungan internal memiliki keunggulan karena mengetahui serta memahami
lekuk-lekuk organisasi, mencetak pemimpin-pemimpin baru tidak semudah membalik
telapak tangan. Di belakang kata “create more leader”, mestinya ada proses yang
panjang, yakni proses men-develop leader.
Laiknya orang yang bercocok tanam, atau mengandung, proses
untuk mendapatkan hasil memerlukan waktu yang tidak sebentar. Pengembangan
calon pemimpin tidaklah bisa sekejap. Proses ini butuh sejumlah hal, mulai dari
keseriusan, daya tahan, kejelian, dan yang satu ini: kerendahan hati.
Semua itu diperlukan karena dalam mengembangkan calon
pemimpin, seseorang mesti mampu membantu yang bersangkutan mengidentifikasi
serta menghubungkan apa yang menjadi potensinya dengan hal-hal yang akan
meningkatkan kapasitas dirinya. Selanjutnya, dia juga harus bisa mendorong sang
calon mengembangkan diri sehingga seluruh potensinya tersebut akan keluar
secara maksimal. Agar seluruh potensinya itu keluar, dia kudu sanggup mendesain
tantangan yang akan membuatnya berkembang lebih matang, baik sebagai individu
maupun pemimpin.
Untuk terus berjaya, semua organisasi harus menghindari
kelangkaan pemimpin. Sebagai organisasi yang ingin melesat, sudah semestinya perusahaan
menjadi ladang tumbuhnya bibit-bibit pemimpin baru. Semua pemimpin di level
unit dan divisi, harus bisa mendorong bawahannya tumbuh menjadi pemimpin yang
lebih hebat dari dirinya. Mereka harus menjadi leader, juga teacher. Mentalnya
seperti petani: menyirami, menyemai benih, memberinya cahaya, dan menyiangi
dari hal-hal yang akan mengganggu pertumbuhannya.
Alhasil, buat para pemimpin, ada baiknya melihat ke dalam:
sudahkah kita berupaya melahirkan pemimpin-pemimpin baru? Atau kita justru
ingin menunjukkan diri sebagai terhebat, yang tak bisa disaingi orang lain?
Bila perasaan terakhir yang muncul, rasa takut disaingi, itu
berarti tak memahami arti dan tugas pemimpin. Tak memahami makna “one get
three”.