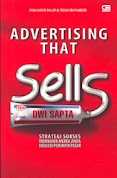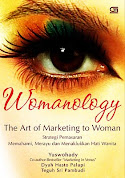Di mana-mana bisnis keluarga seringkali menyajikan drama: jatuh bangkrut atau hidup berlumur sengketa. Toh tetap saja ada yang bertahan dan tumbuh melewati generasi demi generasi.
Kita mungkin sering mendengar tentang tingkat bertahannya bisnis keluarga yang rentan: hanya 30% yang bisa mengalihkan ke generasi kedua, dan cuma 12% yang sanggup menyerahkan ke generasi ketiga.
Faktanya, di pentas global pun kenyataan itu tetap sering terjadi. Banyak perusahaan keluarga yang akhirnya tumbang sebelum genap satu abad. Bahkan ketika para pendirinya pun masih menghirup udara, mereka telah gulung tikar. Tak cukup semusim perusahaan telah tertiup angin.
Awal Februari ini, ambil contoh. Boston Globe melaporkan Harvard Square, perusahaan stationary legendaris akhirnya resmi gulung tikar. Perusahaan milik Mallory Slate (73 tahun) serta saudara laki-lainya itu ditutup karena tidak kunjung mendapat pembeli. Sejak tahun 2009, Slate sudah wara-wiri cari penawar. Tapi para calon pembeli rupanya tidak melihat ada harapan perusahaan ini bisa bersaing dengan kompetitiornya.
Mallory sebelumnya sudah berupaya keras merevitalisasi bisnis keluarganya di pertengahan 1980-an dari tekanan perusahaan pemasok kebutuhan alat tulis kantor berskala besar. Tapi mereka benar-benar tak lagi bisa bersaing. Apa daya, otot-otot finansial mereka kian melemah. Alhasil, jaringan toko mereka di sejumlah tempat, dengan sangat terpaksa, satu persatu memasang tanda: closed.
Pada Boston Globe, Mallory bercerita bahwa lingkugan bisnis sudah tak lagi nyaman buatnya. Di tengah tekanan pesaing yang begitu kuat, dia juga menilai masyarakat tidak lagi banyak menulis dengan tangan serta menggunakan produk-produk berbasis kertas. Sementara itu, anggota keluarga sudah tidak ada yang tertarik. Mereka lebih memilih berkarir di luar dunia ritel. Akhirnya, lonceng kematian pun berdentang. Setelah berdiri 75 tahun, Harvard Square menutup tirainya.
Bisnis keluarga Slate mungkin terhitung kecil. Tapi barangkali dia jauh lebih beruntung dibanding kegegeran di Makau baru-baru ini, dan masih berlangsung hingga sekarang. Stanley Ho, si raja judi Makau, bertempur dengan dua anaknya, Pansy dan Daisy. Mereka memerebutkan saham 31,7% senilai US$ 1,4 miliar di perusahaan kasinonya. Dua anak ini adalah anak dari istri keduanya. Ho sendiri punya 16 anak dari 4 istri. Ho menuduh dua putrinya itu secara ilegal mengambil alih aset-asetnya.
Usia Ho sudah 89 tahun. Tapi untuk urusan bisnis keluarga yang dirintisnya ini, Pak Tua itu rupanya tak mau kompromi. Dia tak mau kekayaannya yang ditaksir Forbes mencapai US$ 3,1 miliar jatuh secara tidak benar. Kekisruhan mereka diperkirakan masih akan berlanjut.
Bisnis keluarga memang sering melahirkan drama. Mari kita geser sedikit ke India. 4 Juli 2004, Priyamvada Birla, janda Madhav Prasad Birla, mangkat. Madhav adalah salah seorang dari Birla bersaudara yang membangun kerajaan bisnis Birla.
Bukan kematiannya yang bikin masalah. Priyamvada membuat ulah begitu surat wasiat dibuka. Rupanya dia mewariskan kekayaannya, termasuk sahamnya di Pilani Investment kepada akuntannya, R. S. Lodha. Dengan wasiat itu, maka otomatis Lodha masuk dalam keluarga Birla. Tanpa ayal, guncanglah Birla Group. Mereka menolak orang dari luar keluarga mengelola perusahaan.
Kericuhan di Birla, ditambah sebelumnya keributan di keluarga Ambani – sengketa bisnis Anil dan Mukesh Ambani –, membuat raksasa-raksasa bisnis India yang kebanyakan adalah perusahaan keluarga kini mulai berpikir serius untuk menata struktur kepemilikan keluarga masing-masing. Bahkan banyak yang membuat roadmap dan family constitution yang mengakomodasi keterlibatan anggota keluarga, mulai dari anak hingga cucu. “Mereka jadi lebih serius,” ujar Salil Bhandari, Mitra Pengelola BGJC, perusahaan konsultan di Delhi. Dengan demikian, kakak-adik boleh saja bertengkar, tapi sistem yang ada tak membuat hubungan persaudaraan pecah, menimbulkan sengketa kepemilikan.
Bisnis keluarga di India, relatif berbeda ketimbang di belahan Barat. Di negeri ini, kebanyakan bisnis keluarga merupakan gabungan dari sejumlah keluarga. Bagi kalangan profesional yang bekerja di sebuah perusahaan keluarga, siap-siap saja mereka menerima pil pahit: memerlukan waktu bertahun-tahun untuk bisa menduduki posisi pengambil keputusan dalam perusahaan.
Lantaran struktur kepemilikan yang melibatkan banyak keluarga, di India bahkan ada anekdot bahwa hasil riset global berlaku di sini: bisnis keluarga tak akan bisa bertahan lebih dari tiga generasi. Sebabnya, tali-temali kepentingan antarkeluarga begitu rumit. Memang tidak ada data yang utuh, tapi bukti menunjukkan riset di atas terjadi. Keluarga Birla pecah setelah 3 generasi. Ambani retak pada generasi ke-2. Sementara Bajaj, seperti halnya Birla, pecah pada generasi ke-3.
Selain struktur kepemilikan yang kompleks, titik picu keributan akhir-akhir ini juga menjadi kian menarik ketika bisnis keluarga di India saling berebut talenta terbaik dengan perusahaan multinasional. Bagi anggota keluarga yang kompeten, mereka bisa seperti mata pedang: menjadi sumber daya bagi keluarganya, atau hengkang ke multinasional. Menimbang persaingan ini, banyak keluarga yang kini sudah mengakomodasi talenta-talenta internal itu sebaik-baiknya. Buat mereka disediakan tempat di masa depan sehingga sang talenta tahu bagaimana peran yang bisa dimainkannya.
Setelah ribut di Birla dan Ambani, pergeseran dalam cara mengelola bisnis keluarga semakin terasa. Selain ada roadmap dan family constitution, kini perusahaan keluarga di India sudah sering melibatkan anak dan cucu untuk bicara perencanaan suksesi. Bila terjadi adu argumen, maka penasehat keluarga akan masuk memberi pandangan. Pergeseran lain adalah melibatkan anak-anak perempuan dalam diskusi tersebut, termasuk membicarakan posisi mereka. Sebelumnya, kebanyakan perusahaan India sangat tabu melakukan ini. Rencana bisnis keluarga biasanya hanya membicarakan nasib anak-anak wanita, bukan melibatkan mereka.
Salah satu grup yang dipuji adalah Godrej Group. Dua anak perempuan Adi Godrej, Tanya Dubash dan Nisa, terlibat aktif dalam grup. Grup Piramal, raksasa kesehatan India, juga menuai puji. Putri Ajay Piramal, Nandini memainkan peran penting saat Piramal membeli bisnis obat generik miliki Abbott. Hal lebih drastis terjadi di keluarga konglomerat Jindal. Kendali operasi konglomerasi itu kini di tangan Savitri Jindal.
Terlepas dari potensi konflik, bisnis keluarga, biar bagaimanapun tetap memiliki kekuatan tersendiri. Di AS, salah satu perusahaan terbesar adalah perusahaan keluarga, Koch Industries. Di dunia fashion, rata-rata raksasa global juga perusahaan keluarga yang sudah kenyang pasang-surut bisnis. L’Oreal dan Louis Vuitton, contohnya. L’Oreal kini makin ekspansif. Ia terus melebarkan sayapnya, terutama ke pasar sedang berkembang, termasuk Indonesia. Begitu pula dengan Louis Vuitton yang kini dipegang sang cucu, Patrick Louis Vuitton. Mereka berupaya terus melaju dalam naungan keluarga. Di luar nama-nama itu, masih ada Ford, Motorolla, News Corp, dan Faber Castell yang sudah melewati 8 generasi.
Bicara tentang kekuatan bisnis keluarga, artikel di majalah Inc tahun 1992 rasanya tetap menarik untuk disimak. Bertajuk Why Family Businesses Are Best, dalam artikel itu disebutkan mengapa bisnis keluarga memiliki kekuatan, yakni karena anggota keluarga mengetahui kualitas satu sama lain, saling menghargai, cenderung lebih bisa berkompromi. Bahkan, ada hubungan telepati yang tidak dimiliki perusahaan non-keluarga lantaran tumbuh bersama.
Di samping nama besar-nama besar seperti disebutkan di atas, salah satu perusahaan keluarga yang dipuji di AS adalah Mrs. G TV and Appliance. Perusahaan berbasis di Lawrenceville, New Jersey ini disebut agak langka karena sanggup bertarung dengan jaringan Lowe’s dan Home Depot.
Dibesut pada 1935 oleh Abe dan Beatrice Greenberg, perusahaan itu kini berada di tangan generasi ke-3. Di tengah gempuran jaringan lokal milik Lowe’s dan Home Depot, perusahaan ini sanggup mencetak penjualan US$ 10 juta. Jumlah pendapatan yang cukup besar untuk sebuah perusahaan keluarga di kota kecil.
Debbie Schaeffer, CEO Mrs. G mengungkap apa rahasia kekuatan bisnis keluarga yang menjadi pilar kesuksesan perusahaannya. Menurutnya, salah satunya adalah fokus pada hubungan satu sama lain untuk menciptakan relationship-based culture. Budaya ini diturunkan dari satu generasi demi generasi. Dari dekade demi dekade, sebagai keluarga mereka berbisnis dengan mengedepankan hubungan yang erat satu sama lain.
Ikatan keluarga yang kuat juga bisa menjadi rem yang pakem untuk saling mengingatkan dan bertindak penuh kehati-hatian (prudence). Inilah yang terjadi pada Firstrust Bank. Bank yang berbasis di Philadelphia ini didirikan keluarga Green tahun 1934. Sementara yang lainnya bertumbangan karena krisis subprime mortgage, Firstrust sanggup melewati gejolak ekonomi tanpa kerugian sedikit pun. “Juga tanpa memerlukan bailout pemerintah atau investasi pihak manapun,” tulis Philadelphia Inquirer, 27 Desember lalu.
Tentu saja plus-minus akan selalu ada dalam bisnis keluarga. Tapi buat bisnis keluarga yang tumbuh melewati generasi demi generasi, lazimnya nilai-nilai keluarga menjadi fondasi yang penting, bahkan kerap di atas kepentingan bisnis itu sendiri, yang seringkali disempitkan hanya untuk menimbun laba. Termasuk salah satu yang dipentingkan itu adalah memelihara hubungan dengan pelanggan.
Dalam konteks ini, Schaeffer punya cerita menarik. “Kakekku adalah pebisnis yang pintar,” ujarnya, “tapi, nenekku adalah orang yang selalu melihat bahwa hubungan baik adalah segalanya. Dia mencintai pelanggan. Jika seseorang datang, membutuhkan kulkas dan tidak bisa membelinya, dia akan duduk dan bicara selama setengah jam, ngobrol tentang keluarga dan pekerjaannya. Kemudian tak berapa lama, pelanggan itu akan keluar dari toko dengan kulkas yang diinginkannya. Nenek cuma bilang, ‘cicil US$ 5 per minggu, ya’.” Schaeffer bilang nilai ini diwariskan generasi demi generasi. Dan dengan tersirat, dia menegaskan bahwa relationship-based culture semacam ini seringkali tak dimiliki perusahaan non-keluarga, apalagi yang telah melewati musim demi musim.