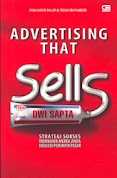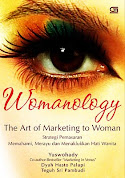Gerogotan pesaing di segmen smartphone membuatnya panas dingin. Sejumlah inisiatif diluncurkan. Dan pertaruhan pun dimulai.
Teguh S. Pambudi
Sudah setahun terakhir ini kabut seakan menggayuti Nokia. Memang, raksasa dari Finlandia ini masih nomor wahid di pasar telepon seluler lantaran menguasai 40% pangsa pasar dengan jumlah pengguna mencapai 1,1 miliar di 150 negara. Tahun lalu, 472 juta ponsel sukses dijualnya dengan nilai penjualan US$ 70 miliar, dan menghasilkan laba US$ 7 miliar. Tingkat produktivitasnya pun masih luar biasa. Tahu berapa ponsel yang dibuatnya setiap detik? “Kami membuat 13 ponsel setiap detiknya. Jadi bisa dibayangkan berapa ponsel yang kami buat ketika Anda makan malam,” ujar Tero Ojanperä, EVP Entertainment and Communities Nokia.
Ojanperä tak berseloroh. Nokia memang gigantik. Akan tetapi, sudah setahun ini ia dirundung duka karena justru kehilangan pijakan di arena yang sangat bergengsi: smartphone. Untuk ponsel kelas ratusan ribu hingga 2 juta rupiah, pemain yang satu ini memang rajanya. Siapapun tak bisa membantah itu. Tapi untuk kelas smartphone yang biasanya Rp 5 juta ke atas, ia memble. Penghadangnya siapa lagi kalau bukan Apple dengan iPhone-nya, serta Research In Motion (RIM) dengan BlackBerry-nya. Bahkan HTC pun ikut-ikutan menggerogoti kue di segmen ini.
Apple adalah penantang paling serius. Sekalipun hanya menguasai 2% dari seluruh pasar telepon genggam, iPhone telah menggigit pangsa pasar Nokia di smartphone yang berkembang di negara-negara maju seperti AS dan di belahan Eropa. Tilik data berikut: tahun 2008, jumlah smartphone yang terjual di seluruh dunia mencapai 139 juta, naik 14% dibanding tahun 2007. Dari jumlah sebanyak itu, 61 juta meluncur ke Nokia sementara 11,4 juta milik Apple. Bila diprosentase, jagoan Finlandia itu menguasai 43,7% sementara Apple 8,2%. Namun, di tahun 2009, terlihat betapa digdayanya pemain dari Amerika Serikat itu. Kuartal pertama tahun ini, pangsa pasar Nokia merosot ke 41,2% sementara Apple naik jadi 10,8%. Dan mengacu catatan Gartner Group, kuartal kedua 2009, penjualan iPhone tumbuh 27%.
Melihat situasi yang berkembang, tak heran bila Generator Research, perusahaan konsultan dari Inggris bahkan memprediksi pangsa pasar Nokia di smartphones akan menjadi 20% saja pada tahun 2013. Ancaman yang boleh jadi bukan mengada-ngada karena selain laju iPhone, BlackBerry, serta HTC, pemain lama macam Palm pun terus menggeliat lewat produknya yang paling gres, Palm Pre.
Para pesaing yang semakin kuat dari waktu ke waktu di segmen smartphone yang gurih benar-benar membuat raksasa Finlandia ini panas dingin. “Kami memang tak happy dengan situasi yang berkembang,” aku Anssi Vanjoki, EVP Nokia. “Tapi Anda harus hati-hati agar tak memfokuskan diri terlalu banyak di satu sisi,” lanjutnya. Maksudnya, mereka memang harus berupaya keras menahan semua prediksi mengerikan itu terjadi. Tapi, perhatian jangan cuma diarahkan ke segmen premium ini.
Untuk smartphone, Nokia mencoba bertindak dingin. Ia berusaha menandingi kehebatan Apple yang mampu menciptakan user experience yang superior. Serangkaian produk untuk menunjukkan ponselnya sebagus iPhone sudah diluncurkan, khususnya N-series dan E-series. N97, misalnya, sudah menampilkan diri sebagai laptop saku, dengan slide-out keyboard untuk mengetik atau kirim email, atau memasukkan data ke website. E71 juga produk bagus, dengan fitur smartphone yang diharapkan user: jaringan 3G dan Wi-Fi untuk data. Para pengembang independen pun kian banyak diundang untuk membuat aplikasi yang ciamik.
Toh di luar itu, Nokia sebenarnya benar-benar gusar dengan iPhone yang memang kini tengah jadi primadona – dibanding BlackBerry sekalipun. Pada 22 Oktober 2009, Nokia menggugat Apple atas tudingan pelanggaran paten pada perangkat iPhone. Raja ponsel ini menengarai iPhone yang diproduksi sejak 2007 telah menggunakan sepuluh patennya tanpa izin. Paten-paten tersebut berhubungan dengan dasar teknologi agar sebuah perangkat bisa bekerja dalam berbagai standar teknologi seperti GSM, UMTS, dan wireless LAN. Adapun paten-paten lainnya terkait transfer data nirkabel, speech coding, security, dan enkripsi data.
Urusan ini memang baru berkembang. Tapi, seperti kata Vanjoki, smartphone hanyalah satu sisi. Nokia tak mau perang bubat di sini. Mereka melihat pertempuran yang jauh lebih besar. Perusahaan ini meyakini bahwa area pertempuran yang sebenarnya adalah yan satu ini: bagaimana menciptakan peranti yang mobile, yang bisa memenuhi kebutuhan untuk online services, aplikasi dan hiburan.
Berpandangan demikian, Nokia berupaya mengerahkan kekuatannya. Pertama, tak seperti Apple atau RIM yang produknya tidak menjangkau semua kalangan, Nokia bermain di seluruh segmen, dari ratusan ribu hingga 7 juta rupiah. Kedua, perusahaan ini memiliki 10 laboratorium di dunia, yang bergerak berdasarkan filosofi inovasi terbuka dan bekerja sama dengan universitas ternama, diantaranya Berkeley, Stanford, MIT, dan Cambridge.
Smartphone memang gurih. Tapi Nokia tak cuma membidik AS. Mereka juga melihat Afrika dan Asia, khususnya di pedesaan merupakan pasar yang sangat luar biasa bila dapat dieksploitasi dengan maksimal. “Di AS, kami memang underdog,” ujar CEO Nokia, Olli-Pekka Kallasvuo, “tapi di dunia secara keseluruhan, kami adalah penguasa.” Karena itulah dia berupaya menghasilkan rangkaian produk yang bisa memberikan fitur yang dibutuhkan user. Mengandalkan kekuatan laboratoriumnya, salah satu produk yang sukses diluncurkan adalah Nokia Life Tools. Ini adalah aplikasi yang menyasar kalangan petani. Diuji coba di India, para petani cukup membayar US$ 1,30 perbulan untuk mendapatkan informasi tentang pertanian mulai dari info cuaca dan berita pertanian, hingga tip bercocok tanam. Kesuksesan di India ini rencananya akan dibawa ke sejumlah negara yang berbasis pertanian, termasuk Indonesia.
Uang US$ 1,30 per bulan memang tergolong kecil. Namun, seperti diungkap analis Gartner Group, Nick Jones, “India punya miliaran penduduk, yang kebanyakan tinggal di pedesaan. Jika Anda mendapat satu dolar sebulan dari 200 juta petani, itu adalah bisnis yang asyik.” Dan bisa dibayangkan bila program ini terduplikasi ke banyak negara berbasis pertanian.
Lantaran potensi yang oke punya itulah Nokia berupaya menggenjot laboratoriumnya untuk terus menghasilkan aplikasi serta produk yang semakin kaya. Henry Tirri, sang kepala riset Nokia yang mengurusi laboratorium R&D mengungkap sederet rencana, salah satunya menancapkan aplikasi semacam kompas yang menunjukkan arah kiblat. Raksasa Finlandia ini membidik pasar Muslim.
Inisiatif lainnya yang diumumkan 26 Agustus lalu adalah Nokia Money. Ini adalah aplikasi yang membuat para pengguna bisa mengakses jasa layanan perbankan. Tim riset Nokia menemukan fakta bahwa dari 4 miliar pemilik telepon seluler, hanya 1,6 miliar yang punya rekening bank. Nokia Money menyasar sisanya. Di Kenya, layanan ini menjadi proyek perdana dan mulai menampakkan hasil menggembirakan.
Nokia Money adalah bagian dari strategi mendapatkan pasar online services, khususnya mobile financial services yang dalam beberapa tahun mendatang akan semakin menjamur dengan nilai transaksi yang terus membesar: naik dari US$ 2,7 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 37 miliar di tahun 2011, yang faktor pemicunya adalah semakin menggeliatnya aktivitas ekonomi di negara-negara berkembang. “Dengan menyajikan layanan dan konten yang dikustomisasi bahkan untuk pasar low-end, kami akan menjadi pendukung kehidupan," ujar Ojanperä penuh keyakinan.
Sebagai pendukung strategi memperkaya layanan buat segala segmen dan menangkap potensi besar khususnya di negara-negara berkembang Asia dan Afrika, Nokia meluncurkan Ovi Store pada Juni 2009. Ini semacam perpustakaan global. Isinya adalah aplikasi dari seluruh pengembang di dunia yang bisa diunduh para pengguna Nokia. Kini sedikitnya tersedia 65 ribu aplikasi di store.ovi.com.
Nokia Life Tools, Nokia Money dan Ovi Store adalah upaya Nokia memenangkan perang di medan pertempuran yang sesungguhnya: mobile devices yang bisa memenuhi kebutuhan untuk online services, aplikasi dan hiburan. Inisiatif lain yang kini mengundang perbincangan adalah masuknya sang raja ponsel ke pasar netbook dengan meluncurkan Booklet 3G. Pasar netbook?
Benar. Diumumkan pada 24 Agustus 2009, laptop mini yang memiliki kemampuan battery life 12 jam dan koneksi ke jaringan broadband mobile ini merupakan upaya jagoan Finlandia untuk turut mencicipi pasar laptop yang mobile. Dengan meluncurkan Booklet 3G, Nokia punya peluang untuk mengeksploitasi koneksi dengan operator telekom sekaligus meredefinisi pasar.
Menariknya, Booklet bukan semata jawaban untuk para pembuat PC seperti Acer dan Dell yang telah terlebih dahulu menggarap mobile market. Nokia meluncurkan produk yang menggunakan sistem operasi Windows dan chip Intel ini supaya tidak didahului Apple yang kabarnya juga akan meluncurkan netbook tablet sebelum akhir 2009. Jadi, ini semacam preemptive strike. “Ketika Apple mengumumkan versi pertama netbook-nya, Nokia dapat meluncurkan versi kedua,” analisis N. Venkat Venkatraman, guru besar Boston University yang intens mengamati industri teknologi.
Nokia dan Apple, dua perusahaan yang kini berseteru adalah korporasi yang dikagumi. Namun, banyak analis meragukan Nokia bisa bertempur dengan Apple di pasar netbook. Charlie Wolf, analis senior di Needham & Co. menunjukkan bukti bahwa Ovi Store tak sepopuler iTunes. “Nokia itu bukan perusahaan peranti lunak. Apple sebaliknya, ia adalah perusahaan software. Apa yang membedakan iPhone dan iPod touch adalah software mereka,” katanya.
John Hwang, mantan eksekutif Yahoo! adalah orang yang direkrut Nokia untuk membidani Booklet. Terhadap kritik tentang laptop mini ini, dia berujar santai, “Ini hanya permulaan, kok, bukan akhir.”
Masuk ke netbook memang pertaruhan sang raja ponsel sebagaimana halnya mereka meluncurkan Life Tool serta sederet inisiatif lainnya. Namun manajemen Nokia memang tengah berupaya membuat produk yang bukan hanya seksi, mudah digunakan, tapi juga terhubung ke online services. Untuk itu, jangan dulu memusatkan perhatian pada Booklet. Lho, mengapa?
Sebab, Nokia disebut-sebut akan meluncurkan sebuah produk antara smartphone dan netbook, kemungkinan bahkan sebelum akhir 2009. "Industri ponsel tengah dalam perubahan besar dalam 20 tahun perjalanannya, dan terbuka peluang untuk kami bentuk,” kata Kallasvuo penuh keyakinan.
Wow… Beginilah kalau sang raja terusik.
Saturday, October 31, 2009
Monday, September 28, 2009
Mereka yang Bukan Orang Biasa
Sejumlah figur kelas dunia tampil menjadi orang hebat di bidangnya masing-masing. Dari mereka ada pelajaran: jangan terlalu memuja intelegensia dan bakat.
Teguh S. Pambudi
Banyak orang masih meributkan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa: Diego Armando Maradona, atau Edison Arantes do Nascimento alias Pele? Tapi di jagat tenis, tak ada keraguan untuk menyematkan predikat the Greatest Tennis Player Of All Time pada seorang pria kelahiran Basel, Swiss, 8 Agustus 1981 bernama Roger Federer yang sejauh ini telah menyabet 15 gelar grand slam dan diprediksi masih akan terus menambah koleksinya. Begitu pula tak ada perdebatan untuk menahbiskan sosok yang sesungguhnya layak mendapat sebutan Greatest Of Them All. Anda tahu siapa? Ya, Si Mulut Besar, Muhammad Ali.
Hidup mereka, di mata sebagian orang mungkin terlihat nikmat. Penuh bakat dan bergelimang sukses – sekalipun Ali didera Parkinson. Hal yang sama juga terlihat pada orang-orang di panggung bisnis macam Steve Jobs, duo pendiri Google (Larry Page dan Sergey Brin), sang fenomenal, Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), serta Jack Dorsey, pembuat Twitter. Mereka adalah orang-orang hebat. Dan jauh sebelum mereka, banyak orang-orang hebat di jamannya masing-masing. Ford dan Toyoda di otomotif, Matsushita dan Bill Hewlett-Dave Packard di elektronik, bahkan Ruth Handler si pencipta Barbie dan Mattel Inc. Nama-nama terakhir bahkan sering disebut sebagai “suvenir di abad-20” lantaran saking besarnya kontribusi yang diberikan.
Bagaimana mereka bisa sehebat itu?
Mereka memang dikaruniai kecerdasan serta bakat yang luar biasa. Tapi dalam kacamata Malcolm Gladwell, bakat serta intelejensia bukanlah segalanya. Mereka bisa menjadi kaum outlier, orang-orang hebat nan sukses itu, lantaran bantuan orang-orang sekitarnya sehingga bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dalam bahasa Gladwell, dan itu yang diyakininya, "People don't rise from nothing. We do owe something to parentage and patronage". Betul, dua “P” itulah, parentage and patronage yang memegang peranan. Faktor pengasuhan serta patronaselah yang berperan signifikan dalam membentuk seseorang menjadi “somebody” atau tidak sama sekali.
Tulisan si kribo Gladwell, mendapat dukungan Geoff Colvin lewat bukunya yang juga inspiratif, Talent is Overrated. Ya, bakat memang karunia yang distingtif pada manusia-manusia istimewa – bahkan sejatinya bakat itu ada pada tiap manusia. Tapi, sarannya, hendaknya orang tak terlalu menilai tinggi (overrated) sekaligus memuja-muji atas sesuatu yang disebut bakat karena banyak faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya seseorang. Dengan kata lain: bakat memang perlu, tapi itu tidak mutlak mengangkat nasib seseorang ke derajat yang lebih tinggi.
Dan rasanya, itu benar adanya. Anda tahu Lionel Andres Messi, sang penerus Maradona? Pemain Terbaik UEFA 2009 yang juga berpeluang besar meraih Ballon d'Or (Bola Emas) 2009 ini mungkin hanya menjadi seorang anak biasa di Rosario, Argentina bila para pemandu bakat dari FC Barcelona (Spanyol) tak bisa membujuk kedua orang tuanya untuk membawanya ke Barcelona dan memberinya suntikan hormon agar badannya tidak boncel.
Bocah kelahiran 24 Juni 1987 ini memang dikarunia bakat luar biasa. Bermain sepakbola sejak usia 5 tahun untuk klub Grandoli yang dilatih ayahnya, Jorge Messi, si bocah jenius ini kemudian pindah ke Newell’s Old Boy di tahun 1995. Malang tak bisa ditolak, saat usianya 11 tahun, dokter mendiagnosis anak ini mengidap apa yang disebut “growth hormone deficiency”. Tubuh Messi akan sulit berkembang karena defisiensi hormon pertumbuhan. Tinggi badannya divonis tak bisa melewati 140 cm. Mendekati setinggi itu pun sudah untung.
River Plate, salah satu klub besar Argentina yang juga pesaing Newell’s Old Boy, awalnya berniat mengambil persoalan ini. Rencananya: Messi ditarik ke klub itu dan diberikan treatment khusus. Tapi, biaya terapi hormon yang sebesar US$ 900 per bulan membuat manajemen River Plate mengurungkan niat. Mereka masih pikir-pikir untuk investasi yang tingkat pengembaliannya masih samar buat bocah 11 tahun. Buntutnya, nasib Messi pun menjadi ikut-ikutan tidak jelas.
Charles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona yang mencium bakat besar di Rosario segera bertindak. Dari Spanyol dia datang ke Rosario. Dia menawari Messi pengobatan bila keluarganya bersedia pindah ke wilayah Catalan, tempat Barcelona bermarkas. Dan begitulah cerita tentang anak jenius itu dirajut. Messi bergabung dengan klub Barcelona, dilatih hingga puluhan ribu jam di La Masia (Akademi Barcelona), diberikan suntikan hormon hingga akhirnya kini seperti yang dikenal dunia: Messi yang memberi banyak gelar pada Barcelona, Messi yang dipatok harga jualnya 70 juta pound, Messi sang Mesiah dengan tinggi 169 cm.
Messi jelas punya bakat yang dipertunjukkannya saat meliuk-liuk melewati lawan serta menjaringkan si kulit bundar. Namun, faktor orang tua, patron yang bernama Rexach serta manajemen Barcelona memegang peranan dalam menciptakan lingkungan yang membuat seluruh bakatnya berkembang maksimal. Messi sungguh beruntung mendapatkan itu semua. Akan tetapi, anak Rosario itu sendiri juga berperan besar, khususnya dalam membangun mentalitas juara. Mentalitas untuk melewati titik “kutukan” 140 cm dengan kesabaran menerima suntikan hormon secara berkala. Mentalitas untuk belajar menendang dan menaikkan jam terbang dalam urusan melatih dribling kaki kirinya yang luar biasa dan paket skill lainnya mulai dari mengoper hingga mencetak gol. Melihat semua yang terjadi, mungkin orang layak menerung: apa jadinya bakat Messi bila tak ditunjang dengan lingkungan serta mentalitas seperti itu?
Billy Jean King, sang legenda tennis dari AS pernah bilang dengan nada serius, “pressure is privileged”. Tekanan hanya datang pada orang-orang tertentu. Ya, tekanan adalah privilese, tidak datang pada setiap orang. Hanya para juara bermental baja yang sanggup menghadapinya. Dan di jagat tenis, kini Roger Federer adalah orangnya. 15 gelar grand slam koleksinya (6 gelar Wimbledon, 5 kali AS Terbuka, 3 gelar Australia Terbuka, dan satu dari Perancis Terbuka) akan sulit disamai para petenis manapun, terlebih mengingat usianya yang secara matematis masih panjang untuk mengejar tambahan raihan trofi. Dalam sejarah tenis, Federer adalah yang terbanyak masuk final grand slam, 21 kali. Terakhir, dia kalah atas Juan Martin Del Potro di final AS Terbuka, 15 September 2009. Dan dalam urusan uang, lelaki murah senyum ini juga jagonya: ditaksir lebih dari US$ 50,7 juta telah dikantunginya.
Menatap sepak terjang Federer adalah seperti melihat kesempurnaan. Namun, jelas sangat keliru bila melihat posisi berikut seluruh raihan petenis yang dijuluki Federer Express itu hanya dengan cara mengukurnya dari sisi bakat. Pencapaian Federer adalah buah dari lingkungan kondusif yang diberikan orang tuanya, Robert Federer dan Lynette Du Rand. Juga keseriusannya sendiri untuk terus mengasah jam terbang: memukul bola dengan segala jenis gaya, dan di atas segala jenis lapangan.
Mulai belajar tenis di usia 6 tahun, pada usia 12 tahun, Federer yang juga berbakat pada sepakbola dan fans berat FC Basel, akhirnya menyatakan pada orang tuanya bahwa dia memutuskan tenis sebagai masa depannya. Mendapat restu orang tua, Federer kemudian menempa diri. Dia tak henti berlatih, bahkan dengan porsi yang tinggi, minimal 4-6 jam sehari. Kelak, kebiasaan ini tak pernah hilang dari dirinya. Lelaki setingi 1,85 m itu bahkan mengaku hanya libur berlatih selama dua hari ketika menemani istrinya, Miroslava Vavrinec melahirkan anak kembar mereka, Charlene Riva dan Myla Rose, Juli 2009. Setelah itu, dia kembali berlatih, mengasah dan mempertajam seluruh kekuatan pukulannya.
Tak pelak, latihan spartan inilah yang kemudian menjadi dasar kekuatannya sehingga Jimmy Connors, mantan petenis top AS memujinya habis-habisan. "Di era spesialis seperti sekarang, Anda mungkin jago di clay court, spesialis lapangan rumput, kampiun hard court, atau ... Anda adalah Roger Federer," katanya. Masudnya?
Tak seperti pemain lainnya yang cuma piawai pada lapangan tertentu, Federer jago semua jenis lapangan turnamen besar, khususnya grand slam. Karena itu dia dijuluki “an all-court player”. Lapangan apapun, disikatnya!
Ada banyak cerita tentang outlier dari jagat olahraga. Namun, pesan yang mereka kirim adalah sama: bakat mereka berkembang sempurna di lingkungan yang bisa memaksimalkannya sehingga dapat menjadi persona-persona nan hebat. Contoh dari dunia sepakbola adalah bakat-bakat terbaik dari Afrika, Amerika Latin dan Asia yang mencorong di Eropa karena lingkungan di Benua Biru itu kondusif, terutama dengan adanya sistem kompetisi serta liga yang profesional, juga pelatih-pelatih bertangan dingin.
Di sejumlah negara Afrika, terutama, bakat-bakat itu terancam hanya akan tergerus usia dan tersia-siakan karena persoalan-persoalan non teknis serta politis, seperti perang, kemiskinan, dan kelaparan. Begitu pula dengan bakat yang tersia-sia di sejumlah negara Asia yang liganya sangat tidak profesional. Faktor lingkungan yang kondusif untuk menyemai bakat ini penting karena fakta membuktikan betapa negara-negara Asia dengan sistem kompetisi yang profesional seperti Jepang dan Korea Selatan mampu menghasilkan pemain-pemain hebat melebihi negara-negara Asia lainnya yang sistem kompetisinya amburadul.
Dari jagat profesional di dunia bisnis, hal serupa juga sering terjadi: bahwa bakat tidaklah selalu berperan paling dominan dalam kesuksesan.
Pertengahan 1978. Di markas besar Procter & Gamble di Cincinnati, AS, dua anak muda berusia 22 tahun yang baru saja lulus sedang asyik mencorat-coret memo bisnis. Keduanya tengah ditugaskan menjual adonan brownies Duncan Hines. Keduanya cerdas, yang satu dari Harvard, yang satunya dari Dartmouth College. Keduanya karyawan baru di P&G. Keduanya berada di ruang yang sama.
Saat itu tak ada yang menonjol dibanding rekrutmen baru P&G lainnya. Tapi, apa yang membuat keduanya kelak berbeda dibanding rekan-rekan seangkatan adalah keduanya penuh dengan ambisi di samping bakat bisnis yang besar. Tahukah Anda siapa mereka?
Mereka adalah Jeffrey Robert Immelt dan Steven Anthony Ballmer yang sebelum menginjak usia 50 tahun telah menjadi CEO dari dua perusahaan raksasa dunia, General Electric dan Microsoft. Apa yang membuat keduanya hebat, selain penuh dengan ambisi dan bakat kepemimpinan, juga keberuntungan mendapat patron yang luar biasa. Ballmer mendapat mitra yang hebat dalam diri Bill Gates ketika memutuskan bergabung dengan Microsoft pada tahun 1980, sementara Jeffrey Immelt yang bergabung dengan GE pada 1982 sangat beruntung karena digembleng patron terbesarnya yang juga seorang legenda bisnis, Jack Welch. Bila tak bertemu dua titan tersebut, mungkin mereka hanyalah orang-orang biasa. Atau, kalaupun hebat, belum tentu seperti sekarang. Keduanya, Gates dan Welch, berpengaruh sangat besar dalam membentuk jalan sehingga mereka bisa duduk di kursi yang sangat tinggi ini.
Memang, hidup tampak jauh lebih nikmat bagi mereka yang penuh bakat. Mereka punya lebih banyak pilihan, punya lebih peluang untuk sukses. Tapi, tunggu dulu, sebagaimana ditulis Gladwell dan Colvin: sebetulnya tidak ada masalah dengan apa yang Anda miliki ketika dilahirkan karena sukses besar tersedia bagi siapa saja yang bersedia untuk terus mengasah diri, melatih mental, mencari lingkungan yang kondusif, berada dalam jejaring yang positif, dan… tentu saja memiliki keberuntungan.
Jack Welch yang dijuluki Manajer Abad 20, misalnya, tak menunjukkan minatnya pada bisnis hingga usia pertengahan 20-an. Dengan gelar doktor rekayasa kimia, dia baru bersentuhan dengan dunia bisnis pada usia 25 tahun. Itupun setelah dia memutuskan bekerja di bagian pengembangan kimia di General Electric dan mengabaikan kemungkinan bekerja di universitas Syracuse serta West Virigia. Tapi kesediaannya untuk belajar membuatnya menjadi outlier di kalangan profesional bisnis, yang mengundang kekaguman hingga kini.
Bakat memang karunia. Tapi sebagaimana juga ditulis Colvin, “para ilmuwan hingga kini belum bisa menemukan atau mengidentifikasi gen yang membawa bakat tertentu seperti gen pemain piano, gen investasi, atau gen akuntansi”. Apa yang bisa membuat sukses seseorang, yang disebut Gladwell sebagai 10 ribu jam terbang, menurut Colvin adalah "deliberate practice". Ini bukan sekedar frekuensi atau lamanya sebuah latihan, tapi istilah untuk sebuah latihan atau praktik yang dilakukan secara konsisten guna meningkatkan performa. Jadi, pendekatannya adalah kualitas, bukan kuantitas. Dalam konteks ini, para maestro yang telah melakukannya sejak dini dan disebut sebagai contoh terbaik adalah Tiger Woods, Pablo Picasso serta Wolfgang Amadeus Mozart.
Tentu tak semua orang dapat keberuntungan melatih satu bakat atau keahlian tertentu pada usia yang sangat dini. Namun, praktik yang konsisten ini sangat penting karena begitu satu kesempatan datang, level performa tertentu telah dimiliki. Alhasil, deliberate practice adalah kunci penting untuk menjemput sukses, the key when opportunity comes. Hanya saja, seperti juga telah disinggung Jean King, deliberate practice memerlukan sikap mental yang kuat karena latihan yang konsisten kerap kali tidak mudah, penuh cobaan. “It's highly demanding mentally,” tulis Colvin.
Selain mental, deliberate practice juga membutuhkan upaya untuk fokus dan konsentrasi tinggi. Itu artinya membutuhkan daya tahan pikiran. Federer menjadi maestro karena ketahanannya untuk tetap fokus memukul bola di tengah segala tekanan saat bermain. Dia juga jarang terlihat emosional ketika dalam posisi tertinggal. Saking hebatnya dia bermain, sampai-sampai banyak artikel bermunculan hanya dengan satu topik: bagaimana mengalahkan Federer yang selalu tampil prima?
Tentang pentingnya kekuatan fokus dalam deliberate practice dialami Nathan Mironovich Milstein, salah seorang dari pemain biola terbaik abad 20. Milstein yang kelahiran Odessa (Ukraina) adalah murid dari guru terkenal, Leopold Auer di St. Pertersburg. Suatu waktu, sehabis berlatih, Milstein bertanya pada gurunya: apakah latihannya sudah memadai? Auer menjawab singkat, tapi dalam, “Berlatihlah dengan jari-jarimu, maka kamu akan butuh sehari penuh. Sebaliknya, berlatihlah dengan pikiranmu, maka kamu cuma butuh 1,5 jam saja”. Apa yang dimaksudkan Auer adalah jika Anda benar-benar berlatih dengan menggunakan pikiran sepenuhnya, alias konsentrasi, maka 1,5 jam sudah memadai untuk memupuk kompetensi diri. Ingat, memupuk, yang artinya melakukannya secara berkesinambungan.
Yang menarik, Colvin kemudian menarik aspek kesuksesan individu ini untuk kemudian meletakkannya dalam konteks korporasi. Menurutnya, perusahaan yang hebat, adalah mereka yang juga bisa membuat bakat-bakat yang ada di dalamnya tumbuh berkembang dengan baik. Itu artinya, perusahaan perlu menciptakan iklim yang kondusif seperti budaya mentoring, coaching, dan kebiasaan membangun karir dengan pemberian tugas yang membangun potensi diri karyawan. Meminjam Gladwell, budaya kondusif di atas tak ubahnya menciptakan pola pengasuhan (parentage) yang tepat sehingga potensi-potensi terbaik bisa terasah. Apple, Google, serta Intuit adalah segelintir perusahaan yang bisa menciptakan iklim seperti itu.
Repotnya, tandas Colvin, banyak perusahaan mengabaikan faktor fundamental tersebut. Padahal, boleh jadi akan banyak outlier dalam tubuh suatu perusahaan begitu kultur tersebut dibangun. Outlier yang berwujud para profesional pilihan macam Ballmer atau Immelt, atau orang-orang sekreatif Steve Jobs. Orang-orang yang dijuluki the great man on their job.
Teguh S. Pambudi
Banyak orang masih meributkan tentang siapa pesepak bola terbaik sepanjang masa: Diego Armando Maradona, atau Edison Arantes do Nascimento alias Pele? Tapi di jagat tenis, tak ada keraguan untuk menyematkan predikat the Greatest Tennis Player Of All Time pada seorang pria kelahiran Basel, Swiss, 8 Agustus 1981 bernama Roger Federer yang sejauh ini telah menyabet 15 gelar grand slam dan diprediksi masih akan terus menambah koleksinya. Begitu pula tak ada perdebatan untuk menahbiskan sosok yang sesungguhnya layak mendapat sebutan Greatest Of Them All. Anda tahu siapa? Ya, Si Mulut Besar, Muhammad Ali.
Hidup mereka, di mata sebagian orang mungkin terlihat nikmat. Penuh bakat dan bergelimang sukses – sekalipun Ali didera Parkinson. Hal yang sama juga terlihat pada orang-orang di panggung bisnis macam Steve Jobs, duo pendiri Google (Larry Page dan Sergey Brin), sang fenomenal, Mark Zuckerberg (pendiri Facebook), serta Jack Dorsey, pembuat Twitter. Mereka adalah orang-orang hebat. Dan jauh sebelum mereka, banyak orang-orang hebat di jamannya masing-masing. Ford dan Toyoda di otomotif, Matsushita dan Bill Hewlett-Dave Packard di elektronik, bahkan Ruth Handler si pencipta Barbie dan Mattel Inc. Nama-nama terakhir bahkan sering disebut sebagai “suvenir di abad-20” lantaran saking besarnya kontribusi yang diberikan.
Bagaimana mereka bisa sehebat itu?
Mereka memang dikaruniai kecerdasan serta bakat yang luar biasa. Tapi dalam kacamata Malcolm Gladwell, bakat serta intelejensia bukanlah segalanya. Mereka bisa menjadi kaum outlier, orang-orang hebat nan sukses itu, lantaran bantuan orang-orang sekitarnya sehingga bisa memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya. Dalam bahasa Gladwell, dan itu yang diyakininya, "People don't rise from nothing. We do owe something to parentage and patronage". Betul, dua “P” itulah, parentage and patronage yang memegang peranan. Faktor pengasuhan serta patronaselah yang berperan signifikan dalam membentuk seseorang menjadi “somebody” atau tidak sama sekali.
Tulisan si kribo Gladwell, mendapat dukungan Geoff Colvin lewat bukunya yang juga inspiratif, Talent is Overrated. Ya, bakat memang karunia yang distingtif pada manusia-manusia istimewa – bahkan sejatinya bakat itu ada pada tiap manusia. Tapi, sarannya, hendaknya orang tak terlalu menilai tinggi (overrated) sekaligus memuja-muji atas sesuatu yang disebut bakat karena banyak faktor yang mempengaruhi sukses tidaknya seseorang. Dengan kata lain: bakat memang perlu, tapi itu tidak mutlak mengangkat nasib seseorang ke derajat yang lebih tinggi.
Dan rasanya, itu benar adanya. Anda tahu Lionel Andres Messi, sang penerus Maradona? Pemain Terbaik UEFA 2009 yang juga berpeluang besar meraih Ballon d'Or (Bola Emas) 2009 ini mungkin hanya menjadi seorang anak biasa di Rosario, Argentina bila para pemandu bakat dari FC Barcelona (Spanyol) tak bisa membujuk kedua orang tuanya untuk membawanya ke Barcelona dan memberinya suntikan hormon agar badannya tidak boncel.
Bocah kelahiran 24 Juni 1987 ini memang dikarunia bakat luar biasa. Bermain sepakbola sejak usia 5 tahun untuk klub Grandoli yang dilatih ayahnya, Jorge Messi, si bocah jenius ini kemudian pindah ke Newell’s Old Boy di tahun 1995. Malang tak bisa ditolak, saat usianya 11 tahun, dokter mendiagnosis anak ini mengidap apa yang disebut “growth hormone deficiency”. Tubuh Messi akan sulit berkembang karena defisiensi hormon pertumbuhan. Tinggi badannya divonis tak bisa melewati 140 cm. Mendekati setinggi itu pun sudah untung.
River Plate, salah satu klub besar Argentina yang juga pesaing Newell’s Old Boy, awalnya berniat mengambil persoalan ini. Rencananya: Messi ditarik ke klub itu dan diberikan treatment khusus. Tapi, biaya terapi hormon yang sebesar US$ 900 per bulan membuat manajemen River Plate mengurungkan niat. Mereka masih pikir-pikir untuk investasi yang tingkat pengembaliannya masih samar buat bocah 11 tahun. Buntutnya, nasib Messi pun menjadi ikut-ikutan tidak jelas.
Charles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona yang mencium bakat besar di Rosario segera bertindak. Dari Spanyol dia datang ke Rosario. Dia menawari Messi pengobatan bila keluarganya bersedia pindah ke wilayah Catalan, tempat Barcelona bermarkas. Dan begitulah cerita tentang anak jenius itu dirajut. Messi bergabung dengan klub Barcelona, dilatih hingga puluhan ribu jam di La Masia (Akademi Barcelona), diberikan suntikan hormon hingga akhirnya kini seperti yang dikenal dunia: Messi yang memberi banyak gelar pada Barcelona, Messi yang dipatok harga jualnya 70 juta pound, Messi sang Mesiah dengan tinggi 169 cm.
Messi jelas punya bakat yang dipertunjukkannya saat meliuk-liuk melewati lawan serta menjaringkan si kulit bundar. Namun, faktor orang tua, patron yang bernama Rexach serta manajemen Barcelona memegang peranan dalam menciptakan lingkungan yang membuat seluruh bakatnya berkembang maksimal. Messi sungguh beruntung mendapatkan itu semua. Akan tetapi, anak Rosario itu sendiri juga berperan besar, khususnya dalam membangun mentalitas juara. Mentalitas untuk melewati titik “kutukan” 140 cm dengan kesabaran menerima suntikan hormon secara berkala. Mentalitas untuk belajar menendang dan menaikkan jam terbang dalam urusan melatih dribling kaki kirinya yang luar biasa dan paket skill lainnya mulai dari mengoper hingga mencetak gol. Melihat semua yang terjadi, mungkin orang layak menerung: apa jadinya bakat Messi bila tak ditunjang dengan lingkungan serta mentalitas seperti itu?
Billy Jean King, sang legenda tennis dari AS pernah bilang dengan nada serius, “pressure is privileged”. Tekanan hanya datang pada orang-orang tertentu. Ya, tekanan adalah privilese, tidak datang pada setiap orang. Hanya para juara bermental baja yang sanggup menghadapinya. Dan di jagat tenis, kini Roger Federer adalah orangnya. 15 gelar grand slam koleksinya (6 gelar Wimbledon, 5 kali AS Terbuka, 3 gelar Australia Terbuka, dan satu dari Perancis Terbuka) akan sulit disamai para petenis manapun, terlebih mengingat usianya yang secara matematis masih panjang untuk mengejar tambahan raihan trofi. Dalam sejarah tenis, Federer adalah yang terbanyak masuk final grand slam, 21 kali. Terakhir, dia kalah atas Juan Martin Del Potro di final AS Terbuka, 15 September 2009. Dan dalam urusan uang, lelaki murah senyum ini juga jagonya: ditaksir lebih dari US$ 50,7 juta telah dikantunginya.
Menatap sepak terjang Federer adalah seperti melihat kesempurnaan. Namun, jelas sangat keliru bila melihat posisi berikut seluruh raihan petenis yang dijuluki Federer Express itu hanya dengan cara mengukurnya dari sisi bakat. Pencapaian Federer adalah buah dari lingkungan kondusif yang diberikan orang tuanya, Robert Federer dan Lynette Du Rand. Juga keseriusannya sendiri untuk terus mengasah jam terbang: memukul bola dengan segala jenis gaya, dan di atas segala jenis lapangan.
Mulai belajar tenis di usia 6 tahun, pada usia 12 tahun, Federer yang juga berbakat pada sepakbola dan fans berat FC Basel, akhirnya menyatakan pada orang tuanya bahwa dia memutuskan tenis sebagai masa depannya. Mendapat restu orang tua, Federer kemudian menempa diri. Dia tak henti berlatih, bahkan dengan porsi yang tinggi, minimal 4-6 jam sehari. Kelak, kebiasaan ini tak pernah hilang dari dirinya. Lelaki setingi 1,85 m itu bahkan mengaku hanya libur berlatih selama dua hari ketika menemani istrinya, Miroslava Vavrinec melahirkan anak kembar mereka, Charlene Riva dan Myla Rose, Juli 2009. Setelah itu, dia kembali berlatih, mengasah dan mempertajam seluruh kekuatan pukulannya.
Tak pelak, latihan spartan inilah yang kemudian menjadi dasar kekuatannya sehingga Jimmy Connors, mantan petenis top AS memujinya habis-habisan. "Di era spesialis seperti sekarang, Anda mungkin jago di clay court, spesialis lapangan rumput, kampiun hard court, atau ... Anda adalah Roger Federer," katanya. Masudnya?
Tak seperti pemain lainnya yang cuma piawai pada lapangan tertentu, Federer jago semua jenis lapangan turnamen besar, khususnya grand slam. Karena itu dia dijuluki “an all-court player”. Lapangan apapun, disikatnya!
Ada banyak cerita tentang outlier dari jagat olahraga. Namun, pesan yang mereka kirim adalah sama: bakat mereka berkembang sempurna di lingkungan yang bisa memaksimalkannya sehingga dapat menjadi persona-persona nan hebat. Contoh dari dunia sepakbola adalah bakat-bakat terbaik dari Afrika, Amerika Latin dan Asia yang mencorong di Eropa karena lingkungan di Benua Biru itu kondusif, terutama dengan adanya sistem kompetisi serta liga yang profesional, juga pelatih-pelatih bertangan dingin.
Di sejumlah negara Afrika, terutama, bakat-bakat itu terancam hanya akan tergerus usia dan tersia-siakan karena persoalan-persoalan non teknis serta politis, seperti perang, kemiskinan, dan kelaparan. Begitu pula dengan bakat yang tersia-sia di sejumlah negara Asia yang liganya sangat tidak profesional. Faktor lingkungan yang kondusif untuk menyemai bakat ini penting karena fakta membuktikan betapa negara-negara Asia dengan sistem kompetisi yang profesional seperti Jepang dan Korea Selatan mampu menghasilkan pemain-pemain hebat melebihi negara-negara Asia lainnya yang sistem kompetisinya amburadul.
Dari jagat profesional di dunia bisnis, hal serupa juga sering terjadi: bahwa bakat tidaklah selalu berperan paling dominan dalam kesuksesan.
Pertengahan 1978. Di markas besar Procter & Gamble di Cincinnati, AS, dua anak muda berusia 22 tahun yang baru saja lulus sedang asyik mencorat-coret memo bisnis. Keduanya tengah ditugaskan menjual adonan brownies Duncan Hines. Keduanya cerdas, yang satu dari Harvard, yang satunya dari Dartmouth College. Keduanya karyawan baru di P&G. Keduanya berada di ruang yang sama.
Saat itu tak ada yang menonjol dibanding rekrutmen baru P&G lainnya. Tapi, apa yang membuat keduanya kelak berbeda dibanding rekan-rekan seangkatan adalah keduanya penuh dengan ambisi di samping bakat bisnis yang besar. Tahukah Anda siapa mereka?
Mereka adalah Jeffrey Robert Immelt dan Steven Anthony Ballmer yang sebelum menginjak usia 50 tahun telah menjadi CEO dari dua perusahaan raksasa dunia, General Electric dan Microsoft. Apa yang membuat keduanya hebat, selain penuh dengan ambisi dan bakat kepemimpinan, juga keberuntungan mendapat patron yang luar biasa. Ballmer mendapat mitra yang hebat dalam diri Bill Gates ketika memutuskan bergabung dengan Microsoft pada tahun 1980, sementara Jeffrey Immelt yang bergabung dengan GE pada 1982 sangat beruntung karena digembleng patron terbesarnya yang juga seorang legenda bisnis, Jack Welch. Bila tak bertemu dua titan tersebut, mungkin mereka hanyalah orang-orang biasa. Atau, kalaupun hebat, belum tentu seperti sekarang. Keduanya, Gates dan Welch, berpengaruh sangat besar dalam membentuk jalan sehingga mereka bisa duduk di kursi yang sangat tinggi ini.
Memang, hidup tampak jauh lebih nikmat bagi mereka yang penuh bakat. Mereka punya lebih banyak pilihan, punya lebih peluang untuk sukses. Tapi, tunggu dulu, sebagaimana ditulis Gladwell dan Colvin: sebetulnya tidak ada masalah dengan apa yang Anda miliki ketika dilahirkan karena sukses besar tersedia bagi siapa saja yang bersedia untuk terus mengasah diri, melatih mental, mencari lingkungan yang kondusif, berada dalam jejaring yang positif, dan… tentu saja memiliki keberuntungan.
Jack Welch yang dijuluki Manajer Abad 20, misalnya, tak menunjukkan minatnya pada bisnis hingga usia pertengahan 20-an. Dengan gelar doktor rekayasa kimia, dia baru bersentuhan dengan dunia bisnis pada usia 25 tahun. Itupun setelah dia memutuskan bekerja di bagian pengembangan kimia di General Electric dan mengabaikan kemungkinan bekerja di universitas Syracuse serta West Virigia. Tapi kesediaannya untuk belajar membuatnya menjadi outlier di kalangan profesional bisnis, yang mengundang kekaguman hingga kini.
Bakat memang karunia. Tapi sebagaimana juga ditulis Colvin, “para ilmuwan hingga kini belum bisa menemukan atau mengidentifikasi gen yang membawa bakat tertentu seperti gen pemain piano, gen investasi, atau gen akuntansi”. Apa yang bisa membuat sukses seseorang, yang disebut Gladwell sebagai 10 ribu jam terbang, menurut Colvin adalah "deliberate practice". Ini bukan sekedar frekuensi atau lamanya sebuah latihan, tapi istilah untuk sebuah latihan atau praktik yang dilakukan secara konsisten guna meningkatkan performa. Jadi, pendekatannya adalah kualitas, bukan kuantitas. Dalam konteks ini, para maestro yang telah melakukannya sejak dini dan disebut sebagai contoh terbaik adalah Tiger Woods, Pablo Picasso serta Wolfgang Amadeus Mozart.
Tentu tak semua orang dapat keberuntungan melatih satu bakat atau keahlian tertentu pada usia yang sangat dini. Namun, praktik yang konsisten ini sangat penting karena begitu satu kesempatan datang, level performa tertentu telah dimiliki. Alhasil, deliberate practice adalah kunci penting untuk menjemput sukses, the key when opportunity comes. Hanya saja, seperti juga telah disinggung Jean King, deliberate practice memerlukan sikap mental yang kuat karena latihan yang konsisten kerap kali tidak mudah, penuh cobaan. “It's highly demanding mentally,” tulis Colvin.
Selain mental, deliberate practice juga membutuhkan upaya untuk fokus dan konsentrasi tinggi. Itu artinya membutuhkan daya tahan pikiran. Federer menjadi maestro karena ketahanannya untuk tetap fokus memukul bola di tengah segala tekanan saat bermain. Dia juga jarang terlihat emosional ketika dalam posisi tertinggal. Saking hebatnya dia bermain, sampai-sampai banyak artikel bermunculan hanya dengan satu topik: bagaimana mengalahkan Federer yang selalu tampil prima?
Tentang pentingnya kekuatan fokus dalam deliberate practice dialami Nathan Mironovich Milstein, salah seorang dari pemain biola terbaik abad 20. Milstein yang kelahiran Odessa (Ukraina) adalah murid dari guru terkenal, Leopold Auer di St. Pertersburg. Suatu waktu, sehabis berlatih, Milstein bertanya pada gurunya: apakah latihannya sudah memadai? Auer menjawab singkat, tapi dalam, “Berlatihlah dengan jari-jarimu, maka kamu akan butuh sehari penuh. Sebaliknya, berlatihlah dengan pikiranmu, maka kamu cuma butuh 1,5 jam saja”. Apa yang dimaksudkan Auer adalah jika Anda benar-benar berlatih dengan menggunakan pikiran sepenuhnya, alias konsentrasi, maka 1,5 jam sudah memadai untuk memupuk kompetensi diri. Ingat, memupuk, yang artinya melakukannya secara berkesinambungan.
Yang menarik, Colvin kemudian menarik aspek kesuksesan individu ini untuk kemudian meletakkannya dalam konteks korporasi. Menurutnya, perusahaan yang hebat, adalah mereka yang juga bisa membuat bakat-bakat yang ada di dalamnya tumbuh berkembang dengan baik. Itu artinya, perusahaan perlu menciptakan iklim yang kondusif seperti budaya mentoring, coaching, dan kebiasaan membangun karir dengan pemberian tugas yang membangun potensi diri karyawan. Meminjam Gladwell, budaya kondusif di atas tak ubahnya menciptakan pola pengasuhan (parentage) yang tepat sehingga potensi-potensi terbaik bisa terasah. Apple, Google, serta Intuit adalah segelintir perusahaan yang bisa menciptakan iklim seperti itu.
Repotnya, tandas Colvin, banyak perusahaan mengabaikan faktor fundamental tersebut. Padahal, boleh jadi akan banyak outlier dalam tubuh suatu perusahaan begitu kultur tersebut dibangun. Outlier yang berwujud para profesional pilihan macam Ballmer atau Immelt, atau orang-orang sekreatif Steve Jobs. Orang-orang yang dijuluki the great man on their job.
Labels:
Leadership
Tuesday, September 15, 2009
Gonjang-ganjing Leadership Global
Krisis finansial tak hanya mengakibatkan CEO berguguran, tetapi juga membuat nilai-nilai kepemimpinan di kancah bisnis global digugat. Apa yang sebenarnya terjadi?
Teguh S. Pambudi
25 November 2008. Barbara Kellerman mengeluarkan catatan menarik dalam tulisannya, Leadership Malpractice. Pada tulisan yang dimuat di Harvard Business Online itu, pengajar Public Leadership di John F. Kennedy School of Government itu mencatat bahwa dalam 9 bulan pertama di tahun 2008, sedikitnya ada 1.132 CEO di sejumlah negara yang terpental dari posisinya, atau diminta untuk segera hengkang. Tekanan krisis membuat mereka rontok, atau dirontokkan karena dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial.
Angka yang dikutip Kellerman mungkin terbilang fantastis. Namun, Booz & Company, dalam surveinya yang dirilis 26 Mei 2009 mencatat bahwa turnover CEO memang meningkat: dari 13,8% menjadi 14,4% di tahun 2008. Dalam laporannya bertajuk CEO Succession 2008 itu, sedikitnya tercatat 361 suksesi di antara 2.500 perusahaan publik papan atas global di tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 180 CEO dilengserkan karena memang telah direncanakan sebelumnya (pensiun, sakit), 54 CEO diganti karena terjadi merger-akuisisi, dan hanya 127 orang yang dipaksa mundur karena kinerja yang buruk serta persoalan etika.
Sejak krisis finansial meledak, pembahasan tentang peran para leader di panggung bisnis global memang kian mengemuka. Umumnya mengerucut pada hal berikut: apa yang terjadi sehingga leader justru menjadikan kondisi memburuk? Tidakkah cukup kasus Enron dan WorldComm mengajarkan betapa leadership yang buruk membuat malapetaka besar?
“Ada ingredient yang hilang,” cetus Rick Wartzman, Direktur Drucker Institute at Claremont Graduate University. Menurut hematnya, dengan mengutip Drucker, the true leader adalah mereka yang membawa tanggung jawab, konsistensi, dan sense yang tajam untuk semua hal yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di Wall Street yang kemudian mengguncang dunia, menurut Wartzman, menunjukkan mereka kehilangan itu semua. Sebagai leader, mereka yang mestinya penuh tanggung jawab dalam bertindak, justru dengan seenaknya berperilaku, mempermainkan kuasa yang mereka punya.
Yang membuat publik makin kesal, tulis Wartzman, sejumlah CEO sepertinya tidak mau disalahkan sekaligus menanggung beban atas ulahnya yang menjengkelkan itu. Mantan petinggi Lehman Brothers dan American International Group (AIG), ketika berbicara di Capitol Hill menuduh bahwa kekacauan finansial terjadi di luar diri dan institusi mereka. Dengan gagahnya, mereka justru menuding kalangan pasar modal, short-seller, juga regulator yang menimbulkan malapetaka ini semua. “Kalau melihat saat saya jadi CEO,” tukas Robert Willumstad, “saya tidak percaya AIG berbuat sesuatu yang aneh-aneh.” Begitu kata mantan CEO AIG ini. “Ya, kami sama-sama prudent,” tukas Richard Fuld, Chairman merangkap CEO Lehman Brothers dengan enteng.
“The leader's first task is to be the trumpet that sounds a clear sound.” Demikian Peter F. Drucker pernah menulis. “Effective leadership – and again this is very old wisdom – is not based on being clever; it is based primarily on being consistent,” lanjutnya.
Jelas, perilaku yang didemonstrasikan Fuld dan Willumstald itu, tak ayal mengundang kegeraman banyak pihak. “Mereka adalah teroris keuangan,” kata Max Keiser, kolomnis di Huffington Post, media online yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Wajar saja dia gusar. Keiser mewakili perasaan publik yang menyaksikan jutaan pekerjaan hilang dan kebanyakan tak pernah kembali. Begitu pula dengan triliunan dolar yang… wuzzz… menguap entah ke mana.
Alhasil, flawed leadership (kepemimpinan yang cacat), leadership malpractice adalah sinisme terhadap para business leader di Barat hari-hari ini. Mereka marah. Geram. Gusar.
Menariknya, di tengah sorotan demikian, kalangan sekolah bisnis pun tak luput dari sinisme. Banyak orang percaya bahwa pendidikan manajemen telah menyumbang pada kegagalan sistemik atas kepemimpinan bisnis yang mengantar ke krisis keuangan. Satu tulisan di Harvard Business Review (Juni 2009) mencatat dengan baik kejengkelan tersebut. Berjudul The Buck Stops (and Starts) at Business School, Joel M. Podolny mencatat bahwa dia marah karena tiadanya perhatian pada apa yang disebut ethics and value-based leadership di sekolah-sekolah bisnis.
Vice President Apple University in Cupertino, Kalifornia ini merespons sejumlah surat yang dimuat di New York Times, edisi 3 Maret 2009. Surat yang masuk itu membuat tekanan agar sekolah bisnis juga mengajarkan humanities. Mereka menyatakan bahwa dengan mempelajari seni, sejarah budaya, sastra, filsafat, dan juga agama, akan membuat orang mengembangkan daya nalar yang dipenuhi moralitas. Apa yang diajarkan sekolah bisnis masa kini adalah melahirkan pemimpin bisnis yang berpikir pendek, sekadar dimensi bisnis, dan mengambil keputusan hanya atas pertimbangan keuntungan. Bagi Podolny, seperti disinggung di atas, lebih tepatnya karena kurang aktifnya pengajaran perihal ethics and value-based leadership.
Gayung pun bersambut. Pemikiran tentang perlunya kurikulum Rethinking C-school demi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas secara intelektual-moral-spiritual memang dirasa semakin mendesak (BusinessWeek, 30 Juli 2009). Tak heran, sejak Agustus 2009, dunia sekolah bisnis di Barat mengalami banyak perubahan. Sejumlah kelas bukan lagi mengajarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi – berikut penyebab munculnya krisis – atau tentang manajemen risiko, tetapi juga menitikberatkan pada etika. Bahkan, pelajaran seputar hal tersebut diprediksi akan memainkan porsi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gonjang-ganjing yang menyoroti pemimpin bisnis, menariknya bukan cuma membuat kalangan sekolah bisnis “dihajar” habis-habisan. Yang cukup menggelitik, sejumlah pakar leadership pun kini kian mempertanyakan nilai-nilai kepemimpinan Barat yang dipandang tidak bisa menolong dari kondisi bisnis yang memburuk, malah membuat semakin parah.
Salah satu gerakan yang muncul adalah upaya melirik moral leadership dari Cina dan berharap ada sesuatu di sana yang bisa membantu dunia kepemimpinan dan bisnis secara keseluruhan dari nilai-nilai Konfusianisme. “Kerakusan eksekutif dan sistem keyakinan yang salah dalam sistem kapitalisme modern membuat ini terjadi. Barat telah kehilangan basis moralnya,” sebagaimana dikutip BusinessWeek (15 Mei 2009).
Faktanya, pemerhati kepemimpinan dan para profesional Cina itu sendiri kini memang tengah aktif-aktifnya menggali nilai kepemimpinan bisnis dari nilai tradisional mereka. Mereka yang ada di pusat bisnis seperti Shanghai dan Beijing, disebut-sebut semakin tidak percaya nilai kepemimpinan Barat yang terbukti berkali-kali memunculkan krisis dan skandal. Bahkan, seperti juga gugatan yang muncul di Barat, mereka mempertanyakan ajaran Adam Smith tentang the invisible hand di pasar, yang ternyata membuat para pemimpin pasar bertindak seliar-liarnya.
Pemerintah Cina sendiri, jauh sebelum krisis meledak, sudah mendorong kalangan swasta untuk mencari moral leadership dari leluhurnya. Tahun 2006, Pemerintah Cina mendorong digelarnya the World Buddhist Forum di Hangzhou yang salah satunya mencari nilai kepemimpinan bisnis. Selain dari Buddha, mereka juga mencari nilai-nilai dari Konfusianisme dan Taoisme untuk menjadi vitamin bagi kalangan pemimpin bisnis.
Konferensi itu akhirnya menetaskan Deklarasi Putuoshan. Bunyinya: “Setiap orang bertanggung jawab pada keharmonisan dunia, yang dimulai dari pikirannya.” Deklarasi itu benar-benar menohok. Meminta agar orang, terutama pemimpin bisnis, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga dunia global. Dan itu harus dimulai dari pikirannya.
Deklarasi itu muncul sebelum krisis meledak. Setelah krisis datang mengentak, keinginan untuk kian menggali nilai-nilai dari Cina, apakah Konfusius atau Tao, terus menggelinding. Percakapan di kalangan wirausaha Cina, pemimpin korporasi, dan akademisi mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar mencari kompas moral yang bisa digunakan di tengah kegaduhan nilai kepemimpinan Barat yang ternyata keropos. Mereka mencari nilai kepemimpinan yang telah tercerabut dari akar budaya mereka. Baik karena pengaruh revolusi kebudayaan Mao Zedong maupun hasil interaksi dengan Barat.
Dalam konteks pencarian ini, memang banyak kalangan yang meragukan apakah nilai kepemimpinan Cina sanggup mengatasi persoalan di dunia bisnis global. Mereka ragu bukan lantaran Cina baru tahap menjadi aktor ekonomi global. Mereka ragu dengan menyoroti bahwa negeri itu terhitung tempat berbisnis dengan sistem yang dikeluhkan masih kurang transparan dan nepotisme. Apa bisa negeri ini menawarkan sesuatu sementara sistem mereka sendiri juga bermasalah? Apa yang bisa diharapkan sementara pemerintah mereka masih kerja keras memberangus korupsi?
Keraguan yang masuk akal. Namun, yang meyakini pun tidak sedikit. Asumsinya, terlepas dari Pemerintah Cina sendiri menghadapi persoalan, nilai Konfusianisme dan Taoisme dapat diadopsi secara universal. Di antara nilai Konfusianisme yang kini relevan adalah unselfishness, careful thinking dan careful acting.
Terlepas dari pro dan kontra pencarian terhadap nilai kepemimpinan Cina, pesan yang sesungguhnya ditangkap dari gonjang-ganjing kepemimpinan global saat ini bahwa sesungguhnya nilai-nilai atau kebijakan lokal ada dalam setiap masyarakat, di mana pun di dunia ini. Terkait dengan Indonesia, kinilah saatnya kembali menggali nilai-nilai kepemimpinan yang sudah dimiliki, yang sesungguhnya sangat luhur bila diaplikasikan.
Teguh S. Pambudi
25 November 2008. Barbara Kellerman mengeluarkan catatan menarik dalam tulisannya, Leadership Malpractice. Pada tulisan yang dimuat di Harvard Business Online itu, pengajar Public Leadership di John F. Kennedy School of Government itu mencatat bahwa dalam 9 bulan pertama di tahun 2008, sedikitnya ada 1.132 CEO di sejumlah negara yang terpental dari posisinya, atau diminta untuk segera hengkang. Tekanan krisis membuat mereka rontok, atau dirontokkan karena dianggap menjadi orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya krisis finansial.
Angka yang dikutip Kellerman mungkin terbilang fantastis. Namun, Booz & Company, dalam surveinya yang dirilis 26 Mei 2009 mencatat bahwa turnover CEO memang meningkat: dari 13,8% menjadi 14,4% di tahun 2008. Dalam laporannya bertajuk CEO Succession 2008 itu, sedikitnya tercatat 361 suksesi di antara 2.500 perusahaan publik papan atas global di tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 180 CEO dilengserkan karena memang telah direncanakan sebelumnya (pensiun, sakit), 54 CEO diganti karena terjadi merger-akuisisi, dan hanya 127 orang yang dipaksa mundur karena kinerja yang buruk serta persoalan etika.
Sejak krisis finansial meledak, pembahasan tentang peran para leader di panggung bisnis global memang kian mengemuka. Umumnya mengerucut pada hal berikut: apa yang terjadi sehingga leader justru menjadikan kondisi memburuk? Tidakkah cukup kasus Enron dan WorldComm mengajarkan betapa leadership yang buruk membuat malapetaka besar?
“Ada ingredient yang hilang,” cetus Rick Wartzman, Direktur Drucker Institute at Claremont Graduate University. Menurut hematnya, dengan mengutip Drucker, the true leader adalah mereka yang membawa tanggung jawab, konsistensi, dan sense yang tajam untuk semua hal yang mereka lakukan. Apa yang terjadi di Wall Street yang kemudian mengguncang dunia, menurut Wartzman, menunjukkan mereka kehilangan itu semua. Sebagai leader, mereka yang mestinya penuh tanggung jawab dalam bertindak, justru dengan seenaknya berperilaku, mempermainkan kuasa yang mereka punya.
Yang membuat publik makin kesal, tulis Wartzman, sejumlah CEO sepertinya tidak mau disalahkan sekaligus menanggung beban atas ulahnya yang menjengkelkan itu. Mantan petinggi Lehman Brothers dan American International Group (AIG), ketika berbicara di Capitol Hill menuduh bahwa kekacauan finansial terjadi di luar diri dan institusi mereka. Dengan gagahnya, mereka justru menuding kalangan pasar modal, short-seller, juga regulator yang menimbulkan malapetaka ini semua. “Kalau melihat saat saya jadi CEO,” tukas Robert Willumstad, “saya tidak percaya AIG berbuat sesuatu yang aneh-aneh.” Begitu kata mantan CEO AIG ini. “Ya, kami sama-sama prudent,” tukas Richard Fuld, Chairman merangkap CEO Lehman Brothers dengan enteng.
“The leader's first task is to be the trumpet that sounds a clear sound.” Demikian Peter F. Drucker pernah menulis. “Effective leadership – and again this is very old wisdom – is not based on being clever; it is based primarily on being consistent,” lanjutnya.
Jelas, perilaku yang didemonstrasikan Fuld dan Willumstald itu, tak ayal mengundang kegeraman banyak pihak. “Mereka adalah teroris keuangan,” kata Max Keiser, kolomnis di Huffington Post, media online yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Wajar saja dia gusar. Keiser mewakili perasaan publik yang menyaksikan jutaan pekerjaan hilang dan kebanyakan tak pernah kembali. Begitu pula dengan triliunan dolar yang… wuzzz… menguap entah ke mana.
Alhasil, flawed leadership (kepemimpinan yang cacat), leadership malpractice adalah sinisme terhadap para business leader di Barat hari-hari ini. Mereka marah. Geram. Gusar.
Menariknya, di tengah sorotan demikian, kalangan sekolah bisnis pun tak luput dari sinisme. Banyak orang percaya bahwa pendidikan manajemen telah menyumbang pada kegagalan sistemik atas kepemimpinan bisnis yang mengantar ke krisis keuangan. Satu tulisan di Harvard Business Review (Juni 2009) mencatat dengan baik kejengkelan tersebut. Berjudul The Buck Stops (and Starts) at Business School, Joel M. Podolny mencatat bahwa dia marah karena tiadanya perhatian pada apa yang disebut ethics and value-based leadership di sekolah-sekolah bisnis.
Vice President Apple University in Cupertino, Kalifornia ini merespons sejumlah surat yang dimuat di New York Times, edisi 3 Maret 2009. Surat yang masuk itu membuat tekanan agar sekolah bisnis juga mengajarkan humanities. Mereka menyatakan bahwa dengan mempelajari seni, sejarah budaya, sastra, filsafat, dan juga agama, akan membuat orang mengembangkan daya nalar yang dipenuhi moralitas. Apa yang diajarkan sekolah bisnis masa kini adalah melahirkan pemimpin bisnis yang berpikir pendek, sekadar dimensi bisnis, dan mengambil keputusan hanya atas pertimbangan keuntungan. Bagi Podolny, seperti disinggung di atas, lebih tepatnya karena kurang aktifnya pengajaran perihal ethics and value-based leadership.
Gayung pun bersambut. Pemikiran tentang perlunya kurikulum Rethinking C-school demi menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas secara intelektual-moral-spiritual memang dirasa semakin mendesak (BusinessWeek, 30 Juli 2009). Tak heran, sejak Agustus 2009, dunia sekolah bisnis di Barat mengalami banyak perubahan. Sejumlah kelas bukan lagi mengajarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi – berikut penyebab munculnya krisis – atau tentang manajemen risiko, tetapi juga menitikberatkan pada etika. Bahkan, pelajaran seputar hal tersebut diprediksi akan memainkan porsi lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Gonjang-ganjing yang menyoroti pemimpin bisnis, menariknya bukan cuma membuat kalangan sekolah bisnis “dihajar” habis-habisan. Yang cukup menggelitik, sejumlah pakar leadership pun kini kian mempertanyakan nilai-nilai kepemimpinan Barat yang dipandang tidak bisa menolong dari kondisi bisnis yang memburuk, malah membuat semakin parah.
Salah satu gerakan yang muncul adalah upaya melirik moral leadership dari Cina dan berharap ada sesuatu di sana yang bisa membantu dunia kepemimpinan dan bisnis secara keseluruhan dari nilai-nilai Konfusianisme. “Kerakusan eksekutif dan sistem keyakinan yang salah dalam sistem kapitalisme modern membuat ini terjadi. Barat telah kehilangan basis moralnya,” sebagaimana dikutip BusinessWeek (15 Mei 2009).
Faktanya, pemerhati kepemimpinan dan para profesional Cina itu sendiri kini memang tengah aktif-aktifnya menggali nilai kepemimpinan bisnis dari nilai tradisional mereka. Mereka yang ada di pusat bisnis seperti Shanghai dan Beijing, disebut-sebut semakin tidak percaya nilai kepemimpinan Barat yang terbukti berkali-kali memunculkan krisis dan skandal. Bahkan, seperti juga gugatan yang muncul di Barat, mereka mempertanyakan ajaran Adam Smith tentang the invisible hand di pasar, yang ternyata membuat para pemimpin pasar bertindak seliar-liarnya.
Pemerintah Cina sendiri, jauh sebelum krisis meledak, sudah mendorong kalangan swasta untuk mencari moral leadership dari leluhurnya. Tahun 2006, Pemerintah Cina mendorong digelarnya the World Buddhist Forum di Hangzhou yang salah satunya mencari nilai kepemimpinan bisnis. Selain dari Buddha, mereka juga mencari nilai-nilai dari Konfusianisme dan Taoisme untuk menjadi vitamin bagi kalangan pemimpin bisnis.
Konferensi itu akhirnya menetaskan Deklarasi Putuoshan. Bunyinya: “Setiap orang bertanggung jawab pada keharmonisan dunia, yang dimulai dari pikirannya.” Deklarasi itu benar-benar menohok. Meminta agar orang, terutama pemimpin bisnis, tidak cuma memikirkan dirinya sendiri, melainkan juga dunia global. Dan itu harus dimulai dari pikirannya.
Deklarasi itu muncul sebelum krisis meledak. Setelah krisis datang mengentak, keinginan untuk kian menggali nilai-nilai dari Cina, apakah Konfusius atau Tao, terus menggelinding. Percakapan di kalangan wirausaha Cina, pemimpin korporasi, dan akademisi mengindikasikan bahwa mereka memang benar-benar mencari kompas moral yang bisa digunakan di tengah kegaduhan nilai kepemimpinan Barat yang ternyata keropos. Mereka mencari nilai kepemimpinan yang telah tercerabut dari akar budaya mereka. Baik karena pengaruh revolusi kebudayaan Mao Zedong maupun hasil interaksi dengan Barat.
Dalam konteks pencarian ini, memang banyak kalangan yang meragukan apakah nilai kepemimpinan Cina sanggup mengatasi persoalan di dunia bisnis global. Mereka ragu bukan lantaran Cina baru tahap menjadi aktor ekonomi global. Mereka ragu dengan menyoroti bahwa negeri itu terhitung tempat berbisnis dengan sistem yang dikeluhkan masih kurang transparan dan nepotisme. Apa bisa negeri ini menawarkan sesuatu sementara sistem mereka sendiri juga bermasalah? Apa yang bisa diharapkan sementara pemerintah mereka masih kerja keras memberangus korupsi?
Keraguan yang masuk akal. Namun, yang meyakini pun tidak sedikit. Asumsinya, terlepas dari Pemerintah Cina sendiri menghadapi persoalan, nilai Konfusianisme dan Taoisme dapat diadopsi secara universal. Di antara nilai Konfusianisme yang kini relevan adalah unselfishness, careful thinking dan careful acting.
Terlepas dari pro dan kontra pencarian terhadap nilai kepemimpinan Cina, pesan yang sesungguhnya ditangkap dari gonjang-ganjing kepemimpinan global saat ini bahwa sesungguhnya nilai-nilai atau kebijakan lokal ada dalam setiap masyarakat, di mana pun di dunia ini. Terkait dengan Indonesia, kinilah saatnya kembali menggali nilai-nilai kepemimpinan yang sudah dimiliki, yang sesungguhnya sangat luhur bila diaplikasikan.
Labels:
Leadership
Saturday, August 15, 2009
Bezos dan Revolusi Pasca-Guttenberg

Meski tak gegap gempita, kelahirannya memicu revolusi baru. Inilah produk digital yang diyakini membuat buku serta artefak cetak lainnya cepat atau lambat akan ke museum.
Teguh S. Pambudi
Sebagian kalangan menyebutnya “iPod of reading”. Dengan layar 9,7 inch, resolusi 1200 x 824 pixel, keyboard QWERTY di bagian bawah, dan 4 GB kapasitas penyimpanan yang bisa menampung hingga 3500 non-illustrated e-books, alat ini memang sungguh istimewa. Penggunanya bisa mengunduh buku, membaca surat kabar, majalah, blog, dan mengakses Internet. Hebatnya, semuanya dilakukan wirelessly dan tanpa terkoneksi ke komputer.
Kindle. Itulah namanya. Puja-puji kini mengalir deras untuknya. Orang terus membelinya. Dan sebagian pengamat meyakini sebuah revolusi budaya telah lahir tanpa gemuruh. Bahkan di Newsweek, Jacob Weisberg, editor-in-chief the Slate Group mengulas dengan setumpuk sanjung. “Jeff Bezos telah membuat mesin yang menandai sebuah revolusi budaya. Buku cetak, artefak yang paling paling penting dalam peradaban manusia, kini menyusul surat kabar dan majalah yang telah berada di sebuah jalan yang usang,“ katanya. Setahun terakhir, surat kabar dan majalah cetak memang deras bertumbangan. Economist bahkan meramal pada 2040, surat kabar serta majalah cetak tamat riwayatnya. Buah karya Guttenberg hanya tinggal cerita.
Jeff Bezos yang dimaksud Weisberg tentu saja sang pendiri, pemilik sekaligus CEO Amazon, ritel online terbesar di jagat raya. Kindle adalah software sekaligus hardware yang dikembangkan Bezos lewat anak usahanya, Lab126. Kindle pertama kali diluncurkan pada 19 November 2007, disusul Kindle 2 pada 23 Februari 2009. Teranyar, pada 10 Juni 2009, dirilis Kindle DX yang dipatok US$ 489 perbuah. Lebih mahal US$ 130 dibanding produk sebelumnya, produk terbaru ini dilengkapi accelerometer, yang secara otomatis bisa memutar halaman menjadi orientasi landscape atau portrait. Alat terbaru ini memiliki layar lebih besar ketimbang pendahulunya, mendukung format PDF, dan terasa lebih pas untuk membaca surat kabar, majalah dan isi buku teks.
Membaca buku, surat kabar dan majalah memang menjadi fitur utama yang ditawarkan Kindle. Siapapun yang memilikinya, dapat mengunduh isi dari situs Amazon serta sejumlah content providers yang menjadi mitra Amazon untuk kemudian membacanya. Pengguna juga dapat mengunduh di Kindle Store, yang sedikitnya menyediakan 300 ribu judul per Juli 2009. Harga buku yang ditawarkan bervariasi, tapi lebih murah dari versi cetak. Buku terbitan baru dan bestsellers dari New York Times di kisaran US$ 10. Novel On Beauty karya Zadie Smith, misalnya, dibandrol US$ 10,20 untuk edisi cetak, dan US$ 9,99 bagi yang ingin mengunduhnya.
Untuk membaca surat kabar, tarif langganannya antara US$ 5,99 hingga US$ 14,99 per bulan, sementara majalah antara US$ 1,25 - US$ 3,49 per bulan. Surat kabar yang ditawarkan adalah The New York Times, Wall Street Journal, dan Washington Post, adapun majalah yang tersedia diantaranya TIME, Atlantic Monthly, dan Forbes. Semuanya terkirim wirelessly. Surat kabar internasional juga tersedia seperti Le Monde, Frankfurter Allgemeine, dan The Irish Times. Kemudian, sedikitnya ada 5000 blog ternama yang membahas bisnis, teknologi, olahraga, hiburan, dan politik, diantaranya BoingBoing, Slashdot, TechCrunch, Bill Simmons, The Onion, Michelle Malkin, dan The Huffington Post. Bagi yang ingin terhubung dan terus up-date dengan blog yang dipilih, seseorang tinggal membayar US$ 0,99-US$ 1,99 perbulan.
Dengan fitur seperti itu, maka Kindle jelas membantah anggapan yang menilainya sebagai e-book reader. Bahkan dalam versinya yang pertama, produk ini sudah didedikasikan untuk membaca narasi dalam aneka bentuk yang panjang (long-form). Bukan sekedar e-book. Tapi, apapun anggapan yang beredar, satu pelajaran yang sangat penting dari produk ini adalah: keinginan para pemilik Kindle untuk membeli content secara harian menunjukkan bahwa "the business is news, not paper". "Saya tak ingin terlalu menyederhanakan apa yang terjadi di media. Tapi buat saya sangat sulit untuk percaya bahwa orang masih membaca surat kabar dalam bentuk cetak pada 10 tahun mendatang," kata Bezos.
Lelaki berkepala plontos itu sudah lama merancang produk yang kemudian dilabelinya Kindle. Sejak tahun 2000, lewat Amazon dia telah menawarkan beragam e-book untuk bisa dibaca di komputer. Hasilnya? Jauh dari harapan. “Tak banyak orang membeli e-book,” katanya. Waktu itu pergeseran ke halaman digital belum terjadi. Mengapa? “Karena buku masih sangat bagus,” jawabnya lagi.
Tak berputus asa, Bezos menarik para teknisi, termasuk Gregg Zehr – yang sebelumnya bekerja untuk Palm dan Apple –, dengan tugas mendesain software serta hardware untuk menghasilkan produk yang diidamkannya: mampu mengunduh buku, dan membaca surat kabar serta majalah.
Keputusan menarik para teknisi ini sangat diperlukan karena model bisnis yang akan dilakoni memerlukan seperangkat kompetensi baru. Sebagai pelaku ritel, Bezos sudah membuktikan kapasitasnya lewat Amazon yang telah menjadi hipermarket maya dengan kemampuan menjual aneka barang mulai dari buku hingga elektronik. Tapi sebagai manufaktur yang memproduksi sesuatu (create a thing), Bezos tak berpengalaman. Ada gap antara dunia ritel dan dunia manufaktur yang memproduksi sebuah benda. Gap yang mesti diisi para teknisi.
Selanjutnya, maka lahirlah Kindle. Namun Kindle versi pertama (sering disebut Kindle 1) tak memiliki banyak keistimewaan. Halaman bergerak perlahan diiringi layar yang kurang jernih. “Hal pertama untuk dicatat adalah layarnya tidak seperti membuat kita membaca kertas beneran,” kritik Joseph Weisenthal yang menulis di paidContent.org. “Tidak terang dan memantul jika ada cahaya yang langsung menyinarinya,” lanjutnya.
Banyak ulasan yang mengritiknya habis-habisan. Beruntung, Kindle 1 diapresiasi sang ratu talk show, Oprah Wifrey yang justru menyatakan bahwa dia terobsesi dengan alat ini. “It’s absolutely my new favorite, favorite thing in the world. It’s life-changing for me,” katanya. Bezos pun selamat.
Saat Kindle 1 meluncur, sebetulnya sudah ada produk yang mendahuluinya, Sony Reader. Begitu mengetahui kritik mengalir deras ke arah Kindle 1, Sony segera menggenjot produknya. Tapi malang, lantaran produknya tidak jauh lebih berkualitas, upaya raksasa Jepang itu menemui batu karang. Sebelum Natal 2007, meski diiringi kritikan di sana-sini, Kindle laris manis.
Meluncur lebih dulu dibanding Kindle, Sony Reader yang dibandrol US$ 279 memiliki kelemahan mendasar: menyaratkan penggunanya menghubungkan alat itu ke komputer saat ingin mengunduh buku. Wireless connectivity yang diberikan Amazon untuk para pemilik Kindle, membuat Sony Reader yang sebetulnya pioner langsung terlihat ketinggalan jaman, tampak menjadi produk usang.
Toh kemenangan atas Sony tak membuat Bezos berpuas diri. Apalagi kritik terhadap Kindle 1 membuat matanya terbuka betapa produknya masih menyimpan banyak persoalan. Lantaran itulah dia memacu inovasi-inovasi baru yang kemudian diwujudkan lewat Kindle 2 dan Kindle DX yang lebih berkualitas.
Dan faktanya, pasar mengapresiasi revolusi pasca Guttenberg ini dengan baik. Citigroup melaporkan penjualan Kindle telah tembus 500 ribu unit. Saking suksesnya, Barclays Capital memprediksi nilai penjualan produk ini mencapai US$ 3,7 miliar pada tahun 2012 dan memberi laba bersih sedikitnya US$ 840 juta. Nilai itu berarti hampir 20% dari total penjualan dan laba Amazon saat ini. Dengan kinerja yang ada, tak mengherankan bila Bezos menulis kepada para pemegang sahamnya dengan nada penuh kebanggaan: “Kindle sales have exceeded our most optimistic expectations.”
Pasar bukan hanya mengapresiasi dengan baik. Kindle bahkan telah melahirkan banyak orang yang kesengsem dengannya sehingga mengatakan “I love my Kindle”, dan menuliskannya di situs Amazon. “If I dropped my Kindle down a sewer, I would buy another one immediately,” ujar pemilik yang lain. Kepada mereka dan para pengguna Kindle, Bezos selalu menyapa begitu produk ini dihidupkan. “Kindle is an entirely new type of device, and we’re excited to have you as an early customer!”
Banyak kalangan melihat Bezos berada pada posisi yang tepat untuk meraup sukses dari penjualan alat yang spektakuler ini. Sebab, sebagai hipermarket online terbesar, khususnya yang menjual buku, dia memiliki keunggulan dibanding Sony yang sekedar menjual produk elektronik. Lewat Kindle, Bezos telah mengikat para pengunjung dan pembeli buku di Amazon dalam satu wadah.
Namun, lazimnya bisnis, kesuksesan selalu mengundang perusahaan lain menirukan langkah serupa. Kesuksesan Kinde bukan hanya memicu Sony memperbaiki produknya, tapi juga melahirkan pemain-pemain baru. Yang akan segera terjun adalah penerbit Hearst, Hewlett-Packard, demikian juga Apple yang dikabarkan tertarik memasuki pasar sejenis. Dan bila mereka benar-benar merealisasikannya, maka sayonara pantas untuk diucapkan pada buah karya Guttenberg.
Sementara menunggu itu terjadi, masyarakat dunia layak berharap semoga Kindle yang kini baru bisa dinikmati sebatas di AS, akan segera melebarkan pasarnya ke seluruh penjuru bumi.
Labels:
Technopreneur
Saturday, June 6, 2009
Menggenjot Agrobisnis, Mengamankan Masa Depan
Sejumlah negara intensif memajukan agrobisnisnya. Beberapa diantaranya bahkan aktif mencari lahan serta medium investasi agrobisnis di mancanegara. Mereka bergerak sebelum terlambat.
Teguh S. Pambudi
Jangan pernah abaikan agrobisnis! Dan rasanya, Indonesia sebagai negara agraris memang harus lebih memperhatikan comparative advantage-nya sebagai negeri dengan tanah yang subur ini sebelum segalanya menjadi terlambat. Apa pasal?
Lima tahun terakhir ini, dunia menjadi saksi makin agresifnya Cina menggarap sektor agrobisnis di Afrika. Triliunan rupiah dikucurkan, ribuan tenaga ahli diterjunkan. Itulah yang dilakukan Negeri Tirai Bambu di Benua Hitam.
Agresifnya Cina makin terasa setelah China-Africa Summit digelar November 2006. Saat itu, di hadapan sejumlah pemerintahan negara di Afrika, Cina setuju membangun 10 pusat agribisnis di benua Afrika, yang tersebar di sejumlah negara. Setelah pertemuan itu, sejumlah pusat agribisnis pun dibangun. Pusat-pusat agribisnis ini fokus pada pemberian bantuan kepada petani lokal lewat bibit serta pelatihan untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas lahan.
Mengapa Cina demikian agresif?
Pergerakan Cina ke Benua Hitam tidaklah muncul begitu saja. Sejak tahun 1990-an, untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Cina mendorong warganegaranya, terutama BUMN-nya untuk berinvestasi mengembangkan agrobisnis di mancanegara.
Pemerintah Cina rupanya tak mau kembali mengalami nasib buruk. Kurun 1958-1961, sedikitnya 36 juta orang Cina meninggal lantaran kesulitan pangan. Membaca tanda-tanda jaman, mereka akan mengalami nasib yang sama bila tak mengambil tindakan antisipatif. Tanda-tanda jaman itu adalah: Cina yang menjadi rumah tempat bagi 22% populasi dunia, ternyata hanya 7% lahannya yang bisa ditanami. Seiring laju pembangunan industri, lahan itu bahkan kian menyempit. Menurut Departemen Pertanian Cina, negeri itu kehilangan 8,9 juta hektar antara 1995-2007, digunakan untuk fasilitas industri manufaktur. Tanpa tindakan cepat, malapetaka tinggal sepelembaran batu. Cina butuh food security. Apalagi secara global, pertambahan penduduk terus melaju sementara lahan kian menciut.
Untuk menakar “rakusnya” orang Cina, lihat contoh berikut: konsumsi daging orang Cina hanya sebesar 25 kg pertahun pada 1985. Dua dekade kemudian menjadi 52 kg/tahun, dan ditaksir mencapai 70kg/tahun di 2010. Selain daging, yang melaju cepat adalah konsumsi kentang, kacang kedelai, dan sereal, yang tumbuh 30% pada satu dekade terakhir. Khusus kacang kedelai, Cina adalah importir terbesar di dunia, mencapai US$ 2,6 miliar dari AS. Bagaimana dengan beras? Konsumsi beras justru menurun karena banyak orang Cina kian menyukai diet ala Barat.
Didorong kebijakan berinvestasi di mancanegara, awalnya banyak dana investasi mengalir ke negara-negara terdekat seperti Laos, Burma dan Kamboja. Namun, lantaran ancaman instabilitas politik di negara-negara Indo-China tersebut, pemerintah Cina pun mengalihkan perhatian ke Afrika. Maka mulailah invasi besar ke benua itu.
Investasi pertama Cina di sektor agribisnis Afrika adalah pada tahun 1995 ketika Zhongkan Farm, sebuah perusahaan swasta mengucurkan US$ 220 ribu di proyek peternakan di Zambia. Setelah itu, berduyun-duyun perusahaan Cina terutama BUMN mengikuti jejaknya. Hingga tahun 2007, sedikitnya mereka memiliki 63 proyek agrobisnis di Afrika pada beragam jenis: pertanian, perkebunan hingga peternakan. Lalu, sedikitnya 1.134 pakar agrikultura Cina membantu perkembangan agrobisnis Afrika sementara dana yang dikucurkan sudah melewati Rp 6 triliun.
Kebanyakan investasi berada di bagian selatan Afrika, Mozambique, Tanzania, Malawi dan Angola. Di satu negara, Cina bisa mengucurkan US$ 30 juta untuk menggenjot agrobisnis yang sangat tersebar: pertanian, produksi dan pengolahan ternak, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta komoditas lainnya.
Di Mozambique, umpamanya, Cina memordenisasi sektor agrobisnis negeri itu dengan menopang berdirinya Advance Crop Research Institute dan mendirikan sejumlah sekolah pertanian. Lebih dari 100 tenaga ahli didatangkan, termasuk tim dari Hunan Hybrid Rice Institute, lembaga penelitian papan atas di di dunia dalam urusan beras hibrida. Juga dibangun jaringan irigasi dan terusan yang menghubungkan Malawi dengan Mozambique.
Saking bergairahnya Cina, banyak anggapan muncul di media internasional yang mengatakan bahwa Afrika adalah “mangkuk makanan” baru bagi Negeri Tirai Bambu. Dan bagi yang tidak menyukai langkah-langkah itu, mereka mengritik apa yang dilakukan merupakan bentuk kolonialisasi terhadap negara-negara Afrika yang didasarkan pada kepentingan sendiri semata.
Tentu saja menjadi hak setiap negara mengamankan kepentingannya di sektor pangan. Dan pemerintah Cina terbilang berpandangan ke depan. Menyadari tak bisa sepenuhnya bergantung pada investasi di mancanegara, mereka tetap tak melupakan domestik kendati lahan terus menyusut. Mei 2009, Deputi Menteri Pertanian Cina, Niu Dun menyatakan bahwa pemerintahnya juga berupaya memaksimalkan tanah mereka sendiri untuk mempertahankan food self-sufficiency yang pada akhirnya mengantar pada food security. Keputusan ini dibuat karena mereka tak ingin dan tak bisa bergantung pada di negeri seberang. Apalagi Afrika adalah benua yang boleh dikata tidak sestabil Eropa dalam konteks sosial-politik.
Faktanya, sekalipun lahan terus menciut, pemerintah Cina terus menggenjot produk hortikultura, peternakan, serta aquaculture. Dan mereka terbilang sukses. Negeri ini adalah produsen dan eksportir produk aquaculture dengan keuntungan melebihi US$ 10 miliar pada 2007. Lalu, beberapa contoh sukses lain: nilai ekspor jus apel ke AS meningkat dari US$ 1 juta di awal 1990-an menjadi US$ 108 juta di kurun 2002-2004, dan telah menggantikan AS sebagai eksportir jus apel terbesar ke Jepang pada tahun 2006. Untuk sayur-sayuran, Cina juga telah bersaing dengan produk AS menembus pasar Jepang.
Cina sadar agrobisnis adalah salah satu pusaran bisnis masa depan di samping energi. Namun, bukan hanya mereka yang sadar atas hal tersebut. Bukan hanya Cina yang berusaha melebarkan sayap ke mancanegara, mencari lahan-lahan kosong. Negeri Timur-Tengah dan Afrika Utara juga menyadari arti penting agrobisnis. Libya akan mengarap jagung di Ukraina, sementara Arab Saudi sudah menyatakan akan menggelontorkan uang untuk proyek-proyek agrobisnis di mancanegara guna security food sekaligus turut mengontrol harga komoditas di dunia.
Qatar juga tak mau kalah. Negara ini telah menginvestasikan US$ 200 juta di Kamboja untuk membangun infrastruktur buat pertanian. Terang-terangan, pemerintah Qatar mengutarakan ingin mengamankan pasokan pangan di masa mendatang.
Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara Timur-Tengah memang rentan terhadap pasokan pangan dan menjadi sasaran mereka yang kuat di agrobisnis. Salah satu negara yang aktif menggarap kawasan ini adalah Brazil. Ekspor Negeri Samba ke negara-negara Arab pada tahun 2008 mencapai US$ 6 miliar, tumbuh 30% dibanding tahun 2007. Saudi Arabia, Mesir, United Arab Emirates, Aljazair dan Maroko. Produk-produk yang dikapalkan ke negeri-negeri itu diantaranya adalah ayam, sapi, gula, jagung, dan kopi.
Di tengah meningkatnya kesadaran atas food security di banyak negara, salah satu yang cukup menonjol memang Brazil. Ia sungguh terus menjelma menjadi pemain penting. Media di AS bahkan menyebutnya “the new food superpower”. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, air yang berlimpah, dan lahan yang luas, Brazil tengah menuju apa yang disebut “the next great global breadbasket”. "Brazil dapat menjadi nomor wahid dalam produksi agrikultur. Kami akan melewati AS,” tegas André Nassar, ekonomis di São Paulo.
Para pelaku agrobisnis AS memandang Brazil dengan perasaan campur aduk: cemas, takut, kagum, dan tergoda untuk bekerja sama. Faktanya, banyak dari mereka yang memilih untuk bergandengan tangan. Pelaku-pelaku agrobisnis Negeri Abang Sam mengalir ke lembah-lembah Brazil untuk berinvestasi sebanyak mungkin. Dan mereka menemukan realita betapa luasnya negeri ini. Sementara mereka di AS kadang mengelola lahan 600-800 hektar, sementara para peternak di Brazil mengelola lahan 8000 hektar.
Tak usah jauh-jauh ke Brazil yang agrobisnisnya aktif didorong pemerintah. Negeri tetangga kita, Thailand juga aktif menggenjot sektor agrobisnisnya. Mei lalu, pemerintah Thailand mengumumkan akan menggelar serangkaian agricultural roadshows di Cina belahan utara untuk mengakselerasi ekspor agrobisnis Negeri Gajah Putih. Lima kunjungan digelar di Tianjin, Beijing, Dalian, Shenyang dan Xi'an dari 6-15 Juni 2009. Ekspor ke Cina, kata Menteri Perdagangan Thailand, Porntiva Nakasai sangat menguntungkan. Ekspor agrobisnis (agrikultur, peternakan, dan perikanan) ke Cina mencapai US$ 4,2 miliar kurun Januari-April 2009, turun 23,9% dari US$ 5,5 miliar di periode yang sama tahun 2008.
“China adalah pasar dengan daya beli yang tinggi,” ujar Porntiva. “Kami berharap roadshow yang menampilkan produk agrikultur dan buah-buahan akan mendongkrak penjualan,” tandas wanita ini. Buah-buahan utama yang digenjot adalah mangga dan durian yang memang sangat terkenal (siapa tak tahu durian monthong?). Tahun lalu, total ekspor produk agro Thailand mencapai US$ 177,8 miliar, naik 15,6% dibanding catatan tahun 2007. Khusus Cina, produk yang laris dari Thailand adalah buah-buahan segar dan dikalengkan, serta ikan (beku dan segar).
Seraya menggelar roadshow, pemerintah Thailand juga memfasilitasi salah satu perusahaan papan atas nasionalnya, Charoen Pokphand Group agar bisa melakukan Thai Fruit Festival di Shanghai pada 14 Mei hingga 17 Juni 2009. Festival ini dilakukan Charoen agar masyarakat Cina kian aware atas keragaman buah-buahan Thailand. Dan sejauh ini, festival tersebut sukses. Shanghai Kinghill, operator supermarket Lotus di Cina menjajakan buah-buahan Thailand di 78 outletnya. Seluruh rangkaian promosi ini, menurut Menteri Perdagangan Thailand merupakan upaya mereka yang ingin menjadikan negerinya, ”the kitchen of the world''.
Langkah-langkah pemerintah tersebut memang belum menghasilkan para pemain dari negaranya masing-masing yang sudah sebesar para pemain agrobisnis papan atas dunia seperti Archer Daniels Midland, Cargill, Bunge, Monsanto, Dupont Agriculture and Nutrition, Potash Corporation, serta Mosaic. Namun setidaknya mereka telah menunjukkan betapa pentingnya agrobisnis. Dan Indonesia jelas tak boleh kalah dari mereka. Potensi negeri ini terlalu besar untuk didiamkan.
Teguh S. Pambudi
Jangan pernah abaikan agrobisnis! Dan rasanya, Indonesia sebagai negara agraris memang harus lebih memperhatikan comparative advantage-nya sebagai negeri dengan tanah yang subur ini sebelum segalanya menjadi terlambat. Apa pasal?
Lima tahun terakhir ini, dunia menjadi saksi makin agresifnya Cina menggarap sektor agrobisnis di Afrika. Triliunan rupiah dikucurkan, ribuan tenaga ahli diterjunkan. Itulah yang dilakukan Negeri Tirai Bambu di Benua Hitam.
Agresifnya Cina makin terasa setelah China-Africa Summit digelar November 2006. Saat itu, di hadapan sejumlah pemerintahan negara di Afrika, Cina setuju membangun 10 pusat agribisnis di benua Afrika, yang tersebar di sejumlah negara. Setelah pertemuan itu, sejumlah pusat agribisnis pun dibangun. Pusat-pusat agribisnis ini fokus pada pemberian bantuan kepada petani lokal lewat bibit serta pelatihan untuk meningkatkan hasil panen dan kualitas lahan.
Mengapa Cina demikian agresif?
Pergerakan Cina ke Benua Hitam tidaklah muncul begitu saja. Sejak tahun 1990-an, untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Cina mendorong warganegaranya, terutama BUMN-nya untuk berinvestasi mengembangkan agrobisnis di mancanegara.
Pemerintah Cina rupanya tak mau kembali mengalami nasib buruk. Kurun 1958-1961, sedikitnya 36 juta orang Cina meninggal lantaran kesulitan pangan. Membaca tanda-tanda jaman, mereka akan mengalami nasib yang sama bila tak mengambil tindakan antisipatif. Tanda-tanda jaman itu adalah: Cina yang menjadi rumah tempat bagi 22% populasi dunia, ternyata hanya 7% lahannya yang bisa ditanami. Seiring laju pembangunan industri, lahan itu bahkan kian menyempit. Menurut Departemen Pertanian Cina, negeri itu kehilangan 8,9 juta hektar antara 1995-2007, digunakan untuk fasilitas industri manufaktur. Tanpa tindakan cepat, malapetaka tinggal sepelembaran batu. Cina butuh food security. Apalagi secara global, pertambahan penduduk terus melaju sementara lahan kian menciut.
Untuk menakar “rakusnya” orang Cina, lihat contoh berikut: konsumsi daging orang Cina hanya sebesar 25 kg pertahun pada 1985. Dua dekade kemudian menjadi 52 kg/tahun, dan ditaksir mencapai 70kg/tahun di 2010. Selain daging, yang melaju cepat adalah konsumsi kentang, kacang kedelai, dan sereal, yang tumbuh 30% pada satu dekade terakhir. Khusus kacang kedelai, Cina adalah importir terbesar di dunia, mencapai US$ 2,6 miliar dari AS. Bagaimana dengan beras? Konsumsi beras justru menurun karena banyak orang Cina kian menyukai diet ala Barat.
Didorong kebijakan berinvestasi di mancanegara, awalnya banyak dana investasi mengalir ke negara-negara terdekat seperti Laos, Burma dan Kamboja. Namun, lantaran ancaman instabilitas politik di negara-negara Indo-China tersebut, pemerintah Cina pun mengalihkan perhatian ke Afrika. Maka mulailah invasi besar ke benua itu.
Investasi pertama Cina di sektor agribisnis Afrika adalah pada tahun 1995 ketika Zhongkan Farm, sebuah perusahaan swasta mengucurkan US$ 220 ribu di proyek peternakan di Zambia. Setelah itu, berduyun-duyun perusahaan Cina terutama BUMN mengikuti jejaknya. Hingga tahun 2007, sedikitnya mereka memiliki 63 proyek agrobisnis di Afrika pada beragam jenis: pertanian, perkebunan hingga peternakan. Lalu, sedikitnya 1.134 pakar agrikultura Cina membantu perkembangan agrobisnis Afrika sementara dana yang dikucurkan sudah melewati Rp 6 triliun.
Kebanyakan investasi berada di bagian selatan Afrika, Mozambique, Tanzania, Malawi dan Angola. Di satu negara, Cina bisa mengucurkan US$ 30 juta untuk menggenjot agrobisnis yang sangat tersebar: pertanian, produksi dan pengolahan ternak, buah-buahan dan sayur-sayuran, serta komoditas lainnya.
Di Mozambique, umpamanya, Cina memordenisasi sektor agrobisnis negeri itu dengan menopang berdirinya Advance Crop Research Institute dan mendirikan sejumlah sekolah pertanian. Lebih dari 100 tenaga ahli didatangkan, termasuk tim dari Hunan Hybrid Rice Institute, lembaga penelitian papan atas di di dunia dalam urusan beras hibrida. Juga dibangun jaringan irigasi dan terusan yang menghubungkan Malawi dengan Mozambique.
Saking bergairahnya Cina, banyak anggapan muncul di media internasional yang mengatakan bahwa Afrika adalah “mangkuk makanan” baru bagi Negeri Tirai Bambu. Dan bagi yang tidak menyukai langkah-langkah itu, mereka mengritik apa yang dilakukan merupakan bentuk kolonialisasi terhadap negara-negara Afrika yang didasarkan pada kepentingan sendiri semata.
Tentu saja menjadi hak setiap negara mengamankan kepentingannya di sektor pangan. Dan pemerintah Cina terbilang berpandangan ke depan. Menyadari tak bisa sepenuhnya bergantung pada investasi di mancanegara, mereka tetap tak melupakan domestik kendati lahan terus menyusut. Mei 2009, Deputi Menteri Pertanian Cina, Niu Dun menyatakan bahwa pemerintahnya juga berupaya memaksimalkan tanah mereka sendiri untuk mempertahankan food self-sufficiency yang pada akhirnya mengantar pada food security. Keputusan ini dibuat karena mereka tak ingin dan tak bisa bergantung pada di negeri seberang. Apalagi Afrika adalah benua yang boleh dikata tidak sestabil Eropa dalam konteks sosial-politik.
Faktanya, sekalipun lahan terus menciut, pemerintah Cina terus menggenjot produk hortikultura, peternakan, serta aquaculture. Dan mereka terbilang sukses. Negeri ini adalah produsen dan eksportir produk aquaculture dengan keuntungan melebihi US$ 10 miliar pada 2007. Lalu, beberapa contoh sukses lain: nilai ekspor jus apel ke AS meningkat dari US$ 1 juta di awal 1990-an menjadi US$ 108 juta di kurun 2002-2004, dan telah menggantikan AS sebagai eksportir jus apel terbesar ke Jepang pada tahun 2006. Untuk sayur-sayuran, Cina juga telah bersaing dengan produk AS menembus pasar Jepang.
Cina sadar agrobisnis adalah salah satu pusaran bisnis masa depan di samping energi. Namun, bukan hanya mereka yang sadar atas hal tersebut. Bukan hanya Cina yang berusaha melebarkan sayap ke mancanegara, mencari lahan-lahan kosong. Negeri Timur-Tengah dan Afrika Utara juga menyadari arti penting agrobisnis. Libya akan mengarap jagung di Ukraina, sementara Arab Saudi sudah menyatakan akan menggelontorkan uang untuk proyek-proyek agrobisnis di mancanegara guna security food sekaligus turut mengontrol harga komoditas di dunia.
Qatar juga tak mau kalah. Negara ini telah menginvestasikan US$ 200 juta di Kamboja untuk membangun infrastruktur buat pertanian. Terang-terangan, pemerintah Qatar mengutarakan ingin mengamankan pasokan pangan di masa mendatang.
Qatar, Arab Saudi, dan negara-negara Timur-Tengah memang rentan terhadap pasokan pangan dan menjadi sasaran mereka yang kuat di agrobisnis. Salah satu negara yang aktif menggarap kawasan ini adalah Brazil. Ekspor Negeri Samba ke negara-negara Arab pada tahun 2008 mencapai US$ 6 miliar, tumbuh 30% dibanding tahun 2007. Saudi Arabia, Mesir, United Arab Emirates, Aljazair dan Maroko. Produk-produk yang dikapalkan ke negeri-negeri itu diantaranya adalah ayam, sapi, gula, jagung, dan kopi.
Di tengah meningkatnya kesadaran atas food security di banyak negara, salah satu yang cukup menonjol memang Brazil. Ia sungguh terus menjelma menjadi pemain penting. Media di AS bahkan menyebutnya “the new food superpower”. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, air yang berlimpah, dan lahan yang luas, Brazil tengah menuju apa yang disebut “the next great global breadbasket”. "Brazil dapat menjadi nomor wahid dalam produksi agrikultur. Kami akan melewati AS,” tegas André Nassar, ekonomis di São Paulo.
Para pelaku agrobisnis AS memandang Brazil dengan perasaan campur aduk: cemas, takut, kagum, dan tergoda untuk bekerja sama. Faktanya, banyak dari mereka yang memilih untuk bergandengan tangan. Pelaku-pelaku agrobisnis Negeri Abang Sam mengalir ke lembah-lembah Brazil untuk berinvestasi sebanyak mungkin. Dan mereka menemukan realita betapa luasnya negeri ini. Sementara mereka di AS kadang mengelola lahan 600-800 hektar, sementara para peternak di Brazil mengelola lahan 8000 hektar.
Tak usah jauh-jauh ke Brazil yang agrobisnisnya aktif didorong pemerintah. Negeri tetangga kita, Thailand juga aktif menggenjot sektor agrobisnisnya. Mei lalu, pemerintah Thailand mengumumkan akan menggelar serangkaian agricultural roadshows di Cina belahan utara untuk mengakselerasi ekspor agrobisnis Negeri Gajah Putih. Lima kunjungan digelar di Tianjin, Beijing, Dalian, Shenyang dan Xi'an dari 6-15 Juni 2009. Ekspor ke Cina, kata Menteri Perdagangan Thailand, Porntiva Nakasai sangat menguntungkan. Ekspor agrobisnis (agrikultur, peternakan, dan perikanan) ke Cina mencapai US$ 4,2 miliar kurun Januari-April 2009, turun 23,9% dari US$ 5,5 miliar di periode yang sama tahun 2008.
“China adalah pasar dengan daya beli yang tinggi,” ujar Porntiva. “Kami berharap roadshow yang menampilkan produk agrikultur dan buah-buahan akan mendongkrak penjualan,” tandas wanita ini. Buah-buahan utama yang digenjot adalah mangga dan durian yang memang sangat terkenal (siapa tak tahu durian monthong?). Tahun lalu, total ekspor produk agro Thailand mencapai US$ 177,8 miliar, naik 15,6% dibanding catatan tahun 2007. Khusus Cina, produk yang laris dari Thailand adalah buah-buahan segar dan dikalengkan, serta ikan (beku dan segar).
Seraya menggelar roadshow, pemerintah Thailand juga memfasilitasi salah satu perusahaan papan atas nasionalnya, Charoen Pokphand Group agar bisa melakukan Thai Fruit Festival di Shanghai pada 14 Mei hingga 17 Juni 2009. Festival ini dilakukan Charoen agar masyarakat Cina kian aware atas keragaman buah-buahan Thailand. Dan sejauh ini, festival tersebut sukses. Shanghai Kinghill, operator supermarket Lotus di Cina menjajakan buah-buahan Thailand di 78 outletnya. Seluruh rangkaian promosi ini, menurut Menteri Perdagangan Thailand merupakan upaya mereka yang ingin menjadikan negerinya, ”the kitchen of the world''.
Langkah-langkah pemerintah tersebut memang belum menghasilkan para pemain dari negaranya masing-masing yang sudah sebesar para pemain agrobisnis papan atas dunia seperti Archer Daniels Midland, Cargill, Bunge, Monsanto, Dupont Agriculture and Nutrition, Potash Corporation, serta Mosaic. Namun setidaknya mereka telah menunjukkan betapa pentingnya agrobisnis. Dan Indonesia jelas tak boleh kalah dari mereka. Potensi negeri ini terlalu besar untuk didiamkan.
Labels:
Macroeco
Friday, May 22, 2009
Agar Dompet Republik Seperti Dubai
Potensinya yang hebat seharusnya bisa membuatnya seperti Dubai. Apa saja langkah yang bisa dilakukan agar membuatnya kian berkembang?
Teguh S. Pambudi
Kalimantan Timur sebagai provinsi terkaya di Tanah Air, kiranya tak bisa didebat lagi. Bahkan, “Dompet Republik ini ada di Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak. Pernyataan Gubernur Kaltim ini, pastinya bukan seloroh di siang bolong. Pada 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai Rp 315,02 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,82%. Provinsi yang luasnya 1,5 kali Jawa itu (198.441,17 km2) memang aduhai. “Dompet republik” itu menyetor ke kas negara mencapai Rp 212 triliun setiap tahunnya. Luar biasa!
Hanya saja, karena sky is the limit, maka orang pun boleh bertanya dan berandai-andai: apakah Kaltim bisa bergerak lebih hebat lagi? Seperti Dubai, misalnya. Atau, Singapura. Dan kalau memang ingin seperti itu, bagaimana caranya?
Bicara potensi, Bambang PS Brodjonegoro, ahli otonomi daerah dan guru besar Universitas Indonesia, mengakui bahwa provinsi yang beribukota di Samarinda ini memiliki potensi paling besar di Indonesia. “Bisa dilihat dengan melimpahnya tambang batu bara, minyak dan gas bumi, hingga hasil hutan,” katanya. Kontribusi terbesar PDRB memang berasal dari sektor pertambangan, yakni sebesar 44,16%. Tapi, Kaltim juga memiliki areal perhutanan yang sangat luas, mencapai 21,14 juta ha. Untuk membuat Kaltim yang lebih hebat dari sekarang, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konteks pembangunan wilayah ini. “Mau diarahkan ke mana? Apakah hanya bisa memanfaatkan uang dari SDA yang ada, atau mengolah SDA tersebut?,” tandas Bambang. Menurutnya, hal ini akan sangat menentukan masa depan Kaltim.
Faroek punya jawaban akan ke mana provinsi yang dipimpinnya bergerak. Tapi, lontaran Bambang adalah contoh dari kritik yang memang mengalir menyoroti bagaimana Kaltim berjalan sejauh ini.
Kaltim yang sekarang berderap, kendati penuh puji, juga dilumuri masalah. Pasalnya, di balik kemilau angka-angka kehebatannya, tersimpan kepiluan. Data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa dari sekitar 3,1 juta jiwa dan dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 26,69 juta, jumlah penduduk miskin di provinsi kaya raya itu mencapai 324.800 jiwa. Dari data tersebut, Kutai Kartanagara ada di posisi pertama dengan 63.500 jiwa, lalu Samarinda (38.200), diikuti Kutai Timur (31.700). Tiga provinsi itu adalah sumbu-sumbu pertumbuhan.
Ada banyak analisis yang mencoba mengurai hal ini. Pendekatan capital investment menyatakan bahwa Kaltim kekurangan investasi untuk membangun dirinya. Dengan kontribusi sebesar Rp 212 triliun kepada negara, yang diterima provinsi itu hanya Rp 24 triliun sebagai modal pembangunan. Kaltim benar-benar termehek-mehek untuk menggenjot pembangunan. Akibatnya, infrastruktur pun terseok-seok. Bukan hanya jalan yang buruk, pemadaman listrik menjadi menu biasa. Maklum, pembangkit listrik di provinsi ini umumnya sudah berusia lanjut: 15-25 tahun, sehingga acap melakukan pemadaman bergilir lantaran daya dukung yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Faroek serta pejabat eksekutif Kaltim lainnya sering menyuarakan “ketidakadilan” ini: menyumbang banyak, tapi menerima sedikit. Koor yang juga kerap terlantun dari lembaga legislatif provinsi itu.
Sementara itu, pendekatan competitive strategy mengritik industri yang sementara ini muncul. Kaltim memang kaya sumber daya alam (SDA), atau biasa disebut resource-rich. Minyak, gas, batu bara merupakan komoditas yang membuat provinsi itu memiliki keunggulan komparatif dibanding provinsi yang tidak kaya SDA (resource-poor). Namun, industri yang ada baru tahap primary industry, tahap awal yang hanya mengambil kekayaan dari perut bumi untuk kemudian menjualnya. Belum dihasilkan industri-industri pengolah (smelter) yang akan mengubah kekayaan bumi menjadi aneka ragam produk turunan untuk dimanfaatkan industri di hilir. Dari hasil penjualan kekayaan alam inilah yang kemudian masuk ke kas Kaltim lewat aneka royalti, yang kemudian mengalir ke kas negara.
Industri pertambangan yang capital intensive ini, yang pandai mengekspor barang mentah ini, tidak terhubung (linked) dengan industri-industri lokal yang dibutuhkan masyarakat setempat. Industri energi ini tak bisa menjadi prime mover (penggerak mula) untuk mendukung industri-industri lainnya (industri pertanian, guna menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat; industri barang-barang modal seperti mesin; dan industri barang konsumsi). Padahal, kalau rantai industri ini terjadi, antara bagian hulu (primary product seperti pertambangan) dengan hilir (industri turunannya, termasuk industri lokal), maka akan tercipta multiplier effect yang besar. Kritik lain, Kaltim juga belum memaksimalkan potensi SDA dari sektor lain, seperti pertanian.
Sesungguhnya, pola di atas (hanya mengekspor barang mentah) juga berlaku di hampir seluruh provinsi di Tanah Air yang resource-rich. Di bagian hulu mengekspor untuk kemudian bagian hilir (industri-industri lokal) mengimpor dalam bentuk produk turunan yang harganya lebih mahal karena adanya penambahan nilai di dalamnya (value added). Sebuah rantai industri yang sungguh-sungguh pendek. Dan sesungguhnya, Indonesia sudah banyak kehilangan momentum karena primary product yang diekspor itu tidak akan pernah terbarukan lagi.
Faroek menyadari hal tersebut. Karena itulah dia berupaya membuat lompatan untuk provinsinya. Dan lantaran pertambangan adalah non renewable resources, dia akan merevitalisasi pertanian. “Kaltim harus menyiapkan lokomotif ekonomi yang baru,” katanya. Konkritnya, agribisnis akan menjadi tumpuan. Untuk itu, dia telah menyiapkan kebijakan pengembangan industri pertanian dengan konsep Integrated Agricultural Industrial Approach. Terdiri dari integrated farming, integrated rice processing, down stream industry, dan management and empowerment. “Kami akan memoles sektor ini agar investor semakin berdatangan,” tandasnya.
Untuk lahan pertanian, Kaltim memang memiliki banyak lahan potensial. Lahan sawah mencapai 205,100 ha dan bukan sawah 22,65 juta ha. Dari luas potensi lahan sawah tersebut, yang ditanami padi setahun dua kali mencapai 35,9 ribu ha dan ditanami sekali seluas 53,7 ribu ha. Sedangkan lahan yang tidak diusahakan seluas 104,265 ha, dan tidak ditanami seluas 25,2 ribu ha.
Sementara itu, Kaltim juga luar biasa. Ia memiliki potensi lahan kering seluas 5.324.488 ha yang terletak di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Dari jumlah itu, seluas 4,25 juta ha lahannya cocok untuk komoditi perkebunan (termasuk kelapa sawit). Hingga 2008, yang telah dimanfaatkan baru seluas 528.848 ha untuk pengembangan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao dan aneka tanaman lainnya. Sementara sisanya (3.73 juta ha), belum dikembangkan.
Selain cetak biru pertanian, Faroek juga tak meninggalkan industri energi, serta berupaya mengembangkan industri-industri lainnya. Dia membuat pembangunan kawasan industri di tiga area, meliputi; Bontang (Bontang Industri Estate), Banjarmasin, dan Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau).
Untuk menggenjot pengembangan industri itulah dia berupaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Sedikitnya, jalan sepanjang 1902 km akan dibangunnya di beberapa lokasi. Lalu, jalan kereta api, dan pelabuhan Maloy yang menjadi pusat keluarnya (outlet) crude palm oil (CPO) di Kalimantan. Tak lupa, dia juga akan memperlebar Bandara Sepinggan. Sebagai bandara tersibuk keempat di Indonesia, daya tampungnya sudah tidak memungkinkan. Landasan pacu (runway) akan direntang dari 2.500 m menjadi 3.100 m. Sepinggan terletak di Balikpapan yang terkenal sebagai kota bisnis. Di kota ini, bangunan-bangunan tinggi menjulang, berdampngan dengan hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel berbintang. Balikpapan adalah tempat perusahaan tambang besar berkantor seperti Pertamina, Total, Unocal dan Chevron.
Rencananya, seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi tolak punggung untuk transportasi hasil SDA, atau menghubungkan pusat pertumbuhan. Misalnya, rel yang menghubungkan Kutai Barat dan Balikpapan. Rel ini khusus untuk mengangkut batu bara, CPO, karet, kayu, dan dan cokelat.
Karena menggejot infrastruktur itu pula, Faroek berikhtiar menggaet dana, baik dari pemerintah pusat, maupun investor dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, diantaranya yang akan masuk adalah Ras-Al Khaimah, salah satu emirat dalam Uni Emirat Arab yang akan mengucurkan Rp 18 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Pertanyaannya: apakah langkah-langkah tersebut akan memadai, apalagi menopang menjadi seperti Dubai?
Sesungguhnya, dengan kekayaan potensi SDA yang luar biasa, Kaltim punya segalanya untuk melebihi Dubai, dan Singapura, dua negara kota (city state)yang luar biasa itu. Dubai tidak kaya akan SDA, sementara Singapura adalah benar-benar resource-poor yang pasir pun beli dari negara lain. Sejauh ini, langkah Kaltim untuk seperti Dubai – atau Singapura – bisa dikatakan sudah berada di jalurnya dengan berdirinya pusat-pusat pertumbuhan (growth area) di tiga kawasan industri (Bontang).
Namun, untuk menjadi seperti Dubai, sesungguhnya ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan. Pusat-pusat pertumbuhan di tiga kawasan industri itu, adalah semacam cluster, yang telah ditempuh Dubai – dan sebelumnya Singapura, juga Korea Selatan. Tapi, kritik yang sejauh ini meluncur adalah Faroek belum membuat industri yang terhubung satu sama lain, dan masih bertumpu pada energi. Di Bontang, misalnya, yang terbangun adalah lebih banyak industri kimia.
Dubai tumbuh dengan caranya tersendiri. Didukung stabilitas pemerintahan yang kuat, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mendirikan infrastruktur serta mengundang investor untuk menjadikan Dubai sebagai financial hub dan pusat industri manufaktur, sekaligus menyediakan properti serta tempat-tempat pariwisata sebagai wahana leisure, termasuk juga ajang pertandingan olahraga dunia. Al Maktoum bukan hanya mengundang pebisnis untuk datang, orang biasa pun diundangnya. Karena itu, kulturnya pun dibuat menjadi sangat fleksibel. “Semua orang ke Dubai karena di sana bebas. Semua orang merasa nyaman di sana. Orang bule juga bebas dan merasa nyaman. Orang berbikini dan yang pakai burqa bisa hidup berdampingan,” ujar Hermawan Kartajaya dari MarkPlus&Co. sambil tertawa.
Jelas tidaklah keliru bila Kaltim membuat industri yang memanfaatkan kekayaan SDA-nya. Namun, dengan kekayaan SDA-nya tersebut, sudah selayaknya provinsi ini tidak semata bergerak di fase primary dan menjualnya sebagai produk komoditas, tapi melangkah pada penciptaan industri-industri manufaktur serta industri pengolahan yang bisa memanfaatkan primary product (hasil tambang), baik dari Kaltim atau tetangganya di bumi Kalimantan, atau pulau-pulau kaya tambang terdekat seperti Sumatera, Sulawesi dan Irian. Faktor proximity (kedekatan) dengan lahan-lahan tambang sebagai bahan baku mestinya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan multiplier effect yang besar. Rantai industri di Kaltim mestinya bisa lebih panjang.
Tentang hal ini, Kaltim mestinya tak boleh kalah dari Dubai yang bahkan sudah membuat Dubai Alumunium. Ini merupakan smelter terbesar di dunia di luar Rusia yang memproduksi billet serta foundry alloy dengan kapasitas produksi 659 ribu ton setahun. Selain alumunium, Dubai Alumunium juga memproduksi baja sebanyak 400 ribu ton setahun yang dapat memenuhi 25% kebutuhan dalam negeri Uni Emirate Arab yang terus mengenjot sektor properti, dan sisanya diekspor ke seluruh dunia. Dari mana mereka mendapat bahan baku yang bisa diubah menjadi lebih dari 10 produk turunan itu? Jelas dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi penghasil timah nomor 2 di dunia. Kalau Dubai bisa, mengapa Kaltim tidak? Faroek bisa mengundang investor melakukan hal ini. Dia bisa memilih akan mengembang rantai industri yang feasible untuk Kaltim.
Intinya, Kaltim sudah sepatutnya membuat cluster yang di dalamnya menciptakan rantai industri yang panjang. Bukan yang rantainya pendek, menggali dari perut bumi lalu mengekspor dalam kondisi mentah. Dan tentang ini, Faroek, serta juga kepala daerah lain, punya legalitas kuat lewat UU Mineral Batu Bara No. 4/2009 yang baru disahkah Januari 2009 yang mewajibkan produsen bahan tambang mengolahnya lebih dahulu di dalam negeri. Dalam konteks membuat rantai industri yang lebih panjang, Faroek telah melangkah lebih maju dengan rencana membuat industri pengolahan kelapa sawit sehingga menghasilkan sejumlah produk turunan ketimbang hanya CPO. Dengan Kutai Timur sebagai pusat CPO di Kalimantan, ada 7 perusahaan nasional berminat untuk bekerja sama dalam pengembangan kelapa sawit di Kaltim.
Kaltim jelas bukan Dubai. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Tapi untuk urusan cara menjadi hebat, pembangunan berbasis SDA di Kaltim dengan rantai industri yang panjang akan lebih hebat juga bila ditunjang dengan pendekatan pembangunan berbasis SDM yang unggul. Dubai meniru Singapura dalam urusan mengumpulkan orang-orang terbaik – Singapura malah terhitung paling rakus mengumpulkan manusia terunggul di muka bumi dengan imbalan setinggi-tingginya. Untuk urusan ini, Kaltim termasuk sudah cukup bagus. Menurut Bambang PS Brodjonegoro, Kaltim termasuk lima besar jika dilihat dari indeks kualitas SDM di Indonesia. "Sudah punya modal manusianya, tinggal bagaimana mengoptimalkan termasuk tidak perlu segan-segan menarik orang dari daerah lain. Tidak mungkin berdiri sendiri karena butuh bantuan," ujar Bambang. Lantas, bagaimana rencana Faroek tentang hal ini?
“Saya mengundang profesional untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di Kaltim. Sebentar lagi akan ada iklan yang mengundang profesional untuk kerja di Kaltim. Ha… ha...,” jelas lelaki berambut putih ini.
Di luar pengembangan industri berbasis SDA dan SDM ini, belajar dari Dubai, aspek branding juga tak kalah penting bila ingin melesat. Untuk mem-branding-kan Kaltim, menurut Sumardy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari apa sebenarnya potensi utama Kaltim yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Potensi itu yang kemudian ditonjolkan untuk di-branding di dalam maupun di luar negeri. “Seperti kita lihat, di dekat Kalimantan ada Sulawesi, di mana Makassar tampak juga ingin menjadi daerah yang menjadi sentra pertumbuhan,” jelas pengamat pemasaran dari Octobrand. Artinya, Kaltim mesti piawai mencari positioning dalam konteks ini.
Last but not least, belajar dari Dubai – begitu juga Singapura – diperlukan konsistensi serta persistensi baik politik, sosial dan budaya untuk mengeksekusi seluruh rencana karena sesungguhnya mereka perlu waktu puluhan tahun hingga ke posisi sekarang. Tanpa hal-hal itu, “Dompet Republik” ini sulit untuk berkembang dan lebih hebat dari sekarang. ***
Boks
Dubai,
Buah Visi Para Pemimpin
Pada dekade 1990-an, ada tiga fastest growing cities di dunia, yakni Dublin, Las Vegas serta Dubai. Nama terakhir yang menyusul belakangan masuk di kategori itu, justru sekarang yang paling berkilau. Dubai yang merupakan salah satu dari 7 emirat di Uni Emirat Arab (UEA) kini menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah dengan perkembangan yang tak pernah terkira sebelumnya. Hari ini Dubai adalah trading, business and increasingly financial hub di Teluk Persia. Ia melampaui Abu Dhabi yang nota bene adalah ibu kota Kesultanan Teluk itu.
Sukses Dubai tak bisa dilepaskan dari kesolidan UEA. Sejak menyatakan menjadi satu negara hasil gabungan 7 emirat pada 1971, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan memimpin UEA relatif tanpa gejolak, dan terpenting, proaktif menggenjot pembangunan. Boom minyak membuat UEA dari desert kingdom menjadi modern metropolis. Sheikh Zayed sendiri adalah Emir Abu Dhabi, sahabat karib Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Emir Dubai. Sheikh Zayed menjadi Presiden UEA sejak 1971 hingga tahun wafatnya, 2004.
Sebagai penguasa Dubai, Sheikh Rashid membangun wilayahnya sejak ladang minyak ditemukan di daerah itu pada tahun 1966. Memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak, dia menggenjot pembangunan infrastruktur. Sejak awal 1967, dia mendorong pembangunan skala besar besaran meliputi bangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan telekomunikasi modern serta bandar udara internasional.
Sheikh Rashid mangkat pada tahun 1981. Setelah itu, tampuk Dubai dipegang anak sulungnya, Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Di tangannya, modernisasi Dubai terus dilanjutkan. Dubai kian dipoles. Dia mendorong Pemerintah Dubai dan keluarga-keluarga berpengaruh di wilayah itu untuk berinvestasi kepada infrastruktur serta merentang rencana-rencana yang ambisius. Kepemimpinan yang stabil, menurut para analis membuat keputusan bisa cepat diambil dalam membangun infrastruktur. Ada istilah yang mengatakan bahwa keputusan “Bangun di sana, bangun di sini” bisa dilakukan Sheikh Maktoum karena tiadanya tentangan.
Maka berdirilah bangunan-bangunan fenomenal seperti Burj Al Arab, Emirates Towers, Burj Dubai, dan Dubai International Airport yang dibangun senilai US$ 4,2 miliar. Terpenting dari itu adalah bangunan untuk menyedot korporasi serta investor kelas dunia seperti Dubai International Financial Centre serta Dubai Metals and Commodities Centre.
Visi Sheikh Maktoum memang menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan dan ekonomi dunia, juga pusat pariwisata. Agar pariwisata kian kencang, dia membuat kebijakan yang mengijinkan orang asing memiliki properti di Dubai. Maka berdirilah kawasan residensial Dubai Marina yang mewah, serta deretan pertokoan seperti Mall of the Emirates.
Namun, sang Sheikh pun bervisi ke luar. Karena itulah dia membangun apa yang sering disebut sebagai Dubai Inc. yang di dalamnya terdiri dari sejumlah perusahaan dalam 4 divisi. Dubai Holding menjadi induk dari Dubai Inc. Dalam naungannya berdiri: Jumeirah Group (membuat hotel), Dubai Property (membangun kota-kota baru), Media Properties (media), dan ujung tombak investasi mancanegara, Dubai International Capital. Diantara anak usaha yang terkenal adalah maskapai Emirates yang menandingi Singapore Airlines. Dan seperti halnya Temasek yang jadi jantung Singapore Inc., Dubai Inc. tak henti berekspansi ke tempat-tempat yang dianggap menguntungkan.
Wafat pada 2006, Sheikh Maktoum digantikan adiknya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang oleh pers Barat disebut Sheik Mo dan diyakini justru merupakan arsitek ekonomi Dubai yang sesungguhnya di balik sang kakak.
Apapun, Dubai kini terus berpendar. GDP-nya mencapai US$ 37 miliar pada tahun 2005, dan tumbuh double digit. Tahun 2008, GDP-nya tumbuh di kisaran 13-16%. Dengan portofolio bisnis yang ada, sumber-sumber pemasukan tidak lagi bertumpu pada minyak yang ditaksir akan sama sekali habis pada 20 tahun mendatang. Minyak dan gas hanya menyumbang 6%. Selebihnya datang dari perdagangan, real estate, jasa keuangan dan pariwisata. Setiap tahun, sedikitnya 7 juta pengunjung mampir ke Dubai, jauh melebihi warga Dubai yang kurang dari 2 juta jiwa.
“Perkembangan ekonomi Dubai yang luar biasa merupakan buah dari visi serta kebijakan progresif keluarga Al Maktoum yang fokus pada pertumbuhan,” ujar Mohamed Ali Alabbar, Dirjen Departemen Pengembangan Ekonomi Pemerintah Dubai, yang juga merangkap Chairman Emaar Properties.
Ya, sesungguhnya Dubai memang tidak dibangun dalam semalam. Ketika keluarga Al Maktoun mulai bermukim di Dubai pada 1883, daerah itu awalnya tempat perdagangan ikan, mutiara serta hasil laut lainnya.
Teguh S. Pambudi
Kalimantan Timur sebagai provinsi terkaya di Tanah Air, kiranya tak bisa didebat lagi. Bahkan, “Dompet Republik ini ada di Kaltim,” kata Awang Faroek Ishak. Pernyataan Gubernur Kaltim ini, pastinya bukan seloroh di siang bolong. Pada 2008 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim mencapai Rp 315,02 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,82%. Provinsi yang luasnya 1,5 kali Jawa itu (198.441,17 km2) memang aduhai. “Dompet republik” itu menyetor ke kas negara mencapai Rp 212 triliun setiap tahunnya. Luar biasa!
Hanya saja, karena sky is the limit, maka orang pun boleh bertanya dan berandai-andai: apakah Kaltim bisa bergerak lebih hebat lagi? Seperti Dubai, misalnya. Atau, Singapura. Dan kalau memang ingin seperti itu, bagaimana caranya?
Bicara potensi, Bambang PS Brodjonegoro, ahli otonomi daerah dan guru besar Universitas Indonesia, mengakui bahwa provinsi yang beribukota di Samarinda ini memiliki potensi paling besar di Indonesia. “Bisa dilihat dengan melimpahnya tambang batu bara, minyak dan gas bumi, hingga hasil hutan,” katanya. Kontribusi terbesar PDRB memang berasal dari sektor pertambangan, yakni sebesar 44,16%. Tapi, Kaltim juga memiliki areal perhutanan yang sangat luas, mencapai 21,14 juta ha. Untuk membuat Kaltim yang lebih hebat dari sekarang, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konteks pembangunan wilayah ini. “Mau diarahkan ke mana? Apakah hanya bisa memanfaatkan uang dari SDA yang ada, atau mengolah SDA tersebut?,” tandas Bambang. Menurutnya, hal ini akan sangat menentukan masa depan Kaltim.
Faroek punya jawaban akan ke mana provinsi yang dipimpinnya bergerak. Tapi, lontaran Bambang adalah contoh dari kritik yang memang mengalir menyoroti bagaimana Kaltim berjalan sejauh ini.
Kaltim yang sekarang berderap, kendati penuh puji, juga dilumuri masalah. Pasalnya, di balik kemilau angka-angka kehebatannya, tersimpan kepiluan. Data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan bahwa dari sekitar 3,1 juta jiwa dan dengan pendapatan per kapita mencapai Rp 26,69 juta, jumlah penduduk miskin di provinsi kaya raya itu mencapai 324.800 jiwa. Dari data tersebut, Kutai Kartanagara ada di posisi pertama dengan 63.500 jiwa, lalu Samarinda (38.200), diikuti Kutai Timur (31.700). Tiga provinsi itu adalah sumbu-sumbu pertumbuhan.
Ada banyak analisis yang mencoba mengurai hal ini. Pendekatan capital investment menyatakan bahwa Kaltim kekurangan investasi untuk membangun dirinya. Dengan kontribusi sebesar Rp 212 triliun kepada negara, yang diterima provinsi itu hanya Rp 24 triliun sebagai modal pembangunan. Kaltim benar-benar termehek-mehek untuk menggenjot pembangunan. Akibatnya, infrastruktur pun terseok-seok. Bukan hanya jalan yang buruk, pemadaman listrik menjadi menu biasa. Maklum, pembangkit listrik di provinsi ini umumnya sudah berusia lanjut: 15-25 tahun, sehingga acap melakukan pemadaman bergilir lantaran daya dukung yang tidak seimbang dengan kebutuhan. Faroek serta pejabat eksekutif Kaltim lainnya sering menyuarakan “ketidakadilan” ini: menyumbang banyak, tapi menerima sedikit. Koor yang juga kerap terlantun dari lembaga legislatif provinsi itu.
Sementara itu, pendekatan competitive strategy mengritik industri yang sementara ini muncul. Kaltim memang kaya sumber daya alam (SDA), atau biasa disebut resource-rich. Minyak, gas, batu bara merupakan komoditas yang membuat provinsi itu memiliki keunggulan komparatif dibanding provinsi yang tidak kaya SDA (resource-poor). Namun, industri yang ada baru tahap primary industry, tahap awal yang hanya mengambil kekayaan dari perut bumi untuk kemudian menjualnya. Belum dihasilkan industri-industri pengolah (smelter) yang akan mengubah kekayaan bumi menjadi aneka ragam produk turunan untuk dimanfaatkan industri di hilir. Dari hasil penjualan kekayaan alam inilah yang kemudian masuk ke kas Kaltim lewat aneka royalti, yang kemudian mengalir ke kas negara.
Industri pertambangan yang capital intensive ini, yang pandai mengekspor barang mentah ini, tidak terhubung (linked) dengan industri-industri lokal yang dibutuhkan masyarakat setempat. Industri energi ini tak bisa menjadi prime mover (penggerak mula) untuk mendukung industri-industri lainnya (industri pertanian, guna menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat; industri barang-barang modal seperti mesin; dan industri barang konsumsi). Padahal, kalau rantai industri ini terjadi, antara bagian hulu (primary product seperti pertambangan) dengan hilir (industri turunannya, termasuk industri lokal), maka akan tercipta multiplier effect yang besar. Kritik lain, Kaltim juga belum memaksimalkan potensi SDA dari sektor lain, seperti pertanian.
Sesungguhnya, pola di atas (hanya mengekspor barang mentah) juga berlaku di hampir seluruh provinsi di Tanah Air yang resource-rich. Di bagian hulu mengekspor untuk kemudian bagian hilir (industri-industri lokal) mengimpor dalam bentuk produk turunan yang harganya lebih mahal karena adanya penambahan nilai di dalamnya (value added). Sebuah rantai industri yang sungguh-sungguh pendek. Dan sesungguhnya, Indonesia sudah banyak kehilangan momentum karena primary product yang diekspor itu tidak akan pernah terbarukan lagi.
Faroek menyadari hal tersebut. Karena itulah dia berupaya membuat lompatan untuk provinsinya. Dan lantaran pertambangan adalah non renewable resources, dia akan merevitalisasi pertanian. “Kaltim harus menyiapkan lokomotif ekonomi yang baru,” katanya. Konkritnya, agribisnis akan menjadi tumpuan. Untuk itu, dia telah menyiapkan kebijakan pengembangan industri pertanian dengan konsep Integrated Agricultural Industrial Approach. Terdiri dari integrated farming, integrated rice processing, down stream industry, dan management and empowerment. “Kami akan memoles sektor ini agar investor semakin berdatangan,” tandasnya.
Untuk lahan pertanian, Kaltim memang memiliki banyak lahan potensial. Lahan sawah mencapai 205,100 ha dan bukan sawah 22,65 juta ha. Dari luas potensi lahan sawah tersebut, yang ditanami padi setahun dua kali mencapai 35,9 ribu ha dan ditanami sekali seluas 53,7 ribu ha. Sedangkan lahan yang tidak diusahakan seluas 104,265 ha, dan tidak ditanami seluas 25,2 ribu ha.
Sementara itu, Kaltim juga luar biasa. Ia memiliki potensi lahan kering seluas 5.324.488 ha yang terletak di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). Dari jumlah itu, seluas 4,25 juta ha lahannya cocok untuk komoditi perkebunan (termasuk kelapa sawit). Hingga 2008, yang telah dimanfaatkan baru seluas 528.848 ha untuk pengembangan karet, kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, lada, kakao dan aneka tanaman lainnya. Sementara sisanya (3.73 juta ha), belum dikembangkan.
Selain cetak biru pertanian, Faroek juga tak meninggalkan industri energi, serta berupaya mengembangkan industri-industri lainnya. Dia membuat pembangunan kawasan industri di tiga area, meliputi; Bontang (Bontang Industri Estate), Banjarmasin, dan Balikpapan (Kawasan Industri Kariangau).
Untuk menggenjot pengembangan industri itulah dia berupaya mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Sedikitnya, jalan sepanjang 1902 km akan dibangunnya di beberapa lokasi. Lalu, jalan kereta api, dan pelabuhan Maloy yang menjadi pusat keluarnya (outlet) crude palm oil (CPO) di Kalimantan. Tak lupa, dia juga akan memperlebar Bandara Sepinggan. Sebagai bandara tersibuk keempat di Indonesia, daya tampungnya sudah tidak memungkinkan. Landasan pacu (runway) akan direntang dari 2.500 m menjadi 3.100 m. Sepinggan terletak di Balikpapan yang terkenal sebagai kota bisnis. Di kota ini, bangunan-bangunan tinggi menjulang, berdampngan dengan hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan hotel berbintang. Balikpapan adalah tempat perusahaan tambang besar berkantor seperti Pertamina, Total, Unocal dan Chevron.
Rencananya, seluruh infrastruktur tersebut akan menjadi tolak punggung untuk transportasi hasil SDA, atau menghubungkan pusat pertumbuhan. Misalnya, rel yang menghubungkan Kutai Barat dan Balikpapan. Rel ini khusus untuk mengangkut batu bara, CPO, karet, kayu, dan dan cokelat.
Karena menggejot infrastruktur itu pula, Faroek berikhtiar menggaet dana, baik dari pemerintah pusat, maupun investor dalam dan luar negeri. Dari luar negeri, diantaranya yang akan masuk adalah Ras-Al Khaimah, salah satu emirat dalam Uni Emirat Arab yang akan mengucurkan Rp 18 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Pertanyaannya: apakah langkah-langkah tersebut akan memadai, apalagi menopang menjadi seperti Dubai?
Sesungguhnya, dengan kekayaan potensi SDA yang luar biasa, Kaltim punya segalanya untuk melebihi Dubai, dan Singapura, dua negara kota (city state)yang luar biasa itu. Dubai tidak kaya akan SDA, sementara Singapura adalah benar-benar resource-poor yang pasir pun beli dari negara lain. Sejauh ini, langkah Kaltim untuk seperti Dubai – atau Singapura – bisa dikatakan sudah berada di jalurnya dengan berdirinya pusat-pusat pertumbuhan (growth area) di tiga kawasan industri (Bontang).
Namun, untuk menjadi seperti Dubai, sesungguhnya ada banyak pekerjaan rumah yang mesti dikerjakan. Pusat-pusat pertumbuhan di tiga kawasan industri itu, adalah semacam cluster, yang telah ditempuh Dubai – dan sebelumnya Singapura, juga Korea Selatan. Tapi, kritik yang sejauh ini meluncur adalah Faroek belum membuat industri yang terhubung satu sama lain, dan masih bertumpu pada energi. Di Bontang, misalnya, yang terbangun adalah lebih banyak industri kimia.
Dubai tumbuh dengan caranya tersendiri. Didukung stabilitas pemerintahan yang kuat, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mendirikan infrastruktur serta mengundang investor untuk menjadikan Dubai sebagai financial hub dan pusat industri manufaktur, sekaligus menyediakan properti serta tempat-tempat pariwisata sebagai wahana leisure, termasuk juga ajang pertandingan olahraga dunia. Al Maktoum bukan hanya mengundang pebisnis untuk datang, orang biasa pun diundangnya. Karena itu, kulturnya pun dibuat menjadi sangat fleksibel. “Semua orang ke Dubai karena di sana bebas. Semua orang merasa nyaman di sana. Orang bule juga bebas dan merasa nyaman. Orang berbikini dan yang pakai burqa bisa hidup berdampingan,” ujar Hermawan Kartajaya dari MarkPlus&Co. sambil tertawa.
Jelas tidaklah keliru bila Kaltim membuat industri yang memanfaatkan kekayaan SDA-nya. Namun, dengan kekayaan SDA-nya tersebut, sudah selayaknya provinsi ini tidak semata bergerak di fase primary dan menjualnya sebagai produk komoditas, tapi melangkah pada penciptaan industri-industri manufaktur serta industri pengolahan yang bisa memanfaatkan primary product (hasil tambang), baik dari Kaltim atau tetangganya di bumi Kalimantan, atau pulau-pulau kaya tambang terdekat seperti Sumatera, Sulawesi dan Irian. Faktor proximity (kedekatan) dengan lahan-lahan tambang sebagai bahan baku mestinya bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan multiplier effect yang besar. Rantai industri di Kaltim mestinya bisa lebih panjang.
Tentang hal ini, Kaltim mestinya tak boleh kalah dari Dubai yang bahkan sudah membuat Dubai Alumunium. Ini merupakan smelter terbesar di dunia di luar Rusia yang memproduksi billet serta foundry alloy dengan kapasitas produksi 659 ribu ton setahun. Selain alumunium, Dubai Alumunium juga memproduksi baja sebanyak 400 ribu ton setahun yang dapat memenuhi 25% kebutuhan dalam negeri Uni Emirate Arab yang terus mengenjot sektor properti, dan sisanya diekspor ke seluruh dunia. Dari mana mereka mendapat bahan baku yang bisa diubah menjadi lebih dari 10 produk turunan itu? Jelas dari seluruh dunia, termasuk Indonesia yang menjadi penghasil timah nomor 2 di dunia. Kalau Dubai bisa, mengapa Kaltim tidak? Faroek bisa mengundang investor melakukan hal ini. Dia bisa memilih akan mengembang rantai industri yang feasible untuk Kaltim.
Intinya, Kaltim sudah sepatutnya membuat cluster yang di dalamnya menciptakan rantai industri yang panjang. Bukan yang rantainya pendek, menggali dari perut bumi lalu mengekspor dalam kondisi mentah. Dan tentang ini, Faroek, serta juga kepala daerah lain, punya legalitas kuat lewat UU Mineral Batu Bara No. 4/2009 yang baru disahkah Januari 2009 yang mewajibkan produsen bahan tambang mengolahnya lebih dahulu di dalam negeri. Dalam konteks membuat rantai industri yang lebih panjang, Faroek telah melangkah lebih maju dengan rencana membuat industri pengolahan kelapa sawit sehingga menghasilkan sejumlah produk turunan ketimbang hanya CPO. Dengan Kutai Timur sebagai pusat CPO di Kalimantan, ada 7 perusahaan nasional berminat untuk bekerja sama dalam pengembangan kelapa sawit di Kaltim.
Kaltim jelas bukan Dubai. Masing-masing punya kelebihan tersendiri. Tapi untuk urusan cara menjadi hebat, pembangunan berbasis SDA di Kaltim dengan rantai industri yang panjang akan lebih hebat juga bila ditunjang dengan pendekatan pembangunan berbasis SDM yang unggul. Dubai meniru Singapura dalam urusan mengumpulkan orang-orang terbaik – Singapura malah terhitung paling rakus mengumpulkan manusia terunggul di muka bumi dengan imbalan setinggi-tingginya. Untuk urusan ini, Kaltim termasuk sudah cukup bagus. Menurut Bambang PS Brodjonegoro, Kaltim termasuk lima besar jika dilihat dari indeks kualitas SDM di Indonesia. "Sudah punya modal manusianya, tinggal bagaimana mengoptimalkan termasuk tidak perlu segan-segan menarik orang dari daerah lain. Tidak mungkin berdiri sendiri karena butuh bantuan," ujar Bambang. Lantas, bagaimana rencana Faroek tentang hal ini?
“Saya mengundang profesional untuk mengelola sumber daya alam yang melimpah di Kaltim. Sebentar lagi akan ada iklan yang mengundang profesional untuk kerja di Kaltim. Ha… ha...,” jelas lelaki berambut putih ini.
Di luar pengembangan industri berbasis SDA dan SDM ini, belajar dari Dubai, aspek branding juga tak kalah penting bila ingin melesat. Untuk mem-branding-kan Kaltim, menurut Sumardy, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara mencari apa sebenarnya potensi utama Kaltim yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Potensi itu yang kemudian ditonjolkan untuk di-branding di dalam maupun di luar negeri. “Seperti kita lihat, di dekat Kalimantan ada Sulawesi, di mana Makassar tampak juga ingin menjadi daerah yang menjadi sentra pertumbuhan,” jelas pengamat pemasaran dari Octobrand. Artinya, Kaltim mesti piawai mencari positioning dalam konteks ini.
Last but not least, belajar dari Dubai – begitu juga Singapura – diperlukan konsistensi serta persistensi baik politik, sosial dan budaya untuk mengeksekusi seluruh rencana karena sesungguhnya mereka perlu waktu puluhan tahun hingga ke posisi sekarang. Tanpa hal-hal itu, “Dompet Republik” ini sulit untuk berkembang dan lebih hebat dari sekarang. ***
Boks
Dubai,
Buah Visi Para Pemimpin
Pada dekade 1990-an, ada tiga fastest growing cities di dunia, yakni Dublin, Las Vegas serta Dubai. Nama terakhir yang menyusul belakangan masuk di kategori itu, justru sekarang yang paling berkilau. Dubai yang merupakan salah satu dari 7 emirat di Uni Emirat Arab (UEA) kini menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Timur Tengah dengan perkembangan yang tak pernah terkira sebelumnya. Hari ini Dubai adalah trading, business and increasingly financial hub di Teluk Persia. Ia melampaui Abu Dhabi yang nota bene adalah ibu kota Kesultanan Teluk itu.
Sukses Dubai tak bisa dilepaskan dari kesolidan UEA. Sejak menyatakan menjadi satu negara hasil gabungan 7 emirat pada 1971, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan memimpin UEA relatif tanpa gejolak, dan terpenting, proaktif menggenjot pembangunan. Boom minyak membuat UEA dari desert kingdom menjadi modern metropolis. Sheikh Zayed sendiri adalah Emir Abu Dhabi, sahabat karib Sheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, Emir Dubai. Sheikh Zayed menjadi Presiden UEA sejak 1971 hingga tahun wafatnya, 2004.
Sebagai penguasa Dubai, Sheikh Rashid membangun wilayahnya sejak ladang minyak ditemukan di daerah itu pada tahun 1966. Memanfaatkan pendapatan dari penjualan minyak, dia menggenjot pembangunan infrastruktur. Sejak awal 1967, dia mendorong pembangunan skala besar besaran meliputi bangunan sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan telekomunikasi modern serta bandar udara internasional.
Sheikh Rashid mangkat pada tahun 1981. Setelah itu, tampuk Dubai dipegang anak sulungnya, Sheikh Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Di tangannya, modernisasi Dubai terus dilanjutkan. Dubai kian dipoles. Dia mendorong Pemerintah Dubai dan keluarga-keluarga berpengaruh di wilayah itu untuk berinvestasi kepada infrastruktur serta merentang rencana-rencana yang ambisius. Kepemimpinan yang stabil, menurut para analis membuat keputusan bisa cepat diambil dalam membangun infrastruktur. Ada istilah yang mengatakan bahwa keputusan “Bangun di sana, bangun di sini” bisa dilakukan Sheikh Maktoum karena tiadanya tentangan.
Maka berdirilah bangunan-bangunan fenomenal seperti Burj Al Arab, Emirates Towers, Burj Dubai, dan Dubai International Airport yang dibangun senilai US$ 4,2 miliar. Terpenting dari itu adalah bangunan untuk menyedot korporasi serta investor kelas dunia seperti Dubai International Financial Centre serta Dubai Metals and Commodities Centre.
Visi Sheikh Maktoum memang menjadikan Dubai sebagai pusat keuangan dan ekonomi dunia, juga pusat pariwisata. Agar pariwisata kian kencang, dia membuat kebijakan yang mengijinkan orang asing memiliki properti di Dubai. Maka berdirilah kawasan residensial Dubai Marina yang mewah, serta deretan pertokoan seperti Mall of the Emirates.
Namun, sang Sheikh pun bervisi ke luar. Karena itulah dia membangun apa yang sering disebut sebagai Dubai Inc. yang di dalamnya terdiri dari sejumlah perusahaan dalam 4 divisi. Dubai Holding menjadi induk dari Dubai Inc. Dalam naungannya berdiri: Jumeirah Group (membuat hotel), Dubai Property (membangun kota-kota baru), Media Properties (media), dan ujung tombak investasi mancanegara, Dubai International Capital. Diantara anak usaha yang terkenal adalah maskapai Emirates yang menandingi Singapore Airlines. Dan seperti halnya Temasek yang jadi jantung Singapore Inc., Dubai Inc. tak henti berekspansi ke tempat-tempat yang dianggap menguntungkan.
Wafat pada 2006, Sheikh Maktoum digantikan adiknya, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang oleh pers Barat disebut Sheik Mo dan diyakini justru merupakan arsitek ekonomi Dubai yang sesungguhnya di balik sang kakak.
Apapun, Dubai kini terus berpendar. GDP-nya mencapai US$ 37 miliar pada tahun 2005, dan tumbuh double digit. Tahun 2008, GDP-nya tumbuh di kisaran 13-16%. Dengan portofolio bisnis yang ada, sumber-sumber pemasukan tidak lagi bertumpu pada minyak yang ditaksir akan sama sekali habis pada 20 tahun mendatang. Minyak dan gas hanya menyumbang 6%. Selebihnya datang dari perdagangan, real estate, jasa keuangan dan pariwisata. Setiap tahun, sedikitnya 7 juta pengunjung mampir ke Dubai, jauh melebihi warga Dubai yang kurang dari 2 juta jiwa.
“Perkembangan ekonomi Dubai yang luar biasa merupakan buah dari visi serta kebijakan progresif keluarga Al Maktoum yang fokus pada pertumbuhan,” ujar Mohamed Ali Alabbar, Dirjen Departemen Pengembangan Ekonomi Pemerintah Dubai, yang juga merangkap Chairman Emaar Properties.
Ya, sesungguhnya Dubai memang tidak dibangun dalam semalam. Ketika keluarga Al Maktoun mulai bermukim di Dubai pada 1883, daerah itu awalnya tempat perdagangan ikan, mutiara serta hasil laut lainnya.
Labels:
Macroeco
Tuesday, May 19, 2009
Pemerintah dan Merek Orisinal
Banyak merek orisinal yang tumbuh dengan dukungan pemerintah. Namun, mentalitas masyarakat pun berperan dalam melahirkan merek yang menjadi tuan di negeri sendiri dan bermain di level internasional.
Teguh S. Pambudi
Siapa tak kenal Apple, Adidas, Starbucks? Bahkan sosok Donald Trump atau David Beckham adalah brand kelas dunia. Mereka menghiasi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan dari yang sifatnya primer hingga tersier.
Di pentas global, sungguh banyak merek yang seperti itu (Apple dkk.): lahir dan berkembang dengan cara yang natural, yang tumbuh identik dengan dirinya sendiri, baik personal maupun korporat. Namun, sesungguhnya tak sedikit pula merek yang diidentikkan dengan negara tempatnya berasal (origin) sehingga peran pemerintahnya pun disebut-sebut ketika satu atau beberapa merek tumbuh mengesankan. Pemerintah negara yang bersangkutan dipandang sebagai promotor di balik lahirnya merek-merek itu.
Yang paling sering dirujuk dalam konteks ini adalah Jepang. Lihatlah Toyota, Suzuki dan Honda sebagai perwakilan dari jalur otomotif, atau Sony, Toshiba dan Panasonic dari lini elektronik, kerap dikaitkan sebagai Japanese brands. Bukan hanya itu, bahkan fantastic Japanese brands. Merek-merek yang fantastis! Dan asosiasi yang muncul dari made in Japan itu pun bukan main-main: kualitas sekaligus keterandalan. Tak heran, banyak produk – terutama elektronik – yang di Indonesia kemudian diembel-embeli dengan kata “teknologi Jepang” sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu produk punya kualitas tinggi. Atau, setidaknya diberi merek yang berbau Jepang. Sebuah langkah cerdik secara branding, tapi miskin rasa percaya diri.
Hal yang sejenis terjadi pada produk Korea Selatan seperti Samsung, LG atau Hyundai. Dengan porsinya tersendiri, mereka juga dipersepsikan sebagai produk yang oke punya karena kualitasnya terjaga. Produk-produk itu bukan hanya menjadi raja di negeri sendiri tapi juga sukses di panggung global.
Jepang dan Kor-Sel memang tergolong negara yang sangat mendorong mentasnya merek-merek asli dari negerinya. Jepang, contohnya. Bisa dikatakan, Japanese brands dibentuk sebagai hasil dari strategi nasional selepas Perang Dunia II. Dihadapkan pada pembatasan di sektor militer, Pemerintah Jepang tak punya pilihan selain memperkuat sektor ekonomi. Mereka menopang bisnis perusahaan-perusahaannya dalam mengembangkan produk dan mereknya, termasuk hingga ke level global. Selain menyediakan infrastruktur untuk produksi, Pemerintah Negeri Matahari Terbit pun menopang investasi uang, waktu dan energi untuk menghasilkan kualitas papan atas agar produk-produknya bisa masuk ke pasar dunia, khususnya Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi sehingga kini, ketika pabrikan mobil Detroit diterjang badai kebangkrutan, Toyota dan pabrikan otomotif lainnya dari Jepang justru masih tegar sekalipun merugi.
Berbeda dari Jepang, merek-merek dari Kor-Sel yang kini tumbuh di pentas global merupakan hasil strategi korporat yang didorong koneksitas milik para chaebol dengan pihak penguasa. Seperti jaringan keiretsu Jepang, para chaebol ini membentuk merek-mereknya dalam rangka ekspor ke pasar internasional, khususnya negara maju di Eropa dan AS.
Cara yang ditempuh kedua negara itu, sekarang tengah coba dilakoni negara lain yang juga ingin merek orisinal dari perusahaannya kian kinclong di panggung internasional. Rusia, ambil contoh. Tak seperti Jepang atau Kor-Sel yang bermain di sektor mass consumer product, Pemerintah Rusia mendukung para oligarki berinvestasi besar-besaran di sektor utilitas yang sifatnya business to business seperti gas dan minyak. Tentu ada yang tidak setuju dengan Pemerintah Rusia yang menopang para oligarki mengembangkan bisnisnya. Yang jelas, cara itulah yang ditempuh sehingga memunculkan nama Gazprom atau Lukoil di panggung global. Gazprom misalnya, kini memasok sepertiga kebutuhan gas Eropa. Dan salah seorang petingginya, Alexander Medvedev merupakan pentolan politik Rusia.
Di luar Rusia, negara lain yang kian peduli nasib original brand-nya adalah India dan Cina. Di kalangan pelaku bisnis India, muncul kerisauan bahwa made in India sering diasosiasikan dengan kualitas rendah dan tidak efisien. Mereka ingin sekali seperti Italia, umpamanya, yang diasosiasikan dan diidentifikasikan sebagai produk dengan sentuhan seni dan desain yang ciamik. Bvlgari atau Armani mewakili ini. Begitu pula dengan Ferrari atau Maserati yang melambangkan produk berkualitas super.
Sejauh ini, India cukup berhasil melahirkan merek yang identik dengan teknologi informasi seperti Wipro atau Infosys. Mereka pun punya Bajaj dan Tata yang mulai dapat pengakuan di pentas global. Namun, Pemerintah India masih terus mencari formula yang pas agar merek lain dari negerinya kian moncer. Meniru Pemerintah Jepang yang terus mendorong perusahaannya go global, Pemerintah India beserta kalangan bisnisnya bahu-membahu mendirikan India Brand Equity Foundation (IBEF) yang berupaya mempromosikan merek-merek dari negeri yang kebetulan sedang dapat momentum cukup bagus untuk mengatrol citra di pentas internasional dengan kemenangan Slumdog Millionaire di acara Academy Award lalu. “Tugas kami membangun persepsi global tentang India, lalu menciptakan buzz (pembicaraan),” ujar CEO IBEF, Ajay Khanna, beberapa waktu lalu.
Lain India, lain pula Cina. Sejak empat tahun terakhir, merek-merek dari Negeri Tirai Bambu mencoba terus merangsek pasar global. Memang ada hambatan untuk melompat ke level internasional karena seperti halnya India, made in China identik atau diasosiasikan sebagai merek murah sehingga kualitasnya pun jelek. Tak mengherankan, produk consumer mass yang mereka lemparkan baik di telepon seluler, elektronik, maupun otomotif dipandang sebelah mata di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Produk mereka bahkan dianggap masih kalah dibanding yang lahir dari tanah Formosa, Taiwan, yang dipandang lebih hi-tech dan bermutu tinggi. Dengan strategi menguatkan R&D, Pemerintah Taiwan sejak 1980-an mendorong perusahaan-perusahaannya mengembangkan teknologi setelah kenyang menjadi basis produksi bagi pabrikan asing. Kini, made in Taiwan adalah citarasa teknologi bermutu tinggi. Sejumlah produk yang tak bisa disangkal lagi adalah Acer, BenQ, Lite-On, Transcend, dan HTC.
Kendati tertinggal dibanding Taiwan, perusahaan Cina tak henti mencoba untuk bermain di level tertinggi. Ada yang melakukannya dengan cara akuisisi seperti yang dilakukan Legend Computer dengan membeli divisi bisnis PC milik IBM yang kemudian bersalin rupa jadi Lenovo, atau TCL yang mengambil RCA dari Thomson. Toh, banyak pula yang didorong Pemerintah Cina untuk terus berekspansi ke mancanegara secara organik seperti Haier (pabrikan home aplliances), Air China, China Mobile, pemain jasa telekomunikasi seperti ZTE, Tsingtao Brewery, ChangYu dan Moutai (minuman keras), Ping An (asuransi jiwa), serta pemain otomotif DongFeng Motors. Pada saat Olimpiade lalu, mereka bahkan didorong Pemerintah Cina untuk kencang berpromosi agar makin dikenal masyarakat global. Pemerintah Cina bahkan terang-terangan mengaku ingin mengikuti jejak Kor-Sel yang merek-mereknya – terutama Samsung – kian ngetop setelah mensponsori Olimpiade Seoul 1988.
Serbuan merek dari Cina sebenarnya tinggal menunggu waktu seiring upaya mereka memperbaiki citra made in China yang dipandang kualitasnya memble. Huawei, umpamanya, kini terus aktif menggelontorkan dana buat riset dan pengembangan produk dengan target menumbangkan pemain global seperti Cisco Systems. Menariknya, dalam analisis Prof. L.D. Mago dari Indian Institute of Foreign Trade, serbuan mereka ini kerap dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak asing lainnya atau perusahaan tempat mereka berekspansi. Mereka juga, disebutkan Mago, cenderung memilih cara evolusi dan menghindari agresivitas yang kental dengan trial and error. Di Indonesia, Huawei dan ZTE aktif memasarkan produknya dengan menggandeng pemain telekomunikasi seperti Indosat.
Perihal peran pemerintah dalam mendorong merek-merek yang lahir dari negerinya ke pentas global, rasanya tak usah jauh-jauh mengambil contoh, jiran kita yakni Thailand aktif pula melakukannya. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu aktif mendorong munculnya resto makanan Thailand di seluruh dunia. Dalam upaya itu, flag carrier-nya, Thai Airways pun terlibat aktif membantu proses pengiriman bahan makanan dari Thailand termasuk pemasarannya.
Membangun merek global sesungguhnya bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Peran pemerintah memang penting dengan mendukungnya dari sisi penyediaan infrastruktur, regulasi yang fair dan kondusif, serta koneksitas (perluasan pasar). Namun, menyerahkan pada pemerintah semata jelaslah tidak fair. Peran pemerintah yang proporsional dalam konteks ini, belajar dari Jepang atau Kor-Sel selain menciptakan regulasi yang mendorong perusahaan mereka bisa bersaing di pentas global, juga penciptaan infrastruktur yang andal. Di luar peran pemerintah, sesungguhnya peran masyarakat itu sendiri sangatlah penting. Mentalitas mencintai produk dalam negeri juga berperan signifikan. Artinya, ada keterhubungan (link) yang kuat antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Keterhubungan yang sifatnya sinergis, tidak semata politis (didukung kebijakan pemerintah) tapi juga kultural.
Ambil contoh Jepang. Ke mana pun orang-orang Jepang melancong, biasanya mereka akan berupaya menggunakan hotel atau penginapan yang dimiliki orang dari negeri sendiri. Hotel Nikko, misalnya. Sementara itu, orang Kor-Sel terkenal militan untuk menggunakan produk buatan negerinya sendiri. Di jalan-jalan Kor-Sel, niscaya sangat sulit menemukan produk otomotif dari Jepang yang memang sangat mereka benci lantaran pernah menjajah negeri itu. Orang-orang Dae Han Min Guk (begitu orang-orang Kor-Sel menyebut dirinya) lebih mencintai Hyundai di otomotif, atau Samsung dan LG di elektronik. Mereka mencintai dan memberi kesempatan pada produk dalam negerinya itu untuk terus memperbaiki diri. Dan sikap ini berperan besar bagi tumbuhnya merek-merek tersebut. Sebuah kultur yang justru masih sulit dijumpai di Indonesia.
Berbicara kultur menggunakan original brand, jangankan negara-negara Asia yang memang memerlukan mental cinta produk dalam negeri untuk mengejar ketertinggalan ekonomi pasca Perang Dunia II, di Inggris ada cerita legendaris yang masih terkenang hingga kini seputar mentalitas menggunakan produk negeri sendiri. Cerita itu adalah tentang mendiang Lady Diana yang diprotes masyarakat Inggris lantaran mengendarai BMW, bukan Jaguar atau Rolls Royce yang buatan anak Inggris. Memang banyak orang setempat yang lebih memilih produk otomotif non-Inggris, tapi sebagai figur yang mewakili Inggris, diharapkan wanita yang tewas mengenaskan di Prancis itu menggunakan produk asli dari negerinya.
Pertanyaannya kini: mengapa original brand penting bagi sebuah negara?
“Setiap bangsa atau negara punya original brand, dan ketika merek-merek dari suatu negara itu disukai dan dipercayai, maka masyarakat dunia akan membeli produk dan jasa dari negara itu,” ujar Mago.
Indonesia, seperti dicanangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berupaya mengantarkan 200 merek nasional go global tahun ini dengan bertumpu pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Jelas ini merupakan inisiatif yang menarik dan patut diapresiasi. Namun, belajar dari negara-negara lain, Pemerintah RI seyogyanya juga berupaya menciptakan asosiasi yang clear dan interesting tentang apa yang dimaksud dengan made in Indonesia itu sendiri. Pemerintah dan kalangan bisnis mesti bersatu dalam hal ini.
Barangkali Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya meniru pemerintah negara lain yang sangat serius dalam membangun merek, termasuk untuk negaranya. Seperti dikutip LA Times, 3 Mei 2009, Presiden Kor-Sel, Lee Myung-bak sangat marah begitu mengetahui negaranya hanya nomor 33 di Global Brand Index yang baru saja keluar. Kor-Sel berada di bawah Polandia dan Republik Cek yang ekonominya lebih tertinggal – nomor satu dipegang Jerman. Rupanya, Kor-Sel masih dipersepsikan negatif karena dekat dengan Kor-Ut. Beruntung, merek-merek dari negara itu seperti Samsung, LG dan Hyundai sudah masuk dalam BusinessWeek Global Brands dan kian ngetop. Toh, Pemerintah Kor-Sel tak berdiam diri. Meresponsnya, Lee membentuk Presidential Council on Nation Branding. Targetnya: bergerak ke posisi 15 di tahun 2013. Dan kini mereka tengah membangun strategi ke arah itu.
Seperti disinggung di atas, di luar peran pemerintah, masyarakat pun harus punya mentalitas cinta produk dalam negeri yang pada gilirannya mesti direspons pelaku pasar dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Dan kalangan pejabat sebagai representasi negara, juga harus lebih sering menggunakan produk dalam negeri dan memperkenalkannya di mancanegara. Adalah dagelan yang tak lucu ketika salah seorang menteri SBY dalam suatu kesempatan mengaku sulit menemukan sepatu produksi dalam negeri. Sungguh sebuah ironi yang mestinya tak pernah terjadi.
Teguh S. Pambudi
Siapa tak kenal Apple, Adidas, Starbucks? Bahkan sosok Donald Trump atau David Beckham adalah brand kelas dunia. Mereka menghiasi kehidupan manusia, memenuhi kebutuhan dari yang sifatnya primer hingga tersier.
Di pentas global, sungguh banyak merek yang seperti itu (Apple dkk.): lahir dan berkembang dengan cara yang natural, yang tumbuh identik dengan dirinya sendiri, baik personal maupun korporat. Namun, sesungguhnya tak sedikit pula merek yang diidentikkan dengan negara tempatnya berasal (origin) sehingga peran pemerintahnya pun disebut-sebut ketika satu atau beberapa merek tumbuh mengesankan. Pemerintah negara yang bersangkutan dipandang sebagai promotor di balik lahirnya merek-merek itu.
Yang paling sering dirujuk dalam konteks ini adalah Jepang. Lihatlah Toyota, Suzuki dan Honda sebagai perwakilan dari jalur otomotif, atau Sony, Toshiba dan Panasonic dari lini elektronik, kerap dikaitkan sebagai Japanese brands. Bukan hanya itu, bahkan fantastic Japanese brands. Merek-merek yang fantastis! Dan asosiasi yang muncul dari made in Japan itu pun bukan main-main: kualitas sekaligus keterandalan. Tak heran, banyak produk – terutama elektronik – yang di Indonesia kemudian diembel-embeli dengan kata “teknologi Jepang” sebagai alat untuk menunjukkan bahwa suatu produk punya kualitas tinggi. Atau, setidaknya diberi merek yang berbau Jepang. Sebuah langkah cerdik secara branding, tapi miskin rasa percaya diri.
Hal yang sejenis terjadi pada produk Korea Selatan seperti Samsung, LG atau Hyundai. Dengan porsinya tersendiri, mereka juga dipersepsikan sebagai produk yang oke punya karena kualitasnya terjaga. Produk-produk itu bukan hanya menjadi raja di negeri sendiri tapi juga sukses di panggung global.
Jepang dan Kor-Sel memang tergolong negara yang sangat mendorong mentasnya merek-merek asli dari negerinya. Jepang, contohnya. Bisa dikatakan, Japanese brands dibentuk sebagai hasil dari strategi nasional selepas Perang Dunia II. Dihadapkan pada pembatasan di sektor militer, Pemerintah Jepang tak punya pilihan selain memperkuat sektor ekonomi. Mereka menopang bisnis perusahaan-perusahaannya dalam mengembangkan produk dan mereknya, termasuk hingga ke level global. Selain menyediakan infrastruktur untuk produksi, Pemerintah Negeri Matahari Terbit pun menopang investasi uang, waktu dan energi untuk menghasilkan kualitas papan atas agar produk-produknya bisa masuk ke pasar dunia, khususnya Amerika Serikat. Dan itulah yang terjadi sehingga kini, ketika pabrikan mobil Detroit diterjang badai kebangkrutan, Toyota dan pabrikan otomotif lainnya dari Jepang justru masih tegar sekalipun merugi.
Berbeda dari Jepang, merek-merek dari Kor-Sel yang kini tumbuh di pentas global merupakan hasil strategi korporat yang didorong koneksitas milik para chaebol dengan pihak penguasa. Seperti jaringan keiretsu Jepang, para chaebol ini membentuk merek-mereknya dalam rangka ekspor ke pasar internasional, khususnya negara maju di Eropa dan AS.
Cara yang ditempuh kedua negara itu, sekarang tengah coba dilakoni negara lain yang juga ingin merek orisinal dari perusahaannya kian kinclong di panggung internasional. Rusia, ambil contoh. Tak seperti Jepang atau Kor-Sel yang bermain di sektor mass consumer product, Pemerintah Rusia mendukung para oligarki berinvestasi besar-besaran di sektor utilitas yang sifatnya business to business seperti gas dan minyak. Tentu ada yang tidak setuju dengan Pemerintah Rusia yang menopang para oligarki mengembangkan bisnisnya. Yang jelas, cara itulah yang ditempuh sehingga memunculkan nama Gazprom atau Lukoil di panggung global. Gazprom misalnya, kini memasok sepertiga kebutuhan gas Eropa. Dan salah seorang petingginya, Alexander Medvedev merupakan pentolan politik Rusia.
Di luar Rusia, negara lain yang kian peduli nasib original brand-nya adalah India dan Cina. Di kalangan pelaku bisnis India, muncul kerisauan bahwa made in India sering diasosiasikan dengan kualitas rendah dan tidak efisien. Mereka ingin sekali seperti Italia, umpamanya, yang diasosiasikan dan diidentifikasikan sebagai produk dengan sentuhan seni dan desain yang ciamik. Bvlgari atau Armani mewakili ini. Begitu pula dengan Ferrari atau Maserati yang melambangkan produk berkualitas super.
Sejauh ini, India cukup berhasil melahirkan merek yang identik dengan teknologi informasi seperti Wipro atau Infosys. Mereka pun punya Bajaj dan Tata yang mulai dapat pengakuan di pentas global. Namun, Pemerintah India masih terus mencari formula yang pas agar merek lain dari negerinya kian moncer. Meniru Pemerintah Jepang yang terus mendorong perusahaannya go global, Pemerintah India beserta kalangan bisnisnya bahu-membahu mendirikan India Brand Equity Foundation (IBEF) yang berupaya mempromosikan merek-merek dari negeri yang kebetulan sedang dapat momentum cukup bagus untuk mengatrol citra di pentas internasional dengan kemenangan Slumdog Millionaire di acara Academy Award lalu. “Tugas kami membangun persepsi global tentang India, lalu menciptakan buzz (pembicaraan),” ujar CEO IBEF, Ajay Khanna, beberapa waktu lalu.
Lain India, lain pula Cina. Sejak empat tahun terakhir, merek-merek dari Negeri Tirai Bambu mencoba terus merangsek pasar global. Memang ada hambatan untuk melompat ke level internasional karena seperti halnya India, made in China identik atau diasosiasikan sebagai merek murah sehingga kualitasnya pun jelek. Tak mengherankan, produk consumer mass yang mereka lemparkan baik di telepon seluler, elektronik, maupun otomotif dipandang sebelah mata di banyak tempat, termasuk di Indonesia. Produk mereka bahkan dianggap masih kalah dibanding yang lahir dari tanah Formosa, Taiwan, yang dipandang lebih hi-tech dan bermutu tinggi. Dengan strategi menguatkan R&D, Pemerintah Taiwan sejak 1980-an mendorong perusahaan-perusahaannya mengembangkan teknologi setelah kenyang menjadi basis produksi bagi pabrikan asing. Kini, made in Taiwan adalah citarasa teknologi bermutu tinggi. Sejumlah produk yang tak bisa disangkal lagi adalah Acer, BenQ, Lite-On, Transcend, dan HTC.
Kendati tertinggal dibanding Taiwan, perusahaan Cina tak henti mencoba untuk bermain di level tertinggi. Ada yang melakukannya dengan cara akuisisi seperti yang dilakukan Legend Computer dengan membeli divisi bisnis PC milik IBM yang kemudian bersalin rupa jadi Lenovo, atau TCL yang mengambil RCA dari Thomson. Toh, banyak pula yang didorong Pemerintah Cina untuk terus berekspansi ke mancanegara secara organik seperti Haier (pabrikan home aplliances), Air China, China Mobile, pemain jasa telekomunikasi seperti ZTE, Tsingtao Brewery, ChangYu dan Moutai (minuman keras), Ping An (asuransi jiwa), serta pemain otomotif DongFeng Motors. Pada saat Olimpiade lalu, mereka bahkan didorong Pemerintah Cina untuk kencang berpromosi agar makin dikenal masyarakat global. Pemerintah Cina bahkan terang-terangan mengaku ingin mengikuti jejak Kor-Sel yang merek-mereknya – terutama Samsung – kian ngetop setelah mensponsori Olimpiade Seoul 1988.
Serbuan merek dari Cina sebenarnya tinggal menunggu waktu seiring upaya mereka memperbaiki citra made in China yang dipandang kualitasnya memble. Huawei, umpamanya, kini terus aktif menggelontorkan dana buat riset dan pengembangan produk dengan target menumbangkan pemain global seperti Cisco Systems. Menariknya, dalam analisis Prof. L.D. Mago dari Indian Institute of Foreign Trade, serbuan mereka ini kerap dilakukan secara berkolaborasi dengan pihak asing lainnya atau perusahaan tempat mereka berekspansi. Mereka juga, disebutkan Mago, cenderung memilih cara evolusi dan menghindari agresivitas yang kental dengan trial and error. Di Indonesia, Huawei dan ZTE aktif memasarkan produknya dengan menggandeng pemain telekomunikasi seperti Indosat.
Perihal peran pemerintah dalam mendorong merek-merek yang lahir dari negerinya ke pentas global, rasanya tak usah jauh-jauh mengambil contoh, jiran kita yakni Thailand aktif pula melakukannya. Pemerintah Negeri Gajah Putih itu aktif mendorong munculnya resto makanan Thailand di seluruh dunia. Dalam upaya itu, flag carrier-nya, Thai Airways pun terlibat aktif membantu proses pengiriman bahan makanan dari Thailand termasuk pemasarannya.
Membangun merek global sesungguhnya bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Peran pemerintah memang penting dengan mendukungnya dari sisi penyediaan infrastruktur, regulasi yang fair dan kondusif, serta koneksitas (perluasan pasar). Namun, menyerahkan pada pemerintah semata jelaslah tidak fair. Peran pemerintah yang proporsional dalam konteks ini, belajar dari Jepang atau Kor-Sel selain menciptakan regulasi yang mendorong perusahaan mereka bisa bersaing di pentas global, juga penciptaan infrastruktur yang andal. Di luar peran pemerintah, sesungguhnya peran masyarakat itu sendiri sangatlah penting. Mentalitas mencintai produk dalam negeri juga berperan signifikan. Artinya, ada keterhubungan (link) yang kuat antara pemerintah, pebisnis dan masyarakat. Keterhubungan yang sifatnya sinergis, tidak semata politis (didukung kebijakan pemerintah) tapi juga kultural.
Ambil contoh Jepang. Ke mana pun orang-orang Jepang melancong, biasanya mereka akan berupaya menggunakan hotel atau penginapan yang dimiliki orang dari negeri sendiri. Hotel Nikko, misalnya. Sementara itu, orang Kor-Sel terkenal militan untuk menggunakan produk buatan negerinya sendiri. Di jalan-jalan Kor-Sel, niscaya sangat sulit menemukan produk otomotif dari Jepang yang memang sangat mereka benci lantaran pernah menjajah negeri itu. Orang-orang Dae Han Min Guk (begitu orang-orang Kor-Sel menyebut dirinya) lebih mencintai Hyundai di otomotif, atau Samsung dan LG di elektronik. Mereka mencintai dan memberi kesempatan pada produk dalam negerinya itu untuk terus memperbaiki diri. Dan sikap ini berperan besar bagi tumbuhnya merek-merek tersebut. Sebuah kultur yang justru masih sulit dijumpai di Indonesia.
Berbicara kultur menggunakan original brand, jangankan negara-negara Asia yang memang memerlukan mental cinta produk dalam negeri untuk mengejar ketertinggalan ekonomi pasca Perang Dunia II, di Inggris ada cerita legendaris yang masih terkenang hingga kini seputar mentalitas menggunakan produk negeri sendiri. Cerita itu adalah tentang mendiang Lady Diana yang diprotes masyarakat Inggris lantaran mengendarai BMW, bukan Jaguar atau Rolls Royce yang buatan anak Inggris. Memang banyak orang setempat yang lebih memilih produk otomotif non-Inggris, tapi sebagai figur yang mewakili Inggris, diharapkan wanita yang tewas mengenaskan di Prancis itu menggunakan produk asli dari negerinya.
Pertanyaannya kini: mengapa original brand penting bagi sebuah negara?
“Setiap bangsa atau negara punya original brand, dan ketika merek-merek dari suatu negara itu disukai dan dipercayai, maka masyarakat dunia akan membeli produk dan jasa dari negara itu,” ujar Mago.
Indonesia, seperti dicanangkan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu berupaya mengantarkan 200 merek nasional go global tahun ini dengan bertumpu pada Badan Pengembangan Ekspor Nasional. Jelas ini merupakan inisiatif yang menarik dan patut diapresiasi. Namun, belajar dari negara-negara lain, Pemerintah RI seyogyanya juga berupaya menciptakan asosiasi yang clear dan interesting tentang apa yang dimaksud dengan made in Indonesia itu sendiri. Pemerintah dan kalangan bisnis mesti bersatu dalam hal ini.
Barangkali Pemerintah Indonesia sudah sepatutnya meniru pemerintah negara lain yang sangat serius dalam membangun merek, termasuk untuk negaranya. Seperti dikutip LA Times, 3 Mei 2009, Presiden Kor-Sel, Lee Myung-bak sangat marah begitu mengetahui negaranya hanya nomor 33 di Global Brand Index yang baru saja keluar. Kor-Sel berada di bawah Polandia dan Republik Cek yang ekonominya lebih tertinggal – nomor satu dipegang Jerman. Rupanya, Kor-Sel masih dipersepsikan negatif karena dekat dengan Kor-Ut. Beruntung, merek-merek dari negara itu seperti Samsung, LG dan Hyundai sudah masuk dalam BusinessWeek Global Brands dan kian ngetop. Toh, Pemerintah Kor-Sel tak berdiam diri. Meresponsnya, Lee membentuk Presidential Council on Nation Branding. Targetnya: bergerak ke posisi 15 di tahun 2013. Dan kini mereka tengah membangun strategi ke arah itu.
Seperti disinggung di atas, di luar peran pemerintah, masyarakat pun harus punya mentalitas cinta produk dalam negeri yang pada gilirannya mesti direspons pelaku pasar dengan menghasilkan produk yang berkualitas. Dan kalangan pejabat sebagai representasi negara, juga harus lebih sering menggunakan produk dalam negeri dan memperkenalkannya di mancanegara. Adalah dagelan yang tak lucu ketika salah seorang menteri SBY dalam suatu kesempatan mengaku sulit menemukan sepatu produksi dalam negeri. Sungguh sebuah ironi yang mestinya tak pernah terjadi.
Labels:
Marketing
Monday, April 13, 2009
Ketika Bicara tak Lagi Murah
Menyadari pentingnya WOMM, perusahaan-perusahaan kelas dunia terus mengupayakannya dalam beragam gaya. Bahkan, menjadikannya nyawa operasional sehari-hari.
Teguh S. Pambudi
“It doesn't matter whether you're selling real estate, jelly, or jet engines. People will ask other people about you before they decide to buy from you. We turn to people we trust first -- friends, family, coworkers, and other people like us -- when starting to look for something to buy. Not ads, not brochures, not phone books.”
Itulah petikan dari buku Word of Mouth Marketing karya Andy Sernovitz (2006). Dan di abad ke-21, hal tersebut sangatlah sahih. Alhasil, “Apa yang dikatakan orang tentang merek Anda” merupakan intangible asset yang sangat berharga, dan terbilang sulit menilainya. Ini tak ubahnya aset sejenis seperti yang diutarakan Kaplan dan Norton yakni customer relationships, operating processes, skills, knowledge of the workforce, dan merek itu sendiri.
Sebuah studi yang dilakukan Northeastern University bahkan menguatkan fakta di atas. Studi itu menemukan kenyataan bahwa lebih dari 15% percakapan manusia ternyata membuat referensi tentang perusahaan, merek, produk atau jasa. Demikian Walter J. Carl dalam makalahnya, “What’s All the Buzz About? Everyday Communication and Relational Basis of Word-of-Mouth and Buzz Marketing Practices” (2006).
Karena itulah, banyak perusahaan yang berupaya melakukan word of mouth marketing (WOMM) secerdas mungkin, termasuk memanfaatkan dinamika yang kini berkembang seperti tren media sosial. Dikatakan secerdas mungkin karena dalam mengupayakan WOMM, sesungguhnya kreativitaslah yang menentukan. Sebab, praktik WOMM terdiri atas seperangkat teknik yang terus dikembangkan oleh perusahaan dalam segmen industri yang sangat beragam. Lantaran itu pula, sangatlah sulit mengukur dampak satu aktivitas WOMM. Dalam WOMMA Terminology Framework (2005) disebutkan “Until now, there has been no common language or methodology available for discussing, measuring, or comparing the impact of various word of mouth marketing efforts.”
Di kalangan penggiat WOMM di mancanegara, terutama dari lingkungan akademisi, upaya mencari pengukuran yang sahih hingga kini terus dilakukan. Sejumlah model lahir, antara lain model Tobit dan model ZIP yang menghubung-hubungkan sejumlah variabel yang diasumsikan akan membuat orang mereferensikan produk atau merek tertentu kepada pihak lain. Jadi, jangankan sebuah indeks WOMM, model pengukurannya pun terus berkembang. Sesuatu yang bisa dimaklumi lantaran pihak yang diukur, yakni perusahaan, memang terus mengembangkan teknik-teknik praktik WOMM-nya.
Ya, perkara WOMM sebagai “seperangkat teknis yang terus berkembang” – lebih tepatnya dikembangkan oleh perusahaan dalam pelbagai industri – ini memang benar adanya. Perusahaan tak henti mengembangkan teknik-teknik baru karena tidak bisa menyandarkan diri pada WOMM tipe organic, melainkan lebih kepada tipe amplified.
Tipe organik adalah WOMM yang terjadi secara natural ketika orang dengan sukarela dan penuh antusiasme menjadi advocator lantaran senang dengan produk yang digunakannya. Adapun tipe amplified terjadi secara by design. Pemasar meluncurkan aneka strategi untuk menciptakan sekaligus mempercepat WOMM di komunitas yang disasarnya. Sementara medianya bisa melalui jalur online maupun offline.
Dalam konteks WOMM tipe amplified, cara atau aktivitas yang lazim dilakukan perusahaan di antaranya membuat blog sekaligus berinteraksi dengan blogger, menggelar customer reference program termasuk program VIP, menciptakan fans club/komunitas loyal, kampanye viral, dan program evangelis. Itu hanya beberapa contoh, masih banyak lagi jenis teknik yang dikembangkan, yang sangat dinamis serta inovatif.
Yang pasti, menyadari pentingnya WOMM tipe amplified, perusahaan-perusahaan kelas dunia berupaya mengerahkan segala cara untuk bisa melakukannya dengan efisien, tepat dan sesuai dengan harapan. Konteks tepat serta sesuai dengan harapan di sini artinya membuat pelanggan membicarakan (do the talking), mempromosikan (do the promotion) dan menjual (do the selling). Dan yang pasti, hal mendasar tidak boleh dilupakan: kualitas produk/jasa itu sendiri mesti excellent.
Salah satu contoh perusahaan kaliber dunia yang dipuji Sernovitz dalam menggelar WOMM adalah Microsoft lewat program Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Ini merupakan penghargaan bagi orang-orang di seluruh dunia yang dipandang telah menyumbangkan keahlian teknisnya untuk masyarakat dengan menggunakan produk atau teknologi milik Microsoft.
Langkah-langkah yang dilakukan Microsoft untuk mencari para MVP terbilang sederhana tapi sistematis. Pertama, find the talkers. Microsoft menelusuri message boards, blog, komunitas, untuk menemukan the most engaged and credible talkers. Mereka mencari orang-orang yang piawai dalam hal software dan senang menolong sesama.
Kedua, surprise them. Para MVP mendapat surat pemberitahuan bahwa mereka telah diseleksi. Mereka juga memperoleh kotak hadiah kejutan seperti tas komputer. Hadiah ini kelak jadi legendaris karena seputar isinya menjadi bahan terkaan dan spekulasi.
Ketiga, make them feel special. MVP mendapat surat dari Microsoft yang harus dikirim ke tiga alamat: bosnya, pasangannya dan tempat kuliahnya. Keempat, engage them. Para MVP mendapat kesempatan melihat langsung dan berbicara dengan para pengembang sekaligus memperoleh informasi di belakang layar tentang produk Microsoft yang mereka gunakan. Microsoft menyediakan lebih dari 500 live web meetings, chats dan webcasts setiap tahun untuk para MVP.
Kelima, have fun. Pertemuan tahunan MVP Summit di Redmond, AS, menjadi acara yang wajib dikunjungi para MVP. Microsoft menyediakan dan membayar semuanya. Para MVP akan bertemu dengan pemenang tahun-tahun sebelumnya sekaligus dengan para pengembang produk-produk Microsoft. Di sini, dua “dewa” Microsoft, Bill Gates atau Steve Ballmer, akan tampil.
Acara ini sepertinya sederhana, tapi bagi Microsoft sangat berguna karena progam MVP menjadi ajang yang disebut para penggiat WOMM sebagai energizing talkers. Para MVP seperti disuntik energi yang luar biasa dengan pengalaman yang tidak didapat setiap orang. Mereka menjadi advokator paling depan dalam urusan mempromosikan dan menggunakan produk-produk Microsoft.
Experience. Itulah yang ditawarkan Microsoft. Hal yang serupa juga ditempuh Zara, salah satu merek yang kenaikan brand value-nya tertinggi dibanding merek lain pada Interbrand Best Brand Global 2008. Posisi Zara memang peringkat 62 dari 100 merek. Kendati demikian, brand value-nya naik 15%.
Selain kustomisasi yang tinggi dengan tingkat produktivitas yang mengagumkan, kunci sukses Zara hingga bisa meraih prestasi seperti itu adalah kemampuannya dalam strategi WOMM. Tak bertumpu pada iklan-iklan konvensional, Zara menawarkan customer experience yang membuat para pelanggannya menjadi advokator.
Customer experience ini dimulai dari di toko-toko Zara yang eksklusif. Semua toko Zara yang jumlahnya mencapai 500 di 70 negara – termasuk Indonesia – menerima model pakaian baru sekitar dua kali dalam sepekan. Kondisi ini membuat para pelanggan datang secara reguler guna mengecek koleksi terbaru dengan hukum reservasi yang absolut: siapa cepat, dia dapat. Dan pelanggan bisa memberikan umpan balik yang akan diterima oleh para desainer Zara, termasuk usulan-usulan mode. Pengalaman menyenangkan inilah yang mendorong pelanggan membicarakan, mempromosikan dan menjual Zara ke komunitasnya, sekaligus menjadikan merek dari Spanyol ini terus menjadi brand papan atas dunia.
Apa yang dilakukan Microsoft atau Zara bisa dikatakan belumlah memanfaatkan media sosial yang kini tumbuh berkembang. Sekarang, banyak perusahaan yang berupaya menggunakan media sosial sebaik-baiknya, di antaranya blog atau website, dalam menggelar WOMM.
Epson, umpamanya, lewat Epson & Sparkplugging. Sparkplugging adalah kumpulan 14 blogger. Epson mendanai mereka, para penulis, yang ingin pergi ke pertemuan BlogWorld Expo di AS. Lewat jejaring sosial yang mulai menyaingi Facebook, yakni Twitter, para penulis itu kemudian membuat sebuah game dengan hadiah printer Epson yang akan diluncurkan. Mereka ini juga membuat blog baru yang khusus meliput pelaksanaan BlogWorld. Di dalam situs tersebut terdapat wawancara, foto dan informasi seputar pertemuan akbar itu dengan menampilkan logo-logo Epson. Dalam blog tersebut, pembicaraan tentang Epson mengalir deras.
Apa yang dipraktikkan Epson merupakan pengejawantahan dari saran Sernovitz tentang bagaimana memanfaatkan media sosial yang kini kian berkembang dalam melakukan WOMM. Setidaknya ada lima saran yang bisa dilakukan: pertama, look on the web for people talking about you. Kedua, assign someone to join these conversations. Start today. Ketiga, create a blog. Keempat, make a new rule: Ask "Is this buzzworthy?" in every meeting. Dan kelima, come up with one buzzworthy topic. Keep it simple.
Buatlah tetap sederhana. Di tempat lain, prinsip ini dipraktikkan Nivea dengan gayanya sendiri. Pada malam tahun baru lalu, lewat acara "Kiss and Be Kissed" di New York Times Square, Nivea memberikan 25 ribu sampel lini produk Lip Care yang mengandung minyak jojoba dan Shea butter kepada pasangan-pasangan yang hadir. Nivea memberi kesempatan kepada pasangan yang saling berciuman di malam pergantian tahun untuk mengunggah foto-fotonya ke http://www.niveaxoxo.com/ buat memenangi kompetisi yang hadiahnya bertemu dengan Lionel Richie.
Lewat program ini Nivea ingin membuat konsumennya merasakan emotional attachment ketika bibir-bibir mereka yang telah dibasahi Nivea Lip Care saling berpagut. Nivea ingin konsumennya merasakan itu ketimbang melihat produknya sebatas functional product. Dia ingin menciptakan hal-hal penting: hasrat dan pembicaraan (buzz) di kalangan para penggunanya. Agar makin hot, Nivea juga mensponsori situs selebriti Yahoo!'s yakni OMG!, menampilkan foto para selebriti yang saling berciuman. "We like to do things in a way that is not pretentious, but is still surprising to the consumer," ujar Nicolas Maurer, SVP Pemasaran Nivea dan Eucerin, Beiersdorf.
Saking pentingnya WOMM, perusahaan seperti Zappos malah menjadikannya “nyawa” operasionalnya sehari-hari. Berdiri pada 1999, Zappos nyaris tidak punya prestasi apa-apa dalam rapor penjualan di awal-awal tahun berdirinya. Namun pada 2007 penjualannya lebih dari US$ 800 juta dan ditaksir menembus US$ 1 miliar pada 2008.
Kunci sukses perusahaan yang kini disebut the world’s biggest online shoe store ini adalah keahliannya dalam WOMM. Dari sekitar 1.400 karyawannya, ada sedikitnya 440 orang yang aktif di Twitter untuk terus membincangkan perusahaan dan terus keep in touch dengan pelanggan. Cara ini ditempuh karena manajemen Zappos sadar bahwa bisnis online shoes bersandar pada kepercayaan pelanggan atas perusahaan yang menjualnya. Karena itulah, manajemen harus membuat karyawannya enganged dengan para pembeli dan rajin-rajin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan.
Dengan stok lebih dari 3 juta sepatu, tas tangan, pakaian dan aksesori dari sedikitnya 1.100 merek, Zappos harus bisa menjual terus-menerus agar inventorinya terjaga. Dan lewat layanan yang memuaskan, pelanggan terus berdatangan. Tingkat repeat customer bahkan mencapai 60%. Mereka yang datang kembali ini lalu terus menyuarakan kepuasannya dan merekomendasikan kepada orang lain lewat aneka media, termasuk lewat blog dan Twitter. Seperti virus, kepuasan ini kian menyebar, mengundang datangnya pelanggan-pelanggan baru.
Apa yang ditempuh perusahaan-perusahaan di atas jelas suatu hal yang bisa ditiru dengan kreativitas dan inovasi sendiri. Yang jelas, apa pun cara yang dipilih, buatlah agar konsumen melakukan apa yang diutarakan Sumardy dari Octobrand: TAPS (talking, promoting dan selling).
Dulu, kata Walter J. Carl, “Talk is cheap”. Sekarang, itu tidak lagi. Sebab, dari omongan biasa, akan lahir buzz yang berefek besar bagi bisnis. Ya, talk is not cheap anymore.
Teguh S. Pambudi
“It doesn't matter whether you're selling real estate, jelly, or jet engines. People will ask other people about you before they decide to buy from you. We turn to people we trust first -- friends, family, coworkers, and other people like us -- when starting to look for something to buy. Not ads, not brochures, not phone books.”
Itulah petikan dari buku Word of Mouth Marketing karya Andy Sernovitz (2006). Dan di abad ke-21, hal tersebut sangatlah sahih. Alhasil, “Apa yang dikatakan orang tentang merek Anda” merupakan intangible asset yang sangat berharga, dan terbilang sulit menilainya. Ini tak ubahnya aset sejenis seperti yang diutarakan Kaplan dan Norton yakni customer relationships, operating processes, skills, knowledge of the workforce, dan merek itu sendiri.
Sebuah studi yang dilakukan Northeastern University bahkan menguatkan fakta di atas. Studi itu menemukan kenyataan bahwa lebih dari 15% percakapan manusia ternyata membuat referensi tentang perusahaan, merek, produk atau jasa. Demikian Walter J. Carl dalam makalahnya, “What’s All the Buzz About? Everyday Communication and Relational Basis of Word-of-Mouth and Buzz Marketing Practices” (2006).
Karena itulah, banyak perusahaan yang berupaya melakukan word of mouth marketing (WOMM) secerdas mungkin, termasuk memanfaatkan dinamika yang kini berkembang seperti tren media sosial. Dikatakan secerdas mungkin karena dalam mengupayakan WOMM, sesungguhnya kreativitaslah yang menentukan. Sebab, praktik WOMM terdiri atas seperangkat teknik yang terus dikembangkan oleh perusahaan dalam segmen industri yang sangat beragam. Lantaran itu pula, sangatlah sulit mengukur dampak satu aktivitas WOMM. Dalam WOMMA Terminology Framework (2005) disebutkan “Until now, there has been no common language or methodology available for discussing, measuring, or comparing the impact of various word of mouth marketing efforts.”
Di kalangan penggiat WOMM di mancanegara, terutama dari lingkungan akademisi, upaya mencari pengukuran yang sahih hingga kini terus dilakukan. Sejumlah model lahir, antara lain model Tobit dan model ZIP yang menghubung-hubungkan sejumlah variabel yang diasumsikan akan membuat orang mereferensikan produk atau merek tertentu kepada pihak lain. Jadi, jangankan sebuah indeks WOMM, model pengukurannya pun terus berkembang. Sesuatu yang bisa dimaklumi lantaran pihak yang diukur, yakni perusahaan, memang terus mengembangkan teknik-teknik praktik WOMM-nya.
Ya, perkara WOMM sebagai “seperangkat teknis yang terus berkembang” – lebih tepatnya dikembangkan oleh perusahaan dalam pelbagai industri – ini memang benar adanya. Perusahaan tak henti mengembangkan teknik-teknik baru karena tidak bisa menyandarkan diri pada WOMM tipe organic, melainkan lebih kepada tipe amplified.
Tipe organik adalah WOMM yang terjadi secara natural ketika orang dengan sukarela dan penuh antusiasme menjadi advocator lantaran senang dengan produk yang digunakannya. Adapun tipe amplified terjadi secara by design. Pemasar meluncurkan aneka strategi untuk menciptakan sekaligus mempercepat WOMM di komunitas yang disasarnya. Sementara medianya bisa melalui jalur online maupun offline.
Dalam konteks WOMM tipe amplified, cara atau aktivitas yang lazim dilakukan perusahaan di antaranya membuat blog sekaligus berinteraksi dengan blogger, menggelar customer reference program termasuk program VIP, menciptakan fans club/komunitas loyal, kampanye viral, dan program evangelis. Itu hanya beberapa contoh, masih banyak lagi jenis teknik yang dikembangkan, yang sangat dinamis serta inovatif.
Yang pasti, menyadari pentingnya WOMM tipe amplified, perusahaan-perusahaan kelas dunia berupaya mengerahkan segala cara untuk bisa melakukannya dengan efisien, tepat dan sesuai dengan harapan. Konteks tepat serta sesuai dengan harapan di sini artinya membuat pelanggan membicarakan (do the talking), mempromosikan (do the promotion) dan menjual (do the selling). Dan yang pasti, hal mendasar tidak boleh dilupakan: kualitas produk/jasa itu sendiri mesti excellent.
Salah satu contoh perusahaan kaliber dunia yang dipuji Sernovitz dalam menggelar WOMM adalah Microsoft lewat program Microsoft Most Valuable Professional (MVP). Ini merupakan penghargaan bagi orang-orang di seluruh dunia yang dipandang telah menyumbangkan keahlian teknisnya untuk masyarakat dengan menggunakan produk atau teknologi milik Microsoft.
Langkah-langkah yang dilakukan Microsoft untuk mencari para MVP terbilang sederhana tapi sistematis. Pertama, find the talkers. Microsoft menelusuri message boards, blog, komunitas, untuk menemukan the most engaged and credible talkers. Mereka mencari orang-orang yang piawai dalam hal software dan senang menolong sesama.
Kedua, surprise them. Para MVP mendapat surat pemberitahuan bahwa mereka telah diseleksi. Mereka juga memperoleh kotak hadiah kejutan seperti tas komputer. Hadiah ini kelak jadi legendaris karena seputar isinya menjadi bahan terkaan dan spekulasi.
Ketiga, make them feel special. MVP mendapat surat dari Microsoft yang harus dikirim ke tiga alamat: bosnya, pasangannya dan tempat kuliahnya. Keempat, engage them. Para MVP mendapat kesempatan melihat langsung dan berbicara dengan para pengembang sekaligus memperoleh informasi di belakang layar tentang produk Microsoft yang mereka gunakan. Microsoft menyediakan lebih dari 500 live web meetings, chats dan webcasts setiap tahun untuk para MVP.
Kelima, have fun. Pertemuan tahunan MVP Summit di Redmond, AS, menjadi acara yang wajib dikunjungi para MVP. Microsoft menyediakan dan membayar semuanya. Para MVP akan bertemu dengan pemenang tahun-tahun sebelumnya sekaligus dengan para pengembang produk-produk Microsoft. Di sini, dua “dewa” Microsoft, Bill Gates atau Steve Ballmer, akan tampil.
Acara ini sepertinya sederhana, tapi bagi Microsoft sangat berguna karena progam MVP menjadi ajang yang disebut para penggiat WOMM sebagai energizing talkers. Para MVP seperti disuntik energi yang luar biasa dengan pengalaman yang tidak didapat setiap orang. Mereka menjadi advokator paling depan dalam urusan mempromosikan dan menggunakan produk-produk Microsoft.
Experience. Itulah yang ditawarkan Microsoft. Hal yang serupa juga ditempuh Zara, salah satu merek yang kenaikan brand value-nya tertinggi dibanding merek lain pada Interbrand Best Brand Global 2008. Posisi Zara memang peringkat 62 dari 100 merek. Kendati demikian, brand value-nya naik 15%.
Selain kustomisasi yang tinggi dengan tingkat produktivitas yang mengagumkan, kunci sukses Zara hingga bisa meraih prestasi seperti itu adalah kemampuannya dalam strategi WOMM. Tak bertumpu pada iklan-iklan konvensional, Zara menawarkan customer experience yang membuat para pelanggannya menjadi advokator.
Customer experience ini dimulai dari di toko-toko Zara yang eksklusif. Semua toko Zara yang jumlahnya mencapai 500 di 70 negara – termasuk Indonesia – menerima model pakaian baru sekitar dua kali dalam sepekan. Kondisi ini membuat para pelanggan datang secara reguler guna mengecek koleksi terbaru dengan hukum reservasi yang absolut: siapa cepat, dia dapat. Dan pelanggan bisa memberikan umpan balik yang akan diterima oleh para desainer Zara, termasuk usulan-usulan mode. Pengalaman menyenangkan inilah yang mendorong pelanggan membicarakan, mempromosikan dan menjual Zara ke komunitasnya, sekaligus menjadikan merek dari Spanyol ini terus menjadi brand papan atas dunia.
Apa yang dilakukan Microsoft atau Zara bisa dikatakan belumlah memanfaatkan media sosial yang kini tumbuh berkembang. Sekarang, banyak perusahaan yang berupaya menggunakan media sosial sebaik-baiknya, di antaranya blog atau website, dalam menggelar WOMM.
Epson, umpamanya, lewat Epson & Sparkplugging. Sparkplugging adalah kumpulan 14 blogger. Epson mendanai mereka, para penulis, yang ingin pergi ke pertemuan BlogWorld Expo di AS. Lewat jejaring sosial yang mulai menyaingi Facebook, yakni Twitter, para penulis itu kemudian membuat sebuah game dengan hadiah printer Epson yang akan diluncurkan. Mereka ini juga membuat blog baru yang khusus meliput pelaksanaan BlogWorld. Di dalam situs tersebut terdapat wawancara, foto dan informasi seputar pertemuan akbar itu dengan menampilkan logo-logo Epson. Dalam blog tersebut, pembicaraan tentang Epson mengalir deras.
Apa yang dipraktikkan Epson merupakan pengejawantahan dari saran Sernovitz tentang bagaimana memanfaatkan media sosial yang kini kian berkembang dalam melakukan WOMM. Setidaknya ada lima saran yang bisa dilakukan: pertama, look on the web for people talking about you. Kedua, assign someone to join these conversations. Start today. Ketiga, create a blog. Keempat, make a new rule: Ask "Is this buzzworthy?" in every meeting. Dan kelima, come up with one buzzworthy topic. Keep it simple.
Buatlah tetap sederhana. Di tempat lain, prinsip ini dipraktikkan Nivea dengan gayanya sendiri. Pada malam tahun baru lalu, lewat acara "Kiss and Be Kissed" di New York Times Square, Nivea memberikan 25 ribu sampel lini produk Lip Care yang mengandung minyak jojoba dan Shea butter kepada pasangan-pasangan yang hadir. Nivea memberi kesempatan kepada pasangan yang saling berciuman di malam pergantian tahun untuk mengunggah foto-fotonya ke http://www.niveaxoxo.com/ buat memenangi kompetisi yang hadiahnya bertemu dengan Lionel Richie.
Lewat program ini Nivea ingin membuat konsumennya merasakan emotional attachment ketika bibir-bibir mereka yang telah dibasahi Nivea Lip Care saling berpagut. Nivea ingin konsumennya merasakan itu ketimbang melihat produknya sebatas functional product. Dia ingin menciptakan hal-hal penting: hasrat dan pembicaraan (buzz) di kalangan para penggunanya. Agar makin hot, Nivea juga mensponsori situs selebriti Yahoo!'s yakni OMG!, menampilkan foto para selebriti yang saling berciuman. "We like to do things in a way that is not pretentious, but is still surprising to the consumer," ujar Nicolas Maurer, SVP Pemasaran Nivea dan Eucerin, Beiersdorf.
Saking pentingnya WOMM, perusahaan seperti Zappos malah menjadikannya “nyawa” operasionalnya sehari-hari. Berdiri pada 1999, Zappos nyaris tidak punya prestasi apa-apa dalam rapor penjualan di awal-awal tahun berdirinya. Namun pada 2007 penjualannya lebih dari US$ 800 juta dan ditaksir menembus US$ 1 miliar pada 2008.
Kunci sukses perusahaan yang kini disebut the world’s biggest online shoe store ini adalah keahliannya dalam WOMM. Dari sekitar 1.400 karyawannya, ada sedikitnya 440 orang yang aktif di Twitter untuk terus membincangkan perusahaan dan terus keep in touch dengan pelanggan. Cara ini ditempuh karena manajemen Zappos sadar bahwa bisnis online shoes bersandar pada kepercayaan pelanggan atas perusahaan yang menjualnya. Karena itulah, manajemen harus membuat karyawannya enganged dengan para pembeli dan rajin-rajin mengucapkan terima kasih kepada pelanggan.
Dengan stok lebih dari 3 juta sepatu, tas tangan, pakaian dan aksesori dari sedikitnya 1.100 merek, Zappos harus bisa menjual terus-menerus agar inventorinya terjaga. Dan lewat layanan yang memuaskan, pelanggan terus berdatangan. Tingkat repeat customer bahkan mencapai 60%. Mereka yang datang kembali ini lalu terus menyuarakan kepuasannya dan merekomendasikan kepada orang lain lewat aneka media, termasuk lewat blog dan Twitter. Seperti virus, kepuasan ini kian menyebar, mengundang datangnya pelanggan-pelanggan baru.
Apa yang ditempuh perusahaan-perusahaan di atas jelas suatu hal yang bisa ditiru dengan kreativitas dan inovasi sendiri. Yang jelas, apa pun cara yang dipilih, buatlah agar konsumen melakukan apa yang diutarakan Sumardy dari Octobrand: TAPS (talking, promoting dan selling).
Dulu, kata Walter J. Carl, “Talk is cheap”. Sekarang, itu tidak lagi. Sebab, dari omongan biasa, akan lahir buzz yang berefek besar bagi bisnis. Ya, talk is not cheap anymore.
Labels:
Marketing