Perubahan di lingkup domestik serta global memunculkan persoalan besar bagi para pemimpin bisnis. Karakter dan kemampuan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasinya?
Teguh S. Pambudi
Dalam 6 bulan terakhir, isu seputar kepemimpinan bisnis kian marak dikupas majalah maupun jurnal manajemen. Terpentalnya beberapa CEO top macam Charles O. Prince di Citigroup dan ancaman dipenjarakannya para pemimpin bisnis yang dipandang telah melakukan fraud, menjadi santapan media. Jauh sebelum Lehmann Brothers tutup usia, Harvard Business Review edisi Januari 2008, bahkan khusus mengangkat topik leadership. Rupanya, kekisruhan krisis kredit perumahan di AS yang membawa tsunami finansial sedikit banyak memunculkan kembali trauma atas skandal-skandal korporasi era Enron. Dan ujung pertanyaan dari masalah ini, siapa lagi kalau bukan para pemimpin bisnis; mengapa ini sampai terjadi? Apa yang mereka lakukan sebagai pemimpin?
Dalam tulisannya di New York Times (11 November 2007), Nelson D. Schwartz melempar wacana menarik. Mengutip guru besar tentang leadership di School of Management at Yale, Jeffrey A. Sonnenfeld, kini dunia korporasi (khususnya di AS) memerlukan apa yang disebut CEO versi 3.0. Versi 1.0. adalah mereka yang fokus pada mega-merger serta manajemen finansial untuk memuaskan Wall Street dan rasa lapar para investor. Mereka adalah para empire builder. Berlangsung 1950-1990-an, fase yang terpaku pada pemuasan bottom line ini segera berakhir begitu Enron meledak. Lahirlah era CEO versi 2.0., para pemimpin berjenis cleanup artist yang tugasnya membereskan masalah. Mereka disebut juga kaum Fix-it Man. Sayang, mereka yang berkiprah di awal 2000-an ini pun banyak yang tidak sukses. Terbukti lahir skandal subprime mortgage yang hingga kini menimbulkan kerugian besar; lebih dari US$ 400 miliar.
Dari sinilah dibutuhkan CEO Versi 3.0. Mereka adalah para pemimpin yang bukan hanya fokus pada bottom line, tapi juga menyinergikan bisnis secara kelompok (tim). Mereka bervisi membangun kerajaan (empire builder), diiringi kerendahatian, dan mampu membangun tim yang kuat. Contohnya adalah CEO-nya P&G, AG Lafley serta Anne Mulcahy di Xerox. Disiplin individu yang mereka kembangkan bukan hanya teknikal seperti keuangan atau pemasaran, tapi lebih mengarah pada team oriented approach. Dan perusahaan yang mereka pimpin terbukti tangguh menghadapi krisis yang kini terjadi akibat subprime mortgage.
Pemikiran Sonnenfeld boleh jadi terlalu menyederhanakan, kendati ada hal-hal yang masuk akal, seperti fakta betapa menghambanya para pemimpin bisnis pada kalangan investor, terutama di tahun-tahun 1980-an ketika falsafah “greedy is good” menjadi “agama”. Lantas, bagaimana dengan wacana kepemimpinan bisnis di Indonesia? Apakah kita juga membutuhkan CEO versi 3.0.?
Sebelum menjawab hal tersebut, ada baiknya diketahui apa saja isu yang mengelilingi para pemimpin bisnis kita. Sebab, dari sini bisa ditarik garis bagaimana sesungguhnya dinamika bisnis yang sedang berlangsung, beserta lanskap yang menjadi arena permainannya. Untuk mencari tahu apa persoalan para pemimpin bisnis di Tanah Air, beberapa waktu lalu SWA melakukan survei pada 46 CEO, dengan pola jawaban terbuka dan bersifat multiple answers. Hasilnya?
Managing change, sustaining business growth, dan develop leader. Itulah 3 besar (berturut-turut) isu seputar leadership yang dihadapi para pemimpin bisnis kita. Perubahan yang makin sulit diprediksi serta dikelola, menjadi permasalah besar mereka (67,39%). Ini sesuatu yang wajar. Sekedar menyebutkan beberapa contoh, cobalah tengok ke panggung internasional. Krisis serta fluktuasi harga minyak, membuat lanskap bisnis kian tak ramah lagi. Tak heran, perkara ini akhirnya membuat mereka juga merasa bahwa mempertahankan pertumbuhan bisnis kian tak mudah, meski optimisme harus dipelihara (56,52%).
Yang menarik, urusan develop leader cukup mendapat porsi yang besar (56,52%). Ini sebuah sinyal positif sebagai jawaban terhadap isu bahwa stok leader kita terbatas, alias yang itu-itu saja. Artinya, bagi para responden, menjadi pemimpin hebat tidaklah cukup. Sanggup melahirkan para pemimpin selanjutnya, itu baru disebut hebat. Pemimpin-pemimpin baru ini tidak saja dalam konteks untuk berekspansi bisnis -- yang nota bene memerlukan orang-orang yang akan mengendalikan percepatan usaha --, tapi juga dalam regenerasi serta kelangsungan perusahaan.
Urusan yang satu ini, bukan perkara main-main. Garuda Food, misalnya, kini tengah serius menggojlok program creating business leader. Hingga 3-5 tahun ke depan, kelompok usaha di sektor makanan-minuman ini membutuhkan sedikitnya 400 orang pemimpin bisnis untuk mengelola akselerasi usahanya. Hal yang sama juga terjadi di Pertamina. Perusahaan itu mencanangkan bisa mencetak 200 business leader guna mengelola laju ekspansi di tengah gempuran para pesaing. Apakah target itu tercapai atau tidak, itu perkara lain. Yang pasti, urusan mencetak para pemimpin baru sangat mendesak.
Perkara mencetak leader memang hal penting. Steven Wheeler, Walter McFarland, dan Art Kleiner di Strategic+Business, 10 Januari 2008 menggugah para CEO untuk membangun kepemimpinan strategis, yakni “build an organization in which executives will flourish”. Menumbuhkan para eksekutif dari dalam adalah tugas yang makin krusial. Bahkan, bagi Robby Djohan, orang yang telah menelurkan sejumlah pemimpin bisnis di negeri ini, mencetak leader merupakan tugas yang tak bisa ditawar. “Sering kawan-kawan dalam pertemuan berkata pada saya, 'CEO saya pergi nih. Saya butuh CEO baru. Menurut kamu, saya harus bagaimana?' Di mata saya, itu a stupid question! Mengapa? Yang saya katakan adalah mengapa kamu tidak melihat portofolio manusia yang ada di dalam organisasimu untuk dilihat mana yang berpotensi menjadi CEO, dan pikirkan langkah yang tepat dan terbaik untuk menjadikan calon itu siap menjadi pemimpin.”
Adapun cara melahirkan pemimpin itu sendiri, Riri Satria, Consulting Director People Performance Consulting, melihatnya bisa dilakukan dalam 2 jalur; berdasarkan sistem, atau tidak berdasarkan sistem (sentuhan individu). Jalur pertama ditandai adanya kebijakan tertulis yang mengatur pengembangan kompetensi dengan memberikan peluang yang sama kepada karyawan. Adapun jalan yang kedua sifatnya lebih kepada personal touch. Para pimpinan sudah membidik orang-orang tertentu untuk menjadi kader dengan memberi kesempatan dan tantangan yang lebih banyak. ”Pendekatan yang ideal dan banyak dilakukan adalah kombinasi dari kedua pendekatan di atas,” katanya.
Kembali pada wacana CEO versi 3.0. Secara sederhana, sesungguhnya lanskap bisnis di Tanah Air juga bisa diklasifisikan dengan periode tertentu, dengan meminjam pandangan Sonnenfeld. Pertama, pra-1997. Ditandai -- terutama -- dengan deregulasi perbankan 1988, sedikit banyak para CEO di Indonesia juga menjadi empire builder. Sebutlah ini versi 1.0. Tandanya; semua berlomba berekspansi demi kebesaran kelompok usahanya sampai akhirnya krisis moneter 1997 menyapu bangunan yang ada, sekaligus mengantar pada era ke-2; pembenahan. Mulai 1998, dunia usaha melakukan restrukturisasi utang dan skala usaha, yang membuat para CEO menjadi kaum fix-it man yang sibuk membenahi sekaligus mengonsolidasi diri. Inilah versi 2.0. Dan dibubarkannya BPPN beserta sejumlah inisiatif macam Prakarsa Jakarta, semestinya menjadi tanda bahwa para CEO memasuki fase ke tiga; era stabilisasi dan pertumbuhan.
Tahun 2008 adalah satu dasawarsa setelah krisis menerpa. Dan kini, 2009, ancaman krisis kembali datang. Bicara lanskap bisnis, sungguh banyak perubahan yang semestinya membuat para CEO kita juga masuk pada fase atau menjadi versi tersendiri (3.0.). Di lingkup domestik, ranah ekonomi tak bisa dilepaskan dari proses demokratisasi, otonomi daerah dan tekanan stakeholders yang lebih kuat, mulai dari good corporate governance hingga corporate social responsibility. Ini berjalan seiring persaingan yang lebih ketat karena kompetisi berjalan tanpa bayangan monopoli. Sementara itu, di lingkup internasional, persoalan menjadi lebih rumit karena mengglobalnya perekonomian diikuti pelebaran kutub-kutub pertumbuhan di sejumlah belahan dunia, khususnya Asia. Ini ditandai dengan kebangkitan Cina dan India, yang segera akan diikuti pemain dari negara lain, mulai dari Uni Emirates Arab, Qatar, Vietnam, dan bersiap-siaplah menyambutnya; Kamboja. Mereka menambah daftar pesaing yang sebelumnya telah mapan menunggangi globalisasi.
Kalau begitu, bagaimana karakter serta kemampuan versi 3.0. yang dibutuhkan CEO kita untuk melakukan stabilisasi dan menggenjot pertumbuhan?
Dari persoalan yang ada, tampaknya CEO masih dituntut menjalankan hal-hal yang kerap disebut basic task; konsolidasi bisnis dan biaya, reorganisasi, serta menjalankan prioritas strategis. Adapun nilai yang dikembangkan sering disebut sebagai classic leadership values, seperti disiplin. fokus, dan eksekusi. Akan tetapi, itu saja tampaknya tidak memadai.
Dalam pandangan Harry Sasongko, Presdir & CEO GE Money Indonesia, mengglobalnya ekonomi menuntut pemimpin perusahaan bersikap sekaligus berpikiran terbuka. Dari sisi jabatan CEO itu sendiri, misalnya. Globalisasi membuat orang bergerak lintas negara dan perusahaan. Menurutnya, kalau tidak sigap serta mempunyai keahlian yang lebih unggul dari warganegara asing, CEO akan tersingkir. Dan bisnisnya juga otomatis akan tersingkir kalau dia tak pandai meniti setiap peluang yang ada.
Bersikap sekaligus berpikiran terbuka, atau openness. Selanjutnya, Tanri Abeng menambahkan bahwa di era sekarang yang kian menuntut kecepatan sekaligus ketepatan bertindak, CEO harus mampu bersikap adaptif. Artinya sanggup menyesuaikan diri dengan situasi serta kondisi ekstrim sekalipun. Bedanya dengan sikap fleksibel? Fleksibel hanyalah sebatas bersedia bertoleransi dengan ketidaknyamanan, tetapi belum tentu mau beradaptasi. “Pemimpin yang fleksibel belum tentu mampu beradaptasi. Tetapi pemimpin yang mampu beradaptasi, itu pasti punya sikap fleksibilitas tinggi. Sikap adaptif sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam mengambil berbagai keputusan bisnis,” tandas Komisarit Utama PT Telkom ini. Cuma itu?
Openness dan adaptif saja, rupanya tidaklah memadai. Bagi Nugroho Supangat, mantan Mitra Pengelola Dunamis Organization Services, CEO masa kini juga harus lebih mampu merangkul stakeholders, terutama di lingkungan internal. Para pemimpin harus bisa mengayomi SDM yang kini disebut knowledge worker di tengah tuntutan standar kerja yang tinggi. Adapun untuk lingkup eksternal, kompetisi global yang menjadi salah satu dari 10 persoalan CEO, harus dijawab dengan kemampuan negosiasi yang hebat. “Mereka harus memiliki negotiation level tidak hanya level nasional tapi minimal regional level. Jadi tidak hanya bisa buat lobby dan network di Indonesia saja. Karena keran globalisasi di Indonesia ini rupanya terbuka lebar,” ujarnya serius.
Menambahkan pendapat di atas, Andreas Budihardjo, Guru Besar Manajemen Organisasi & SDM Prasetiya Mulya menggarisbawahi perlunya CEO memiliki kemampuan lain. “Dia juga harus bisa mengelola paradoks,” ulasnya. Paradoks dalam konteks ini, menurutnya adalah mengatasi antara persaingan dan kolaborasi sekaligus. “Mungkin kita sama-sama pengusaha restoran. Kita bersaing. Tapi kita juga berkolaborasi, bersama-sama membesarkan bisnis ini,” tutur peraih gelar master Manajemen Organisasi di Universitas Groningen, Belanda itu penuh arti.
Buat TP Rahmat, sejatinya tidak ada tipe karakter tertentu yang dibutuhkan oleh pemimpin bisnis masa kini. Baginya, yang terpenting adalah ketegasan, keberanian dan integritas. Di atas itu semua, hal terpenting yang harus ada dalam diri seorang CEO adalah karakter kejujuran dan ketegasan. Apapun, kondisi dan situasinya. “Kalau 'gak jujur, keras dan tegas mah sekarang ini lewat sajalah,” ujar Teddy dengan logat Sunda yang cukup kental. “Seperti Pak Agus (Matowardojo) di Bank Mandiri. Kalau semua CEO BUMN kayak dia, wah, beres deh permasalahan,” tambah mantan CEO Astra yang pernah meraih predikat Best CEO dari SWA itu. Teddy terkesan dengan gaya Agus membenahi Bank Mandiri. “Contohnya pengumuman di media massa (tentang) para pengutang. Itu butuh keberanian,” ujarnya.
Bagi Teddy, keberanian selalu dibutuhkan pemimpin dalam situasi serta kondisi apapun. Karena itulah, di luar tantangan eksternal dan internal organisasi, persoalan terbesar bagi CEO, justru datang dari dalam dirinya sendiri. “CEO juga manusia. Punya anak istri, butuh duit. Itu yang membuat sebagian diantara mereka tidak memiliki keberanian dan ketegasan. Kalau yang pintar mah banyak,” tandasnya. Teddy melanjutkan, “Jadi, tantangan terbesar adalah mengalahkan rasa takut di dalam diri sendiri atas tekanan dari luar yang mengancam akan mencopot dari posisinya.”
Billy Jean King, mantan ratu tenis dunia pernah berujar bahwa bagi sang juara, pressure is privilege. Begitu juga bagi para CEO, sejatinya tekanan adalah privilese yang tak dinikmati sembarang orang. Dan kata Jenderal AS, George Patton, “Pressure makes diamonds.” Tekananlah yang akan mengantar seseorang menjadi emas atau loyang.
Bicara karakter dan kemampuan yang dibutuhkan CEO kita, tulisan Klaus-Peter Gushurst, The New Leadership; Sober, Spirited, and Spiritual, layak disimak. Menurutnya, era terbaik di masa globalisasi adalah mengombinasikan antara classic leadership values dengan contemporary values, termasuk openness, komunikasi yang berkualitas, dan kebersahajaan (naturalness), yang nota bene sejalan dengan pandangan Sonnenfeld. Tak lupa, juga memiliki nilai-nilai spiritualitas.
Dunia bisnis terus dinamis. Persoalan demi persoalan yang muncul, merupakan gambaran betapa dunia bisnis membutuhkan pemimpin-pemimpin hebat. CEO Versi 3.0. Andakah itu orangnya?
skip to main |
skip to sidebar

Catatan ringan dari Taman Tanah Abang III
Come on
Follow me @teguhspambudi
Calendare
Time is ...
Welcome
Salam. Blog ini dihadirkan di tengah Taman Tanah Abang III. Celoteh ringan di sela pekerjaan. Sebagian dimuat di SWA. Sebagian tercurah begitu saja.
About Me
From Zero to Growth

Categories
- Creative Economy (33)
- CSR (3)
- Diaspora (2)
- Digital Technology (11)
- Entrepreneur (26)
- Entrepreneurship (24)
- Family Business (7)
- Green Business (1)
- HR (4)
- Leadership (44)
- Life (12)
- Live (3)
- Macroeco (6)
- Management (21)
- Marketing (28)
- Social Entrepreneur (8)
- Social Media (4)
- Strategy (34)
- Sustainability Development (2)
- Technopreneur (12)
- Women Leadership (7)
Blog Archive
-
▼
2009
(22)
-
▼
April
(15)
- Ketika Bicara tak Lagi Murah
- CEO versi 3.0.
- Inspirasi dari Kakek Jeno
- Mengentaskan Para Pangeran
- Pembuktian Kaisar Es Krim
- Kembalinya Sang Legenda
- Tiga Menguak Cokelat
- Hidup di Tengah Komunitas
- Empat Kaki Kapitalisme Kreatif
- Duh, Carly ...
- Master Efisiensi di HP
- Raja e-Commerce Negeri Sakura
- Mark si Fenomenal
- Maestro Desain dari Boxtel
- Lelaki di Balik Anomali Porsche
-
▼
April
(15)



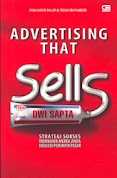
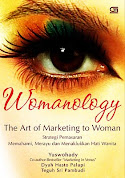












2 comments:
Assalamu'alaikum wr wb Pak Pambudi salam kenal saya Muji Widodo dari blog SAUNG HIJAU PAWEWET, saya mohon izin untuk mengikuti terus tulisan anda, tulisan yang bagus-bagus. semakin mencerahkan pikiran saya.
salam untuk keluarga anda, smoga Allah SWT merahmati kita semua
Wassalamu'alaikum wr wb
Waalaikumussalam Mas. Wah, sorry saya baru bales. Saya senang banget kalau Mas Muji baca tulisan-tulisan ini. Semoga Allah SWT merahmati Mas dan keluarga.
Post a Comment