Skandal tata
kelola perusahaan tak kunjung berhenti. Etika kerap hanya jadi
seperangkat aturan tertulis. Pada akhirnya mengelola korporasi memang
soal yang satu ini: kejujuran.
Bom atom itu bernama
Olympus. Berawal dari tuntutan mantan CEO-nya, Michael Woodford,
skandal busuk yang sudah disimpan rapat selama 20 tahun itu terkuak
sudah. Bahkan bukan hanya di Jepang, bau anyirnya menyebar ke banyak
tempat, memancing mual melihat rakusnya segelintir orang-orang
terhormat di pucuk korporasi.
Pemicu terkuaknya
borok ini bermula dari permintaan Woodford terhadap perusahaan
berumur 92 tahun ini untuk menjelaskan transaksi akuisisi sebesar US$
1,3 miliar (Rp 11 triliun) yang menurutnya janggal. Woodford mencium
bau busuk. Ada yang salah dari kebijakan yang diambil. Dia curiga
dana tersebut mengalir ke pos yang salah.
Awalnya – seperti
lazimnya skandal yang mesti ditutup rapat-rapat –, manajemen
Olympus menyangkal mati-matian. Namun, lewat jalan berliku, akhirnya
produsen kamera asal Jepang itu mengakui telah menyembunyikan
kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama 20 tahun, sejak era
1980-an.
Aib ini bermula dari
akuisisi Olympus atas produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus,
pada tahun 2008. Transaksi senilai US$ 2,2 miliar (Rp 18,7 triliun)
ini juga melibatkan biaya-biaya lain, yakni ongkos penasihat yang
mencapai US$ 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga
perusahaan investasi lokal senilai US$ 773 juta (Rp 6,57 triliun).
Belakangan
terungkap, biaya-biaya lain tersebut (ongkos penasihat dan perusahaan
investasi lokal) adalah akal-akalan. Dana-dana itu digunakan untuk
menutupi kerugian investasi di dua dekade lalu. Modus ini pun
terlihat terang-benderang lantaran pembayaran kepada tiga perusahaan
investasi lokal itu dihapusbukukan.
Laiknya aib besar,
saling tuding pun terjadi diantara pihak-pihak terkait. Presiden
Direktur Olympus Shuichi Takayama menunjuk hidung Tsuyoshi Kikukawa,
yang mundur dari jabatan Presiden dan Komisaris Olympus pada 26
Oktober 2011, sebagai pihak yang bertanggung jawab. "Saya
benar-benar tidak mengetahui kebenaran tentang semua ini," kilah
Takayama, yang mengaku tidak mengetahui kasus ini sejak jabatan
Presiden Direktur diserahkan Kikukawa kepadanya. Baru Wakil Presiden
Direktur Hisashi Mori dan auditor internal Hideo Yamada yang
menyatakan siap jika pada akhirnya dituntut hukuman pidana karena
mengetahui transaksi ini.
Di tengah kepastian
akan diseretnya para direksi serta akuntan dengan delik manipulasi
laporan keuangan, masa depan Olympus menjadi pertanyaan besar.
Sahamnya rontok. Kepercayaan anjlok. Dan masyarakat Jepang pun sontak
diingatkan skandal besar lain di era 1990-an yang menimpa
meluluhlantakkan broker terbesar keempat di Jepang, Yamaichi
Securities pada 1997.
24
November 1997. Yamaichi Securities Co., perusahaan broker tertua di
Jepang, yang juga perusahaan terbesar nomor 4, mengumumkan
kebangkrutannya. Utang yang melilitnya mencapai US$ 23,8 miliar, tapi
kalangan media Negeri Matahari Terbit menaksir utang yang sebenarnya
di kisaran US$ 53 miliar. Kewajiban sebesar itu melibatkan 40
perusahaan terafiliasi, baik dari bisnis investasi, keuangan dan
properti yang bernaung di bawah kelompok Yamaichi.
Saat
itu, banyak kalangan meyakini Yamaichi Securities sebagai core
company dari kelompok
usaha ini akan mampu bertahan dengan mem-bail
out utang-utang
perusahaan afiliasinya. Tapi alih-alih mampu menghapusbukukan utang
di perusahaan afiliasi, Kementrian Keuangan Jepang justru mengungkap
kotoran besar yang selama ini disimpan rapatt: Yamaichi
menyembunyikan kerugian US$ 1,58 miliar dalam neraca keuangannya. Dan
kalangan media membongkar bahwa skandal ini dilakukan dengan modus
kuno: perdagangan ilegal di mana kerugian brokerage
dialihkan dari satu klien ke klien lain sehingga nasabah tidak
mengetahui situasi sebenarnya. Kelak, seluruh kerugian itu kemudian
dikumpulkan di perusahaan bodong di mancanegara.
Skandal
kedua perusahaan Jepang di atas hanyalah sedikit noda dunia korporasi
yang meninggalkan kelu bagi pihak yang dirugikan, sekaligus rasa mual
tatkala membaca atau mendengarnya. Tapi Jepang tidak sendirian. Di
AS, skandal korporasi yang sampai sekarang masih menyakitkan,
tentunya adalah Enron.
Akhir tahun 2002,
raja perdagangan energi yang sebelumnya berkali-kali masuk menjadi
perusahaan yang mengagumkan menjatuhkan bom yang lebih besar dari
Olympus. Tak tanggung-tanggung, salah satu perusahaan terbesar di
dunia ini mengumumkan kebangkrutannya.
Tentu saja ini
berita terbesar setelah serangan ke Menara Kembar WTC setahun
sebelumnya. Bagaimana tidak, Enron selama ini adalah perusahaan yang
penuh puja-puji. Bahkan pada tahun 2001, ia masih melaporkan rapor
keuangan yang seperti biasanya, menawan para investor: pendapatan
mencapai US$ 100 miliar, laba US$ 3,8 miliar. Buat perusahaan sebesar
Enron, tak ada yang mengira kematian datang tiba-tiba setahun
berikutnya ketika melaporkan kerugian US$ 50 miliar.
Sejarah
mencatat, kebangkrutan yang membuat pelaku pasar modal nangis bombay
karena rugi US$ 32 miliar dan ribuan pegawai Enron kering airmatanya
lantaran dana pensiunnya sebesar US$ 1 miliar lenyap itu berangkat
dari praktik window
dressing.
Manajemen Enron di bawah pimpinan Ken Lay dan Jeff Skilling telah
menggelembungkan pendapatan sebesar US$ 600 juta sembari
menyembunyikan utang US$ 1,2 miliar.
Melihat beberapa
skandal di atas, tak heran jika muncul pertanyaan: mengapa semua ini
berulang?
Modus yang digunakan
perusahaan di atas menjadi potret betapa etika telah disimpan di
bawah karpet bersama borok-borok yang ditimbulkannya. Tapi, apakah
tak ada aturan etika bisnis yang selaras dengan tata kelola usaha
mereka?
Justru
di sinilah ironi besar itu terletak. Dilihat
dari sudut pandang etika serta tata kelola perusahaan, apa kurangnya
Enron, Yamaichi dan Olympus? Seperangkat code
of conduct
mereka miliki.
Enron,
ambil contoh. Kode etiknya luar biasa. Berbentuk booklet
setebal 64 halaman, kode etik terakhir diperbarui pada Juli 2000.
Kalimat Pendahuluannya pun sangat indah. “As
officer and employees of Enron Corps., its subsidiaries, and its
affiliated companies, we are responsible for conducting the business
affairs of the companies in accordance with all applicable laws and
in a moral and honest manner”.
Indah bukan? Yang menuliskannya: Ken Lay, Chairman
dan CEO Enron, biang skandal.
Dalam
booklet,
nilai-nilai moral bertebaran di sekujur halaman, bertaburan perintah
ini-itu. Buat karyawan, diantaranya termaktub: dilarang menguntungkan
diri sendiri atau bertindak demi keuntungan pihak lain, diminta
menjaga nama baik Enron dengan standar moral yang tinggi, dan sederet
aturan lain yang amat hebat. Tapi praktik membuktikan, bukan karyawan
yang menghancurkan aturan itu, melainkan para pembuatnya sendiri.
Tak
heran, karena jengkel, setelah Enron kolaps, booklet
ini oleh orang yang sinis dilelang di E-Bay, laku di posisi US$
202,5. Betapa murahnya untuk seperangkat rambu tindakan yang hebat.
Begitu
pula halnya Olympus. Perhatikan code
of conduct-nya: sound
corporate activities, action on behalf of the customer, respect for
human right, serta
working environment
with vitality. Tiap
poin tersebut selanjutnya memiliki penjabarannya masing-masing yang
cukup panjang, terinci dan detail. Pedoman etika ini juga harus
digunakan di seluruh grup. Salah satunya adalah Gyrus ACMI yang
mencantumkan kalimat berikut dalam pedoman perilakunya: "As
members of the Olympus Group, we all understand that in striving to
achieve success in our business lines, we must conduct ourselves in
accordance with the law and with the highest standards of ethics and
integrity."
Sebenarnya,
sejak skandal Enron meledak, banyak upaya dilakukan untuk meredam
perilaku tidak etis yang dibuat para pemuncak korporasi. Boardroom
memang menjadi titik perhatian karena inilah sentrum kapitalisme. Di
sinilah kapitalisme diharapkan bisa mengalirkan kebaikan. Tapi
skandal yang meruyak membuktikan justru di sini juga akar kejahatan
besar itu sering bermula sehingga melahirkan istilah “the
madness in boardrom”,
kegilaan di ruang direksi.
Menyadari
direksi bukan manusia berhati malaikat – malah sering menjadi
serigala berbulu domba di balik jas dan dasi mahalnya – sejumlah
upaya diluncurkan, mulai dari Sarbanes-Oxley (tahun 2002) hingga
ketentuan memperbanyakan direktur independen seperti yang ditetapkan
Wall Street dan Nasdaq pada 2009. Pemikirannya mendasar: perlunya
mekanisme checks and
balances yang
lebih ketat di tengah godaan penyelewengan kuasa yang amat berat.
Peraturan
yang dibuat memang cukup memperketat potensi penyelewengan. Tapi
tetap saja muncul seorang Bernard Lawrence "Bernie" Madoff
yang melakukan penipuan gila-gilaan lewat skema Ponzi. Menilik
posisinya, Madoff mungkin benar-benar orang keblinger.
Bagaimana tidak. Dia mantan kepala bursa Nasdaq yang memahami arti
tata kelola dan etika. Lewat Madoff Investment Securities LLC, ribuan
investor dibuatnya gigit jari karena Madoff tidak melakukan investasi
tetapi memindahkan uang para investor baru untuk membayar uang para
investor lama pada tanggal jatuh tempo. Kerugian akibat skema Ponzi
ditaksir mencapai US$ 20 miliar, yang menjadi kerugian investasi
terbesar di negeri itu. Madoff dihukum 150 tahun.
Melihat
apa yang terjadi, tak heran bila Vineet
Nayar punya pendapat yang tampaknya akan selalu relevan. Katanya,
“Corporate
ethics isn't about rules. It's about honesty.”
Nayar adalah Vice
Chairman
dan CEO HCL Technologies Ltd., perusahaan IT dari India. Dia penulis
buku laris, Employees
First, Customers Second.
Baginya,
corporate
governance
dan etika yang sesungguhnya bukanlah seperangkat aturan formal. Ini
tentang hati. Tentang kejujuran. Khususnya buat para pemimpinnya.
Akuntabilitas para pemimpin, katanya adalah sesuatu yang tak bisa
dinegosiasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. “Hal yang kita
lakukan setiap hari adalah berlaku jujur,” katanya. Tapi justru
itulah yang kini seringkali menjadi barang langka di jagat bisnis.
Padahal, trust
akan
muncul dalam sebuah perusahaan bila para pemimpinnya transparan. Dan
trust
menjadi mata uang paling berharga dalam sebuah perusahaan.
Sayang,
lanjut Nayar, keserakahan para pemimpin membuyarkan itu semua. Etika
pun akhirnya hanya seperangkat aturan yang bersifat lentur, digunakan
sesuka hati, dan disimpan di bawah karpet manakala tidak
menguntungkan. Etika membeku di atas kertas, tidak dihidupkan dalam
perilaku keseharian. Lantas, harus dari mana memulainya?
Tentu
saja seluruh elemen perusahaan wajib menjalankan etika yang
dituliskan. Tapi yang
menarik, Nayar mengingatkan para pemimpin bahwa perilaku etis mereka
sesungguhnya sangat berpengaruh pada karyawannya. Para pemimpin itu,
katanya, berutang kepada karyawannya yang telah memahat kesuksesan
perusahaan. Karyawanlah yang bangun pagi dan berangkat kerja dengan
semangat. Agar tata kelola perusahaan yang baik dapat berjalan,
pemimpin mesti mencontohkan terlebih dahulu sebelum meminta karyawan
bertindak etis. Sebab karyawan akan mencontohnya. “Tuhan hanya
memberi kita satu kehidupan. Lakukanlah hal yang baik,” katanya
menasehati para CEO. ***




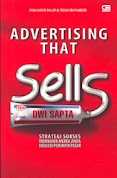
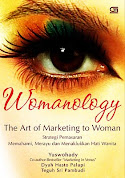













0 comments:
Post a Comment